SEJENGKAL TANAH SETETES DARAH
(Lanjutan TADBM)
karya mbah_man
Padepokan “Sekar Keluwih” Sidoarjo
Website Resmi : https://cersilindonesia.wordpress.com

Website Resmi : https://cersilindonesia.wordpress.com

STSD Jilid 1
Bagian 1
Malam baru saja lewat sirep bocah. Angin
malam yang bertiup cukup keras telah menggugurkan daun-daun kering
pepohonan yang tumbuh di halaman istana Kepatihan. Di ruang dalam,
tampak lima orang sedang duduk terpekur menunggu titah Ki Patih
Mandaraka.
Tidak ada seorang pun yang berani membuka
suara. Masing-masing sedang tenggelam dalam lamunan yang mengasyikkan.
Berbagai kenangan telah hilir mudik dalam benak mereka. Satu-persatu
kenangan itu bagaikan air hujan yang turun membasahi bukit-bukit
berbatu. Mengalir di sela-sela bebatuan susul menyusul saling berebut
hingga akhirnya sampailah air itu di kaki bukit kenangan mereka.
“Ki Rangga,” tiba-tiba terdengar Ki Patih
berkata membuyarkan lamunan mereka, “Bagaimanakah rencana Ki Rangga
selanjutnya sehubungan dengan lolosnya orang yang menyebut dirinya
Pangeran Ranapati itu.”
Ki Rangga Agung Sedayu beringsut setapak
ke depan sambil menyembah. Jawabnya kemudian, “Ampun Ki Patih. Pangeran
Ranapati telah lolos dari medan pertempuran lemah Cengkar karena
ditolong oleh Gurunya, Ki Singawana Sepuh. Menurut perkiraan hamba,
mereka kemungkinan besar telah pulang ke Kademangan Cepaga. Hamba
mempunyai rencana untuk menyusul mereka.”
Untuk beberapa saat Ki Patih termenung.
Ingatannya kembali ke masa puluhan tahun yang silam ketika seorang
pemuda yang bernama Jaka Suta bersama Pamannya singgah di padepokan
Selagilang, di lereng utara gunung Merapi.
Sejenak suasana kembali sepi. Ki Patih
sedang terbawa kenangan sewaktu Panembahan Senapati masih muda dan lebih
dikenal dengan nama Raden Sutawijaya.
“Tugas untuk melacak keberadaan pangeran
Ranapati itu masih tetap berada di pundakmu, Ki Rangga,” berkata Ki
Patih kemudian memecah kesunyian, “Namun yang perlu engkau waspadai, Ki
Ageng Selagilang atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Singawana Sepuh,
tentu akan melindungi orang yang sudah dianggap seperti cucunya sendiri
itu. Ki Ageng Selagilang mempunyai ketinggian ilmu yang tak terukur.
Engkau harus benar-benar siap lahir maupun batin jika ingin berurusan
dengannya lagi,” Ki Patih berhenti sejenak. Setelah menarik nafas
panjang Ki Patih melanjutkan, “Tidak menutup kemungkinan jika Ranapati
masih dapat bertahan dan selamat, dia akan menyusun kekuatan lagi dengan
mempengaruhi dan bergabung dengan para Adipati di pesisir yang sekarang
ditengarai sedang bergolak.”
Ki Rangga tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang tampak terangguk dalam-dalam.
“Nah, Ki Rangga. Untuk sementara
persoalan Ranapati itu kita kesampingkan dulu sambil menunggu
perkembangan dari para petugas sandi. Mereka telah disebar untuk
memantau keberadaan Ranapati.”
Mereka yang hadir di ruang dalam Kepatihan itu hanya dapat mengangguk-angguk tanpa mengucapkan sepatah katapun.
“Sekarang aku akan menyampaikan sesuatu
hal tentang Kademangan Sangkal Putung,” berkata Ki Patih kemudian sambil
membetulkan letak duduknya.
Ki Rangga yang mendengar Kademangan
Sangkal Putung disebut, tanpa sadar telah mengangkat wajahnya. Namun
begitu disadari Ki Patih sedang memandang ke arahnya, dengan cepat
segera ditundukkan kembali wajahnya.
“Mataram sedang mempersiapkan serat
kekancingan bagi Kademangan Sangkal Putung,” berkata Ki Patih
selanjutnya, “Ki Swandaru telah berjasa ikut menjaga kedaulatan Mataram
dari tangan-tangan segolongan orang yang tidak bertanggung jawab. Bentuk
penghargaan itu sedang dipikirkan. Mungkin kademangan Sangkal Putung
akan ditingkatkan kedudukannya menjadi sebuah tanah Perdikan yang tidak
mempunyai kewajiban membayar upeti, namun kewajiban untuk tunduk dan
patuh kepada Mataram tetap ada.”
Berdesir jantung orang-orang yang hadir
di ruang dalam Kepatihan itu. Selama ini Ki Demang Sangkal Putung dalam
tugas sehari-hari telah diambil alih oleh Ki Swandaru karena kesehatan
ki Demang yang sudah menurun serta usianya yang sudah sedemikian sepuh.
Sepeninggal Ki Swandaru, Kademangan Sangkal Putung harus segera menunjuk
seseorang untuk membantu tugas Ki Demang atau bahkan sekalian
mengangkat seorang Pemangku sementara untuk menjalankan tugas
sehari-hari sampai saatnya nanti Ki Demang mengundurkan diri.
“Apakah Kademangan Sangkal Putung sudah
memutuskan siapa Pemangku sementara untuk membantu Ki Demang yang sudah
tua dan sakit-sakitan itu?” tiba-tiba Ki Patih bertanya seolah-olah
mengerti apa yang sedang mereka pikirkan.
Orang-orang yang hadir di ruang dalam
Kepatihan itu untuk sejenak saling berpandangan. Ki Rangga lah yang
akhirnya menjawab, “Ampun Ki Patih, beberapa saat yang lalu Pandan Wangi
telah menyampaikan rencananya kepada hamba. Bayu Swandana anak
laki-laki satu-satunya Ki Swandaru rencananya akan dibesarkan oleh
ibunya di Tanah Perdikan Menoreh.”
Ki Patih mengerutkan keningnya
dalam-dalam. Sambil berpaling ke arah Ki Rangga, Ki Patih pun bertanya,
“Mengapa Pandan Wangi memilih pulang ke Tanah Perdikan Menoreh?”
Ki Rangga yang melihat Ki Patih telah
berpaling ke arahnya segera menyembah sambil menjawab, “Mohon ampun Ki
Patih. Hamba telah memberikan beberapa pertimbangan kepadanya, namun
Pandan Wangi lebih memilih untuk pulang ke Menoreh.”
Kembali Ki Patih mengerutkan keningnya.
Sebagai seorang yang telah kenyang makan asam garamnya kehidupan, Ki
Patih segera maklum apa yang dimaksud oleh Ki Rangga.. Katanya kemudian
sambil menghela nafas panjang, “Ya, aku bisa memaklumi sikap Pandan
Wangi. Sepeninggal suaminya, Pandan Wangi tentu merasa lebih tenang
membesarkan anaknya di tanah kelahirannya sendiri. Sementara di Menoreh,
Ki Argapati pun juga memerlukan pendamping untuk menjalankan tugasnya
sehari-hari.”
“Sudahlah,” berkata Ki Patih kemudian
memecah kesunyian, “Biarlah urusan itu dibicarakan oleh keluarga besar
kedua wilayah itu. Mataram akan menunggu setiap keputusan yang telah
disepakati”, Ki Patih berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Sekarang
aku ingin mendengar laporan tentang perjalanan Glagah Putih beberapa
pekan yang lalu ke Bukit Tidar.”
Glagah Putih yang disebut namanya segera bersingsut ke depan. Sambil menyembah, Glagah Putih pun segera memberikan laporannya.
“Mohon ampun Ki Patih,” berkata Glagah
Putih kemudian, “Rencana perjalanan kami ke bukit Tidar memang sempat
tertunda beberapa hari sehubungan dengan meninggalnya Ki Swandaru,”
Glagah Putih berhenti sejenak. Kemudian lanjutnya, “Gunung Tidar selama
ini ternyata sedang dalam pengamatan para petugas sandi. Kami telah
mengadakan hubungan dengan para petugas sandi di sana. Akhir-akhir ini
perguruan Sapta Dhahana yang berada di lereng gunung Tidar sedang giat
menjalin hubungan dengan segolongan orang yang mengaku sebagai Trah
Sekar Seda Lepen.”
Tampak Ki Patih menarik nafas dalam-dalam
sambil mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar laporan Glagah Putih.
Sekilas wajah Ki Patih tampak sedikit muram. Sedangkan orang-orang yang
hadir di ruangan itu tampak saling pandang dengan kening yang
berkerut-merut.
Ki Waskita yang duduk di sebelah kiri Ki
Rangga memberanikan diri untuk mengajukan pendapatnya, “Ampun Ki Patih.
Bukankah orang-orang yang mengaku pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu
pernah membuat keributan di kediaman Ki Gede Menoreh beberapa saat yang
lalu? Agaknya berita kebangkitan keturunan dari Pangeran Sekar itu bukan
berita ngaya wara.”
“Benar, Ki Waskita,” jawab Ki Patih, “Aku
memang sudah mendapat laporan sebelumnya, namun aku ingin Glagah Putih
di dampingi Ki Jayaraga untuk menelusuri kebenaran berita itu dan
melihat kekuatan yang tersimpan di padepokan Sapta Dhahana serta
hubungannya dengan orang yang menyebut dirinya sebagai trah Sekar Seda
Lepen.”
“Sendika Ki Patih,” Ki Jayaraga yang
sedari tadi diam saja kini menyahut, “Kami berdua telah mengamati
perguruan itu dari dekat. Pemimpin perguruan Sapta Dhahana, Kiai Damar
Sasangko, sering mengadakan hubungan dengan seseorang yang bernama Raden
Wirasena yang mengaku sebagai keturunan Pangeran Sekar, putra tertua
dari Raden Patah Sultan Demak pertama walaupun dari garwa selir. Raden
Wirasena menganggap dirinya lebih berhak atas tahta di tanah ini dari
pada keturunan Panembahan Senapati.”
Untuk beberapa saat mereka yang
mendengarkan penjelasan Ki Jayaraga itu terdiam. Orang yang bernama
Raden Wirasena dan para pengikutnya itu agaknya sedang berusaha
menanamkan pengaruhnya terhadap para kawula Mataram dengan cara
mengungkit kembali akan garis keturunan dari kerajaan Demak lama. Tidak
menutup kemungkinan orang-orang yang masih rindu akan kejayaan Demak
lama akan terpengaruh, karena mereka masih beranggapan bahwa penguasa
negeri ini harus ada garis keturunan dari kerajaan besar yang pernah
ada, yaitu Majapahit. Sedangkan Panembahan Senapati yang kemudian
menjadi raja pertama di Mataram itu sama sekali tidak ada hubungannya
dengan garis keturunan dari Majapahit.
“Ampun Ki Patih,” kembali Ki Waskita
mengajukan pendapatnya sambil menyembah, “Bukankah jaman sudah berganti
dan Wahyu Keprabon sudah berpindah beberapa kali? Dan yang terakhir,
sesuai dengan ramalan seorang Wali yang waskita, Wahyu Keprabon ternyata
telah jatuh di Alas Mentaok yang sekarang ini telah menjadi kerajaan
Mataram.”
“Ki Waskita benar,” jawab Ki Patih
sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, “Namun yang perlu diluruskan
adalah, siapakah yang telah mengaku sebagai trah Pangeran Sekar itu?
Seperti yang telah kita ketahui bersama, Pangeran Sekar meninggalkan dua
orang putra, Harya Penangsang dan Harya Mataram. Harya Penangsang gugur
dalam peperangan antara Pajang dan Jipang di pinggir bengawan sore,
sedangkan Harya Mataram telah lolos dan sampai sekarang tidak ada kabar
beritanya.”
Untuk sejenak ruang dalam Kepatihan itu
kembali menjadi sunyi. Masing-masing telah tenggelam dalam angan-angan
mereka. Sementara di luar angin malam bertiup agak kencang sehingga
telah mengguncang daun-daun pohon sawo kecik yang ditanam di sebelah
regol Kepatihan.
“Sudahlah,” berkata Ki Patih kemudian,
“Persoalan itu akan menjadi pekerjaan para prajurit sandi untuk
mengungkapkan siapakah sebenarnya orang yang mengaku sebagai Trah Sekar
Seda Lepen itu,” Ki Patih berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Nah,
sekarang yang perlu kita ketahui adalah kekuatan sebenarnya dari
Padepokan Sapta Dhahana. Ki Rangga pun agaknya sangat berkepentingan
dengan berita ini. Mungkin Ki Jayaraga dapat memberikan gambaran.”
Selesai berkata demikian Ki Patih
kemudian berpaling kepada Ki Jayaraga. Ki Jayaraga pun tanggap. Secara
singkat segera diceritakan hasil pengamatannya bersama Glagah Putih di
Padepokan Sapta Dhahana.
“Ampun Ki Patih, sebagaimana yang pernah
Ki Patih sampaikan. Perguruan itu memang mempunyai sebuah ritual yang
cukup aneh. Kami berdua sempat menyaksikan walaupun dari jarak yang agak
jauh. Setiap murid perguruan itu senang bermain-main dengan api,” Ki
Jayaraga memulai kisahnya, “Pada tingkat kemampuan yang paling rendah,
murid-murid padepokan itu mampu berjalan dengan kaki telanjang di atas
tumpukan bara api tanpa menderita luka sedikit pun. Sedangkan pada
tingkatan yang lebih tinggi, seseorang telah dilumuri sekujur tubuhnya
dengan sejenis minyak kemudian dibakar. Ternyata tubuh orang tersebut
tidak mempan dibakar api, bahkan pakaian yang dikenakannya pun tetap
utuh, tidak hangus dimakan api.”
Mereka yang hadir di ruangan itu menjadi
berdebar-debar. Jika murid-muridnya saja mampu menunjukkan pengeram-eram
seperti itu, bagaimana dengan kemampuan gurunya sendiri?
“Semasa mudaku aku memang pernah
mendengar perguruan itu,” Ki Patih memberikan tanggapannya, “Seingatku
perguruan itu memang senang bermain-main dengan api, sesuai dengan
namanya Sapta Dhahana,” Ki Patih berhenti sejenak untuk mengumpulkan
daya ingatnya. Lanjutnya kemudian, “Kekuatan yang terpancar dari puncak
ilmu perguruan Sapta Dhahana itu, tentu tidak lepas dari kekuatan api,
entah itu berupa semburan api yang sangat panas, atau bola-bola api yang
sangat panas yang terlontar dengan kekuatan nggegirisi. Aku berharap
semua ini akan memberikan sedikit gambaran tentang kekuatan perguruan
Sapta Dhahana kepada Ki Rangga Agung Sedayu,” kembali Ki Patih berhenti
sejenak. Sambil berpaling ke arah Ki Rangga, Ki Patih pun melanjutkan
kata-katanya, “Bukankah janji Kiai Damar Sasangka itu masih berlaku Ki
Rangga?”
Ki Rangga Agung Sedayu yang mendapat
pertanyaan dari Ki Patih itu hanya dapat menundukkan kepalanya
dalam-dalam sambil menyembah. Dia segera teringat akan penuturan Kiai
Sabda Dadi yang pernah berjumpa langsung dan menerima pesan dari
pemimpin perguruan Sapta Dhahana itu. Kiai Damar Sasangka telah
memberinya waktu sebulan lebih sepuluh hari untuk menyembuhkan
luka-lukanya. Jika batas waktu itu telah tercapai, bagaimana pun keadaan
dirinya, Pemimpin perguruan di lereng gunung Tidar itu tetap akan
membunuhnya, melawan ataupun tidak melawan.
“Sampai kapan aku akan terbebas dari lingkaran dendam yang tak berkesudahan ini?” Ki Rangga hanya dapat mengeluh dalam hati.
Sejenak kemudian, ruang dalam Kepatihan
itu pun kembali sunyi. Hanya terdengar suara angin di luar gedung
Kepatihan yang bertiup kencang sehingga membuat atap gedung Kepatihan
itu berderak-derak.
“Ampun Ki Patih,” tiba-tiba Ki Waskita
berkata sambil menghaturkan sembah, “Orang yang mengaku pengikut Trah
Sekar Seda Lepen yang pernah membuat onar di kediaman Ki Gede Menoreh
itu juga mampu mengungkapkan ilmunya melalui pusaran angin bercampur
lidah api. Bahkan ketika orang itu telah menghentakkan ilmunya, yang
terpancar dari ilmunya benar-benar berupa badai api yang siap melumat
apapun yang menghalanginya.”
“Ya, aku sudah mendapat laporan tentang
itu,” sahut Ki Patih cepat, “Namun orang yang disebut Eyang Guru itu
ternyata telah melarikan diri begitu Ki Rangga hadir. Agaknya dia
ketakutan begitu melihat cambuk di tangan Ki Rangga.”
Orang-orang yang hadir di ruang itu
tersenyum mendengar kelakar Ki Patih, kecuali Ki Rangga Agung Sedayu.
Dengan cepat dia segera menghaturkan sembah sambil berkata, “Ampun Ki
Patih, yang membuat orang yang disebut Eyang Guru itu melarikan diri
adalah suara derap kaki kuda Ki Gede Menoreh dan rombongannya yang sudah
mencapai regol halaman, bukan hamba. Karena sesungguhnya hamba belum
melakukan apa-apa.”
“Engkau benar Ki Rangga,” jawab Ki Patih
sambil tersenyum penuh arti, “Bukankah engkau memang hanya berbaring
saja di tempat tidur ketika pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu membuat
ontran-ontran?”
“Ah,” desah Ki Rangga sambil menundukkan
kepala, sementara KI Waskita justru telah tertawa. Sedangkan yang lain
hanya dapat mengerutkan kening mereka dalam-dalam karena tidak tahu apa
yang maksud oleh Ki Patih.
“Bukankah Kakang Agung Sedayu masih sakit
pada waktu itu?” pertanyaan itu telah berputar-putar dalam benak Glagah
Putih. Sementara Ki Jayaraga hanya dapat menarik nafas dalam-dalam.
Sedikit banyak dia mulai dapat meraba ilmu yang sedang ditekuni oleh
kakak sepupu muridnya itu.
“Nah, sekarang aku akan memberikan tugas
kepada kalian,” berkata Ki Patih kemudian, “Sebenarnya Ki Rangga dan
Glagah Putih saja yang mendapat tugas ini langsung dari Adi Prabu
Panembahan Hanyakrawati.”
Tanpa sadar kelima orang yang menghadap Ki Patih itu telah mengangkat kepala mereka dengan jantung yang berdebaran.
“Namun atas saran Pangeran Pati, dan juga
pertimbanganku sendiri, Ki Bango Lamatan juga aku libatkan dalam tugas
ini.” Ki Patih melanjutkan penjelasannya.
Bagaikan disengat ribuan kalajengking, Ki
Rangga dan kawan-kawannya terlonjak kaget, terutama Ki Rangga Agung
Sedayu. Nama Bango Lamatan tentu saja tidak asing di telinga Ki Rangga
karena memang mereka berdua pernah bertemu. Sedangkan yang lainnya
mengenal nama itu sebagai pengikut setia Panembahan Cahya Warastra.
Serentak keempat orang itu berpaling ke
belakang, kearah seorang yang berperawakan tinggi besar dengan jambang
dan kumis yang hampir menutupi separuh wajahnya.
Sejenak Ki Rangga mengerutkan keningnya
dalam-dalam. Bango Lamatan yang dulu tidak memelihara kumis dan jambang,
namun agaknya sekarang dia lebih senang memeliharanya sehingga orang
yang pernah mengenalnya akan kesulitan untuk mengenalinya kembali.
Memang pada saat mereka berempat memasuki
ruang dalam Kepatihan beberapa saat yang lalu, di dalam ruangan itu
telah hadir seseorang yang hampir seluruh wajahnya tertutup kumis dan
jambang yang lebat. Orang itu selalu menundukkan wajahnya sehingga
wajahnya sulit untuk dikenali.
Sementara Ki Bango Lamatan yang duduk di
belakang sendiri ketika namanya disebut, hanya menundukkan kepalanya
dalam-dalam sambil menyembah tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Agaknya Ki Patih dapat membaca
wajah-wajah yang penuh tanda tanya itu. Maka katanya kemudian, “Ki Bango
Lamatan telah menyediakan dirinya untuk membela tetap tegak dan
berkibarya panji-panji Mataram di seluruh pelosok negeri ini,” Ki Patih
berhenti sebentar. Kemudian sambil berpaling ke arah Ki Bango Lamatan,
Ki Patih bertanya, “Bukankah begitu, Ki Bango Lamatan?”
Dengan penuh rasa takdim, Ki Bango Lamatan pun menyembah sambil berdesis perlahan, “Sendika Ki Patih,”
Hampir bersamaan, Ki Rangga dan
kawan-kawannya pun telah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya sesuatu
telah terjadi pada diri orang kedua di perguruan Cahya Warastra itu
setelah pasukan Panembahan Cahya Warastra dihancurkan oleh pasukan
Mataram.
“Nah, tugas kalian adalah memutus
hubungan perguruan Sapta Dhahana dengan orang yang mengaku sebagai trah
Sekar Seda Lepen itu sebelum semuanya berkembang menjadi besar,”
berkata Ki Patih kemudian yang membuat jantung kelima orang itu
tergetar. “Namun kalian tidak diijinkan membawa pasukan segelar
sepapan untuk menghancurkan perguruan itu. Carilah upadaya agar kalian
mendapatkan ikannya tanpa harus membuat keruh air di sekelilingnya.”
Jantung kelima orang itu menjadi semakin
berdebaran. Agaknya Ki Patih menghendaki cara lain dalam melumpuhkan
perguruan Sapta Dhahana dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah.
“Karena beratnya tugas ini, aku juga
mohon kepada Ki Waskita dan Ki Jayaraga untuk menemani Ki Rangga,”
berkata Ki Patih selanjutnya sambil tersenyum dan memandang ke arah
kedua orang tua itu, “Atas nama Mataram aku hanya dapat mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sungguh, aku pun
secara pribadi rasa-rasanya ingin bergabung dan mengulang kembali
masa-masa muda, menjelajahi hutan dan ngarai. Menuruni lembah dan bukit,
mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah tersentuh oleh tangan
manusia.”
Ki Waskita dan Ki Jayaraga sejenak saling
pandang. Ki Waskita lah yang kemudian menghaturkan sembah sambil
berkata, “Ampun Ki Patih, kami yang tua-tua ini sesungguhnya merasa
takut jika keberadaan kami nantinya hanya menjadi beban. Namun
sesungguhnya kami pun juga merasa sangat kesepian jika hanya duduk-duduk
saja di beranda menunggu waktu berlalu, karena memang kami tidak
mempunyai pekerjaan yang dapat mengikat kami. Sehingga jika tenaga
kami yang sudah rapuh ini memang masih dibutuhkan, kami siap untuk
membantu Ki Rangga.”
“Ah,” Ki Patih tertawa pendek, “Tenaga
Kalian berdua memang terlihat rapuh sebagaimana orang tua kebanyakan.
Namun aku yakin, Ki Waskita masih mampu membakar hutan dengan tatapan
matanya, sedangkan Ki Jayaraga masih mampu meledakkan bukit hanya
dengan ujung jarinya.”
Semua yang hadir di ruangan itu tersenyum
mendengar kelakar Ki Patih. Dengan cepat Ki Jayaraga beringsut ke depan
sambil menyembah. Katanya kemudian, “Ampun Ki Patih sebenarnya hamba
sudah dihinggapi penyakit tua, tidak bisa menunjuk ke sasaran dengan
tepat karena tangan hamba selalu gemetar. Hamba takut jika harus
meledakkan bukit kecil di sebelah istana Kepatihan ini, justru istana
ini yang akan hancur.”
“Ah,” kini semua yang hadir di ruang dalam Kepatihan itu tertawa.
“Nah,” berkata Ki Patih kemudian setelah
tawa mereka mereda, “Mataram tidak mungkin menyerang padepokan Sapta
Dhahana secara terbuka sebelum ada bukti keterlibatan mereka dalam usaha
makar yang diprakarsai oleh orang-orang yang mengaku trah Sekar Seda
Lepen. Untuk itulah aku telah mempertimbangkan masak-masak dengan
memilih cara ini. Semoga Yang Maha Agung selalu meridhoi setiap langkah
kita untuk menuju perdamaian di seluruh penjuru negeri Mataram.”
Hampir bersamaan kelima orang itu telah
menarik nafas dalam-dalam. Sebuah tugas yang memerlukan kesabaran dan
ketabahan. Selain tidak boleh menggunakan kekuatan prajurit, tidak
menutup kemungkinan di padepokan Sapta Dhahana nantinya mereka akan
menghadapi kekuatan yang jauh diluar dugaan mereka .
“Persoalan yang sedang berkembang di
gunung Tidar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Namun jauhkan kesan
keterlibatan Mataram dalam peristiwa ini sebelum ada bukti yang nyata
tentang usaha mereka untuk menggulingkan Mataram.” Titah Ki Patih
kemudian.
Demikianlah untuk beberapa saat mereka
yang berada di ruang dalam Kepatihan itu masih membicarakan masalah
seputar rencana keberangkatan mereka besuk pagi.
Ketika Ki Patih sudah merasa cukup
memberikan pengarahan kepada kelima orang itu, Ki Patih pun segera
menutup pertemuan itu dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat di
tempat yang telah disediakan.
Dalam pada itu malam hampir mencapai
puncaknya ketika kelima orang itu keluar dari ruang dalam Istana
Kepatihan. Hampir tidak ada satu pun yang mengeluarkan suara.
Masing-masing sedang tenggelam dalam angan-angan mereka sehubungan
dengan tugas yang telah diberikan oleh Ki Patih.
Ketika mereka telah tiba di halaman
samping kanan Istana Kepatihan, tiba-tiba saja Ki Bango Lamatan telah
menghentikan langkahnya. Ki Rangga dan kawan-kawannya pun segera saja
ikut menghentikan langkah mereka.
“Ki Rangga,” berkata Ki Bango Lamatan
kemudian, “Aku bermalam di Ndalem Kapangeranan. Pangeran Pati telah
berkenan menerima suwitaku untuk menjadi pengawal pribadinya.”
“Syukurlah,” berkata Ki Rangga, “Tenaga Ki Bango Lamatan sangat dibutuhkan untuk perkembangan Mataram di masa mendatang.”
“Aku hanya berusaha untuk yang terbaik,
Ki Rangga,” jawab Ki Bango Lamatan kemudian. Sementara orang-orang yang
ada di sekitarnya hanya mengangguk-angguk tanpa menanggapi sepatah kata
pun.
“Aku mohon diri,” berkata Ki Bango Lamatan kemudian.
“Silahkan, silahkan..” hampir bersamaan orang-orang yang berada di tempat itu menjawab.
Demikianlah sejenak kemudian mereka
segera berpisah menuju ke tempat masing-masing. Ki Bango Lamatan menuju
ke Ndalem Kapangeranan sedangkan Ki Rangga dan kawan-kawannya menuju ke
gandok sebelah kanan istana Kepatihan.
Namun baru saja Ki Rangga menutup pintu
biliknya, pendengarannya yang tajam telah mendengar desir langkah yang
menuju ke biliknya.
Sejenak Ki Rangga menunggu. Ketika
kemudian terdengar ketukan perlahan di pintu biliknya, dengan tanpa
meninggalkan kewaspadaan, Ki Rangga pun segera melangkah mendekati pintu
sambil bertanya, “Siapa?”
“Aku Ki Rangga, prajurit jaga dari Ndalem Kapangeranan,” terdengar jawaban seseorang dari balik pintu bilik.
KI Rangga menarik nafas dalam-dalam
sambil mengangkat pintu selarak. Sejenak kemudian dari pintu yang
terbuka muncul seorang prajurit lengkap dengan tanda jaga Ndalem
Kapangeranan.
“Ada apa?” bertanya Ki Rangga kemudian.
“Mohon maaf mengganggu istirahat Ki
Rangga,” jawab prajurit itu sambil mengangguk dalam-dalam, “Aku
diperintah Pangeran Pati untuk menjemput Ki Rangga. Pangeran Pati sedang
menunggu kehadiran Ki Rangga di Ndalem Kapangeranan.”
Sebuah desir tajam segera saja menggores
jantung Ki Rangga. Bukan masalah Pangeran Pati itu yang akan menjadi
persoalan jika dia diperintah untuk menghadap, namun keberadaan seorang
perempuan muda yang memiliki kecantikan luar biasa yang kini tinggal di
Ndalem Kapangeranan itu yang akan membebani hatinya, Rara Anjani.
“Apakah Ki Rangga sudah siap?” pertanyaan prajurit jaga itu telah menyadarkan Ki Rangga.
Sejenak Ki Rangga tanpa sadar telah
memandang tajam ke arah prajurit jaga itu. Dengan serta merta prajurit
jaga itu pun segera menundukkan wajahnya.
“Baiklah, aku sudah siap,” jawab Ki Rangga kemudian sambil melangkah keluar dan menutup pintu bilik.
Demikianlah kedua orang itu segera turun
ke halaman Istana Kepatihan yang luas. Setelah terlebih dahulu keluar
dari regol penjagaan istana Kepatihan, untuk sejenak mereka harus
menyusuri lorong yang menghubungkan istana Kepatihan itu dengan Ndalem
Kapangeranan.
Setelah melewati beberapa penjagaan yang
sangat ketat, tanpa kesulitan yang berarti Ki Rangga dan prajurit jaga
itu pun telah sampai di depan Ndalem Kapangeranan.
“Silahkan Ki Rangga,” berkata prajurit
jaga itu mempersilahkan Ki Rangga menaiki tlundak pendapa. Sementara
seorang pelayan dalam telah berdiri menunggu di ujung tangga.
“Pangeran Pati berkenan menerima Ki
Rangga di ruang dalam,” berkata pelayan dalam itu kemudian sambil
mengiringi langkah Ki Rangga menyeberangi pendapa yang luas menuju ke
pintu pringgitan.
Sejenak kemudian Ki Rangga pun telah
duduk bersila di ruang dalam. Sementara pelayan dalam yang
mengantarkannya itu dengan bergegas segera masuk ke ruang tengah untuk
melaporkan kehadiran Ki Rangga kepada Pangeran Pati.
Sambil menunggu kehadiran Pangeran Pati,
Ki Rangga Agung Sedayu harus berkali-kali menarik nafas dalam-dalam
untuk meredakan gejolak di dalam dadanya. Bayangan perempuan cantik yang
kini telah menjadi selir Pangeran Pati itu benar-benar telah
meresahkan hatinya.
“Apakah sekarang aku harus menyembah kepadanya?” di sudut hatinya yang paling dalam bertanya.
“Tentu saja engkau harus menyembah Ki
Rangga,” sudut hatinya yang lain menjawab, “Anjani yang sekarang bukan
Anjani yang dulu, perempuan kleyang kabur kanginan yang tidak mempunyai
masa depan yang jelas. Sekarang dengan gelar Rara dan menjadi selir
Pangeran Pati, semua orang harus menghormatinya, tidak terkecuali
engkau.”
“Ah,” Ki Rangga berdesah. Baginya lebih
baik menghadapi seribu musuh dengan ilmu yang ngedab-edabi sekalipun
dari pada menghadapi satu orang saja, orang yang selama ini dia merasa
bersalah karena belum dapat memenuhi janjinya.
“Dengan berkenannya Pangeran Pati
mengambil Anjani sebagai selir, janjiku kepada Anjani sudah tidak
berlaku lagi,” berkata Ki Rangga dalam hati sambil sekali lagi menarik
nafas dalam-dalam, “Namun entah mengapa, aku merasa malu bahwa pada
akhirnya Anjani telah sinengkakake ing ngaluhur dan tinggal di Ndalem Kapangeranan, sama sekali jauh dengan apa yang pernah aku janjikan, tinggal di Menoreh.”
Ketika Ki Rangga sedang asyik dengan
lamunannya, tiba-tiba saja pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan
ruang tengah terbuka. Pangeran Pati telah muncul sambil tersenyum dan
melangkah memasuki ruang dalam.
“Apakah Ki Rangga telah menungguku
terlalu lama?” bertanya Pangeran Pati itu sambil melangkah mendekat dan
mengulurkan tangannya.
Dengan cepat Ki Rangga segera bangkit
berdiri sambil menyambut uluran tangan Pangeran Pati itu. Jawab Ki
Rangga kemudian, “O, tidak Pangeran. Hamba baru saja duduk beberapa saat
ketika Pangeran telah datang.”
Pangeran Pati tersenyum sambil
mempersilahkan Ki Rangga duduk kembali. Pangeran Pati pun kemudian
mengambil tempat duduk di hadapan Ki Rangga.
Setelah sejenak menanyakan keselamatan
masing-masing, Pangeran Pati pun segera mengungkapkan tujuan yang
sebenarnya untuk memanggil Ki Rangga menghadap.
“Aku telah menitipkan Ki Bango Lamatan
kepada Eyang Buyut Mandaraka untuk menyertakan dia dalam tugas bersama
Ki Rangga,” Pangeran Pati itu berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian,
“Memang Ki Bango Lamatan telah mendapat gemblengan di pertapaan
Mintaraga beberapa saat yang lalu. Kehadirannya di sini atas perintah
dan jaminan dari Kanjeng Sunan dan aku tidak mungkin menolaknya. Untuk
itulah tugas ke gunung Tidar ini aku anggap sebagai pendadaran baginya
sebelum suwitanya di Ndalem Kapangeranan ini benar-benar aku terima.”
Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya
mendengar penjelasan Pangeran Pati. Terjawab sudah pertanyaan yang
selama ini menghantui pikirannya. Pada saat mereka berempat menghadap Ki
Patih di ruang dalam Kepatihan beberapa saat yang lalu, Ki Rangga telah
dikejutkan dengan kehadiran Ki Bango Lamatan di ruangan itu.
Namun Ki Rangga tidak berani
mempermasalahkannya. Dengan hadirnya Ki Bango Lamatan pada saat itu, Ki
Rangga sudah dapat menduga, tentu semua itu sudah menjadi tanggung jawab
Ki Patih Mandaraka.
“Bagaimana Ki Rangga? Apakah Ki Rangga berkeberatan?” pertanyaan Pangeran Pati telah membuyarkan lamunannya.
Dengan cepat Ki Rangga menghaturkan
sembah sambil menjawab, “Justru hamba menghaturkan banyak terima kasih
atas perkenan Pangeran Pati memperbantukan Ki Bango Lamatan. Tugas kami
ke gunung Tidar benar-benar cukup berat dan semoga kehadiran Ki Bango
Lamatan akan memberikan bantuan tenaga yang sangat berarti.”
Pangeran Pati mengangguk-anggukkan
kepalanya sambil tersenyum. Namun pertanyaan selanjutnya dari Putra
Mahkota itu hampir saja membuat jantung Ki Rangga terlepas dari
tangkainya.
“Ki Rangga,” berkata Pangeran Pati kemudian , “Aku ingin bertanya sesuatu sehubungan dengan Rara Anjani.”
Berdesir jantung Ki Rangga bagaikan
tersentuh ujung duri kemarung. Namun dengan cepat Ki Rangga segera
menyesuaikan dirinya. Katanya kemudian, “Ampun Pangeran, masalah apakah
yang ingin Pangeran sampaikan sehubungan dengan diri Rara Anjani?”
Sejenak Pangeran Pati termenung. Namun
sebelum Pangeran Pati menjawab pertanyaan Ki Rangga, tiba-tiba saja
pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan ruang tengah berderit dan
terbuka.
Ketika Ki Rangga kemudian berpaling, yang
muncul dari pintu ruang tengah itu adalah sesosok tubuh yang langsing
terbalut seperangkat pakaian mewah dan gemerlap, Rara Anjani.
Tertegun Ki Rangga melihat seorang
perempuan yang kecantikannya nyaris sempurna. Dalam pakaian yang paling
sederhana pun Rara Anjani sudah terlihat begitu menawan. Apalagi kini
dengan pakaian yang gemerlap penuh berhiaskan permata, Rara Anjani
benar-benar menjelma menjadi seorang Putri Raja yang kecantikannya hanya
ada dalam tulisan babat dan dongeng-dongeng.
Ki Rangga benar-benar terpesona
seolah-olah baru kali ini dia bertemu Rara Anjani. Segala gerak-geriknya
tidak luput dari pengamatan Senapati pasukan khusus yang berkedudukan
di Menoreh itu. Langkahnya yang kemudian dengan hati-hati berlutut
bertumpu pada kedua lututnya di atas lantai. Dengan cekatan namun tetap
terkesan gemulai, diturunkannya dua mangkuk minuman hangat dan beberapa
makanan dari atas nampan kayu dan kemudian dihidangkan di hadapan
mereka berdua. Sejenak kemudian Rara Anjani pun surut selangkah, berdiri
perlahan-lahan sambil membalikkan badan dan akhirnya hilang kembali di
balik pintu.
Ketika bayangan Rara Anjani telah hilang
di balik pintu yang tertutup rapat, barulah Ki Rangga Agung Sedayu
bagaikan tersadar dari sebuah mimpi yang mengasyikkan.
Dalam pada itu di ruang tengah, dengan
setengah berlari Rara Anjani segera menuju ke biliknya. Ketika dia
berpapasan dengan pelayan dapur yang sedianya bertugas mengantar minuman
dan makanan itu ke ruang dalam, nampan kayu itu pun segera
diserahkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Pelayan dapur itu menerima nampan dengan
kening berkerut. Tampak Rara Anjani begitu tergesa-gesa menyerahkan
nampan itu kepadanya sehingga tidak ada sepatah kata pun yang terucap
dari bibir yang memerah delima itu.
“Aneh,” desis pelayan itu begitu bayangan
Rara Anjani menghilang di balik pintu, “Tidak biasanya Rara Anjani
bertingkah seperti ini. Dia selalu ramah kepada siapa saja termasuk kami
para pelayan. Dan yang tak pernah lupa dari Rara Anjani adalah ucapan
terima kasih dan senyum yang tulus setiap dia meminta pertolongan kepada
siapa saja, khususnya kepada para pelayan Ndalem Kapangeranan.”
Namun pelayan Ndalem Kapangeranan yang
sudah cukup berumur itu tidak dapat menarik kesimpulan apa pun dari
peristiwa yang baru saja terjadi.
“Mungkin hati Rara sedang suntuk,” berkata pelayan itu dalam hati sambil berjalan kembali ke dapur.
Dalam pada itu sesampainya di bilik, Rara
Anjani segera menjatuhkan tubuhnya di atas pembaringan sehingga
terdengar suara kayu yang berderak-derak. Wajahnya tampak sebentar pucat
sebentar memerah. Tanpa terasa air mata telah menganak sungai dari
sudut kedua belah matanya yang terpejam rapat.
Tidak ada isak tangis. Hanya suara desah
tertahan serta nafas yang sedikit memburu. Hati Rara Anjani benar-benar
sedang didera oleh rasa kecewa.
“Mengapa aku masih tidak bisa menerima
kenyataan ini?” desahnya diantara nafas yang memburu sehingga tampak
dadanya bergelombang, ”Aku telah mencoba menyembunyikan perasaan ini
dengan mengabdikan diriku seutuhnya di Ndalem Kapangeranan. Dengan
demikian aku berharap tidak akan pernah lagi berjumpa dengan Ki Rangga.
Biarlah kenangan indah itu terkubur bersama dengan berlalunya waktu.
Namun kenyataannya, aku tetap tidak mampu melupakan Ki Rangga, orang
yang pertama kali telah menyentuh hatiku dengan segala kelebihan dan
kekurangannya. Dengan kesabaran serta keteladanan yang selama ini telah
ditunjukkannya.”
tiba-tiba Rara Anjani menjadi gelisah.
Tanpa sadar dia bangkit dan duduk di bibir pembaringan. Berkali-kali dia
berusaha menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan gejolak di dalam
dada sambil menyeka air mata yang membasahi kedua pipinya dengan ujung
bajunya.
“Sengaja aku mengenakan pakaian yang
indah ini agar Ki Rangga menjadi silau dan tidak punya keberanian untuk
menatapku,” berkata Rara Anjani kemudian sambil matanya menerawang ke
langit-langit bilik, “Aku ingin menunjukkan kepada Ki Rangga bahwa
ternyata yang aku dapatkan jauh lebih baik dari apa yang dijanjikannya.
Namun ternyata Ki Rangga tidak menjadi silau dan menundukkan kepalanya.
Dia justru telah menatapku dengan tatapan mata seperti pertama kali
kita bertemu. Tatapan yang memancarkan cahaya penuh kekaguman, penuh
kedamaian serta penuh harapan namun yang ternyata telah membuatku salah
paham.”
Kembali Rara Anjani menarik nafas
panjang. Sambil membetulkan letak sanggulnya kembali dia berkata dalam
hati, “Sebenarnyalah hati kecilku tidak mampu untuk membenci Ki Rangga.
Apa yang ingin aku pamerkan di hadapan Ki Rangga justru telah melukai
hatiku sendiri.”
Untuk beberapa saat Rara Anjani masih
merenungi dirinya. Tiba-tiba saja sebuah gagasan menyelinap di dalam
benaknya dan membuat Rara Anjani tersenyum.
“Aku akan melakukannya,” desisnya
kemudian sambil bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke geledek
kayu jati berukir indah yang terletak di sudut bilik.
Dalam pada itu di ruang dalam,
sepeninggal Rara Anjani, Pangeran Pati yang sedari tadi selalu mengikuti
gerak gerik Ki Rangga telah menahan senyumnya. Katanya kemudian, “Ki
Rangga, Rara Anjani telah banyak bercerita tentang diri Ki Rangga,”
Pangeran Pati itu berhenti sejenak sambil mengamati perubahan yang
terjadi pada wajah Ki Rangga. Namun Ki Rangga tampak hanya diam membisu.
Maka kata Pangeran Pati kemudian, “Rara Anjani mengaku telah ditolong
oleh Ki Rangga dari cengkeraman kedua gurunya yang jahat.”
Sampai disini Ki Rangga masih diam
membisu sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia belum dapat
menebak ke arah mana pembicaraan Putra Mahkota itu.
“Rara Anjani juga bercerita tentang janji Ki Rangga untuk membawanya ke Menoreh,” berkata Pangeran Pati selanjutnya.
Sampai disini jantung Ki Rangga
benar-benar bagaikan ditusuk ujung duri kemarung. Sejenak dada Senapati
pasukan khusus yang berkedudukan di Menoreh itu menjadi pepat bagaikan
tertindih berbongkah-bongkah batu padas yang berguguran dari lereng
bukit.
Akhirnya setelah menarik nafas
dalam-dalam terlebih dahulu untuk meredakan gejolak di dalam dadanya,
barulah Ki Rangga menjawab sambil menyembah, “Ampun Pangeran. Jika
diperkenankan, hamba akan menjelaskan tentang Rara Anjani dalam
hubungannya dengan hamba.”
Pangeran Pati mengerutkan keningnya.
Tampak Putra Mahkota itu sedikit ragu-ragu. Namun katanya kemudian, “Ki
Rangga, bukan maksudku untuk mengungkit masa lalu Rara Anjani. Aku sudah
menerima dia sebagaimana adanya,” Pangeran Pati itu berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian, “Yang sebenarnya ingin aku sampaikan kepada Ki
Rangga adalah kesetiaannya kepada Mataram. Rara Anjani adalah bekas
murid perguruan Tal Pitu yang dengan jelas telah berpihak pada Kadipaten
Panaraga pada saat pemberontakan Pamanda Jayaraga. Apakah Rara Anjani
dapat dipercaya atas kesetiaannya kepada Mataram?”
Untuk beberapa saat Ki Rangga justru
telah membeku. Dia tidak pernah menduga bahwa arah pembicaraan Pangeran
Pati itu justru telah mengarah kepada peran kedua guru Rara Anjani pada
saat terjadi pemberontakan Adipati Panaraga.
“Ampun Pangeran,” jawab Ki Rangga pada
akhirnya setelah gelora di dalam dadanya sedikit mereda, “Hamba memang
telah terlibat perang tanding dengan kedua guru Rara Anjani, Goh Muka
dan Roh Muka. Kedua orang guru Rara Anjani itu adalah murid dari
perguruan Tal Pitu. Mereka menuntut kematian guru mereka, Ajar Tal
Pitu.”
Pangeran Pati mengangguk-anggukkan
kepalanya. Katanya kemudian, “Rara Anjani telah bercerita kepadaku
tentang perang tanding itu,” Pangeran Pati berhenti sejenak. Lanjutnya
kemudian, “Bukankah Ki Rangga telah mengajukan syarat Rara Anjani
sebagai taruhannya?”
“Hamba Pangeran,” jawab Ki Rangga, “Hamba
mempunyai panggraita bahwa kedua guru Rara Anjani itu pada akhirnya
pasti akan berbuat curang dengan mengeroyok hamba. Padahal perjanjian
perang tanding itu hanya dengan salah satu dari mereka. Untuk itulah
hamba berusaha memancing kemarahan mereka dengan mengajukan syarat Rara
Anjani sebagai taruhannya.”
“Dan ternyata Ki Rangga lah yang keluar sebagai pemenang,” sahut Pangeran Pati cepat.
Berdesir dada Ki Rangga mendengar ucapan
Pangeran Pati itu. Namun dengan cepat Ki Rangga segera menghilangkan
segala syak wasangka dengan menjawab, “Sendika Pangeran. Atas
pertolongan dan dikabulkannya doa hamba kepada Yang Maha Agung, hamba
masih diberi keselamatan sampai saat ini.”
Pangeran Pati sejenak menarik nafas
dalam-dalam sambil mengangguk-angguk kecil. Setelah terdiam beberapa
saat, barulah Pangeran Pati mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat
jantung Ki Rangga berpacu kencang kembali.
“Bagaimanakah selanjutnya nasib Rara Anjani? Apakah Ki Rangga jadi membawanya ke Menoreh?”
“Ampun Pangeran,” jawab Ki Rangga sambil
beringsut dari duduknya setapak, “Setelah kedua gurunya tewas,
sebenarnya hamba mengira Rara Anjani akan bela pati, namun ternyata Rara
Anjani merasa bersyukur telah terbebas dari cengkeraman kedua gurunya,”
Ki Rangga berhenti sejenak untuk sekedar membasahi kerongkongannya yang
tiba-tiba saja menjadi kering. Lanjutnya kemudian, “Mohon beribu ampun
Pangeran, setelah mengetahui keadaan Rara Anjani yang sebenarnya, hamba
telah memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih sendiri masa depannya
dengan pertimbangan bahwa Rara Anjani sama sekali tidak terlibat
dengan pemberontakan di Panaraga.”
Kembali calon pewaris tahta Mataram itu
mengangguk-angguk mendengar penjelasan Ki Rangga. Namun pertanyaan
selanjutnya telah membuat jantung Ki Rangga yang sudah agak tenang itu
melonjak-lonjak kembali.
“Menurut pengakuan Rara Anjani, dia lebih
memilih mengikuti Ki Rangga ke Menoreh,” berkata Pangeran Pati
selanjutnya, “Apakah keberatan Ki Rangga yang sebenarnya jika Rara
Anjani memang berkeinginan untuk menjadi bagian dari keluarga Ki Rangga
di Menoreh?”
Sampai disini Ki Rangga benar-benar tidak
mampu untuk menjawab. Berbagai pertimbangan memang bergolak di dalam
dadanya dan ingin disampaikan kepada Pangeran Pati. Namun hati kecilnya
telah mencegahnya. Ki Rangga merasa lebih baik diam saja dan menunggu
titah dari Pewaris Mataram itu.
Melihat Ki Rangga hanya diam termangu
tanpa menjawab pertanyaannya, Pangeran Pati pun maklum, tentu ada
sesuatu yang menyebabkan Ki Rangga tidak mampu menjawab pertanyaannya.
Untuk beberapa saat suasana di ruang
dalam Ndalem Kapangeranan itu menjadi sepi. Di luar lamat-lamat
terdengar kentongan ditabuh dengan nada dara muluk, menunjukkan malam
telah sampai ke puncaknya.
“Sudahlah Ki Rangga,” berkata Pangeran
Pati kemudian, “Malam sudah semakin larut dan Ki Rangga harus
beristirahat untuk mempersiapkan perjalanan besok pagi,” Pangeran Pati
itu berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian “Aku mengerti jalan pikiran Ki
Rangga. Memang untuk sebagian laki-laki, dengan mudahnya mereka akan
mengambil selir tanpa rasa ewuh pekewuh. Namun bagi Ki Rangga
mungkin akan sangat sulit untuk membagi cinta dengan perempuan lain.
Tapi percayalah Ki Rangga, menyia-nyiakan sebuah cinta dan harapan yang
tulus dari seorang perempuan adalah termasuk sebagian dari dosa, jika
kita tidak mampu menjelaskannya secara bijak. Dan semua itu akan
menjadi sebuah penyesalan yang tiada akhirnya sepanjang kehidupan kita
nantinya.”
Kalimat demi kalimat dari Pangeran Pati
itu satu demi satu bagaikan ujung sebuah pisau bermata rangkap yang
terhunjam ke jantungnya perlahan-lahan. Menimbulkan rasa sakit dan pedih
yang tak terperikan.
“Ki Rangga,” berkata Pangeran Pati
kemudian begitu melihat Ki Rangga hanya diam termangu, “Kesalahan yang
kadang tidak kita sadari adalah, memberi harapan yang berlebih padahal
kita hanya berusaha menjalin sebuah tali persaudaraan. Semua itu harus
dijelaskan secara bijak agar tidak terjadi kesalah-pahaman di kemudian
hari,” Pangeran Pati berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Dalam hal
Rara Anjani, aku tidak bisa menyalahkan dia karena janji yang
disampaikan Ki Rangga sudah jelas. Jika Ki Rangga keluar sebagai
pemenang dalam perang tanding itu, Ki Rangga akan membawanya ke Menoreh.
Semua orang pasti paham dengan maksud yang terkandung dalam janji itu.
Tidak mungkin dengan membawa Rara Anjani ke Menoreh kemudian Ki Rangga
akan menempatkannya di sembarang tempat, di gardu peronda atau di banjar
padukuhan misalnya. Semua orang tentu maklum bahwa Ki Rangga secara
tidak langsung telah berjanji untuk mengambil Rara Anjani sebagai
istri.”
Jika saja ada guntur yang meledak di
langit saat itu, tentu Ki Rangga tidak akan sekaget mendengar kata-kata
pewaris Mataram itu. Betapa penyesalan telah merajam hatinya atas
keterlanjuran sikapnya ketika menghadapi perang tanding dengan murid
perguruan Tal Pitu itu. Seharusnya dia tidak perlu mengikut-sertakan
Rara Anjani sebagai persyaratan dalam perang tanding itu.
Namun semua itu sudah menjadi masa lalu,
dan kini Rara Anjani telah menjadi selir pangeran Pati. Maka jawab Ki
Rangga kemudian sambil menyembah dalam-dalam, “Mohon ampun Pangeran,
semua itu memang salah hamba. Hamba tidak mengira bahwa tanggapan Rara
Anjani menjadi begitu dalam atas persyaratan yang hamba minta dalam
perang tanding itu. Namun hamba kira semuanya kini telah berlalu dan
Rara Anjani telah hidup berbahagia di Ndalem Kapangeranan.”
“Siapa bilang Rara Anjani telah hidup
berbahagia?” sergah Pangeran Pati itu sedikit keras, “Aku mengambilnya
menjadi selirku karena aku tidak tahu dengan gamblang latar belakangnya.
Demikian juga Rara Anjani, dia menerima pinanganku dengan harapan untuk
membuka lembaran baru,” Pangeran Pati berhenti sejenak. Lanjutnya
kemudian, “Namun seiring dengan berlalunya waktu, aku sering melihat
Rara Anjani termenung berlinang air mata di malam-malam yang sunyi.
Kadang aku memergoki Rara Anjani hampir seharian duduk di taman Ndalem
Kapangeranan tanpa berbuat apa-apa, hanya berlinang air mata dengan
tatapan mata yang kosong menerawang ke kejauhan.”
Kali itu jantung Ki Rangga bagaikan
sebuah belanga yang jatuh di atas tanah berbatu-batu, hancur
berkeping-keping tak berbentuk lagi.
“Sudahlah Ki Rangga. Bukan maksudku
mengungkit masa lalu kalian berdua. Namun aku di sini merasa ikut
bertanggung-jawab atas masa depan Rara Anjani. Jujur saja, aku ingin
melihat Rara Anjani meraih kebahagiaan yang diimpikannya. Demikian juga
aku harap Ki Rangga menjadi laki-laki yang tangguh tanggon bukan hanya
dalam hal olah kanuragan jaya kawijayan saja, namun juga kuat dalam
menjalani kehidupan bebrayan khususnya dalam membina sebuah keluarga.”
Ki Rangga masih terdiam belum berusaha menjawab. Hatinya telah teraduk-aduk oleh perasaan bersalah.
“Sekarang aku akan memberitahu Ki Rangga,
tentang rencanaku sehubungan dengan masa depan Rara Anjani” berkata
Pangeran Pati kemudian tanpa memperdulikan Ki Rangga yang terlihat
semakin gelisah, “Rara Anjani sekarang sedang mendapat karunia dari Yang
Maha Agung untuk mengemban amanahNYA. Dalam beberapa bulan kedepan jika
Yang Maha Agung mengijinkan, Rara Anjani akan segera melahirkan anakku,
darah dagingku.”
Entah sudah untuk ke berapa kalinya
jantung Ki Rangga terkoyak-koyak. Namun senapati pasukan khusus itu
tetap bertahan dalam kediamannya.
“Setelah anakku lahir, aku akan
memberikan kebebasan kepada Rara Anjani,” berkata Pangeran Pati
selanjutnya yang membuat dada Ki Rangga semakin berdebar-debar. Lanjut
Pangeran Pati kemudian, “Jika Rara Anjani merasa tidak bahagia tinggal
di Ndalem Kapangeranan, aku akan menawarkan kepadanya untuk menjadi
Putri Triman.”
Jantung Ki Rangga kali ini benar-benar
meledak. Gemuruhnya terasa sampai ke dasar hatinya yang paling dalam.
Sejenak nafas kakak sepupu Glagah Putih itu bagaikan tersumbat. Dia
menyadari sepenuhnya, siapakah yang akan menerima Rara Anjani itu
nantinya sebagai Putri Triman.
“Yang akan mendapat kehormatan menerima
Putri Triman itu nantinya adalah seorang Tumenggung,” berkata Pangeran
Pati selanjutnya yang membuat Ki Rangga terlonjak. Tanpa sadar Ki Rangga
pun telah mengangkat wajahnya. Sementara Pangeran Pati pun segera
melanjutkan kata-katanya, “Seorang Tumenggung yang bergelar Tumenggung
Ranakusuma, yang mengandung makna bunga peperangan, karena selama ini
namanya selalu harum di setiap medan pertempuran.”
Untuk beberapa saat Ki Rangga justru
telah diam membeku. Dia tidak mengerti akan arah pembicaraan Pangeran
Pati. Sedangkan Pangeran Pati justru telah tersenyum melihat Ki Rangga
yang kebingungan itu.
“Penerimaan Putri Triman itu nantinya
akan digelar bersamaan dengan wisuda kenaikan pangkat seorang prajurit
yang berpangkat Rangga. Atas jasa-jasanya selama ini dalam menegakkan
panji-panji Mataram, dia akan dianugrahi pangkat menjadi Tumenggung
dengan gelar Tumenggung Ranakusuma.”
Dengan dada yang berdebaran Ki Rangga
mencoba memandang ke arah Pangeran Pati. Kali ini agaknya Pangeran Pati
sudah tidak sampai hati untuk berteka teki. Maka katanya kemudian, “Ki
Rangga, sudah menjadi ketetapan Ayahanda Prabu Hanyakrawati dan juga
atas saran Eyang Buyut Patih Mandaraka, sudah waktunya pasukan khusus
yang berkedudukan di Menoreh dipimpin oleh seorang Tumenggung, dan Ki
Rangga akan segera diwisuda menjadi Tumenggung dengan gelar Tumenggung
Ranakusuma.”
Kali ini sekujur tubuh Ki Rangga terasa
dingin bagaikan diguyur banyu sewindu. Bahkan seluruh persendiannya
bagaikan terlepas satu-persatu. Ki Rangga benar-benar tidak menduga
bahwa dirinya akan mendapat anugrah diwisuda menjadi seorang Tumenggung.
Namun yang paling mendebarkan dari semua peristiwa yang rencananya akan
dilaksanakan beberapa bulan ke depan itu adalah hadiah Putri Triman
itu.
“Ki Rangga.” berkata Pangeran Pati
selanjutnya, “Nama Tumenggung Ranakusuma itu adalah pilihan Ayahanda
Prabu Hanyakrawati sendiri. Apakah Ki Rangga mempunyai pilahan gelar
tersendiri?”
Kalimat terakhir dari Pangeran Pati itu
barulah membangunkan Ki Rangga dari mimpi panjangnya. Dengan
merangkapkan kedua tangannya yang gemetar, Ki Rangga pun segera
menghaturkan sembah sambil menjawab, “Mohon beribu ampun Pangeran. Hamba
hanya dapat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Hamba tidak
pernah bermimpi untuk menjadi seorang Tumenggung.”
“Bagaimana dengan Putri Triman itu?” bertanya Pangeran Pati kemudian dengan serta merta.
Untuk sesaat lidah Ki Rangga bagaikan
kelu. Namun Ki Rangga segera menyadari bahwa titah seorang Pangeran Pati
tidak mungkin ditolak. Maka jawabnya kemudian sambil menyembah dan
membungkuk dalam-dalam, “Hamba akan menjunjung tinggi setiap titah dari
paduka Pangeran Pati Mataram.”
“Ngger,” berkata ki Waskita kemudian begitu mereka berdua telah duduk bersila kembali di ruang dalam, “Sedari tadi aku merasakan sepertinya ada sebuah kegelisahan yang sedang membebani pikiranmu.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam sambil membetulkan letak duduknya. Jawabnya kemudian dengan setengah berbisik, “Ki Waskita, aku mempunyai firasat, sepertinya orang itu akan kembali lagi.”
Ki Waskita mengerutkan keningnya. Juga sambil berbisik, Ki Waskita pun kemudian bertanya, “Mengapa angger mempunyai dugaan seperti itu?”
“Entahlah Ki Waskita,” jawab Ki Rangga sambil menggeleng perlahan, “Namun ada baiknya jika aku mencoba untuk melacak keberadaannya lagi.”
“Ya, ngger,” sahut Ki Waskita cepat, “Mumpung malam masih panjang. Sebaiknya angger mengetrapkan aji pengangen-angen untuk melacak keberadaan orang itu.”
Untuk sejenak Ki Rangga tertegun. Tanyanya kemudian, “Apakah itu perlu Ki Waskita?”
“Ya ngger,” jawab Ki Waskita mantap, “Dengan demikian angger tidak hanya melacak keberadaan pembunuh itu, namun jika memungkinkan angger sekalian dapat melumpuhkannya.”
Sejenak Ki Rangga termangu-mangu. Mengetrapkan aji pengangen-angen bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pemusatan nalar dan budi sampai ke titik yang tertinggi. Selain itu, selama Ki Rangga dalam puncak semedinya, raganya akan sangat lemah, selemah selembar daun yang tergeletak di atas tanah.
Agaknya Ki Waskita dapat membaca keragu-raguan Ki Rangga. Maka katanya kemudian sambil tersenyum, “Jangan khawatir, ngger. Selama engkau dalam puncak samadimu, aku akan menjaga ragamu dengan taruhan nyawaku sendiri.”
Ki Rangga tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
Demikianlah, sejenak kemudian Ki Rangga segera membaringkan dirinya di atas tikar yang terbentang di tengah-tengah ruangan itu. Kedua tangannya segera bersilang diatas dada. Beberapa saat kemudian, terdengar aliran nafas Ki Rangga semakin lama semakin halus dan pelan. Ki Rangga pun telah memasuki puncak samadinya. Sementara Ki Waskita dengan sabar dan penuh kewaspadaan duduk bersila berjaga di samping Ki Rangga.
Dalam pada itu, begitu hujan reda, seseorang tampak bangkit dari duduknya di bawah sebatang pohon yang rindang. Pohon itu terletak di pinggir jalan menuju banjar padukuhan. Kira-kira diperlukan waktu sepemakan sirih untuk berjalan dari tempat itu sampai ke banjar padukuhan Klangon.
“Semoga saja berita yang aku terima dari Raden Wirasena itu benar,” berkata orang itu dalam hati sambil menegakkan tubuhnya. Ditengadahkan wajahnya untuk melihat langit yang kelam. Lanjutnya kemudian, “Salah satu dari kelima orang yang bermalam di banjar itu adalah Senapati pasukan khusus Mataram yang berkedudukan di Menoreh, Ki Rangga Agung Sedayu.”
Untuk beberapa saat orang itu tampak termenung. Dilemparkan pandangan matanya ke kejauhan yang tampak hitam kelam tanpa batas.
“Jika apa yang aku dengar selama ini memang benar, tentu orang yang bernama Ki Rangga Agung Sedayu itu pasti mengetahui kehadiranku beberapa saat tadi,” gumam orang itu kemudian sambil melangkahkan kakinya, “Namun jika apa yang diberitakan orang-orang selama ini ternyata terlalu dilebih-lebihkan, agul-agulnya Mataram itu pasti akan kebingungan mendapatkan orang di balik dinding itu tiba-tiba saja sudah tak bernyawa.”
Sambil mengayunkan langkahnya, tampak bibir orang itu menyunggingkan sebuah senyuman, senyum yang menandakan kemenangan yang seolah-olah sudah berada di dalam genggaman tangannya.
“Tidak perlu Raden Wirasena sendiri yang turun tangan,” kembali orang itu berangan-angan, “Cukup Ki Kebo Mengo yang akan mrantasi semua penghalang.”
Namun tiba-tiba panggraita orang yang bernama Ki Kebo Mengo itu merasakan akan kehadiran seseorang di tempat itu.
Dengan segera dia menghentikan langkahnya. Dalam sekejap Ki Kebo Mengo telah memusatkan nalar dan budinya dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Sejenak kemudian, panggraitanya telah menangkap bayangan seseorang yang sedang berdiri melekat pada sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan hanya beberapa langkah saja dari tempatnya berdiri.
“Keluarlah Ki Sanak,” berkata Ki Kebo Mengo kemudian dengan suara yang berat dan dalam sambil mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada, “Tidak ada gunanya Ki Sanak bersembunyi lagi. Aku tidak pernah mengampuni para pengecut yang beraninya hanya main petak umpet. Aku lebih senang membunuh dari pada berbantah yang tidak ada ujung pangkalnya.”
Namun jantung Ki Kebo Mengo itu bagaikan tersulut bara api dari tempurung kelapa. Bayangan yang melekat pada sebatang pohon itu sama sekali tidak bergerak. Seakan-akan tidak menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Ki Kebo Mengo.
“Hem,” geram Ki Kebo Mengo sambil berusaha menajamkan pandangan matanya. Untuk beberapa saat Ki Kebo Mengo menjadi ragu-ragu sendiri dengan pengamatannya.
“Siapa berani mempermainkan Ki Kebo Mengo, he?!” teriak Ki Kebo Mengo dengan suara menggelegar. Untunglah jalan yang menuju ke banjar padukuhan itu keadaannya sangat sepi. Beberapa rumah letaknya berjauhan serta tempat Ki Kebo Mengo berhenti itu adalah tanah kosong yang membujur sepanjang jalan dan belum didirikan sebuah bangunan pun di atasnya.
Ketika melihat bayangan itu sama sekali tidak bergerak, Ki Kebo Mengo menjadi gusar. Dengan segera diayunkan langkahnya mendekat.
Ketika jarak Ki Kebo Mengo dengan pohon tempat bayangan itu berdiri tinggal tiga langkah, tiba-tiba bayangan itu hilang begitu saja bagaikan sinar sebuah dlupak yang padam karena tertiup angin kencang.
“Iblis!” teriak Ki Kebo Mengo sambil meloncat ke depan. Tangannya terayun deras menghantam batang pohon sebesar pelukan orang dewasa itu.
Akibatnya adalah sangat dahsyat. Pohon itu memang tetap berdiri tegak, hanya batangnya saja yang tampak bergetar hebat. Namun seluruh daun-daunnya telah rontok dan berguguran jatuh ke tanah bagaikan baru saja dilanda angin puting beliung.
“Aji rog-rog asem,” tiba-tiba terdengar suara perlahan beberapa langkah saja di belakang Ki Kebo Mengo yang sedang asyik menikmati hasil kedahsyatan ilmunya.
Bagaikan disengat seribu kalajengking, Ki Kebo Mengo pun terlonjak kaget. Dengan cepat dia segera memutar tubuhnya. Tampak seseorang yang berperawakan sedang namun tegap telah berdiri beberapa langkah saja di hadapannya.
Sejenak Ki Kebo Mengo bagaikan membeku di tempatnya, namun itu hanya sekejap. Sesaat kemudian terdengar tawanya yang berderai-derai memecah kesunyian malam.
“O, alangkah sombongnya,” katanya kemudian disela-sela suara tertawanya, “Seseorang telah dengan deksura mencoba mempermainkan Ki Kebo Mengo. Hanya orang-orang yang mempunyai nyawa rangkap tujuh sajalah, yang berani mempermainkan Ki Kebo Mengo.”
Namun jawaban bayangan itu justru sangat menyakitkan. Berkata bayangan itu kemudian, “Ki Sanak benar, aku memang mempunyai nyawa rangkap tujuh. Namun aku hanya memerlukan satu nyawa saja untuk menangkap orang yang bernama Kebo Mengo.”
“Tutup mulutmu!” bentak Ki Kebo Mengo dengan muka merah padam, “Jangan hanya bersembunyi di balik bayangan semu, tidak akan ada artinya bagiku. Keluarlah, kita akan bertempur secara jantan.”
Namun jawaban bayangan itu kembali terdengar menyakitkan di telinga Ki Kebo Mengo, “Sudah aku katakan Ki Sanak, aku hanya memerlukan satu nyawa saja untuk menangkap Ki Kebo Mengo, dan inilah yang aku sebut dengan satu nyawaku itu. Aku tidak perlu menghadirkan wadagku untuk sekedar menangkap seekor kerbau!”
“Gila!” kembali Ki Kebo Mengo membentak, “Untuk apa aku melayani sebuah bayangan semu yang tak berarti? Aku tahu Ki Sanak sedang bersembunyi di sekitar tempat ini dan aku akan menemukanmu. Hanya membutuhkan waktu tidak lebih lama dari mijet wohing ranti untuk menemukan persembunyianmu.”
Selesai berkata demikian Ki Kebo Mengo segera menyilangkan kedua tangannya di depan dada sambil menundukkan wajahnya. Namun yang terjadi kemudian adalah sangat mengejutkan Ki Kebo Mengo itu sendiri. Panggraitanya telah menemukan getaran orang yang dicarinya itu berada tidak jauh di hadapannya.
“Hem!” geram Ki Kebo Mengo sambil mengurai kedua tangan dan mengangkat wajahnya. Dipandangi bayangan semu yang berdiri beberapa langkah di hadapannya itu dengan raut wajah yang terheran-heran. Menurut panggraitanya, yang berdiri di hadapannya sekarang ini bukanlah hanya sebuah bayangan semu belaka, namun benar-benar seseorang dalam ujud yang sebenarnya.
“Aneh,” berkata Ki Kebo Mengo dalam hati, “Seumur hidup aku belum pernah menjumpai ilmu sejenis ini. Namun aku yakin, sebenarnya ini hanya sejenis ilmu untuk bersembunyi sebagaimana ilmu halimunan atau sejenisnya. Aku pasti akan dapat menemukan kelemahannya.”
Berpikir sampai disitu, Ki Kebo Mengo segera maju selangkah. Katanya kemudian, “Baiklah Ki Sanak, kita akan bertempur. Aku tidak peduli lagi berapa nyawa yang akan Ki Sanak pergunakan untuk melawanku. Namun yang jelas, aku telah mengetahui kelemahan ilmumu ini, sebuah ilmu untuk bersembunyi. Di mana pun Ki Sanak bersembunyi, aku pasti akan menemukannya.”
Bayangan itu tampak menarik nafas dalam-dalam. Entah apa yang sedang ada dalam benaknya. Namun yang jelas bayangan itu segera mundur selangkah sambil berkata, “Ki Kebo Mengo, sebenarnya aku bukan orang yang suka dengan keributan. Aku menghadang Ki Kebo Mengo di tempat ini hanya untuk menuntut pertanggung-jawaban Ki Kebo Mengo atas rajapati yang baru saja terjadi.”
Terkejut Ki Kebo Mengo mendengar ucapan bayangan itu. Sebenarnya bukan kebiasaan Ki Kebo Mengo untuk berlama-lama berbantah. Dia tidak peduli siapa orang yang akan dibunuhnya dan atas dasar apa dia melakukan pembunuhan itu. Baginya membunuh itu memang sudah menjadi kebiasaan dan kadang cukup menyenangkan. Namun bayangan itu telah menyebut rajapati yang baru saja terjadi. Dengan demikian Ki Kebo Mengo dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang sekarang berdiri di hadapannya itu, apapun bentuknya tentulah salah satu dari orang yang sedang bermalam di banjar padukuhan Klangon.
Maka dengan suara berat dan dalam, Ki Kebo Mengo pun kemudian berdesis, “Apakah aku sedang berhadapan dengan agul-agulnya Mataram Ki Rangga Agung Sedayu?”
Bayangan itu sejenak termangu-mangu. Ada sedikit keseganan untuk menyebut namanya. Justru karena dia selalu berusaha menghindari kesan yang berlebihan jika seseorang mengetahui jati dirinya.
Namun akhirnya bayangan itu tampak menganggukkan kepalanya.
Berdesir dada Ki Kebo Mengo begitu menyadari sekarang ini dia sedang berhadapan dengan agul agulnya Mataram, walaupun hanya dalam bentuk ujud semu.
“Ujud semu tidak akan mempunyai pengaruh apapun selain menyesatkan pandangan sehingga penalaran pun akan menjadi buram,” berkata Ki Kebo Mengo dalam hati, “Ilmu ini sebenarnya tidak lebih dari permainan kanak-kanak. Manakala aku mampu memecahkan rahasianya, aku akan dapat menemukan tempat persembunyiannya dan sekaligus menghancurkannya.”
Ketika keyakinan itu mulai tumbuh di dalam hatinya, Ki Kebo Mengo pun mulai menggeser kedudukannya, siap untuk melancarkan serangan penjajagan.
Namun tiba-tiba sepercik keragu-raguan muncul kembali di dalam dadanya.
“Bayangan semu tidak akan mampu melukai dan dilukai. Jadi untuk apa aku harus bertempur melawan bayangan semu?” tiba-tiba pertanyaan itu menyelinap di dalam hatinya.
Untuk beberapa saat Ki Kebo Mengo justru hanya berdiri termangu-mangu. Berbagai pertimbangan bergolak di dalam dadanya.
“O,” gumam Ki Kebo Mengo dalam hati. Akhirnya sebuah kesadaran rasa-rasanya telah mengencerkan otaknya yang beku, “Aku tahu maksud Ki Rangga dengan menampilkan bayangan semunya ini. Ki Rangga berharap aku terpancing untuk bertempur sampai tenagaku terkuras habis. Pada saat itulah ujud aslinya akan muncul dan kemudian menangkapku dengan sangat mudahnya.”
Sejenak Ki Kebo Mengo menarik nafas dalam-dalam. Kesimpulan terakhir ini agaknya yang masuk akal. Namun jika memang demikian keadaannya, yang dapat dilakukannya hanyalah menunggu kemunculan ujud asli lawannya.
“Lebih baik aku meneruskan perjalananku ke banjar padukuhan,” berkata Ki Kebo Mengo dalam hati, “Jika aku tidak mampu menemukan persembunyian Ki Rangga di sekitar tempat ini, kemungkinannya dia telah mampu melontarkan ilmu bayangan semunya itu dari jarak jauh, dari banjar padukuhan Klangon.”
Berpikir sampai disitu, tanpa menghiraukan ujud semu lawannya, Ki Kebo Mengo pun segera mengayunkan langkahnya meninggalkan tempat itu.
“Ki Kebo Mengo,” tiba-tiba saja terdengar suara bayangan itu memanggilnya, “Berhentilah! Urusan kita belum selesai. Mengapa engkau begitu tergesa-gesa pergi?”
Namun Ki Kebo Mengo tidak menjawab, bahkan berpaling pun tidak. Tekadnya sudah bulat untuk tidak melayani permainan lawannya. Tujuannya hanya satu, segera sampai di banjar padukuhan Klangon dan membuat perhitungan dengan ujud asli Ki Rangga Agung Sedayu.
“Ki Kebo Mengo!” kembali terdengar bayangan itu berteriak memanggilnya, kali ini lebih keras, “Berhentilah atau aku akan menghentikanmu dengan caraku!”
Namun Ki Kebo Mengo benar-benar sudah bulat tekadnya untuk segera menyingkir dari tempat itu. Dia benar-benar sudah muak dengan permainan yang disangkanya hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang baru saja belajar loncat-loncatan dalam olah kanuragan.
Ketika melihat Ki Kebo Mengo sama sekali tidak mempedulikannya. Dengan sebuah teriakan peringatan, bayangan itu melesat menghantam punggung Ki Kebo Mengo.
Ki Kebo Mengo terkejut bukan buatan ketika merasakan ada sebuah sambaran angin yang cukup deras mengarah ke punggung. Namun semua itu sudah terlambat bagi ki Kebo Mengo untuk memutar tubuh. Yang mampu dilakukan oleh ki Kebo Mengo kemudian adalah dengan tergesa-gesa mengetrapkan ilmu pertahanan dirinya, walaupun tidak sempat sampai ke puncak untuk melindungi punggungnya.
Benturan yang terjadi kemudian memang tidak terlalu keras. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Ki Rangga hanyalah sebatas pengetahuan bagi lawannya, bahwa ujud semu yang sedang dihadapinya bukanlah ujud semu sebagaimana biasanya.
Yang terdengar kemudian adalah sebuah umpatan yang sangat kotor dari mulut Ki Kebo Mengo. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan, walaupun tidak sampai terjatuh. Namun kenyataan yang dihadapinya itulah yang telah membuat jantungnya hampir meledak. Ternyata bayangan semu Ki Rangga mempunyai kemampuan sebagaimana ujud wadag aslinya, mampu menyentuh bahkan melukai sasarannya.
Begitu pengaruh tenaga lontaran lawannya itu telah menghilang, dengan cepat Ki Kebo Mengo berbalik. Sejenak dipandanginya ujud semu Ki Rangga yang hanya berdiri beberapa langkah saja di hadapannya.
“Sebuah ilmu iblis!” geram Ki Kebo Mengo sambil menahan gejolak di dalam dadanya, “Dari mana engkau dapatkan ilmu iblis itu, he?!”
“Sudahlah Ki Kebo Mengo,” jawab bayangan itu, “Bukankah engkau tadi sudah mengatakan tidak suka berbantah? Menyerahlah. Engkau akan aku hadapkan kepada Ki Jagabaya dukuh Klangon untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatanmu.”
“Diam..!” bentak Ki Kebo Mengo dengan raut wajah merah padam, “Tidak seorang pun yang akan mampu menangkap Ki Kebo Mengo, agul-agulnya Mataram pun tidak. Apalagi ki Jagabaya dukuh Klangon. Bersiaplah Ki Rangga, aku akan segera menemukan kelemahan ilmumu. Dan disaat itulah harapanmu untuk menghirup udara esok pagi sudah tidak ada lagi.”
Selesai berkata demikian, tanpa didahului oleh sebuah ancang-ancang, Ki Kebo Mengo begitu saja melontarkan tubuhnya menerjang bayangan semu Ki Rangga.
Namun alangkah terkejutnya Ki Kebo Mengo begitu mendapatkan bayangan lawannya sama sekali tidak bergerak untuk menghindar. Serangannya yang berlandaskan pada kekuatan penuh itu menembus bayangan lawannya bagaikan menerjang angin saja. Ki Kebo Mengo justru telah terdorong oleh kekuatannya sendiri. Sejenak kemudian Ki Kebo Mengo harus menguasai lontaran tubuhnya sendiri yang meluncur dengan deras ke depan.
Disaat tubuh Ki Kebo Mengo itu terhuyung-huyung ke depan karena pengaruh dorongan kekuatannya sendiri, tiba-tiba saja bayangan Ki Rangga dengan cepat berbalik dan kali ini sebuah hantaman yang cukup keras kembali telah melanda punggung Ki Kebo Mengo.
Tubuh Ki Kebo Mengo yang sedang terhuyung ke depan itu bagaikan mendapat dorongan dua kali lipat dari kekuatannya sendiri. Akibatnya benar-benar telah membuat tubuh Ki Kebo Mengo kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya jatuh terjerembab di atas tanah yang mulai basah oleh embun malam.
“Setan, demit, iblis, gendruwo, tetekan!” sumpah serapah pun meluncur dari mulut Ki Kebo Mengo. Sambil berguling ke samping kanan untuk menghindari kemungkinan serangan susulan lawan, dengan sigap Ki Kebo Mengo pun segera melenting berdiri.
Sambil mengusap wajahnya yang penuh dengan debu, terdengar Ki Kebo Mengo menggeram, “Ki Rangga, aku mengakui kedahsyatan ilmumu, namun jangan berbangga dulu. Rahasia ilmu petak umpetmu ini sebentar lagi akan kau temukan dan kebesaran nama Ki Rangga Agung Sedayu, agul-agulnya Mataram hanya akan tinggal nama saja.”
Tampak bayangan itu seolah menarik nafas panjang. Berkata bayangan itu kemudian, “Terima kasih atas pujian Ki Kebo Mengo. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu Ki Kebo Mengo menemukan rahasia ilmuku.”
“Tutup mulutmu!” bentak Ki Kebo Mengo sambil kembali melontarkan serangan. Namun kali ini Ki Kebo Mengo tidak ingin mengulangi kesalahannya. Serangannya yang meluncur deras itu hanya sekedar sebagai pancingan saja.
Diam-diam dalam hati Ki Kebo Mengo tersenyum gembira begitu melihat bayangan lawannya diam tak bergerak. Dengan demikian Ki Kebo Mengo berharap kejadian sebelumnya akan berulang. Serangannya hanya akan menembus bayangan kosong. Pada saat tubuhnya meluncur ke depan, begitu kakinya menginjak tanah, dia sudah berencana untuk melenting ke samping sehingga jika bayangan lawannya itu balik menyerangnya, dia sudah siap untuk membenturkan ilmunya.
“Bayangan semu Ki Rangga akan menampakkan kekuatannya jika dia menyerang,” demikian Ki Kebo Mengo mengambil kesimpulan di dalam hati, “Jika aku ingin menyentuhnya sebagaimana menyentuh bentuk wadagnya, aku harus membenturkan kekuatanku justru pada saat dia menyerang.”
Berbekal keyakinan itulah Ki Kebo Mengo tidak mengerahkan kekuatan penuh pada saat dia menyerang. Kakinya yang terjulur lurus mengarah dada itu meluncur tanpa kekuatan penuh.
Namun yang terjadi kemudian kembali membuat Ki Kebo Mengo harus mengumpat dengan umpatan sekotor-kotornya. Agaknya bayangan lawannya itu mampu mengetahui kekuatan yang tersimpan dalam serangannya berdasarkan desir angin yang mendahuluinya. Dengan mengerahkan kekuatan yang cukup besar, bayangan Ki Rangga itu justru telah membenturkan kekuatannya dengan menyilangkan kedua tangannya di depan dada.
Akibatnya serangan Ki Kebo Mengo bagaikan membentur dinding baja setebal satu jengkal. Tubuh Ki Kebo Mengo pun terlempar ke belakang dan melayang bagaikan selembar daun kering yang tertiup angin puyuh, sebelum akhirnya jatuh bergulingan di atas tanah.
Entah sudah untuk ke berapa kalinya Ki Kebo Mengo mengeluarkan umpatan yang sangat kasar. Dadanya rasa-rasanya bagaikan meledak mendapatkan dirinya menjadi bulan-bulanan lawannya. Sambil melenting berdiri dan kemudian berdiri di atas kedua kakinya yang renggang, Ki Kebo Mengo mulai menilai kekuatan ilmu lawannya yang ternyata sangat ngedab-edabi itu.
“Hem,” desah Ki Kebo Mengo dalam hati sambil mencoba menguasai gejolak di dalam dadanya, “Ternyata ilmu Ki Rangga benar-benar ngedab-edabi. Jika dalam waktu dekat aku belum bisa menemukan kelemahannya, aku hanya akan menjadi bulan-bulanan saja seperti seekor tikus pithi di tangan seekor kucing yang garang.”
Untuk beberapa saat Ki Kebo Mengo tidak tahu harus berbuat apa. Dari pengalamannya melakukan serangan sebanyak dua kali, semuanya berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, apa yang telah terjadi itu merupakan aib yang akan mencoreng nama besarnya.
“Pantas bayangan Ki Rangga ini hanya menunggu serangan,” kembali Ki Kebo Mengo berkata dalam hati, “Disitulah letak kunci rahasianya. Dia hanya menunggu lawan untuk menyerangnya dan kemudian dia akan menjebak lawannya dengan kemampuan ilmunya yang mampu mengelabuhi itu.”
Dalam pada itu, selagi Ki Kebo Mengo masih menduga-duga rahasia di balik aji pengangen-angen Ki Rangga Agung Sedayu, dua pasang mata tampak sedang mengawasi mereka dari tempat yang cukup jauh.
“Raden,” bisik seseorang yang tampak sudah sangat tua renta namun terlihat sangat sehat dan kuat, “Aku pernah menghadapi dan merasakan langsung kedahsyatan ilmu Ki Rangga Agung Sedayu itu. Ilmu itu kelihatannya merupakan perkembangan dari ilmu bayangan semu. Sudah sangat jarang orang yang mampu menguasai ilmu itu untuk saat ini. Selama ini memang pernah ada cerita tentang kesaktian tokoh-tokoh di masa lalu. Mereka itu dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Namun apakah mereka itu juga mempunyai kekuatan yang sama dengan ujud aslinya, itu yang belum pernah aku dengar.”
Orang yang berdiri di sebelahnya tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, “Cerita itu memang pernah aku dengar, salah satunya adalah Maha Patih Gajah Mada. Bahkan menurut cerita yang tidak jelas sumbernya, Panembahan Senapati juga mampu melakukan hal itu walaupun kebenarannya sangat meragukan.”
“Raden benar,” sahut orang tua itu, “Memang pernah tersebar cerita tentang Panembahan Senapati yang mampu berada di beberapa tempat di saat yang bersamaan. Namun aku cenderung menganggap itu cerita ngayawara dari orang-orang Mataram sendiri yang sengaja ingin membesar-besarkan nama Panembahan Senapati.”
Sejenak kedua orang itu terdiam. Perhatian mereka kembali tertuju kepada Ki Kebo Mengo yang tampak mulai mempersiapkan diri untuk kembali menyerang bayangan semu Ki Rangga Agung Sedayu. Namun kali ini Ki Kebo Mengo tampak masih berputar-putar saja dan belum mulai menyerang. Agaknya dia sedang membuat perhitungan-perhitungan dengan mencoba untuk memancing lawannya agar menyerang terlebih dahulu.
“Ki Kebo Mengo hanya membuang-buang waktu saja,” desis orang tua renta itu kemudian begitu melihat Ki Kebo Mengo mulai bergerak berputar-putar.
“Eyang Guru,” berkata orang yang di sebelahnya itu kemudian, “Dimana kah sebenarnya kelemahan ilmu Ki Rangga itu?”
“Raden,” jawab orang tua renta yang ternyata adalah Eyang Guru, “Sangat sulit untuk mengalahkan sebuah bayangan semu. Jika ingin menghancurkan ilmu itu, kita harus menghancurkan sumbernya.”
Orang yang dipanggil Raden itu mengerutkan keningnya. Dengan nada sedikit ragu dia kemudian bertanya, “Maksud Eyang Guru, kita langsung menyerang ujud asli Ki Rangga? Tapi bukankah kita tidak tahu di mana dia sekarang ini sedang bersembunyi?”
Eyang Guru tersenyum menanggapi pertanyaan orang yang dipanggilnya Raden itu. Jawabnya kemudian, “Memang agak rumit dan membutuhkan waktu untuk melacak keberadaan ujud asli Ki Rangga. Harus melalui benturan ilmu yang berkali-kali. Namun sekarang kita tidak perlu melakukan itu. Kita dapat langsung mencari ujud asli Ki Rangga dan langsung membunuhnya.”
Kembali orang yang dipanggil Raden itu memandang ke arah Eyang Guru dengan sorot mata ragu-ragu.
Agaknya Eyang Guru tidak mau berteka-teki terlalu lama. Maka katanya kemudian, “Marilah kita menuju ke banjar padukuhan Klangon. Aku yakin bayangan semu itu dipancarkan dari arah sana. Bukankah menurut berita telik sandi kita, ada lima orang asing yang sedang bermalam di banjar padukuhan Klangon?” Eyang Guru berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Aku yakin Ki Rangga sekarang ini sedang dalam puncak samadinya. Jika kawan-kawannya yang lain mungkin melindunginya, itu menjadi tugasku untuk menyingkirkan mereka. Sementara Raden dapat membunuh Ki Rangga dengan sangat mudahnya. Tubuh Ki Rangga akan sangat lemah tanpa perlindungan sama sekali ketika sedang dalam puncak samadinya.”
Orang yang dipanggil Raden itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika dilihatnya Eyang Guru mulai melangkahkan kakinya meninggalkan tempat ini, dengan bergegas dia pun segera mengikuti langkah orang tua itu.
“Kita berjalan agak melingkar agar tidak terpantau oleh Ki Rangga,” berkata Eyang Guru kemudian sambil menyusup gerumbul liar di sisi jalan.
“Bagaimana dengan Ki Kebo Mengo?” bertanya orang yang dipanggil Raden itu sambil ikut berjalan merunduk-runduk.
Sejenak Eyang Guru menegakkan tubuhnya untuk melihat keadaan Ki Kebo Mengo yang terlihat mulai terlibat dalam pertempuran. Jawabnya kemudian, “Biarlah untuk sementara Ki Kebo Mengo meladeni bayangan semu Ki Rangga. Dengan demikian Ki Rangga akan lengah dan tidak menyadari bahwa bahaya sedang menuju ke tempat samadinya.”
“Eyang Guru,” bertanya kembali orang yang dipanggil Raden itu, “Apa yang akan terjadi jika Ki Rangga menyadari bahwa bahaya sedang mengancam jiwanya?”
“Dia akan menghentikan samadinya sehingga kita akan berhadapan langsung dengan wadag Ki Rangga, dan itu akan sama berbahayanya dengan bayangan semunya itu,” sahut Eyang Guru cepat.
Orang yang dipanggil Raden itu mengerutkan keningnya sambil mengikuti kembali langkah Eyang Guru. Agaknya masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Maka tanyanya kemudian, “Bayangan semu Ki Rangga memang tidak dapat tersentuh, namun ujud wadagnya berbeda, kita dapat menyentuh bahkan melukainya. Apa sebenarnya yang perlu kita takutkan?”
Eyang Guru sekilas berpaling ke belakang sambil tertawa perlahan. Jawabnya kemudian, “Raden Surengpati, dalam ujud aslinya Ki Rangga memiliki ilmu kebal yang sangat sulit untuk ditembus. Selain itu Ki Rangga telah menguasai ilmu kakang pembarep dan adi wuragil yang hampir sempurna. Maksudku, kedua ujud semunya itu akan mempunyai kekuatan yang sama dengan aslinya sehingga jika Ki Rangga mengetrapkan ilmu itu, kita akan bertempur seperti melawan tiga orang Ki Rangga sekaligus.”
Berdesir dada Raden Mas Harya Surengpati. Begitu dahsyatnya ilmu-ilmu yang tersimpan dalam diri Ki Rangga Agung Sedayu itu.
“Pantas Ki Rangga menjadi agul-agulnya Mataram,” berkata Raden Surengpati dalam hati, “Jika Eyang Guru saja menghindari bertemu langsung dengan Ki Rangga, siapa lagi di antara kita yang akan mampu menahan agul-agulnya Mataram itu?”
Tiba-tiba Raden Mas Harya Surengpati teringat akan Kakandanya yang sampai saat ini masih belum hadir di antara para pengikutnya.
“Kakangmas Wirasena sedang membuat hubungan dengan perguruan Sapta Dhahana,” berkata Raden Surengpati dalam hati sambil terus berjalan mengikuti langkah Eyang Guru, “Jika perguruan Sapta Dhahana tidak berkeberatan membantu perjuangan kami, tentu Kiai Damar Sasangka pemimpin perguruan Sapta Dhahana akan mampu mengimbangi kemampuan Ki Rangga Agung Sedayu.”
Sejenak kemudian kedua orang itu harus berjalan menjauhi lingkaran pertempuran antara Ki Rangga melawan ki Kebo Mengo. Sesekali mereka berdua harus meloncati pagar halaman yang cukup tinggi dan melintasi halaman-halaman yang sepi.
“Eyang Guru,” berkata Raden Surengpati kemudian sambil terus mengikuti langkah Eyang Guru, “Selain berita dari telik sandi sore tadi, aku juga menerima berita dari orang-orangnya gegedug Dukuh Salam yang biasa dipanggil dengan sebutan Ki Lurah itu,” Raden Surengpati berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Menurut orang-orangnya Ki Lurah, salah satu dari kelima orang itu ada yang mempunyai kemampuan bermain sihir. Kejadian itu mereka alami ketika mereka sedang mengumpulkan derma di sekitar Kali Krasak. Salah satu dari kelima orang itu telah menyumbangkan berbagai perhiasan emas dan sebuah keris berpendok emas. Namun ternyata mereka telah menjadi korban permainan sihir.”
Eyang Guru tidak menjawab. Sambil berjalan terbungkuk-bungkuk dia dengan cepat melintasi halaman sebuah rumah yang tampak kosong, tidak ada seberkas sinar pun yang terlihat menembus keluar dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari bambu itu.
“Eyang Guru?” Raden Mas Harya Surengpati mengulangi pertanyaannya dengan suara sedikit keras.
“Aku sudah dengar, Raden!” sahut Eyang Guru dengan nada sedikit kesal tanpa menghentikan langkahnya, “Aku tidak peduli siapa kelima orang itu, dan sampai setinggi apa kemampuan mereka, kecuali Ki Rangga Agung Sedayu. Permainan sihir bagiku tak lebih dari sebuah permainan kanak-kanak.”
Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan detak jantung di dalam dadanya yang tiba-tiba saja melonjak-lonjak. Sebenarnya dia ingin menyampaikan sesuatu yang menurut pertimbangannya sangat penting. Namun agaknya Eyang Guru sama sekali tidak peduli. Sifat orang yang disebut Eyang Guru itu memang agak aneh. Karena usianya yang sudah sangat tua, kadang-kadang dia menjadi sedikit pikun dan mudah tersinggung serta menjengkelkan.
Tidak terasa kedua orang itu sudah cukup jauh meninggalkan medan pertempuran antara Ki Kebo Mengo melawan Ki Rangga Agung Sedayu. Ketika kedua orang itu telah melintasi sebuah halaman yang cukup luas dari sebuah rumah yang cukup bagus, keduanya pun kemudian memutuskan untuk kembali ke jalur jalan Padukuhan Klangon kembali.
“Eyang Guru,” bertanya Raden Surengpati kemudian sekali lagi untuk menyampaikan sesuatu yang membebani hatinya, “Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang di banjar padukuhan itu? Mereka berlima dan kita hanya berdua saja.”
Eyang Guru menghentikan langkahnya sebelum mencapai regol halaman rumah itu. Jawabnya kemudian sambil memutar tubuhnya, “Raden, sudah aku katakan sedari tadi. Aku tidak peduli dengan kelima orang itu, kecuali Ki Rangga Agung Sedayu. Bagiku tidak ada kekuatan orang-orang Mataram yang perlu diperhitungkan kecuali hanya Ki Rangga Agung Sedayu.”
“Bagaimana dengan Ki Juru Mertani?” desak Raden Surengpati.
Untuk sejenak Eyang Guru justru terdiam. Hanya sepasang matanya saja yang menatap tajam ke arah Raden Surengpati. Namun pada akhirnya Eyang Guru itu pun menjawab juga, “Ki Juru Mertani dikenal karena olah pikirnya saja yang sangat cerdas. Perhitungan-perhitungannya selalu berdasarkan atas penalaran serta pengalaman yang diperolehnya sehingga menjadi sangat tajam dan terpercaya. Namun kemampuan ilmu olah kanuragannya sendiri aku tidak yakin sedahsyat dan sebanding dengan Mas Karebet yang kemudian menjadi Sultan di Pajang, walaupun dapat dikatakan mereka pernah menimba ilmu dari sumber yang sama.”
Sekarang giliran Raden Surengpati yang termenung. Berbagai pertimbangan telah bergolak di dalam dadanya. Namun akhirnya Raden Surengpati pun menyampaikan juga apa yang selama ini membebani hatinya, “Eyang Guru, aku justru mencurigai salah satu dari mereka adalah Ki Juru Mertani sendiri.”
“He?!” bagaikan disengat ribuan kalajengking Eyang Guru terperanjat mendengar kata-kata Raden Surengpati, “Apa pertimbangan Raden?”
Raden Mas Harya Surengpati menarik nafas dalam-dalam sambil melemparkan pandangan matanya ke kejauhan. Jawabnya kemudian dengan perlahan, “Aku hanya menduga-duga saja sesuai dengan cerita orang-orangnya Ki Lurah gegedug dukuh Salam. Di antara kelima orang itu ada seseorang yang tampak sudah sangat tua namun terlihat masih kuat dan sehat. Orang tua itulah yang dikatakan mampu bermain sihir. Mungkin saja orang tua itu adalah Ki Juru Mertani.”
Sejenak Eyang Guru bagaikan membeku di tempatnya. Bagaimana pun juga, dugaan akan kehadiran Ki Juru Mertani di antara kelima orang itu harus diperhitungkan. Jika semula dia menganggap hanya Ki Rangga yang perlu mendapat perhatian, kini dugaan adanya Ki Juru Mertani yang ikut bermalam di banjar padukuhan Klangon itu telah membuat jantung tuanya berdetak semakin cepat.
“Apa boleh buat!’ geram Eyang Guru pada akhirnya, “Kita akan melihat kekuatan mereka terlebih dahulu. Jika memang orang tua dari Sela yang tak tahu diri itu ada di antara mereka, kita harus segera membuat hubungan dengan Kiai Damar Sasangka dan Raden Wirasena.”
Raden Surengpati mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Segala kemungkinan memang harus diperhitungkan agar jangan sampai justru mereka sendiri yang akan terjebak dalam lingkaran kekuatan yang tidak mampu mereka atasi.
“Marilah,” berkata Eyang Guru kemudian sambil memutar tubuhnya, “Kita akan melihat kekuatan kelima orang itu terlebih dahulu sebelum menentukan langkah kita selanjutnya.”
Raden Mas Harya Surengpati tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk sambil melangkah mengikuti Eyang Guru.
Sejenak kemudian mereka berdua segera meneruskan langkah mendekati regol halaman yang terlihat diselarak dari dalam. Setelah mengangkat selarak pintu regol itu terlebih dahulu, keduanya pun segera mendorong pintu regol dan melangkahkan kaki mereka keluar menuju ke jalur jalan padukuhan Klangon.
Namun alangkah terkejutnya mereka berdua. Jantung kedua orang itu bagaikan terlepas dari tangkainya begitu kaki mereka melangkah ke jalur jalan padukuhan Klangon. Beberapa tombak di hadapan mereka, tampak bayangan seseorang dengan sengaja sedang berdiri menunggu sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada.
“Bagaimana mungkin?” terdengar Eyang Guru kembali berdesis sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam, “Apakah Ki Kebo Mengo sedemikian mudahnya dapat ditundukkan oleh Ki Rangga?”
“Belum tentu,” sergah Raden Surengpati dengan dada berdebaran. Pandangan matanya tak pernah lepas dari ujud bayangan Ki Rangga yang berdiri beberapa tombak di depannya, “Ki Kebo Mengo adalah orang kepercayaan Kakangmas Wirasena. Aku yakin ujud bayangan semu Ki Rangga lah yang melarikan diri.”
“Melarikan diri?” ulang Eyang Guru dengan nada keheranan, “Melarikan diri karena kalah beradu ilmu dengan si Kerbau bodoh itu?”
Sejenak merah padam wajah Raden Surengpati. Namun dengan cepat kesan itu dihapus dari wajahnya. Katanya kemudian, “Maksudku, Ki Rangga mungkin mengetahui gerak-gerik kita dan memutuskan untuk mengejar kita berdua.”
Eyang Guru sejenak tertegun. Jika memang benar Ki Rangga telah mengetahui gerak-gerik dirinya dan Raden Surengpati, tentu agul-agulnya Mataram itu telah mencapai tingkat yang nyaris sempurna dalam menguasai panggraitanya untuk melacak keberadaan seseorang.
Namun selagi kedua orang itu menduga-duga apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Ki Kebo Mengo, tiba-tiba saja bayangan semu Ki Rangga perlahan-lahan menghilang bagaikan asap yang tertiup angin kencang.
“He?!” hampir bersamaan keduanya berseru tertahan. Detak jantung mereka yang semula mulai tenang kini melonjak-lonjak kembali.
“Apakah sebenarnya yang telah terjadi?” bertanya Raden Surengpati dengan kening yang berkerut-merut. Sementara Eyang Guru yang berdiri di sebelahnya segera menundukkan kepalanya serta menyilangkan kedua tangannya di depan dada.
Eyang Guru hanya memerlukan waktu sekejab untuk menilai keadaan di sekelilingnya. Sejenak kemudian, Eyang Guru pun telah mengangkat wajahnya serta mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada.
“Ki Rangga telah pergi,” desis Eyang Guru kemudian sambil menarik nafas panjang.
Raden Surengpati yang berada di sebelahnya berpaling. Dengan nada sedikit ragu-ragu, Raden Surengpati pun kemudian bertanya, “Pergi? Mengapa?”
Kembali Eyang Guru menarik nafas dalam. Jawabnya kemudian, “Entahlah. Aku tidak dapat menduga permainan apakah yang sedang ditunjukkan oleh Ki Rangga? Namun yang jelas, ilmu Ki Rangga dari hari ke hari rasa-rasanya semakin tinggi dan mumpuni. Aku khawatir, jika tidak segera dihentikan, cita-cita Trah Sekar Seda Lepen hanya akan tinggal mimpi belaka.”
Berdesir dada Raden Surengpati. Namun di dalam hatinya masih ada sepercik harapan. Jika Kakandanya mampu menarik Kiai Damar Sasangka untuk bergabung, mereka akan mempunyai kekuatan yang setara bahkan mungkin lebih tinggi dibanding dengan kekuatan Mataram.
“Sudahlah,” berkata Eyang Guru kemudian membuyarkan lamunan Raden Surengpati, “Lebih baik kita kembali saja. Aku mempunyai rencana untuk pergi ke gunung Tidar selepas tengange. Ada yang harus segera kita bicarakan dengan Raden Wirasena dan para penghuni perguruan Sapta Dhahana itu.”
Selesai berkata demikian tanpa menunggu tanggapan Raden Surengpati, Eyang Guru segera melangkahkan kaki kembali menuju ke Perdikan Matesih. Sementara Raden Surengpati dengan tergesa-gesa segera mengikuti di belakangnya.
Demikianlah akhirnya, kedua orang itu telah memutuskan untuk kembali ke Tanah Perdikan Matesih. Agaknya Eyang Guru telah memperhitungkan untung ruginya jika harus berhadapan dengan kelima orang yang sedang bermalam di dukuh Klangon itu. Jika dugaan Raden Surengpati benar bahwa Ki Juru Mertani ada di antara kelima orang itu, Trah Sekar Seda Lepen harus benar-benar berhitung cermat dalam mengukur kekuatan mereka.
Sejenak kemudian kedua orang itu telah menyusuri jalan dukuh Klangon yang sepi. Kali ini mereka tidak melewati halaman-halaman rumah yang sepi serta meloncati pagar-pagar yang tinggi. Mereka menyusuri jalan sebagaimana biasanya, tidak harus dengan cara sembunyi-sembunyi.
Namun belum ada sepenginang sirih mereka berdua berjalan, pendengaran Eyang Guru yang lebih tajam dibanding Raden Mas Harya Surengpati telah menangkap desir lembut dari arah yang berlawanan sedang menuju ke tempat mereka.
Segera saja Eyang Guru menghentikan langkahnya.
“Ada apa?” bertanya Raden Surengpati sambil ikut menghentikan langkahnya.
Eyang Guru tidak segera menjawab. Langkah itu memang masih cukup jauh, namun pendengaran Eyang Guru yang luar biasa tajamnya telah mampu menangkapnya.
“Eyang Guru,” kembali Raden Surengpati bertanya, “Apakah Eyang Guru melihat sesuatu yang mencurigakan?”
Eyang Guru menarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu sebelum menjawab. Katanya kemudian setengah berbisik, “Yang datang kemudian ini menurut pengamatanku juga termasuk orang yang mumpuni menilik desir langkahnya yang sangat lembut. Namun aku yakin ini bukan bayangan semu Ki Rangga. Sebuah bayangan semu tidak dapat dikenali desir langkahnya, karena dia hanya berupa sebuah bayangan.”
“Karena itulah kehadiran bayangan semu Ki Rangga beberapa saat tadi tidak dapat diketahui oleh Eyang Guru,” sahut Raden Surengpati.
“Benar Raden,” jawab Eyang Guru, “Aku dapat mengenalinya jika bayangan itu sudah berujud. Namun jika dia menghilang, aku yakin tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk melacaknya. Itulah sebabnya ilmu Ki Rangga itu benar-benar tidak ada duanya. Jika Ki Rangga mampu mematangkannya, seorang diri saja dia akan mampu menggulung jagad.”
“Marilah Raden,” berkata Eyang Guru kemudian, “Kita temui Ki Kebo Mengo. Sekalian kita bicarakan rencana kita untuk ke Padepokan Sapta Dhahana nanti menjelang tengange.”
Raden Surengpati masih ragu-ragu sejenak. Namun ketika pandangan matanya sudah mampu menangkap dan mengenali sesosok tubuh yang berjalan mendekat itu, wajah Raden Surengpati pun menjadi cerah. Sambil tersenyum dan mengangguk-angguk, dia segera mengikuti langkah Eyang Guru.
Dalam pada itu di banjar padukuhan, Ki Rangga yang sedang dalam puncak samadinya itu ternyata telah terganggu oleh sesuatu hal yang belum dimengertinya. Sehingga perlahan-lahan pemusatan nalar dan budi Ki Rangga pun mulai memudar seiring dengan kesadaran yang mulai memenuhi otaknya. Sejenak kemudian Ki Rangga pun telah terjaga dari samadinya dan tersadar sepenuhnya.
“Apa yang sebenarnya telah terjadi, ngger?” pertanyaan itulah yang pertama kali didengar oleh Ki Rangga begitu dia membuka kedua matanya.
Sambil bangkit dan kemudian duduk bersila, Ki Rangga berpaling ke arah Ki Waskita yang duduk di sebelahnya. Jawabnya kemudian, “Ki Waskita, aku merasakan sesuatu yang aneh telah terjadi dalam samadiku.”
Ki Waskita mengerutkan keningnya dalam-dalam. Katanya kemudian, “Angger sedang dalam puncak samadi ketika tiba-tiba saja aku menyadari angger sepertinya mengalami sedikit gangguan dan kemudian samadi angger pun telah badar.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggeser duduknya menghadap penuh ke arah Ki Waskita, Ki Rangga pun kemudian menceritakan pengalaman yang didapatkannya selama dalam puncak samadinya.
“Ketika aku sedang berhadapan dengan orang yang menyebut dirinya Ki Kebo Mengo,” demikian Ki Rangga memulai ceritanya, “Panggraitaku telah menangkap adanya gerakan dari dua orang yang sedang berada di sekitar tempat itu.”
“Apakah angger mengenali mereka?” potong Ki Waskita dengan nada sedikit tidak sabar.
“Ya, Ki,” jawab Ki Rangga, “Aku mengenal salah satu dari mereka adalah orang yang pernah berselisih denganku di kediaman Ki Gede Menoreh beberapa saat yang lalu.”
Mendengar penjelasan Ki Rangga, Ki Waskita pun segera teringat dengan peristiwa yang terjadi di kediaman Ki Gede Menoreh. Maka tanya Ki Waskita kemudian, “Apakah yang angger maksud itu adalah salah satu pengikut Trah Sekar Seda Lepen yang menyebut dirinya Eyang Guru?”
“Benar, Ki,” sahut Ki Rangga dengan serta merta. Lanjutnya kemudian, “Dan yang satunya adalah orang yang selama ini menghantui tanah Perdikan Matesih, Raden Mas Harya Surengpati.”
Ki Waskita mengerutkan keningnya. Tanya Ki Waskita kemudian, “Bagaimana angger bisa mengetahuinya?”
“Aku mendengar Eyang Guru menyebut namanya,” jawab Ki Rangga, “Namun ternyata mereka berdua tidak ikut melibatkan diri dengan Ki Kebo Mengo. Eyang Guru lebih memilih menuju ke banjar padukuhan.”
Sejenak wajah Ki Waskita menegang. Berbagai tanggapan telah muncul dalam benaknya. Namun sebelum Ki Waskita bertanya lebih jauh, ternyata Ki Rangga segera memberi penjelasan.
“Ki Waskita,” berkata Ki Rangga kemudian, “Ternyata Eyang Guru itu telah mengetahui kelemahan aji pengangen-angen. Dengan sangat yakin Eyang Guru berencana untuk mendapatkan wadagku yang sedang dalam puncak samadi dan kemudian dengan sangat mudahnya dia akan membunuhku.”
Ki Waskita menarik nafas panjang mendengar keterangan Ki Rangga. Untuk beberapa saat ayah Rudita itu termenung. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa dari segala yang berkuasa di muka bumi ini. Aji pengangen-angen pada dasarnya adalah sebuah aji sang sangat ngedab-edabi, namun mempunyai satu kelemahan, yaitu justru terletak pada wadag orang yang menguasai ilmu itu sendiri.
Kembali Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bertanya Ki Waskita selanjutnya, “Apakah angger kemudian memutuskan untuk meninggalkan Ki Kebo Mengo dan mengejar mereka berdua?”
Ki Rangga tidak segera menjawab. Untuk beberapa saat Ki Rangga masih mencoba menilai apa yang telah dilakukannya beberapa saat yang lalu.
STSD Jilid 3
Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan Ki Rangga. Setelah terdiam beberapa saat, barulah dengan suara yang sangat sareh Ki Waksita pun berkata, “Ngger, memang tidak ada ilmu yang sempurna di atas bumi ini. Pada dasarnya aji kakang pembarep dan adi wuragil mempunyai sifat dan watak yang berbeda dengan aji pengangen-angen, walaupun keduanya bertumpu pada ujud semu yang sama,” Ki Waskita berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Aji kakang pembarep adi wuragil menuntut kehadiran wadagmu sedekat mungkin, bahkan menuntut wadagmu untuk ikut dalam setiap keberadaan ujud semu itu. Sedangkan aji pengangen-angen tidak menuntut akan kehadiran ujud wadagmu. Justru aji pengangen-angen akan meninggalkan wadagmu sejauh dapat engkau lakukan, menyeberangi lautan misalnya. Semua itu tergantung dari kekuatan pancaran ilmu dari sumbernya, yaitu wadagmu sendiri.”
Sejenak Ki Rangga termenung. Berbagai tanggapan dan harapan sedang bergolak di dalam dadanya.
“Dalam sebuah kancah pertempuran pasukan segelar sepapan yang sebenarnya, aji pengangen-angen ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain,” berkata ki Waskita selanjutnya, “Kehadirannya mungkin akan sempat membingungkan lawan. Namun jika lawan sempat mengetahui kelemahannya dan menemukan tempat persembunyian ujud wadagnya, tentu akan sangat berbahaya. Demikian juga jika seseorang diminta secara khusus untuk menjaga wadagnya selama dia dalam puncak samadinya, siapakah yang dapat menjamin jika orang yang menjaganya itu tidak akan berkhianat?”
Ki Rangga masih berdiam diri dan belum menanggapi penjelasan Ki Waskita. Angan-angannya sedang menerawang entah ke mana.
“Ngger,” berkata Ki Waskita seterusnya begitu melihat Ki Rangga masih termangu-mangu, “Berbeda dengan aji kakang pembarep dan adi wuragil yang kehadirannya di medan pertempuran yang sebenarnya akan sangat berarti. Lawan akan memperhitungkan keberadaan bentuk semu itu karena engkau telah mampu memancarkan ilmumu melalui kedua ujud semu itu. Sehingga lawan akan mendapatkan perlawanan tiga kali lipat dari kekuatan yang sesungguhnya,” Ki Waskita berhenti sejenak sambil mencoba mengamati raut wajah Ki Rangga. Lanjutnya kemudian, “Jika angger ingin menggabungkan kedua aji itu, tentu diperlukan laku khusus yang tentu akan melibatkan persyaratan dari kedua cabang ilmu itu. Dengan demikian, apabila seseorang telah mampu menguasai gabungan kedua aji tersebut, dia akan benar-benar mampu menjaga wadagnya dengan salah satu bentuk semunya, sedangkan bentuk semu yang lain akan mampu bergerak ke tempat yang sangat jauh, sejauh angan-angan dari manusia itu sendiri.”
Kali ini Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Walaupun tampaknya memang masih ada yang membebani pikirannya.
Agaknya Ki Waskita dapat membaca wajah Ki Rangga yang terlihat sedang menyimpan sebuah beban dalam hatinya itu. Maka katanya kemudian, “Ngger, aku melihat sebuah kegelisahan yang terpancar pada wajah angger. Jika memang aku boleh mengetahuinya, apakah sebenarnya yang masih menjadi beban di hati angger?”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu sebelum menjawab. Setelah membetulkan letak duduknya, barulah Ki Rangga menjawab, “Ki Waskita, penggabungan aji kakang pembarep dan adi wuragil dengan aji pengangen-angen itu sebaiknya kita pikirkan di kemudian hari,” Ki Rangga berhenti sejenak untuk sekedar menarik nafas panjang. Lanjutnya kemudian, “Adapun yang masih membebani hatiku sampai saat ini adalah, sejak aku mendalami aji pengangen-angen, aku merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi dalam diriku, terutama panggraitaku. Beberapa kali aku merasakan sepertinya aku mendapatkan firasat tentang sesuatu. Ketika aku menganggapnya itu hanyalah sebagai bentuk kegelisahanku saja, ternyata firasat itu benar-benar terjadi. Namun tidak jarang aku tidak mampu mengurai makna firasat itu sehingga yang terjadi kemudian hanyalah sebuah kegelisahan yang tak berujung pangkal. Aku tidak tahu apakah kejadian dalam diriku ini ada hubungannya dengan usahaku untuk menekuni aji pengangen-angen?”
Untuk beberapa saat Ki Waskita termenung. Setelah menarik nafas dalam-dalam, barulah Ki Waskita menjawab, “Ngger, agaknya angger sedang mengalami keadaan yang sebenarnya wajar bagi angger. Aji pengangen-angen itu pada awalnya adalah suatu bentuk ilmu yang hanya berlandaskan pada sebuah angan-angan. Kemudian dengan memusatkan nalar dan budi serta menyelaraskan ilmu itu dengan pikiran serta persangkaan orang lain, maka akan terciptalah bentuk-bentuk semu sesuai dengan apa yang ada di dalam angan-angan kita,” Ki Waskita berhenti sejenak untuk membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba saja menjadi kering. Lanjutnya kemudian, “Semasa mudaku dulu, aku hanya mampu mempelajari sampai batas ini, walaupun guruku telah memberikan tuntunan sampai sejauh apa yang telah tertulis dalam kitab perguruan kami. Aku memang terlampau puas dengan apa yang telah aku capai waktu itu, tanpa memperhitungkan bahwa ternyata ilmu itu jika disempurnakan dan dikembangkan akan mempunyai kekuatan yang sangat ngedab-edabi.”
Ki Rangga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk. Sementara Ki Waskita meneruskan kata-katanya, “Dalam mendalami ilmu ini, aku pun pada awalnya juga mengalami seperti apa yang sedang engkau alami, ngger. Ketika hal itu aku sampaikan kepada guruku, ternyata aku telah diberi wawasan yang luas bagaimana cara mempelajari dan kemudian mempertajam panggraita kita dalam menyikapi peristiwa itu. Aku pun kemudian justru telah tertarik untuk mengembangkan ilmu dalam mengurai isyarat yang merupakan cabang dari aji pengangen-angen dan telah mengabaikan kelanjutan dari aji pengangen-angen itu sendiri sehingga kemampuanku tidak lebih dari sebuah permainan kanak-kanak,” Ki Waskita berhenti sejenak sambil kembali mencoba mengamati perubahan wajah Ki Rangga. Namun Ki Rangga hanya menundukkan kepalanya saja. Maka Ki Waskita pun melanjutkan kata-katanya, “Ngger, jika memang engkau tertarik dengan ilmu dalam mengurai isyarat ini, usahakan untuk mendalami dan meresapi setiap isyarat yang muncul. Memang kadang-kadang kita salah dalam menafsirkan makna isyarat itu karena memang sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali atas seijin Yang Maha Agung. Oleh karena itu, ngger, semakin kita mendekatkan diri dengan Dzat Yang Maha Mengetahui seluruh alam semesta ini, akan semakin terbukalah cakrawala angan-angan kita sehingga kita akan diijinkan untuk mengetahui sedikit rahasia yang selama ini tersembunyi.”
Kembali Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini hatinya mulai tertata kembali. Tidak ada kegelisahan yang selama ini selalu menggelayuti hatinya. Semuanya yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi adalah di dalam genggamanNYA, di dalam kekuasaanNYA. Jika memang seorang hamba diperkenankan untuk mengetahui sedikit dari apa yang akan terjadi di hari esok, sesungguhnyalah itu adalah sebuah karunia yang tiada taranya.
“Ngger,” tiba-tiba suara Ki Waskita membuyarkan lamunannya, “Jika aku boleh mengetahuinya, sebenarnya isyarat apakah yang sekarang ini sedang angger terima?”
Sejenak Ki Rangga mengerutkan keningnya. Ada sedikit keragu-raguan yang tampak terpancar dari sorot kedua matanya. Namun akhirnya meluncur juga kata-kata dari bibirnya, “Ki Waskita, akhir-akhir ini aku sedang digelisahkan oleh sebuah isyarat yang berhubungan dengan masa depan Kademangan Sangkal Putung sepeninggal Adi Swandaru. Aku sering diperlihatkan sebuah pemandangan yang mengerikan, baik dalam mimpi-mimpiku maupun sebuah firasat yang tiba-tiba saja terasa mencengkam jantungku sehingga telah menggelisahkan hatiku. Namun aku tidak tahu dengan pasti, firasat apakah itu sebenarnya. Yang justru kemudian muncul dalam benakku adalah wajah-wajah yang begitu aku kenal, Sekar Mirah dan Pandan Wangi.”
Sejenak Ki Waskita menahan nafas. Apa yang disampaikan Ki Rangga itu telah menggores jantungnya. Ayah Rudita yang juga diberi karunia untuk menerima isyarat tentang masa depan itu sejenak bagaikan telah membeku.
“Ngger,” berkata Ki Waskita akhirnya sambil menarik nafas dalam-dalam, “Sebagaimana angger, aku juga menerima isyarat yang kurang menyenangkan tentang masa depan Sangkal Putung. Akan tetapi, marilah semua itu kita kembalikan kepada Yang Maha Mengetahui. Kita sebagai hambaNYA hanya dapat berusaha dan berdoa, sekiranya kita dapat membantu Sekar Mirah maupun Pandan Wangi untuk semakin memajukan Sangkal Putung maupun Tanah Perdikan Menoreh.”
Mendengar Ki Waskita menyebut kedua wilayah itu, tiba-tiba saja dada Ki Rangga berdesir tajam. Tanpa sadar Ki Rangga berdesis perlahan, “Siapakah sebenarnya yang berhak atas kedua wilayah itu?”
Ki Waskita hanya menarik nafas panjang mendengar pertanyaan Ki Rangga. Kedua daerah yang subur itu memang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menjadi bahan persengketaan oleh beberapa pihak yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan.
“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Sangkal Putung harus segera mengambil sikap sehubungan dengan niat Pandan Wangi untuk kembali ke Menoreh.”
Untuk kesekian kalinya Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Beberapa hari setelah pemakaman suaminya, Pandan Wangi memang secara khusus telah berbicara dengannya tentang masa depan Bayu Swandana.
“Kakang,” berkata Pandan Wangi pada saat itu ketika mereka berdua saja sedang duduk-duduk di pringgitan, “Sepeninggal kakang Swandaru, rasa-rasanya sudah tidak ada lagi yang dapat mengikatku di Kademangan ini, kakang.”
“Wangi?” terkejut Ki Rangga mendengar ucapan Pandan Wangi, “Mengapa engkau berkata demikian? Bukankah masih ada Ki Demang sebagai mertuamu? Serta Bayu Swandana sebagai penerus Adi Swandaru yang kelak akan memimpin Kademangan Sangkal Putung?”
Pandan Wangi sejenak termangu-mangu. Pandangan matanya jatuh ke tikar tempat duduknya. Seakan-akan Pandan Wangi sedang menghitung helai demi helai anyaman tikar pandan itu di setiap jengkalnya.
“Wangi,” kembali terdengar Ki Rangga bertanya ketika dilihatnya Pandan Wangi hanya tertunduk diam, “Apakah engkau mempunyai keinginan untuk kembali ke Menoreh?”
Kali ini Pandan Wangi mengangkat wajahnya. Ketika dua pasang mata itu saling beradu, alangkah terkejutnya Ki Rangga. Sepasang mata itu terlihat sayu dan penuh air mata. Betapa sepasang mata itu dulu pernah menatapnya seperti itu, berpuluh tahun yang lalu. Masih jelas dalam ingatan Ki Rangga yang pada saat itu menggunakan nama Gupita, dia harus menyampaikan pesan adik seperguruannya, Gupala kepada putri Menoreh itu.
“Sepasang mata yang kecewa, tanpa harapan dan cinta,” desis Ki Rangga dalam hati sambil mencoba menghindari tatapan mata Pandan Wangi. Dilemparkan pandangan matanya jauh keluar pintu pringgitan yang terbuka lebar.
“Kakang,” tiba-tiba terdengar lirih kata-kata Pandan Wangi, “Aku sudah cukup menderita di Sangkal Putung ini, walaupun sebagai istri, aku telah berusaha menjadi istri yang baik. Aku tetap berharap kakang Swandaru dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk memperbaiki hubungan kami sebagaimana dulu pertama kali kita telah berjanji untuk merajut masa depan bersama,” Pandan Wangi berhenti sejenak. Nafasnya menjadi sesak bersamaan dengan air mata yang mulai tumpah membasahi wajahnya. Sambil berusaha menghapus air mata dengan ujung lengan bajunya, Pandan Wangi pun kemudian meneruskan kata-katanya walaupun terdengar timbul tenggelam dalam isak tangisnya, “Kakang, salahkan aku jika aku ingin menghapus kenangan masa laluku yang begitu pahit ini? Aku ingin kembali ke tanah kelahiranku untuk memulai hidup baru sekalian membesarkan anakku serta menunjukkan baktiku kepada orang tuaku yang telah tua dan renta.”
Ki Rangga terdiam. Hanya degup jantungnya saja yang terdengar bertalu-talu.
“Ngger,” tiba-tiba terdengar suara Ki Waskita membangunkan Ki Rangga dari lamunannya, “Sebaiknya memang permasalahan Sangkal Putung segera dibicarakan bersama. Jika Pandan Wangi berkeinginan untuk pulang ke tanah kelahirannya, berarti harus segera ditunjuk Pemangku sementara kademangan Sangkal Putung untuk mendampingi Ki Demang yang sudah sangat sepuh itu.”
“Ki Waskita benar,” jawab Ki Rangga, “Namun siapakah yang berhak untuk menjadi pemangku sementara, sedangkan Bayu Swandana masih terlalu kecil? Sementara Pandan Wangi sebagai istri Adi Swandaru serta ibu Bayu Swandana telah menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Menoreh?”
Ki Waskita tersenyum sekilas. Jawabnya kemudian, “Masih ada saudara sedarah Ki Swandaru yang dapat menjadi pemangku sementara di kademangan Sangkal Putung.”
Ki Rangga mengerutkan keningnya dalam-dalam sambil memandang tajam ke arah Ki Waskita. Katanya kemudian dengan nada yang sedikit ragu-ragu, “Maksud Ki Waskita, Sekar Mirah?”
“Ya, ngger,” jawab Ki Waskita sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, “Sekar Mirah dapat ditunjuk untuk menjadi pemangku sementara sambil menunggu Bayu Swandana dewasa.”
“Tidak, Ki Waskita,” dengan serta-merta Ki Rangga menyela, “Akulah yang berkeberatan jika Sekar Mirah yang akan ditunjuk menjadi pemangku sementara kademangan Sangkal Putung.”
Ki Waskita terkejut mendengar kata-kata Ki Rangga. Orang tua itu sejenak termangu-mangu sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Adalah hal yang diluar kewajaran jika seseorang dengan sadar telah menolak sebuah kedudukan, pangkat dan derajat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.
“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian dengan sareh, “Nyi Sekar Mirah mempunyai hak untuk menerima itu walaupun angger sebagai suaminya juga mempunyai hak untuk menentukan seberapa jauh seorang istri diperbolehkan oleh suaminya untuk berbuat diluar dunianya. Jangan tergesa-gesa untuk memutuskannya sekarang, ngger. Ajaklah istrimu untuk bermusyawarah.”
Untuk beberapa saat Ki Rangga terdiam. Berbagai persoalan sedang bergulat di dalam benaknya.
“Alangkah beruntungnya Bayu Swandana,” berkata Ki Rangga dalam hati, “Dari garis ibunya dia mewarisi Tanah Perdikan Menoreh yang luas, sedangkan dari garis ayahnya, dia adalah pewaris kademangan Sangkal Putung yang subur.”
Tiba-tiba dada Ki Rangga berdesir tajam. Ingatannya melayang kepada anak laki-laki satu-satunya, Bagus Sadewa. Dan tiba-tiba saja hati Ki Rangga telah tersentuh
“Bagus Sadewa,” hampir saja nama itu terloncat dari bibirnya, namun cepat-cepat ki Rangga menelan kembali kata-katanya sendiri yang sudah berada di ujung bibirnya.
“Aku takut seandainya Sekar Mirah ditunjuk menjadi Pemangku sementara Kademangan Sangkal Putung, Bagus Sadewa setelah beranjak dewasa akan mempunyai tanggapan tersendiri atas hak Kademangan Sangkal Putung,” berkata Ki Rangga dalam hati kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam, “Apalagi jika Sekar Mirah sebagai ibu ingin melihat anak laki-laki satu-satunya mempunyai masa depan yang lebih baik, tentu akan timbul pertentangan yang justru berawal dari dalam keluarga sendiri.”
Diam-diam Ki Rangga mengeluh dalam hati. Isyarat yang diterimanya tentang masa depan Sangkal Putung benar-benar telah menggelisahkan hatinya.
“Ngger,” kembali kata-kata Ki Waskita membuyarkan lamunan Ki Rangga, “Biarlah urusan Sangkal Putung kita kesampingkan terlebih dahulu. Sekarang sebaiknya kita bicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan kita lakukan sehubungan dengan telah diketahuinya kehadiran kita di Padukuhan Klangon ini.”
Ki Rangga berpikir sejenak. Jawabnya kemudian, “Ki Waskita, salah satu pengikut Trah Sekar Seda Lepen yang disebut Eyang Guru itu telah mengetahui kehadiranku. Demikian juga dengan orang yang selama ini telah menghantui Perdikan Matesih, Raden Surengpati. Tidak menutup kemungkinan tempat ini akan segera diserbu oleh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen.”
Ki Waskita menarik nafas panjang sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang kemungkinan itulah yang bisa terjadi dalam waktu dekat ini, dan mereka benar-benar harus mempersiapkan diri.
“Kita menunggu Ki Jayaraga dan yang lainnya, ngger,” berkata Ki Waskita kemudian, “Semoga pekerjaan mereka segera selesai dan tidak ada satu aral pun yang melintang dalam perjalanan mereka kembali ke banjar ini.”
Ki Rangga tidak menjawab. Hanya tampak kepalanya saja yang terangguk-angguk.
Dalam pada itu Ki Jayaraga, Ki Bango Lamatan dan Glagah putih telah selesai mengubur mayat orang yang belum diketahui jati dirinya itu. Dengan berjalan sedikit tergesa-gesa, ketiganya pun telah memutuskan untuk segera kembali ke banjar padukuhan.
Namun sesampainya mereka di kelokan jalan yang mengarah ke banjar padukuhan itu, ketiga orang itu telah dikejutkan oleh bayangan seseorang yang tampak berjalan perlahan-lahan di dalam kegelapan malam berlawanan arah dengan mereka.
Agaknya orang itu pun juga melihat Ki Jayaraga dan kawan-kawannya yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa sadar orang itu pun telah menghentikan langkahnya.
“Guru,” desis Glagah Putih yang tampak berjalan di sebelah kiri gurunya sambil memanggul cangkul di pundaknya, “Siapakah orang itu?”
“Aku tidak tahu Glagah Putih,” jawab gurunya, Ki Jayaraga sambil terus melangkah, “Dalam keadaan seperti ini, kita harus berhati-hati dan waspada ketika berhadapan dengan siapapun yang belum kita ketahui jati dirinya.”
Glagah Putih menarik nafas dalam-dalam sambil berpaling ke arah Ki Bango Lamatan. Namun tampaknya Ki Bango Lamatan sedang sibuk mengamati orang yang berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang di tengah jalan itu.
Ketika jarak antara mereka tinggal beberapa tombak, tiba-tiba saja orang yang berdiri tegak itu tanpa membuat sebuah ancang-ancang, demikian saja melontarkan tubuhnya ke samping dan menghilang di antara gerumbul-gerumbul perdu yang banyak berserakan di tepi jalan.
Bagaikan sudah berjanji sebelumnya, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan pun segera meloncat memburu ke tempat orang itu menghilang. Sementara Glagah Putih harus melempar cangkulnya terlebih dahulu ke tepi jalan sebelum menyusul kedua orang tua itu kemudian.
Sejenak kemudian, terjadilah kejar-kejaran di antara keempat orang itu. Ki Jayaraga yang berlari di depan sendiri merasa heran. Guru Glagah Putih itu telah mengerahkan segenap kemampuannya, namun orang itu masih saja berada beberapa langkah di depannya.
Untuk beberapa saat mereka masih berputar-putar di sekitar tempat itu. Memang ada beberapa petak rumah yang telah di bangun di sekitar kelokan jalan itu, namun selebihnya masih berupa gerumbul perdu dan tanah kosong yang ditumbuhi rumput tinggi rapat berjajar-jajar.
Tanpa terasa keempat orang yang sedang bermain kejar-kejaran itu telah merambah pada kemampuan ilmu mereka yang tinggi, baik kemampuan dalam berlari maupun kemampuan untuk menyerap bunyi yang dapat ditimbulkan oleh suara gesekan mereka dengan alam sekitarnya.
Tiba-tiba saja orang yang sedang mereka kejar itu telah mengubah arah larinya. Dia tidak lagi lari berputar-putar, namun telah berlari menjauhi tempat itu menuju ke barat.
Ketika orang itu kemudian menyusup ke dalam rimbunan pohon bambu yang tumbuh membujur di belakang sebuah rumah kecil di tepi jalan, tiba-tiba saja Ki Jayaraga dan kawan-kawannya telah kehilangan jejak.
Serentak mereka bertiga segera menghentikan langkah.
“Kemana perginya orang itu, Guru?” bertanya Glagah Putih kemudian sambil mengatur nafasnya yang sedikit tersengal.
KI Jayaraga tidak menjawab. Disilangkan kedua tangannya di depan dada sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ternyata Ki Bango Lamatan pun telah berbuat serupa.
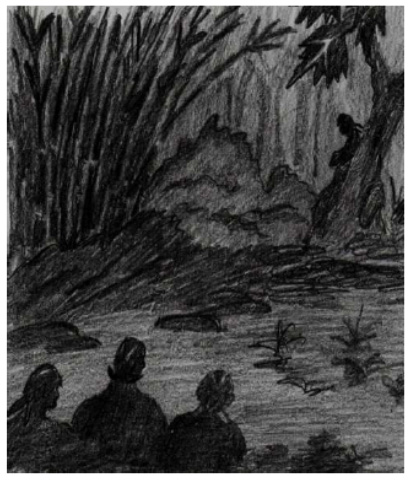
Tidak ada jawaban. Sementara itu Glagah Putih telah mencoba mempertajam penglihatannya dengan lambaran aji sapta pandulu. Segera saja tampak beberapa tombak di depannya, di bawah sebatang pohon keluwih yang tumbuh beberapa langkah dari gerumbul pohon bambu itu, bayangan seseorang sedang berdiri bersandaran pada batang pohon keluwih itu dengan asyiknya.
“Ki Sanak,” Ki Bango Lamatan yang jarang berbicara itu telah maju selangkah, “Apa maksud Ki Sanak melakukan semua ini? Jangan salahkan kami jika Ki Sanak tidak dapat memberikan alasan yang jelas dan masuk akal, kami akan menangkap Ki Sanak.”
Tiba-tiba terdengar bayangan di bawah pohon keluwih itu tertawa perlahan-lahan. Suara tawa yang benar-benar memuakkan.
Berkata bayangan itu kemudian di sela-sela tawanya, “Dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ki Jagabaya Dukuh Klangon? Begitu?”
Ketiga orang itu terkejut. Orang itu telah menyebut Ki Jagabaya Dukuh Klangon. Tentu orang itu telah mengetahui serba sedikit tentang mereka dalam hubungannya dengan Ki Jagabaya Dukuh Klangon.
Namun sebelum Ki Jayaraga menjawab, orang itu telah berkata lagi, “Bagaimana mungkin kalian mau menangkap aku, berlari saja kalian masih seperti kanak-kanak,” orang itu berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Nah, aku akan berlari lagi. Silahkan kalau mau menangkap aku jika kalian merasa mampu.”
Selesai berkata demikian, hampir tidak kasat mata, bayangan itu pun melesat meninggalkan tempat itu menuju ke arah barat.
Ki Jayaraga dan kawan-kawannya merasa tertantang untuk mengejar bayangan itu. Maka sejenak kemudian kejar-kejaran di antara keempat orang itu pun terjadi lagi.
Semakin lama mereka telah semakin jauh meninggalkan padukuhan Klangon dan kini tak terasa mereka telah mendekati tapal batas antara Padukuhan Klangon dengan Tanah Perdikan Matesih sebelah barat.
Sesekali ketiga orang itu kembali kehilangan buruan mereka sehingga ketiga orang itu pun telah menghentikan langkah mereka untuk sejenak. Namun entah mengapa, dengan sengaja orang yang sedang mereka cari itu tiba-tiba saja telah menampakkan diri lagi tidak jauh dari tempat mereka berhenti, sehingga kejar-kejaran itu pun kembali terjadi.
Ketika ketiga orang itu merasakan tanah yang mereka lewati kemudian terasa agak landai, tahulah mereka bahwa sebentar lagi mereka akan mencapai sebuah sungai yang mengalir di sepanjang sisi barat Tanah Perdikan Matesih, kali Praga.
Tiba-tiba saja Ki Jayaraga yang berlari di paling depan telah memperlambat langkahnya. Lamat-lamat Ki Jayaraga mendengar suara aliran air. Sedangkan kedua kawannya yang berlari di belakangnya pun kemudian ikut memperlambat langkah mereka.
“Kita kehilangan jejak kembali,” desis Ki Jayaraga sambil mengatur pernafasannya yang sedikit memburu. Sementara Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih pun telah berbuat serupa.
“Apa maksud orang itu membawa kita ke tepian kali Praga ini?” geram Ki Bango Lamatan sambil menekan lambungnya untuk mengurangi rasa sakit yang tiba-tiba saja terasa menyengat.
“Orang gila,” geram Glagah Putih yang berdiri tersengal-sengal di sebelah Ki Bango Lamatan, “Orang itu berlari seperti setan dan sepertinya memang dengan sengaja dia ingin mempermainkan kita.”
“Sudahlah,” berkata Ki Jayaraga kemudian ketika pernafasannya sudah teratur kembali, “Kita coba untuk turun ke tepian, barangkali di sana ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian.”
Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih tidak menjawab. Hanya kepala mereka saja yang terlihat mengangguk.
Sejenak kemudian ketiga orang itu pun mulai menuruni tebing yang agak curam. Ketika sisi tebing itu mulai landai, mereka pun kemudian mulai berjalan di tepian kali Praga yang berpasir lembut.
Namun baru saja mereka berjalan beberapa langkah, pendengaran mereka yang tajam telah mendengar langkah beberapa orang yang tampak tergesa-gesa menyusuri tepian dari arah yang berlawanan. Memang masih cukup jauh namun ketiga orang itu dengan sangat jelas telah mendengar suara mereka.
Bagaikan sudah berjanji sebelumnya, ketiga orang itu pun segera berloncatan dan bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu yang banyak bertebaran di sisi tebing.
Sejenak kemudian tampak dalam kegelapan malam, beberapa orang muncul dari kelokan sungai. Dengan langkah yang tergesa-gesa mereka menyusuri tepian yang berpasir basah.
“Sebelum ayam jantan berkokok untuk terakhir kalinya, kita sudah harus sampai di banjar Padukuhan Klangon,” berkata seseorang yang berjalan paling depan. Tubuhnya tinggi menjulang dengan sebuah tombak pendek di tangan kanannya, “Perintah Kakang Putut Sambernyawa sudah jelas, kita kepung banjar Padukuhan Klangon tepung gelang agar tidak ada seekor semut pun yang dapat lolos dari pengamatan kita.”
“Kakang Putut Jangkung,” menyela seseorang yang bertubuh gemuk dan pendek yang berjalan di sebelahnya, “Menurut Kakang Putut Sambernyawa tadi, kita sebaiknya membuat hubungan terlebih dahulu dengan Ki Kebo Mengo, orang kepercayaan Raden Wirasena.”
“Persetan dengan Kerbau bodoh itu,” geram Putut Jangkung sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Segera saja terasa bumi di sekitar tempat itu bergetar, “Aku sudah muak sebenarnya dengan orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen beserta para pengikutnya itu. Mereka telah merayu Guru untuk mendukung perjuangan mereka. Dengan berbekal keyakinan seolah-olah wahyu keprabon itu akan menjadi milik mereka, Guru telah dirayu dengan janji-janji yang memabokkan.”
“Apakah janji mereka?” pertanyaan itu dengan serta merta telah terloncat begitu saja hampir dari mulut setiap orang.
Putut Jangkung menarik nafas panjang sebelum menjawab. Sambil mengeluarkan sebuah dengusan dari hidungnya dia menjawab, “Guru dijanjikan akan diangkat menjadi seorang Adipati jika perjuangan mereka berhasil.”
“Sebuah mimpi yang indah,” tiba-tiba saja seseorang yang berjalan di belakang Putut Jangkung terdengar menyahut.
Ki Jangkung berpaling sekilas ke belakang. Katanya kemudian, “Engkau benar, Ki Brukut. Sebuah mimpi yang indah, bahkan terlalu indah jika kita bermimpi ingin menjadi seorang Adipati.”
Ki Brukut menarik nafas panjang. Katanya kemudian, “Kedatanganku ke Padepokan Sapta Dhahana sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala tingkah polah orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pewaris Trah Sekar Seda Lepen itu.”
“Nah, mengapa Ki Brukut ikut rombongan kami?”” sahut orang yang berperawakan gemuk dan pendek yang berjalan di samping Putut Jangkung dengan serta-merta.
Ki Brukut tertawa pendek. Jawabnya kemudian, “Aku datang ke Padepokan Sapta Dhahana sekedar untuk menengok keadaan anakku, Putut Sambernyawa. Anakku lah yang telah meminta aku untuk mengikuti kalian ke Dukuh Klangon, dan memastikan bahwa kalian akan sampai di sana dengan selamat.”
Hampir saja setiap mulut mengumpat mendengar kata-kata Ki Brukut. Namun mereka segera menyadari siapakah Ki Brukut itu. Ayah dari Putut Sambernyawa, Putut tertua dan terpercaya dari Kiai Damar Sasangka, pemimpin tertinggi padepokan Sapta Dhahana.
“Menilik rasa hornat yang diperlihatkan oleh Guru kepada Ki Brukut ini, tentu tingkat ilmunya tidak jauh berbeda dengan Guru,” demikian beberapa orang yang berada dalam rombongan itu berkata dalam hati.
“Atau mungkin keseganan Guru hanya karena Ki Brukut adalah ayah kakang Putut Sambernyawa, bukan tingkat ilmunya,” yang lain justru mempunyai tanggapan yang berbeda.
Tak terasa langkah orang-orang itu pun telah mendekati tempat dimana Ki Jayaraga dan kawan-kawannya sedang bersembunyi.
“Lima belas orang,” berkata Ki Jayaraga dalam hati. Berbagai pertimbangan tengah hilir-mudik dalam benaknya.
Agaknya Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih pun juga telah ikut menghitung jumlah orang-orang yang sedang lewat beberapa langkah di hadapan mereka itu.
“Terlalu banyak dan terlalu berat akibat yang akan ditimbulkan,” berkata Ki Bango Lamatan dalam hati. Memang melawan lima belas orang dengan tingkatan ilmu yang belum mereka ketahui sama saja dengan membunuh diri.
Demikianlah ketika rombongan itu telah berlalu dan tidak tampak lagi bayangannya, ketiga orang yang sedang bersembunyi itu pun berniat untuk keluar dari persembunyiannya. Namun baru saja mereka beringsut setapak, tiba-tiba pendengaran mereka menangkap kembali langkah-langkah mendekati tempat itu. Bahkan sekarang terdengar langkah-langkah itu lebih banyak dari yang pertama.
Segera saja ketiga orang itu membenamkan diri mereka kembali ke dalam gerumbul-gerumbul perdu sambil menahan nafas.
Ternyata yang lewat kemudian adalah serombongan orang yang berjumlah sangat besar, hampir dua kali lipat dari yang pertama. Rombongan yang kedua itu pun kemudian disusul dengan rombongan yang ketiga, keempat dan rombongan kelima adalah rombongan yang terbesar, hampir lima puluh orang.
“Gila!” geram KI Jayaraga perlahan sambil bangkit dari persembunyiannya ketika dirasa sudah tidak ada lagi rombongan yang akan lewat. “Agaknya murid-murid Padepokan Sapta Dhahana telah dikerahkan untuk menutup setiap jalan keluar dari Padukuhan Klangon.”
“Kakang Agung Sedayu dan Ki Waskita pasti akan menemui kesulitan, jika tidak segera diberitahu,” sahut Glagah Putih sambil bangkit berdiri dan mengibas-kibaskan kain panjangnya yang terkena pasir tepian.
Sedangkan Ki Bango Lamatan tampak mengerutkan keningnya dalam-dalam. Katanya kemudian, “Kita harus berterima kasih kepada orang yang telah membawa kita ke tepian ini. Secara tidak langsung dia telah memberitahukan kepada kita, gerakan padepokan Sapta Dhahana yang akan mengepung banjar Padukuhan Klangon.”
Dada Ki Jayaraga dan Glagah Putih berdesir tajam begitu mendengar kata-kata Ki Bango Lamatan. Secara tidak langsung orang itu telah membantu mereka dengan memberitahukan bahaya besar yang akan mengancam jika mereka tetap bertahan di banjar padukuhan.
“Marilah kita segera kembali ke banjar,” berkata Ki Jayaraga kemudian sambil melangkah tergesa-gesa menaiki tebing, “Sesampainya di atas tebing, kita akan berlari kembali sesuai jalur yang telah ditunjukkan oleh orang tadi. Agaknya jalur tadi adalah jalan pintas. Semoga kita dapat mendahului rombongan orang-orang padepokan Sapta Dhahana.”
“Ya, Ki,” sahut Ki Bango Lamatan sambil mengikuti langkah Ki Jayaraga, “Ki Rangga dan Ki Waskita harus segera menyingkir sebelum kedatangan orang-orang itu.”
Glagah Putih yang melihat kedua orang tua itu telah menaiki tebing segera menyusul. Dengan cepat dia segera meloncat di antara batu-batu yang menjorok di lereng untuk menyusul kedua orang tua yang sudah hampir mencapai bibir tebing.
Dalam pada itu di banjar Padukuhan Klangon Ki Rangga dan Ki Waskita masih belum menyadari bahwa bahaya sedang mendekat ke arah mereka. Murid-murid perguruan Sapta Dhahana dari lereng Gunung Tidar secara bergelombang telah memasuki Padukuhan Klangon dari arah barat.
Namun kedua orang yang telah mempelajari ilmu dari sumber yang sama itu ternyata hampir bersamaan panggraita mereka telah menerima getaran-getaran isyarat yang mendebarkan.
Hampir bersamaan keduanya pun segera menyilangkan kedua tangan di depan dada. Sambil menundukkan kepala dalam-dalam dan memejamkan mata, keduanya berusaha memusatkan segenap nalar dan budi untuk memperjelas getaran-getaran isyarat yang mereka terima.
Sejenak kemudian keduanya telah tenggelam dalam pemusatan nalar dan budi. Namun baru beberapa saat berlalu, mereka berdua telah terganggu dengan kedatangan Ki Jayaraga bertiga.
Segera saja Ki Waskita menghentikan usahanya untuk mempertajam panggraitanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam dan mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada, Ki Waskita pun segera menyapa Ki Jayaraga bertiga.
“Bagaimana keadaan kalian bertiga?” bertanya Ki Waskita kemudian sambil mempersilahkan mereka bertiga untuk duduk di atas tikar, “Apakah semuanya dapat berjalan lancar?”
Ketiga orang itu saling pandang sejenak. Perhatian mereka masih tertuju kepada Ki Rangga yang tampak masih mencoba menghentakkan kemampuan panggraitanya untuk memantau keadaan di sekitar Padukuhan Klangon.
Melihat ketiga orang itu tidak menjawab dan justru telah tertarik melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ki Rangga, Ki Waskita pun kemudian berusaha memberikan penjelasan, “Ki Rangga sedang berusaha mempertajam panggraitanya. Agaknya tempat ini sudah tidak nyaman dan aman lagi bagi kita.”
“Benar, Ki Waskita,” tiba-tiba Ki Rangga menyahut sambil membuka kedua matanya dan mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada, “Sepertinya Padukuhan Klangon ini telah kedatangan banyak orang dari arah utara. Aku tidak tahu mereka berasal dari Perdikan Matesih ataukah Gunung Tidar.”
Mendengar Ki Rangga menyebut gunung Tidar, Ki Jayaraga segera beringsut maju. Katanya kemudian, “Ki Rangga, kami bertiga tadi sempat menjumpai murid-murid gunung Tidar sedang berbondong-bondong menuju ke Padukuhan Klangon,” Ki Jayaraga berhenti sebentar sambil memandang ke arah Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih yang tampak mengangguk-angguk. Lanjut Ki Jayaraga kemudian, “Bahkan kami sempat mendengar percakapan mereka. Murid-murid perguruan Sapta Dhahana itu memang sengaja dikirim ke Padukuhan Klangon untuk mengepung serta menutup semua jalan keluar terutama di banjar padukuhan ini.”
Kemudian secara singkat Ki Jayaraga segera menceritakan tentang orang aneh yang telah dengan sengaja menuntun mereka ke tepian kali Praga yang terletak di sebelah barat Perdikan Matesih.
Mendengar cerita Ki Jayaraga, tampak kening Ki Rangga berkerut-merut. Berbagai dugaan telah muncul dalam benaknya tentang orang yang dengan sengaja membawa ketiga orang itu ke tepian Kali Progo.
Namun Ki Rangga benar-benar tidak dapat menduga dengan pasti, siapakah sebenarnya orang itu.
“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian menyadarkan Ki Rangga dari lamunannya, “Apakah tidak sebaiknya kita segera menyingkir?”
Sejenak Ki Rangga memandang ke arah orang-orang yang berada di ruangan itu. Ketika semuanya terlihat mengangguk, Ki Rangga pun segera berkata, “Baiklah, kita segera berkemas. Besok pagi sebelum wayah pasar temawon, salah satu dari kita harus menghubungi Ki Gede Matesih agar membatalkan rencananya untuk mengundang kita.”
Hampir bersamaan yang lainnya telah mengangguk-angguk.
Demikianlah, sejenak kemudian kelima orang itu pun telah berkemas dan meninggalkan tempat itu melalui pintu butulan.
Ketika Ki Rangga sempat melihat para pengawal yang tertidur silang melintang di teritisan, Ki Rangga pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
“Sebuah sirep yang sangat halus,” desis Ki Rangga kemudian sambil berjalan di sebelah Ki Waskita, “Seseorang telah menebarkan sirep yang sangat halus sejak sore tadi. Hampir tidak ada seorang pun dari kita yang menyadarinya.”
“Ya, ngger,” sahut Ki Waskita sambil mendahului melangkahi tlundak pintu butulan di pagar belakang, “Aku hanya merasakan udara begitu sejuk dan sangat nyaman untuk beristirahat sehingga aku tidak menyadari bahwa seseorang telah menebarkan sirep.”
Glagah Putih yang mendengar kata-kata Ki Waskita hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala. Sementara Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan yang mempunyai pengalaman dalam hal ilmu yang dapat membuat orang kehilangan kesadaran itu justru telah tersenyum.
“Diperlukan ketelatenan dalam mengetrapkan sirep sejenis ini,” berkata Ki Jayaraga dalam hati, “Berbeda dengan sirep tajam yang dengan serta merta akan mempengaruhi orang dengan rasa kantuk yang tak tertahankan. Sirep halus ini harus terus menerus ditebarkan di sepanjang waktu dengan kekuatan yang tidak terlalu tajam untuk menyamarkan keberadaan sirep itu sendiri.”
Sedangkan Ki Bango Lamatan yang pernah menebarkan sirep di kediaman Ki Gede Menoreh beberapa waktu yang lalu telah berkata dalam hati, “Aku belum pernah mempelajari sirep jenis ini. Aku lebih senang menebarkan sirep yang langsung dapat membuat orang jatuh pingsan sehingga apa yang menjadi tujuan kita segera dapat tercapai,” Ki bango Lamatan berhenti berangan-angan sejenak. Kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ki Bango Lamatan pun meneruskan angan-angannya, “Namun dengan demikian jika ada seseorang yang mempunyai kemampuan mumpuni akan segera menyadari bahwa seseorang sedang menebarkan sirep.”
Tak terasa langkah-langkah mereka telah semakin jauh meninggalkan banjar Padukuhan Klangon.
Dalam pada itu, ketika ayam jantan telah berkokok untuk terakhir kalinya, banjar padukuhan itu benar-benar telah terkepung rapat dari segala penjuru. Tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari pengamatan murid-murid Padepokan Sapta Dhahana. Namun mereka belum menyadari bahwa buruan mereka telah lolos beberapa saat yang lalu.
Ketika kepungan itu semakin merapat dan mulai mendekati regol banjar, mereka pun mulai melihat sebuah keanehan. Tidak tampak seorang penjaga pun yang sedang berdiri di depan regol.
“He? Kemana perginya para penjaga itu?” geram Putut Jangkung yang memimpin pengepungan itu.
“Apakah mereka belum menyadari akan kehadiran kita?” bertanya kawannya yang bertubuh gemuk dan pendek, “Bukankah kita juga telah mengirimkan para cantrik untuk membantu Ki Dukuh?”
Putut Jangkung tidak menjawab. Sejenak dipicingkan kedua matanya untuk mempertajam penglihatannya. Jarak mereka dengan regol banjar itu hanya tinggal beberapa tombak saja, namun Putut Jangkung masih belum melihat seorang penjaga pun yang berdiri di sebelah menyebelah regol.
“Mereka tentu telah tertidur nyenyak di bawah selimut kain panjang mereka!” geram Putut Jangkung. Kemudian katanya kepada orang yang di sebelahnya, “Putut Pendek, ajak tiga cantrik untuk menemanimu melihat keadaan regol terlebih dahulu.”
“Baik kakang,” jawab Putut Pendek sambil memberi isyarat tiga orang cantrik di dekatnya untuk mengawaninya.
Tanpa meninggalkan kewaspadaan, keempat orang itu pun kemudian segera berjalan mengendap-endap mendekati regol. Masing-masing telah menggenggam tangkai senjata mereka dan setiap saat siap untuk dihunus.
“Sepi,” desis Putut Pendek begitu mereka telah semakin dekat dengan regol.
Salah satu cantrik dengan memberanikan diri telah meloncat ke samping regol. Dengan sangat hati-hati dia mencoba menjengukkan kepalanya ke dalam.
Apa yang dilihatnya kemudian benar-benar telah membuat cantrik itu mengumpat-umpat tak ada habis-habisnya. Di sebelah regol bagian dalam memang ada gardu penjagaan tempat para penjaga regol untuk sekedar melepas lelah. Namun gardu penjagaan itu kini telah dipenuhi oleh para cantrik dan pengawal Padukuhan Klangon yang sedang bertugas malam itu. Mereka terlihat tertidur dengan nyenyak. Ada yang tidur silang melintang di lantai gardu, namun ada juga yang tertidur hanya dengan bersandaran dinding.
Putut Pendek yang melihat cantrik itu justru segera melangkah dengan tergesa-gesa. Namun sebagaimana cantrik itu, Putut Pendek pun telah mengumpat dengan umpatan yang sangat kotor begitu mendapatkan para cantrik dan pengawal yang bertugas menjaga regol justru telah tertidur nyenyak.
“Orang-orang yang tak tahu diri!” geram Putut Pendek kemudian sambil menendang salah satu cantrik yang tertidur sambil bersandaran dinding.
Tentu saja cantrik itu terkejut bukan alang-kapalang merasakan sesuatu telah menghantam pinggulnya dengan keras.
“He?!” teriak cantrik itu sambil terlonjak dari duduknya. Dengan cepat dia segera melenting berdiri.
Namun cantrik itu justru telah membeku begitu menyadari siapa yang sedang berdiri di hadapannya dengan wajah merah padam, Putut Pendek dari perguruan Sapta Dhahana.
“Apa kerja kalian, he?!” terdengar Putu Pendek itu membentuk dengan suara menggelegar. Sementara para cantrik dan pengawal yang lainnya segera tersadar dari tidur nyenyak mereka begitu mendengar suara ribut-ribut.
Dalam pada itu Putut Jangkung yang mendengar suara ribut-ribut di regol segera melangkah mendekat. Yang dilihatnya kemudian adalah para cantrik dan pengawal Padukuhan Klangon yang berdiri dengan kebingungan sementara Putut Pendek telah membentak-bentak mereka tak henti-hentinya.
“Sudahlah, Pendek,” berkata Putut Jangkung kemudian sambil melangkah semakin dekat, “Tentu ada alasannya mengapa mereka telah meninggalkan tugas dan lebih memilih tidur di dalam gardu.”
Putut Pendek menarik nafas panjang untuk meredakan gejolak di dalam dadanya. Katanya kemudian sambil berpaling ke arah Putut Jangkung, “Kakang, tidak ada ampun bagi mereka yang telah melalaikan tugas. Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman yang setimpal, terutama para cantrik padepokan Sapta Dhahana.
Sedang para pengawal Padukuhan Klangon akan kita laporkan kepada Ki Dukuh.”
Putut Jangkung mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya kemudian, “Aku setuju dengan alasanmu itu. Namun kita juga tidak boleh menutup mata sebab musabab yang telah membuat mereka lalai dalam menunaikan tugas.”
“Maaf Kakang Jangkung,” tiba-tiba salah satu cantrik memberanikan diri maju selangkah ke depan, “Kami memang mengakui kesalahan kami. Namun apa yang telah terjadi ini benar-benar diluar kuasa kami. Kami merasakan udara tadi malam memang terasa sangat sejuk. Entah awalnya dari mana, tahu-tahu kami telah dikuasai oleh kantuk yang perlahan–lahan mulai menyergap dan membelenggu kami sejak saat sirep bocah tadi.”
Putut Pendek akan menanggapi kata-kata cantrik itu, namun dengan cepat Putut Jangkung memberi isyarat untuk berdiam diri. Berkata Putut Jangkung kemudian, “Mungkin kalian telah terpengaruh oleh sirep atau sejenisnya yang dapat membuat kalian terserang kantuk tak tertahankan,” Putut Jangkung berhenti sebentar. Lanjutnya kemudian, “Sebelum Matahari terbenam sore tadi, memang Raden Wirasena telah menerima laporan akan kedatangan orang asing di Padukuhan Klangon ini. Untuk itulah Raden Wirasena telah meminta bantuan Guru agar mengutus beberapa murid padepokan Sapta Dhahana untuk menghubungi dan membantu Ki Dukuh. Ternyata Ki Dukuh pun telah menyanggupi dan menyiapkan para pengawal Dukuh Klangon untuk berjaga-jaga bersama para cantrik di banjar padukuhan. Ternyata kalian di sini hanya pindah tidur saja.”
Para cantrik dan pengawal dukuh Klangon itu semakin menundukkan kepala mereka. Entah apa jawab mereka nantinya jika Ki Dukuh menanyakan hal itu.
“Sudahlah,” tiba-tiba Ki Brukut yang telah berada di samping Putut Jangkung menyela, “Yang terpenting sekarang ini adalah keberadaan orang-orang asing itu. Apakah mereka masih berada di dalam banjar?”
Bagaikan disambar halilintar di siang bolong, serentak Putut Jangkung dan Putut Pendek segera meloncat dan berlari menuju ke dalam banjar.
Setelah melewati pendapa yang tidak begitu luas, dengan tergesa-gesa keduanya telah mendorong pintu pringgitan dengan kasar. Ketika keduanya kemudian telah sampai di ruang dalam, yang mereka jumpai hanyalah selembar tikar usang yang terhampar di tengah-tengah ruangan.
“Setan gendruwo, tetekan!” geram Putut Jangkung sambil berjalan mengitari ruangan. Tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk pada sebuah lobang yang tidak seberapa besar yang terdapat di pojok ruangan.
“Lubang ini terlihat masih baru,” desis Putut Jangkung sambil meraba sudut dinding kayu itu, “Seseorang dengan sengaja telah membuat lubang ini dengan suatu tujuan.”
Sedang Putut Pendek dan Ki Brukut yang datang kemudian ternyata lebih memilih menelusuri dapur untuk kemudian lewat pintu butulan ke halaman belakang.
Ternyata di halaman belakang pun kedua orang itu juga dikejutkan oleh para pengawal padukuhan yang terlihat sedang tidur silang melintang di teritisan.
“Sirep,” hampir bersamaan kedua orang itu berdesis.
“Siapakah yang telah menebarkan sirep ini?” tiba-tiba Putut Pendek mengajukan sebuah pertanyaan.
Sejenak Ki Brukut termenung. Jawabnya kemudian, “Tidak menutup kemungkinan orang-orang asing itulah yang telah menebarkan sirep dalam usaha mereka untuk meloloskan diri.”
“Tapi menurut cerita para cantrik dan pengawal yang berjaga di regol depan tadi, mereka merasa di serang kantuk mulai saat sirep bocah,” sela Putut Pendek.
“Entahlah,” akhirnya Ki Brukut menggeleng lemah, “Namun yang jelas kelima orang itu telah pergi dan kita harus memberi jawaban kepada Raden Wirasena dan Kiai Damar Sasangka.”
Berdesir dada Putut Pendek. Jika mereka para cantrik perguruan Sapta Dhahana itu tidak mampu menunaikan tugas karena kelalaian atau ketidak-mampuan mereka, tentu tidak segan-segan guru mereka, Kiai Damar Sasangka, akan memberikan hukuman.
“Sebaiknya kita segera mengirim isyarat,” berkata Putut Pendek kemudian sambil melangkah kembali memasuki bangunan induk banjar.
“Sebaiknya memang demikian,” sahut Ki Brukut sambil mengikuti langkah Putut Pendek, “Dengan demikian Raden Wirasena segera dapat mengambil tindakan dan langkah-langkah berikutnya.”

Demikianlah setelah berunding terlebih dahulu dengan Putut Jangkung, Putut Pendek segera memerintahkan seorang cantrik yang membawa busur dan anak panah sendaren untuk segera mengirim isyarat ke Gunung Tidar.
Sejenak kemudian kesunyian dini hari langit Padukuhan Klangon itu pun telah dipecahkan oleh suara panah sendaren yang meraung-raung dua kali berturut-turut.
Dalam pada itu langit di sebelah timur telah menampakkan cahaya semburat kemerahan. Mendung sisa hujan semalam telah tertiup angin dan bergerak berarak-arak ke arah selatan. Mungkin menjelang pasar temawon hujan akan turun di laut selatan.
Di Perdikan Matesih, seorang pengawal yang sedang berjaga di sebuah gardu perondan telah mendengar isyarat itu. Dengan bergegas diambilnya busur dan anak panah sendaren yang disimpan di gardu perondan. Namun sebelum tangannya meraih busur dan anak panah itu, terdengar seseorang bergumam di belakangnya.
Ketika dia kemudian memutar tubuhnya, tampak Kepala pengawal Perdikan Matesih berdiri hanya dua langkah di depannya dengan kedua tangan bertolak pinggang.
“Ki Wiyaga,” desis pengawal itu mencoba menyapa.
Ki Wiyaga, kepala pengawal Perdikan Matesih itu tersenyum hambar. Tanyanya kemudian, “Untuk apa engkau akan mengambil busur dan anak panah sendaren itu?”
Pengawal itu tidak menjawab. Dia belum yakin, di pihak manakah Ki Wiyaga berdiri. Memang keadaan di Perdikan Matesih saat itu tidak menentu, terutama para perangkatnya telah terpecah menjadi dua.
Sebagian telah ikut arus para pengikut Trah Sekar Seda Lepen, sedangkan sisanya masih bersetia kepada Ki Gede Matesih sebagai kawula Mataram.
“Engkau tidak usah termakan janji-janji ngayawara itu, Lajuwit,” terdengar suara ki Wiyaga berat dan dalam, “Mereka adalah segolongan orang-orang yang sedang kalap dan edan kamukten. Apapun akan diterjang demi meraih mimpi mereka tanpa menyadari bahwa hari sudah menjelang siang dan bukan waktunya lagi bagi mereka untuk bermimpi.”
Lajuwit termenung sejenak. Ada sedikit kebimbangan di dalam hati untuk sekedar menyampaikan apa yang menjadi ganjalan hatinya.
Agaknya Ki Wiyaga dapat membaca raut wajah Lajuwit yang gelisah. Maka katanya kemudian, “Lajuwit, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang tersirat di dalam hatimu. Mungkin pandangan kita berbeda. Namun setelah engkau menyampaikan apa yang telah menjadi arah kiblatmu selama ini, kita dapat saling berbagai dan mempelajari, arah manakah sebenarnya yang paling masuk akal untuk kita ikuti?”
Kembali Lajuwit termenung namun hanya sekejap. Katanya kemudian, “Ki Wiyaga, sebenarnya janji-janji yang disampaikan oleh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu terlalu jauh dari kenyataan. Namun jika kita tetap berharap akan adanya perubahan hidup kita dibawah pemerintahan yang sekarang ini, sepertinya itu juga sebuah mimpi. Kedua-duanya bagiku memang hanya sebatas mimpi, namun jika aku mengikuti Trah Sekar Seda Lepen, setidaknya aku telah menggantungkan sebuah harapan, bukan sekedar mimpi sebagaimana yang telah terjadi saat ini.”
Ki Wiyaga menarik nafas dalam-dalam. Dilemparkan pandangan matanya ke jauh ke depan, ke arah tanah pesawahan yang terbentang luas yang mulai digarap.
“Lajuwit,” berkata Ki Wiyaga kemudian sambil tangan kanannya menunjuk jauh ke tanah pesawahan, “Lihatlah tanah pesawahan yang luas itu. Itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah kenyataan yang harus kita garap, kita kelola sehingga pada saatnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Manfaat yang dapat dipetik turun temurun sampai anak cucu kita.”
Namun jawaban Lajuwit sungguh diluar dugaan kepala pengawal Perdikan Matesih itu.
Jawab Lajuwit kemudian, “Maafkan aku Ki Wiyaga. Bagiku tanah pesawahan itu bukan kenyataan lagi, tapi itu mimpi buruk yang akan terus menghantui sampai anak cucu kita nanti. Tanah-tanah itu dulunya milik para petani, namun kini para tuan tanahlah yang menguasai. Di musim kemarau ketika petak-petak sawah tidak dapat menghasilkan lagi, sedangkan para petani mempunyai keluarga dan anak-anak yang mulut mereka harus tetap disuapi setiap hari, mereka pun tidak mempunyai pilihan lagi. Atau membiarkan saja anak dan istri kelaparan dan mati sehingga hidup merekapun tidak akan berarti lagi.”
“Cukup!” bentak Ki Wiyaga, “Tidak usah menggurui aku. Aku tahu para petani telah terlilit hutang sampai mencekik leher mereka sendiri. Akhirnya sepetak sawah sebagai sumber hidup mereka pun kini sudah terjual kepada para tuan tanah itu dan kini mereka menjadi buruh di atas tanah mereka sendiri. Tapi itu semua akibat dari cara hidup mereka sendiri. Disaat panen mereka tidak berusaha berhemat sehingga di saat musim kering tiba, mereka menjadi kelaparan dan akhirnya hanya menggantungkan hutang kepada para tuan tanah itu.”
Lajuwit hanya berdiam diri saja mendengar bentakan Ki Wiyaga. Namun diam-diam dia telah mempersiapkan diri. Apa boleh buat, jika perselisihan tidak dapat dihindarkan lagi, dia telah menyiapkan dirinya lahir maupun batin.
“Nah,” berkata Ki Wiyaga kemudian, “Agaknya memang kita telah berselisih jalan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersetia kepada Ki Gede Matesih sebagai kawula Mataram.”
Mendengar kata-kata terakhir kepala pengawal Perdikan Matesih ini, Lajuwit sudah dapat menduga akhir dari perdebatan itu. Maka katanya kemudian, “Maafkan aku Ki Wiyaga. Aku sudah terlanjur mengikatkan diriku dengan Trah Sekar Seda Lepen. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.”
Selesai berkata demikian Lajuwit segera menggeser kaki kanannya selangkah ke samping. Sedangkan kedua tangannya telah terkepal di kedua sisi lambungnya.
Ki Wiyaga yang melihat Lajuwit telah mempersiapkan diri, tidak ingin ketinggalan. Maka segera saja Ki Wiyaga menekuk lutut salah satu kakinya sambil bergeser setapak ke belakang.
Ternyata Lajuwit tidak ingin membuang-buang waktu. Dia harus segera mengirim panah sendaren untuk menyambung pesan yang telah diterimanya dari Padukuhan Klangon. Maka sambil membentuk keras, serangannya pun telah meluncur mengarah dada.
Tentu saja Ki Wiyaga tidak ingin dadanya rontok mendapat serangan lawan. Dengan sedikit menggeser kakinya ke samping serangan kaki lawannya itu lewat sejengkal dari dadanya. Kemudian dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, tangan kiri Ki Wiyaga pun mencoba menangkap pergelangan kaki Lajuwit.
Menyadari lawannya mencoba menangkap pergelangan kakinya, Lajuwit segera mengubah arah serangannya. Ketika kaki kanannya sedang terjulur lurus, tiba-tiba saja lututnya telah ditekuk. Kemudian dengan bertumpu pada tumit kaki yang lainnya, tubuhnya pun berputar untuk mengarahkan lututnya menghantam dada lawan.
Terkejut Ki Wiyaga mendapat serangan susulan itu. Namun kepala pengawal Perdikan Matesih itu tidak menjadi gugup. Dengan cepat tangannya yang sedianya akan menangkap pergelangan kaki lawan itu segera ditarik dan disilangkan di depan dadanya.
Sejenak kemudian terjadilah benturan yang cukup keras. Kedua-duanya telah meloncat ke belakang untuk mengambil jarak.
Untuk sejenak Ki Wiyaga termangu-mangu. Sebenarnyalah Ki Wiyaga sebagai kepala pengawal Perdikan Matesih merasa sayang. Lajuwit adalah salah seorang pengawal Perdikan Matesih yang dapat diandalkan karena Lajuwit pernah berguru dan menimba ilmu di padepokan Sapta Dhahana. Padepokan yang terletak di lereng Gunung Tidar di sebelah timur Perdikan Matesih.
“Ki Wiyaga,” tiba-tiba terdengar Lajuwit bertanya begitu melihat kepala pengawal itu termangu-mangu sejenak, “Apakah Ki Wiyaga berubah pikiran? Ingat, Perguruan gunung Tidar telah berdiri di belakang perjuangan Trah Sekar Seda Lepen. Aku kira Ki Wiyaga cukup menyadari kekuatan yang tersembunyi di Gunung Tidar. Kekuatan yang aku yakin akan mampu mengimbangi Mataram.”
“Cukup!” kembali Ki Wiyaga membentak, “Kita buktikan dulu semua itu.”
Selesai berkata demikian, Ki Wiyaga segera mempersiapkan serangannya. Bagaikan tatit yang meloncat di udara, tubuh Ki Wiyaga pun melesat ke depan dengan sebuah serangan yang mengarah ke ulu hati.
Demikianlah sejenak kemudian pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya adalah pengawal Perdikan Matesih yang dapat dibanggakan, namun yang ternyata mempunyai kiblat yang berbeda sehingga harus berselisih jalan.
Dalam pada itu, tanpa mereka sadari, beberapa pasang mata sedang mengawasi jalannya pertempuran itu. Orang-orang yang sedang bersembunyi di balik tanggul dekat gardu perondan itu telah melihat dan mendengar semua yang telah terjadi.
“Itulah gambaran keadaan para perangkat Perdikan Matesih sekarang ini,” desis orang yang usianya sudah lewat setengah abad namun masih tampak muda dan gagah, “Ki Gede Matesih benar-benar prihatin dengan keadaan kawulanya. Apalagi para perangkat tanah perdikan sudah banyak yang terpengaruh dengan janji-janji Raden Mas Harya Surengpati.”
“Kakang,” tiba-tiba terdengar seorang yang masih cukup muda menyela, “Bagaimana jika kita datangi saja rumah tempat kediaman Raden Surengpati itu di Matesih dan kita hancurkan?”
“Tidak semudah itu Glagah Putih,” jawab orang itu, “Dengan demikian kita akan memancing para pengikut Trah Sekar Seda Lepen serta para Cantrik perguruan Sapta Dhahana turun berbondong-bondong ke Perdikan Matesih. Kita akan kesulitan untuk melawan mereka semua.”
“Ki Rangga,” tiba-tiba seseorang yang sudah tua menyahut cepat, “Kita harus ikut mencegah berita lolosnya kita dari banjar padukuhan itu sampai ke telinga orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen.”
“Benar Ki Jayaraga,” jawab orang itu yang ternyata Ki Rangga Agung Sedayu, “Aku mempunyai rencana, selagi para murid padepokan Sapta Dhahana dan para pengawal Padukuhan Klangon disibukkan di banjar Padukuhan Klangon, kita dapat bergerak menyelidiki keadaan di Gunung Tidar.”
“Bagaimana rencana kakang?” sela Glagah Putih tidak sabar.
Ki Rangga menarik nafas panjang terlebih dahulu sebelum menjawab. Dilemparkan pandangan matanya kearah pertempuran antara kedua pengawal perdikan Matesih itu. Tampak Ki Wiyaga sedikit demi sedikit mulai tampak menguasai jalannya pertempuran.
“Kita sebaiknya berpencar untuk menghindari kemungkinan adanya pengamatan para telik sandi lawan,” berkata Ki Rangga kemudian, “Kita akan bergerak dalam dua kelompok. Aku akan bersama dengan Ki Waskita bergerak menyusur ke arah timur lereng Gunung Tidar. Sementara Ki Jayaraga, Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih menyusur sebelah barat lereng Gunung Tidar.”
Tampak kepala orang-orang yang berada di situ terangguk-angguk. Agaknya semuanya setuju dengan rencana Ki Rangga.
“Ngger,’ tiba-tiba Ki Waskita berkata setelah mereka terdiam sejenak, “Bagaimana dengan Ki Gede Matesih? Ki Gede telah berencana untuk mengundang kita sebagai tamu-tamunya, namun ternyata keadaan telah berkembang lain. Kita harus memberitahu perkembangan keadaan ini kepada ki Gede.”
Mendengar pertanyaan Ki Waskita itu, tanpa sadar Ki Rangga telah berpaling ke medan pertempuran antara kedua pengawal itu. Agaknya orang-orang itu dapat membaca pikiran Ki Rangga. Maka kata Ki Waskita kemudian, “Sebuah pemikiran yang bagus, ngger. Kita akan meminta Ki Wiyaga untuk memberitahu Ki Gede.”
Yang mendengar kata-kata Ki Waskita itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka.
Demikianlah sejenak kemudian, Ki Wiyaga benar-benar telah menguasai pertempuran. Lajuwit yang berbadan tinggi besar itu tidak mampu mengatasi kelincahan Ki Wiyaga yang berbadan sedikit lebih pendek. Pengalaman serta ketekunan yang dimiliki oleh kepala pengawal Perdikan Matesih itu selama ini ternyata telah menunjukkan hasil yang gemilang. Lajuwit benar-benar sudah hampir tak berdaya.
Ketika sebuah pukulan kembali mendarat di bagian tubuh Lajuwit, salah satu pengawal yang pernah menimba ilmu di Perguruan Sapta Dhahana itu telah terhuyung-huyung ke samping. Dengan menggeretakkan giginya, Lajuwit mencoba memperbaiki kedudukannya. Namun sebelum tubuhnya benar-benar berdiri tegak, ujung tumit kaki Ki Wiyaga telah mendarat di lambungnya.
Terdengar keluhan tertahan dari mulut Lajuwit. Tanpa dapat dikendalikan lagi, tubuhnya pun terdorong beberapa langkah ke belakang sebelum akhirnya jatuh terlentang di atas tanah.
Ki Wiyaga yang melihat lawannya telah terlempar dan jatuh terlentang di atas tanah telah menghentikan serangannya.
Namun yang terjadi kemudian benar-benar diluar dugaan Ki Wiyaga maupun orang-orang yang bersembunyi di balik tanggul itu. Lajuwit yang terlihat sudah tak berdaya itu, tiba-tiba dengan susah payah telah bangkit berdiri. Dengan berdiri sedikit terhuyung-huyung salah satu tangannya telah mengambil sesuatu dari balik bajunya. Belum sempat Ki Wiyaga menyadari apa yang akan dilakukan oleh Lajuwit, tiba-tiba saja dua buah pisau kecil berwarna gelap telah meluncur menyambar dadanya.
Jarak Lajuwit dengan Ki Wiyaga hanya sekitar empat langkah sehingga Ki Wiyaga benar-benar sedang dalam kesulitan. Sambaran pisau yang pertama masih sempat dihindarinya dengan memiringkan tubuhnya, namun pisau yang kedua telah berhasil menyambar pundaknya.
Terdengar Ki Wiyaga berdesis tertahan. Mulutnya tampak menyeringai menahan rasa pedih yang menyengat pundaknya. Luka itu memang tidak terlalu dalam, namun darah yang mengalir dari luka itu berwarna kehitam hitaman.
“Racun!” seru Ki Wiyaga sambil berusaha menekan sekitar luka itu agar racun yang terlanjur memasuki tubuhnya tidak menjalar mengikuti arus darahnya.
Melihat Ki Wiyaga sibuk dengan lukanya, Lajuwit ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat diraihnya lagi sebilah pisau belati dari balik bajunya. Sambil tertawa penuh rasa kemenangan, sekali lagi sebuah pisau meluncur dari tangannya mengarah ke leher Ki Wiyaga.
Namun di saat yang menentukan itu, tiba-tiba saja dari balik tanggul di dekat gardu perondan meluncur sebuah batu sebesar kepalan orang dewasa menyongsong pisau belati yang mengarah ke leher Ki Wiyaga.
Sejenak kemudian terdengar benturan yang cukup keras. Batu sebesar kepalan orang dewasa itu telah menghantam pisau belati itu. Akibatnya adalah diluar dugaan semua orang. Kekuatan lontaran batu yang berlebihan itu ternyata telah menghantam balik pisau belati itu kembali ke pemiliknya. Arah lontaran batu itu memang segaris dengan arah pisau belati itu. Tanpa dapat dicegah lagi, pisau belati itu pun dengan deras berbalik ke pemiliknya dan dengan tepat menghunjam jantungnya.
Lajuwit hanya sempat mengeluh pendek sebelum tubuhnya terdorong selangkah ke belakang. Sejenak tubuh tinggi besar itu masih limbung sebelum akhirnya jatuh terjerembab tidak bernafas lagi.
Dalam pada itu kelima orang yang bersembunyi di balik tanggul itu pun telah terkejut bukan alang kepalang, terutama Ki Rangga Agung Sedayu. Dengan segera mereka pun kemudian berloncatan keluar dari persembunyian mereka dan berlari menuju ke bekas medan pertempuran kedua pengawal itu.
Ki Rangga segera berlari ke tempat Ki Wiyaga yang tampak terjatuh pada kedua lututnya. Wajahnya pucat serta bibirnya bergetar menahan sakit di pundaknya akibat racun yang mulai menjalar di aliran darahnya. Pandangan matanya mulai gelap dan kesadarannya pun perlahan menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang limbung.
Dengan cepat Ki Rangga segera menangkap tubuh ki Wiyaga yang terlihat mulai limbung akan terjatuh. Setelah dibaringkan di atas tanah, dengan cekatan jari-jemari Ki Rangga segera memijat urat-urat nadi yang berada di sekitar pundak Ki Wiyaga agar racun itu tidak menjalar semakin jauh.
“Kakang,” bisik Glagah Putih yang telah ikut berlutut di sisi tubuh Ki Wiyaga, “Ini barangkali dapat membantu kakang.”
Ki Rangga berpaling. Dilihatnya Glagah Putih mengangsurkan sebuah cincin bermata batu yang berwarna kebiru-biruan dengan garis-garis putih di dalamnya.
Sejenak Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam sambil tersenyum. Cincin bermata batu itu mengingatkan Ki Rangga kepada gurunya, Kiai Gringsing.
“Terima kasih Glagah Putih,” berkata Ki Rangga kemudian sambil menerima uluran tangan Glagah Putih. Dengan tanpa membuang waktu lagi, ditempelkannya batu yang terdapat pada cincin itu di luka Ki Wiyaga.
Beberapa saat kemudian, tampak warna garis-garis putih di dalam batu itu berubah menjadi kehitam-hitaman, sedangkan luka yang terdapat di pundak Ki Wiyaga pun berangsur-angsur mulai mengalirkan darah yang berwarna merah segar, tidak lagi kehitam-hitaman.
“Syukurlah,” berkata Ki Rangga kemudian sambil mengangkat cincin itu dari luka ki Wiyaga dan kemudian mengembalikannya kepada Glagah Putih, “Agaknya Yang Maha Agung telah mengabulkan permohonan dan usaha kita.”
“Ya ngger,” terdengar suara Ki Waskita yang telah ikut berlutut di sisi tubuh Ki Wiyaga, “Racun ini sangat kuat dan jahat. Agaknya orang-orang Gunung Tidur memang senang bermain-main dengan racun.”
Ki Rangga menganggukkan kepalanya sambil tangannya sibuk menaburkan sejenis bubuk berwarna kehijau-hijaun di atas luka Ki Wiyaga. Sejenak kemudian luka itu pun telah mampat walaupun masih belum sempurna.
“Glagah Putih,” berkata Ki Rangga kemudian tanpa berpaling, “Tolong carikan air.”
“Baik kakang,” jawab Glagah Putih dengan serta merta sambil bangkit berdiri.
Sepeninggal Glagah Putih, Ki Waskita segera berbisik, “Ngger. Agaknya tenaga lontaranmu terlalu kuat sehingga pisau itu telah berbalik arah dan mengenai orang itu sendiri.”
Ki Rangga menarik nafas panjang sambil mengangkat kepalanya. Dilihatnya Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan sedang melihat keadaan Lajuwit yang telah terbujur menjadi mayat. Ada rasa penyesalan di dalam hati ki Rangga, namun semua itu dilakukan tanpa kesengajaan sama sekali. Ki Rangga tidak menduga bahwa pengawal itu akan berbuat curang selagi Ki Wiyaga lengah.
“Aku betul-betul tidak sengaja, Ki Waskita,” berkata Ki Rangga kemudian sambil membebat luka yang ada di pundak Ki Wiyaga dengan secarik kain yang didapat dari sobekan kain panjang kepala pengawal itu, “Aku benar-benar dicengkam kecemasan yang luar biasa begitu melihat pisau berikutnya itu meluncur ke arah leher Ki Wiyaga yang sedang tak berdaya.”
Ki Waskita tidak menjawab hanya tampak kepalanya saja yang terangguk-angguk. Sementara Glagah Putih telah datang sambil membawa kendi yang penuh berisi air.
“Dari mana engkau dapatkan kendi ini, Glagah Putih?” bertanya Ki Rangga sambil menerima kendi itu dari tangan adik sepupunya itu.
Glagah Putih tersenyum sambil kembali berlutut. Jawabnya kemudian, “Di setiap gardu perondan pasti disiapkan air minum, namun kadang sudah kosong tidak ada isinya. Untunglah kendi ini masih cukup banyak isinya.”
Ki Rangga tersenyum sambil mengambil sebutir obat yang berwarna hijau dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian katanya kepada Glagah Putih, “Bantu aku mengangkat kepalanya.”
Dengan cepat Glagah Putih segera menyangga kepala Ki Wiyaga. Sementara Ki Rangga telah membuka mulut Ki Wiyaga dan memasukkan sebutir obat yang berwarna hijau itu ke dalam mulutnya. Sambil memijat urat leher Ki Wiyaga dengan tangan kirinya, tangan kanan Ki Rangga meraih kendi berisi air itu dan menuangkan isinya perlahan-lahan ke mulut Ki Wiyaga. Sejenak kemudian obat itu pun telah memasuki perut Ki Wiyaga.
“Turunkan,” perintah Ki Rangga kepada Glagah Putih. Dengan perlahan Glagah Putih pun kemudian menurunkan kepala Ki Wiyaga kembali ke atas tanah.
Demikianlah Ki Rangga pun kemudian segera berusaha untuk menyadarkan Ki Wiyaga. Dengan pijatan perlahan di belakang lehernya, Ki Wiyaga pun tampak mulai menunjukkan tanda-tanda kesadarannya.
Ketika sekali lagi Ki Rangga mengusap tengkuknya, Ki Wiyaga pun telah berdesah perlahan sambil menarik nafas panjang dan menggeliat. Ketika Ki Wiyaga pertama kali membuka matanya, yang tampak kemudian hanyalah bayangan kabur beberapa orang yang sedang mengerumuninya.
Setelah mengerjap-kerjapkan matanya beberapa kali, barulah Ki Wiyaga melihat dengan jelas orang-orang yang sedang mengerumuninya, namun tak satu pun dari mereka yang dikenalnya.
“Siapa?’ bertanya Ki Wiyaga kemudian sambil mencoba bangkit berdiri. Ki Rangga pun segera membantu kepala pengawal perdikan Matesih itu untuk duduk.
“Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian setelah melihat Ki Wiyaga duduk dengan sempurna, “Kami berlima adalah para pengembara dari Prambanan yang kebetulan saja sedang lewat di tempat ini dan melihat kalian sedang bertempur.”
Terkejut Ki Wiyaga mendengar pengakuan Ki Rangga. Tanpa sadar diedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Ketika pandangan matanya kemudian tertumbuk pada Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan yang sedang mengangkat jasad Lajuwit untuk dibawa ke gardu, wajah Ki Wiyaga pun telah menegang.
“Apa yang telah mereka lakukan pada Lajuwit?” pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir ki Wiyaga.
“Tenanglah Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian sambil menahan tubuh kepala pengawal itu yang tiba-tiba saja akan bangkit berdiri, “Temanmu itu telah mati terkena pisau beracunnya sendiri.”
“He?” seru Ki Wiyaga seakan tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Sambil berpaling ke arah Ki Rangga, dia melanjutkan pertanyaannya, “Bagaimana itu bisa terjadi?”
Orang-orang yang sedang mengerumuni Ki Wiyaga itu saling pandang sejenak. Ki Rangga lah yang akhirnya menjawab, “Ki Sanak, dia kurang hati-hati mempergunakan pisau belatinya yang sangat beracun itu sehingga telah merenggut nyawanya sendiri.”
Ki Wiyaga mengerutkan keningnya mendengar penjelasan ki Rangga. Pada saat dia sibuk dengan lukanya beberapa saat tadi, dia telah mendengar sebuah benturan. Namun selanjutnya dia sudah tidak ingat lagi.
“Sudahlah Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian sambil membantu Ki Wiyaga ketika kepala pengawal itu mencoba bangkit dari duduknya, “Sekarang sebaiknya segera kita selenggarakan jasad pengawal itu.”
“Ya Ki Wiyaga,” sahut Ki Waskita, “Bukankah nama Ki Sanak, Ki Wiyaga? Kepala pengawal Perdikan Matesih?”
Ki Wiyaga yang sudah berdiri di atas kedua kakinya berpaling ke arah Ki Waskita. Pertanyaan Ki Waskita tidak dijawabnya, justru dia telah balik bertanya, “Dari mana Ki Sanak mengetahuinya?”
Ki Waskita tersenyum. Jawabnya kemudian, “Sedari tadi kami sudah berada di balik tanggul dekat gardu itu.”
Ki Wiyaga termangu-mangu. Berbagai dugaan muncul dalam benaknya tentang kelima orang yang mengaku berasal dari Prambanan itu.
Ketika Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan kemudian berjalan mendekat, Ki Wiyaga pun tiba-tiba telah melangkah mundur sambil berdesis, “Siapakah kalian ini sebenarnya?”
“Ki Wiyaga,” jawab Ki Rangga sambil maju selangkah, “Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ki Waskita tadi, kami berlima adalah pengembara dari Prambanan. Kami tidak akan mengganggu keberadaan Perdikan Matesih, justru kami ingin membantu tanah Perdikan Matesih ini.”
Kepala pengawal perdikan Matesih itu sejenak mengerutkan keningnya. Tentu saja dia tidak dapat mempercayai keterangan Ki Rangga begitu saja. Tanah Perdikan Matesih sedang mengalami goncangan dan setiap orang dapat saja mengaku sebagai kawan atau bahkan lawan.
“Ki Wiyaga,” berkata Ki Rangga selanjutnya begitu menyadari keragu-raguan tampak menyelimuti wajah Ki Wiyaga, “Percayalah, kami berlima tidak mempunyai maksud jelek, jika kami adalah bagian dari orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen itu, tentu kami akan membiarkan saja Ki Wiyaga terluka dan mati direnggut oleh racun yang sangat kuat dan jahat.”
Terkejut Ki Wiyaga mendengar keterangan Ki Rangga. Tanpa sadar dia meraba pundak kirinya yang dibebat dengan sobekan kain panjangnya sendiri. Menyadari akan keterlanjurannya, Ki Wiyaga pun segera maju mendekati Ki Rangga.
“Maafkan akan keterlanjuranku Ki Sanak,” berkata Ki Wiyaga kemudian sambil berjalan memutar dan menjabat tangan kelima orang itu. Ki Rangga dan kawan-kawannya pun kemudian menyambut uluran tangan Ki Wiyaga sambil satu-persatu menyebutkan nama mereka.
“Nah, Ki Sedayu,” berkata Ki Wiyaga kemudian setelah mengetahui nama Ki Rangga, “Apakah yang dapat aku bantu?”
Sejenak Ki Rangga memandang ke arah kawan-kawannya, namun agaknya kali ini terutama Ki Waskita telah menyerahkan purba wasesa kepada Ki Rangga. Maka jawab Ki Rangga kemudian, “Hari telah semakin terang. Sebaiknya jasad pengawal itu segera dikuburkan.”
“Apakah pengawal itu mempunyai keluarga?” tiba-tiba Glagah Putih bertanya.
Ki Wiyaga menggeleng. Jawabnya kemudian, “Sebenarnya Lajuwit bukanlah orang Matesih. Dia datang entah dari mana dan berguru ke padepokan Sapta Dhahana. Selang beberapa saat kemudian setelah dia merasa cukup menimba ilmu, dia telah turun gunung dan menetap di Matesih.”
“Dan kemudian menjadi salah satu pengawal perdikan Matesih,” sahut Glagah Putih.
“Aku lah yang telah mengusulkan kepada Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga dengan serta merta, “Karena aku melihat kemampuannya yang lebih dari cukup untuk membantu menjaga keamanan di Matesih.”
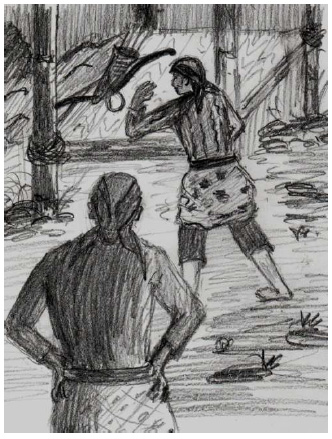
“Nah, sekarang bagaimana dengan mayat itu?” sekarang giliran Ki Jayaraga yang bertanya.
Mendapatkan pertanyaan Ki Jayaraga, Ki Wiyaga pun segera berpaling ke arah Ki Rangga.
“Ki Wiyaga,” berkata Ki Rangga kemudian, “Sebaiknya engkau melaporkan kejadian ini terlebih dahulu kepada Ki Gede. Demikian juga dengan keberadaan kami berlima. Sampaikan kepada Ki Gede bahwa Ki Gede tidak usah mengirim utusan untuk menjemput kami di banjar Padukuhan Klangon. Sampaikan kepada Ki Gede bahwa kami berlima telah memutuskan untuk lolos dari banjar karena menjelang dini hari tadi, banjar Klangon telah dikepung oleh murid-murid dari perguruan Sapta Dhahana.”
Terkejut Ki Wiyaga mendengar keterangan Ki Rangga. Dengan segera dia membungkukkan badannya dalam-dalam sambil berkata, “Maafkan aku yang terlalu deksura terhadap kalian berlima. Aku tidak tahu kalau ternyata kalian adalah tamu-tamu Ki Gede. Sesungguhnya aku telah ditugasi oleh Ki Gede untuk menjemput kalian berlima nanti menjelang saat pasar temawon.”
“Sudahlah Ki Wiyaga,” sahut Ki Jayaraga sambil tertawa pendek, “Kami bukan para bangsawan yang harus dihormati dengan berlebihan. Kami memang masih terhitung saudara jauh dari Ki Gede.”
Ki Wiyaga mengangguk-anggukkan kepalanya. Diam-diam dalam hati Ki Wiyaga bersyukur. Agaknya kelima tamu Ki Gede ini yang akan membantu mengurai benang kusut yang sedang terjadi di Perdikan Matesih.
“Nah, sekarang apakah Ki Sanak berlima akan pergi ke kediaman Ki Gede?” bertanya Ki Wiyaga kemudian.
“O, tidak, tidak,” jawab Ki Rangga dengan serta merta, “Kami masih ada urusan yang harus kami selesaikan. Sampaikan kepada Ki Gede, setelah urusan kami selesai, kami pasti akan menghadap.”
Ki Wiyaga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tidak berani bertanya lebih jauh tentang urusan kelima orang itu.
“Sebaiknya jasad pengawal itu disembunyikan terlebih dahulu sambil menunggu arahan Ki Gede,” berkata Ki Rangga kemudian setelah sejenak mereka terdiam.
“Ki Rangga benar,” sahut Ki Waskita, “Ki Wiyaga dapat memohon arahan Ki Gede tentang jasad pengawal itu, dan jika memang harus dikuburkan, Ki Wiyaga dapat meminta bantuan kawan-kawan Ki Wiyaga yang dapat dipercaya.”
Ki Wiyaga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
“Marilah,” berkata Ki Rangga kemudian sambil melangkah mendekati gardu, “Kita sembunyikan jasad pengawal itu di bawah gardu.”
Demikianlah sejenak kemudian orang–orang itu segera menyembunyikan mayat itu di bawah gardu. Glagah Putih telah mencari rumput-rumput kering untuk menimbuni mayat itu agar tidak terlihat apabila ada orang yang lewat di sekitar tempat itu.
Setelah pekerjaan itu selesai, mereka pun segera berpencar, Ki Wiyaga berjalan menuju ke kediaman Ki Gede, sedangkan kelima orang itu pun telah menempuh jalan mereka sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.
Dalam pada itu Matahari telah semakin terang sinarnya. Butir-butir embun yang menebar di atas rerumputan serta bergelayutan di pucuk-pucuk dedaunan telah menguap. Burung-burung pun berkicau tak henti-hentinya menyambut terbitnya Matahari pagi.
Di padepokan Sapta Dhahana, beberapa cantrik tampak sedang berjaga-jaga di regol depan. Mereka bersenda-gurau dengan riangnya seolah-olah tidak ada beban sama sekali sehingga tidak menyadari bahwa seseorang sedang berjalan menuju ke arah mereka.
Ketika jarak orang itu tinggal beberapa langkah saja dari regol, barulah para cantrik itu menyadari atas kelengahan mereka. Segera saja mereka berloncatan ke tengah-tengah regol menghadang orang itu.
“Berhenti!” bentak cantrik tertua diantara mereka, “Kakek tua, engkau harus minta ijin dulu kepada kami jika ingin memasuki padepokan.”
Orang yang mendatangi regol padepokan itu memang seorang yang sudah sangat renta. Tubuhnya kurus kering dan hanya tubuh bagian bawahnya saja yang dibalut dengan selembar kain panjang yang sangat kumal dan lusuh. Sedangkan bagian atas tubuhnya telanjang sehingga terlihat dengan jelas tulang-tulang iganya yang menonjol. Sementara rambutnya yang panjang dan gimbali itu digelung ke atas dan diikat dengan secarik kain usang.
“Kakek!” kembali cantrik tertua itu membentak begitu dilihatnya kakek tua itu tidak menanggapinya justru malah berdiri sambil memejamkan kedua matanya. Tubuhnya tampak bergoyang-goyang mengikuti aliran angin yang bertiup cukup keras pagi itu.
Melihat kakek itu acuh tak acuh, salah satu cantrik yang berbadan tinggi besar segera maju ke depan. Tanpa basa-basi dicengkeramnya leher kakek tua itu dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya mengepal keras dan disorongkannya tepat di depan hidung kakek tua itu.
“Jangan macam-macam gembel tua!” geram cantrik itu kemudian, “Di sini padepokan Sapta Dhahana, tempat orang-orang sakti. Bukan gardu perondan yang dapat engkau singgahi dengan seenaknya!”
Namun yang terjadi kemudian adalah sangat diluar dugaan setiap orang. Tiba-tiba saja kakek tua itu telah membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian menjulurkan lidahnya keluar. Lidah yang panjang itu pun kemudian menjilat pergelangan tangan cantrik itu.
Bagaikan tersentuh bara api dari tempurung kelapa, cantrik itu pun telah menjerit keras sambil meloncat mundur. Dengan tergesa-gesa diperiksanya pergelangan tangan kirinya. Beberapa kawannya pun telah mendekat untuk melihat apa sebenarnya yang telah terjadi.
Sejenak kemudian, setiap jantung orang yang berada di tempat itu pun bagaikan terlepas dari tangkainya. Kulit pergelangan tangan kiri cantrik itu ternyata telah hangus terbakar.
“Gila!” hampir setiap mulut telah mengumpat. Namun kini mereka tidak berani lagi dengan gegabah untuk mendekati kakek aneh itu.
“Kau, pergilah ke dalam,” perintah cantrik tertua itu kemudian kepada cantrik yang pergelangan tangannya terluka, “Laporkan kejadian ini kepada Kakang Putut Sambernyawa, sekalian ke balai pengobatan untuk mengobati lukamu.”
“Baik, kakang,” jawab cantrik itu. Dengan mulut menyeringai menahan sakit dan tangan kanan menekan seputar pergelangan tangan kirinya, cantrik itupun segera bergeser mundur dan kemudian berlari ke dalam padepokan.
Dalam pada itu, kakek aneh itu ternyata tetap pada sikapnya semula. Berdiri tegak sambil memejamkan kedua matanya dengan tubuh yang bergoyang-goyang mengikuti hembusan angin pagi.
Dengan memberi isyarat kepada kawan-kawannya terlebih dahulu, cantrik tertua itupun kemudian segera bergeser mundur selangkah. Kawan-kawannya ternyata telah tanggap dan segera mengikuti bergerak setapak demi setapak sambil berpencar sehingga sejenak kemudian, kakek tua itu telah berada di dalam lingkaran para cantrik.
Untuk beberapa saat suasana benar-benar menegangkan. Para cantrik itu tidak ada yang berani mendahului bergerak. Mereka hanya berusaha menahan kakek tua itu agar tidak meloloskan diri sambil menunggu kedatangan cantrik tertua, Putut Sambernyawa.
Dalam keheningan yang menegangkan itu, tiba-tiba saja kakek tua itu dengan tetap memejamkan keduanya matanya, bibirnya telah mengeluarkan suara siulan yang aneh. Pada awalnya suara siulan itu terdengar seperti desis seekor ular. Namun lama kelamaan suara siulan itu terdengar meninggi mirip seperti suara jeritan seekor burung elang. Sesaat kemudian tiab-tiba saja suara siulan itu menurun dan terdengar menyayat seperti rintihan seekor burung kedasih.
Para cantrik yang mendengarkan suara siulan yang berubah-ubah itu menjadi heran. Mereka tidak mengetahui maksud dari kakek aneh itu. Mereka hanya dapat berdiri termangu-mangu sambil tetap tidak meninggalkan kewaspadaan.
Dalam pada itu, di ruang dalam padepokan, Raden Wirasena yang sedang duduk-duduk ditemani Kiai Damar Sasangka telah dikejutkan oleh suara siulan aneh yang terdengar sangat jelas dari ruang dalam itu.
“Begawan Cipta Hening?” desis Raden Wirasena. Namun terdengar nada suaranya sedikit ragu-ragu.
“He?!” Kiai Damar Sasangka pun tak kalah terkejutnya mendengar Raden Wirasena telah menyebut sebuah nama.
“Tidak mungkin Raden,” berkata Kiai Damar Sasangka kemudian, “Keberadaan Begawan itu sepertinya hanya sebuah dongeng belaka. Jika memang dia itu benar-benar ada dan masih hidup sampai sekarang ini, tentu umurnya telah mencapai ratusan tahun lebih.”
Sejenak Raden Wirasena termenung. Memang Raden Wirasena sendiri belum pernah bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Begawan Cipta Hening itu.
“Aku memang belum pernah bertemu secara pribadi dengan begawan itu,” berkata Raden Wirasena dalam hati, “Sesuai saran Panembahan Cahaya Warastra, sebelum pecah perang di Menoreh, seharusnya aku sudah menghadap Begawan Cipta Hening di puncak pebukitan Menoreh,” Raden Wirasena berhenti berangan-angan. Lanjutnya kemudian, “Namun aku belum sempat dan Panembahan Cahya Warastra ternyata telah terbunuh di Menoreh.”
Seakan masih jelas tergambar dalam ingatan Raden Wirasena, ketika suatu hari dia sedang mengunjungi padepokan Cahya Warastra. Panembahan Cahya Warastra pada saat itu sedang mempersiapkan penyerbuan ke Menoreh dan berpesan untuk meminta bantuan dan dukungan kepada Begawan Cipta Hening yang sedang bertapa di pucak pebukitan Menoreh. Namun belum sempat Raden Wirasena mendaki pebukitan Menoreh, terdengar kabar bahwa Panembahan Cahaya Warastra telah terbunuh dalam peperangan di Menoreh.
“Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Begawan itu, namun Panembahan telah memberiku petunjuk ciri-ciri orang yang bernama Begawan Cipta Hening itu” berkata Raden Wirasesa dalam hati, “Panembahan Cahaya Warastra juga telah mengajari aku bagaimana cara menghubungi Begawan itu dengan sebuah isyarat khusus,”
Raden Wirasena berhenti berangan-angan sejenak. Lanjutnya, “Mungkin sebelum pecah perang di Menoreh, Panembahan itu masih sempat menghadap Begawan dan menyampaikan keinginanku untuk memohon bantuannya.”
Ketika suara siulan itu tiba-tiba terdengar melengking tinggi, Raden Wirasena pun sudah tidak dapat menahan diri lagi. Maka katanya kemudian, “Marilah Kiai, kita lihat siapakah sebenarnya yang telah datang mengunjungi padepokan Sapta Dhahana ini.”
“Baik Raden,” sahut Kiai Damar Sasangka sambil bangkit dari duduknya mengikuti Raden Wirasena yang telah terlebih dahulu bangkit berdiri.
Sejenak kemudian, kedua orang itu pun dengan berjalan beriringan segera menuju ke pringgitan untuk kemudian keluar ke pendapa.
Begitu keduanya membuka pintu pringgitan, dari jauh mereka telah melihat orang-orang yang berkerumun di depan regol. Tampak Putut Sambernyawa sedang membentak-bentak seorang kakek-kakek yang hanya mengenakan kain panjang yang dibebatkan pada bagian tubuhnya dari pinggang sampai ke lutut.
“Begawan Cipta Hening,” tanpa sadar bibir Raden Wirasena berdesis perlahan.
“Benarkah Raden?” sela Kiai Damar Sasangka. Hatinya sedikit ragu akan keberadaan Begawan itu yang hidup ratusan tahun yang lalu.
“Marilah Kiai,” jawab Raden Wirasena kemudian, “Semua itu memang perlu dibuktikan.”
Dengan langkah yang sedikit bergegas, keduanya segera menyeberangi pendapa yang cukup luas itu untuk kemudian turun ke halaman.
Namun ternyata ada salah satu cantrik yang melihat kedatangan kedua orang itu. Maka katanya kemudian setengah berteriak, “Kiai Damar Sasangka pemimpin padepokan Sapta Dhahana bersama Raden Wirasena Trah Sekar Seda Lepen telah berkenan hadir!”
Tiba-tiba saja suara siulan itu berhenti dan kakek yang aneh itu pun segera membuka kedua matanya. Sementara kerumunan para cantrik di depan regol itu segera menyibak memberi jalan kepada kedua orang yang sangat disegani itu.
Raden Wirasena segera saja mengenali kakek tua itu sebagai Begawan Cipta Hening, sesuai ciri-ciri yang diberitahukan oleh Panembahan Cahya Wirastra.
“Selamat datang Begawan,” sapa Raden Wirasena ramah, “Mohon dimaafkan sambutan para Cantrik yang kurang menyenangkan. Sesungguhnyalah mereka hanya menjalankan tugas.”
Begawan Cipta Hening mengerutkan keningnya yang sudah keriput itu. Dipandanginya kedua orang yang datang kemudian itu ganti berganti. Tanyanya kemudian dengan sorot mata yang menyala, “Siapakah di antara kalian yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen?”
Berdesir dada Raden Wirasena mendapat pertanyaan itu. Namun dengan cepat Raden Wirasena segera maju selangkah. Jawabnya kemudian, “Begawan, akulah Trah Sekar Seda Lepen yang seharusnya berhak atas tahta di negeri ini.”
“Omong kosong!” sergah Begawan Cipta Hening, “Setiap orang dapat saja mengaku berhak atas tahta negeri ini. Aku pun juga berhak,” Begawan berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian sambil membusungkan dadanya yang kurus, “Aku adalah keturunan Jaka Umbaran yang kemudian bergelar Menak Jingga di Blambangan. Bukankah seharusnya yang menjadi Raja Majapahit adalah Jaka Umbaran? Mengapa dia justru telah difitnah dan disingkirkan?”
Orang-orang yang hadir di tempat itu telah membeku. Kebanyakan dari mereka memang tidak begitu mengetahui sejarah, atau bahkan oleh orang-orang tertentu sejarah itu dengan sengaja telah dikaburkan.
“Maaf Begawan,” berkata Raden Wirasena kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Sejarah memang harus diluruskan, dan sudah menjadi kewajiban kita bersama. Aku selaku Trah dari Pangeran Sekar tidak akan menutup mata terhadap para pendahulu yang juga mempunyai trah dari Majapahit atau lainnya. Kita akan bersama-sama bahu membahu mengusir orang-orang dari trah pidak pedarakan yang sekarang ini justru sedang berkuasa di Mataram.”
Begawan menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Katanya kemudian, “Memang seharusnya negeri ini tetap dipimpin dari trah Kusuma Rembesing Madu, bukan para petani dari Sela yang hanya karena minum air kelapa muda kemudian keturunannya bisa menjadi Raja.”
“Begawan benar,” jawab Raden Wirasena, “Sekarang marilah kita bicarakan segala sesuatunya di dalam agar lebih tenang dan nyaman.”
Begawan Cipta Hening tertawa pendek mendengar ajakan Raden Wirasena. Jawabnya kemudian, “Apakah aku sudah disiapkan makanan yang enak-enak? Tuak yang terbaik dan terkeras? Gadis-gadis cantik yang akan melayani aku sepanjang malam?”
Berdesir dada Raden Wirasena mendengar permintaan Begawan aneh itu. Tanpa sadar dia telah berpaling ke arah Kiai Damar Sasangka.
Kiai Damar Sasangka tersenyum sekilas. Setelah maju selangkah, barulah Kiai Damar Sasangka itu berkata, “Kami atas nama seluruh penghuni padepokan Sapta Dhahana mengucapkan selamat datang kepada Begawan Cipta Hening. Marilah Begawan, kami persilahkan untuk beristirahat sejenak di tempat yang telah kami sediakan. Urusan selanjutnya akan kita bicarakan kemudian.”
Begawan Cipta Hening untuk sejenak kembali mengerutkan keningnya yang sudah keriput itu. Dipandanginya wajah pemimpin perguruan Sapta Dhahana itu dalam-dalam. Katanya kemudian, “Sapta Dhahana yang berarti api yang panasnya tujuh kali lipat dengan panasnya api biasa,” Begawan itu berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian setengah berteriak, “He! Aku sepertinya pernah mengenal orang sakti dari Sapta Dhahana, Kiai Guntur Geni. Dimana dia sekarang? Panggil dia untuk menyambut aku.”
Kiai Sapta Dhahana tertegun, orang yang disebutkan oleh Begawan Cipta Hening itu adalah Kakek Gurunya yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Maka katanya kemudian, “Begawan memang benar, Kiai Guntur Geni itu adalah Kakek guru kami. Beliau telah meninggal dunia berpuluh tahun yang lalu. Dan sekarang aku, Kiai Damar Sasangka adalah cucu beliau yang memimpin perguruan Sapta Dhahana ini.”
Begawan Cipta Hening menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya kemudian, “Semua sahabatku telah mati, tinggal aku sendiri. Rasanya dunia ini menjadi sepi.”
Mendengar ucapan begawan yang bernada keluh kesah itu, Raden Wirasena pun segera berkata, “Marilah Begawan. Kita dapat membicarakan segala sesuatunya di dalam agar lebih nyaman.”
Selesai berkata demikian Raden Wirasena segera mempersilahkan Begawan Cipta Hening untuk berjalan di depan.
Demikianlah kedatangan Begawan Itu telah menambah kekuatan dari orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen. Kekuatan yang belum disadari dan diperhitungkan dengan cermat oleh Ki Rangga dan kawan-kawannya.
Dalam pada itu ketika Matahari sudah bersinar dengan cerahnya, di rumah ki Gede Matesih, Ki Gede sedang mengumpulkan para bebahu tanah Perdikan yang masih setia mendukung setiap kebijakkan Ki Gede dan dapat dipercaya.
“Keadaan telah berkembang semakin tidak menentu,” berkata Ki Gede memulai pembicaraan, “Kita harus semakin waspada justru di antara kawan sendiri. Aku berharap kelima tamu yang akan datang ke rumah ini akan menambah kekuatan kita untuk melawan pengaruh Raden Surengpati.”
Orang-orang yang hadir di ruang dalam itu pun tampak mengangguk-angguk. Berkata seorang yang berkumis tipis kemudian, “Ma’af Ki Gede. Apakah Ki Gede sudah yakin dengan kemampuan mereka? Maksudku dalam hal ilmu olah kanuragan. Kita semua menyadari bahwa Raden Surengpati dan para pengikutnya tidak dapat dipandang dengan sebelah mata.”
“Engkau benar Ki Jagatirta,” jawab Ki Gede, “Aku memang belum mempunyai gambaran yang jelas tentang kemampuan kelima orang tersebut. Namun aku percaya menilik sorot mata mereka yang tajam dan tenang serta ketegasan mereka dalam berbicara terutama orang yang bernama Ki Sedayu itu. Aku telah menaruh harapan yang besar kepada mereka untuk membebaskan tanah perdikan ini dari pengaruh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen.”
“Sudah Ki Kamitua,” sahut ki Gede cepat, “Aku telah memerintahkan kepada Ki Wiyaga pagi tadi sebelum Matahari terbit untuk pergi ke dukuh Klangon menjemput para tamu kita.”
Ki Kamitua mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, “Ki Gede, para pengawal di Perdikan Matesih ini telah terpecah menjadi dua golongan. Sebagian tetap bersetia kepada Perdikan Matesih di bawah panji-panji kebesaran Mataram, sedangkan yang lainnya, terutama yang muda-muda, mereka lebih senang berangan-angan bersama para pengikut Trah Sekar Seda Lepen. Aku khawatir jika Ki Wiyaga sebagai pemimpin pengawal Perdikan Matesih lebih condong untuk mengikuti golongan yang terakhir.”
Terdengar orang-orang yang hadir di ruang dalam itu bergeremang satu dengan lainnya. Agaknya masing-masing mempunyai tanggapan yang berbeda.
“Ki Kamitua,” berkata Ki Gede kemudian sambil mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam sejenak, “Aku percaya dengan Ki Wiyaga. Dia telah menjadi pengawal perdikan Matesih sejak masih muda. Kedudukan pemimpin pengawal itu pun aku percayakan kepadanya setelah ayahnya mengundurkan diri karena usia tua. Jadi aku percaya kepada Ki Wiyaga sebagaimana dulu aku juga percaya kepada ayahnya.”
Sejenak mereka yang hadir di tempat itu terdiam. Masing-masing telah tenggelam dalam kenangan masa lalu yang tenang dan tentram.
“Perdikan Matesih adalah perdikan yang tenang dan damai,” berkata seorang yang rambutnya sudah putih semua dalam hati, “Hampir tidak ada gejolak sama sekali di tanah perdikan ini. Semua penghuninya hidup rukun, guyup dan saling membantu. Namun dengan kedatangan orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen dan para pengikutnya itu, penghuni tanah Perdikan ini telah terpecah belah dan jauh dari yang disebut rukun dan damai.”
Pembicaraan itu terhenti sejenak ketika tiba-tiba saja terdengar pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan dapur berderit. Sejenak kemudian dari pintu yang terbuka muncullah seorang gadis yang sedang beranjak dewasa sambil membawa nampan berisi minuman dan makanan.
Semua orang segera menundukkan wajahnya kecuali Ki Gede Matesih. Dipandanginya wajah anak perempuan satu-satunya itu dengan kening yang berkerut merut. Seraut wajah yang menginjak dewasa dengan segala kelebihannya dibanding dengan gadis-gadis sebayanya.
Ratri, nama gadis semata wayang Ki Gede itu segera berjongkok dan meletakkan minuman dan makanan di depan para tamu. Setelah semuanya selesai, Ratri pun kemudian segera mundur setapak untuk kemudian berdiri dan membalikkan badan. Sejenak kemudian gadis cantik dengan keindahan bentuk tubuh yang mulai beranjak dewasa itu pun telah hilang di balik pintu yang tertutup rapat.
Sepeninggal putrinya, tampak wajah Ki Gede menjadi muram, semuram langit yang sedang turun hujan.
Sambil menarik nafas dalam-dalam dan menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali, Ki Gede pun kemudian berdesis perlahan seolah-olah hanya ditujukan kepada dirinya sendiri, “Aku mungkin salah satu dari sekian banyak orang tua yang tidak mampu memberikan tuntunan yang baik kepada anaknya.”
Suara itu terdengar seperti sebuah keluh kesah atau penyesalan yang tiada taranya.
Orang-orang yang mendengar keluh kesah Ki Gede itu tidak ada yang berani mengangkat kepalanya atau pun membuka suara. Mereka tetap menundukkan kepala dalam-dalam menunggu apa yang akan disampaikan oleh Ki Gede.
“Ah, sudahlah,” berkata Ki Gede kemudian mencoba mencairkan suasana, “Semoga sebelum wayah tengange, para tamu kita telah hadir di rumah ini.”
Orang-orang itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Nah,” berkata Ki Gede selanjutnya, “Apakah masih ada yang ingin disampaikan?”
Namun sebelum salah satu dari orang-orang yang hadir itu membuka suara, tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu, pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan pringgitan.
“Masuklah!” terdengar suara Ki Gede cukup lantang.
Sejenak kemudian terdengar pintu berderit dan seseorang telah muncul dari balik pintu.
“Ki Wiyaga?” hampir serentak mereka yang berada di ruang dalam itu telah berdesis.
Orang yang memasuki ruang dalam itu memang Ki Wiyaga. Namun tidak tampak luka di pundaknya. Bahkan bajunya tampak bersih serta memakai kain panjang yang bersih pula. Agaknya Ki Wiyaga sempat mampir ke rumah terlebih dahulu untuk berganti baju sebelum menghadap Ki Gede.
Setelah mengangguk terlebih dahulu kepada orang-orang yang hadir, terutama Ki Gede, Ki Wiyaga pun segera mengambil duduk di sebelah Ki Jagatirta.
Setelah menanyakan keselamatan Ki Wiyaga terlebih dahulu, barulah Ki Gede bertanya, “Ki Wiyaga, mengapa sepagi ini engkau sudah kembali?”
Sejenak Ki Wiyaga menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan getaran di dalam dadanya. Jawabnya kemudian, “Maaf Ki Gede, aku belum sempat menjemput tamu-tamu kita di banjar Padukuhan Klangon.”
“Mengapa?” tiba-tiba dengan serta-merta Ki Jagatirta telah menyela. Namun begitu disadarinya Ki Gede telah berpaling ke arahnya, dengan cepat segera ditundukkan wajahnya.
“Ya, Ki Wiyaga,” sahut Ki Gede kemudian, “Apa sebenarnya yang telah terjadi?”
“Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga kemudian, “Telah terjadi suatu peristiwa diluar rencana kita.”
Ki Gede mengerutkan keningnya dalam-dalam. Katanya kemudian, “Jangan berputar-putar Ki Wiyaga. Ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi.”
Ki Wiyaga sejenak ragu-ragu. Tanpa sadar, diedarkan pandangan matanya ke arah orang-orang yang hadir di ruangan itu.
Agaknya Ki Gede tanggap akan keragu-raguan kepala pengawal Perdikan Matesih itu. Maka katanya kemudian, “Ki Wiyaga, engkau berada di antara para bebahu perdikan Matesih yang dapat dipercaya.”
“Terima kasih ki Gede,” berkata Ki Wiyaga kemudian, “Kelima tamu kita itu ternyata dengan sengaja telah meloloskan diri dari banjar Padukuhan Klangon.”
“He?!” serentak mereka yang ada di ruangan itu terlonjak kaget, terutama Ki Gede. Sejenak wajahnya menjadi merah padam.
“Siapakah sebenarnya mereka itu?” geram Ki Gede, “Apakah mereka mencoba mempermainkan Ki Gede Matesih?”
“O, tidak, tidak Ki Gede,” sahut Ki Wiyaga cepat, “Sungguh mereka berlima itu orang-orang yang dapat dipercaya.”
“Dari mana Ki Wiyaga tahu?” sela Ki Kamitua.
Ki Wiyaga tersenyum. Sambil menyingkapkan baju di bagian pundak kirinya, Ki Wiyaga pun memperlihatkan bekas lukanya yang telah dibebat dengan secarik kain. Katanya kemudian, “Inilah buktinya. Salah satu dari mereka telah menolongku dari luka yang akan dapat membunuhku. Luka akibat goresan pisau belati yang sangat beracun.”
Kemudian secara singkat Ki Wiyaga segera menceritakan kejadian di dekat gardu perondan itu serta pertemuannya dengan kelima orang yang mengaku dari Prambanan itu.
“Jadi engkau telah ditolong oleh mereka?” bertanya Ki Gede kemudian.
“Ya Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga, “Jika saja lukaku itu tidak segera diobati oleh orang yang bernama Ki Sedayu itu, mungkin aku sudah tidak dapat lagi berkumpul di tempat ini.”
“Ah!” beberapa orang justru telah berdesah. Sedangkan Ki Gede segera berkata, “Syukurlah agaknya Yang Maha Agung masih melindungi kita untuk menyelamatkan tanah perdikan ini dari segolongan orang yang tidak bertanggung jawab.”
Setiap orang yang ada di ruangan itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Bagaimana dengan Lajuwit?” tiba-tiba Ki Gede bertanya sambil memandang kearah Ki Wiyaga.
Sejenak Ki Wiyaga ragu-ragu. Bagaimanapun juga secara tidak sengaja dia telah ikut berperan dalam terjadinya rajapati, walaupun kejadian yang sebenarnya dia tidak begitu jelas.
“Mengapa engkau terlihat ragu-ragu Ki Wiyaga?” desak Ki Gede, “Katakanlah sejujurnya apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Lajuwit.”
“Maaf Ki Gede, jawab Ki Wiyaga kemudian setelah Menimbang-nimbang beberapa saat, “Lajuwit telah terbunuh oleh pisau beracunnya sendiri.”
“He?!” orang-orang yang berada di ruang itu pun kembali tersentak.
“Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?” hampir setiap mulut telah mengajukan pertanyaan yang serupa.
Namun Ki Wiyaga justru telah menggelengkan kepalanya. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu, karena pengaruh racun itu begitu kuat sehingga aku telah jatuh pingsan. Namun sebelum aku benar-benar kehilangan kesadaranku, aku masih sempat mendengar suara benturan yang keras.”
“Mungkin Lajuwit telah menyerangmu sekali lagi dengan pisau belatinya di saat engkau lengah karena pengaruh racun itu,” berkata Ki Kamitua memberikan pendapatnya.
“Mungkin saja,” sahut Ki Gede, “Dan suara benturan keras yang engkau dengar itu adalah lontaran belati berikutnya yang mungkin telah dipatahkan oleh salah satu dari kelima orang itu.”
“Mungkin Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga sambil mengangguk-angguk, “Kemungkinan itulah yang sebenarnya telah terjadi.”
“Berarti engkau telah berhutang nyawa dua kali kepada mereka, Ki Wiyaga,” kali ini Ki Jagatirta yang menyahut.
Ki Wiyaga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
Untuk beberapa saat ruangan itu pun justru telah menjadi hening.
Namun Ki Gede segera berusaha untuk menguasai keadaan. Maka katanya kemudian, “Semua itu mungkin sudah takdir dari Yang Maha Agung. Menurut pendapatku, Lajuwit telah memetik buah dari apa yang telah ditanamnya selama ini.”
Tampak semua orang mengangguk-anggukkan kepala mereka sambil menarik nafas dalam-dalam.
“Di manakah mayatnya sekarang?” bertanya Ki Gede kemudian.
“Mayat itu kami sembunyikan di bawah gardu,” jawab Ki Wiyaga, “Salah satu dari kelima orang itu telah menimbuninya dengan rumput-rumput kering agar tidak begitu tampak jika ada orang yang melewati gardu itu.”
“Baiklah,” berkata Ki Gede sambil memandang ke arah Ki Jagatirta, “Ki Jagatirta, bawalah beberapa orang yang dapat dipercaya bersama Ki Wiyaga nanti menjelang sirep uwong. Usahakan untuk tidak begitu menarik perhatian dan hanya kalangan kita saja yang mengetahui peristiwa ini.”
“Baik Ki Gede,” jawab Ki Jagatirta sambil menarik nafas panjang. Mengubur mayat di malam hari memang tidak menyenangkan, namun apa boleh buat. Perintah Ki Gede harus dilaksanakan.
“Nah, Ki Wiyaga,” berkata Ki Gede kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Mengapa engkau tadi mengatakan bahwa kelima orang itu dengan sengaja telah lolos dari banjar Padukuhan Klangon?”
Serentak semua mata segera tertuju ke arah Ki Wiyaga.
Menyadari semua orang sedang menunggu jawabannya, Ki Wiyaga pun segera beringsut setapak ke depan. Sambil membetulkan letak kain panjangnya terlebih dahulu, Ki Wiyaga pun kemudian bercerita tentang pengepungan para murid Padepokan Sapta Dhahana di banjar Padukuhan Klangon menjelang dini hari tadi. Sebagaimana seperti yang telah disampaikan oleh Ki Sedayu.
“Gila!’ geram Ki Gede begitu Ki Wiyaga selesai bercerita, “Ternyata kita kalah cepat dengan mereka,” Ki Gede berhenti sejenak. Kemudian sambil berpaling ke arah Ki Jagatirta, Ki Gede bertanya, “Ki Jagatirta, apakah engkau tahu di mana Ki Jagabaya sekarang ini?”
Untuk sejenak Ki Jagatirta memandang para bebahu lainnya untuk meminta pertimbangan. Namun semua bebahu yang hadir disitu telah menggelengkan kepala mereka. Maka jawab Ki Jagatirta kemudian, “Maaf Ki Gede, kami tidak tahu keberadaan Ki Jagabaya beberapa hari ini. Menurut keterangan yang aku peroleh, Ki Jagabaya sering terlihat berkunjung ke rumah yang ditempati Raden Surengpati dan pengikutnya.”
Kembali terdengar Ki Gede menggeram. Wajahnya terlihat sangat keruh. Berkata Ki Gede kemudian, “Kalian semua berhati-hatilah jika berbicara dengan Ki Jagabaya Perdikan Matesih. Aku melihat gelagat yang mencurigakan dari Ki Jagabaya,” Ki Gede berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian, “Lain halnya dengan Padukuhan Klangon, kalian dapat mempercayai Ki Jagabaya dukuh Klangon, namun jangan sekali-kali berbicara dengan Ki Dukuh Klangon. Dia telah terpengaruh dengan Raden Surengpati, sehingga Ki Dukuh Klangon sore tadi telah mengerahkan para pengawalnya untuk berjaga-jaga di banjar.”
“Untunglah kelima orang dari Prambanan itu mampu lolos dari pengamatan mereka,” sahut Ki Kamitua.
“Benar Ki Kamitua,” berkata Ki Wiyaga menanggapi kata-kata Ki Kamitua, “Dan yang lebih untung lagi, mereka berlima ternyata juga terhindar dari kepungan para murid gunung Tidar.”
“Itu menunjukkan bahwa mereka bukan segolongan orang-orang kebanyakan,” sahut Ki Gede dengan nada suara yang yakin dan mantap.
Para bebahu yang hadir di dalam ruangan itu pun tampak mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Nah, sekarang,” berkata Ki Gede selanjutnya, “Bagaimana cara kita untuk menghubungi mereka?”
Kembali semua mata tertuju ke arah Ki Wiyaga. Mereka berharap kepala pengawal perdikan Matesih itu dapat memberikan jawabannya.
Namun alangkah kecewanya para bebahu perdikan Matesih itu, terutama Ki Gede. Mereka melihat Ki Wiyaga justru telah menggelengkan kepalanya.
“Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ki Gede?” bertanya seorang yang rambutnya sudah putih semua.
Sejenak Ki Gede menarik nafas panjang. Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Ki Wiyaga, Ki Wiyaga pun segera tanggap. Maka katanya kemudian, “Ki Jagawana, kelima orang itu sudah berjanji akan menghadap Ki Gede, hanya waktunya saja yang belum pasti, sebab mereka masih mempunyai sebuah urusan untuk segera diselesaikan.”
“Urusan apa itu?” hampir bersamaan pertanyaan itu terdengar di ruangan itu.
Ki Wiyaga menggeleng. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu dan aku tidak berani menanyakannya.”
Untuk beberapa saat suasana menjadi sunyi kembali. Masing-masing sedang tenggelam dalam angan-angan tentang permasalahan yang sedang dihadapi Perdikan Matesih.
“Nah, aku kira sudah cukup pembicaraan kita kali ini,” berkata Ki Gede kemudian memecah kesunyian, “Kalian dapat kembali ke tempat kerja masing-masing. Aku akan nganglang bersama Ki Wiyaga.”
Kemudian sambil berpaling ke arah kepala pengawal itu, Ki Gede pun telah menjatuhkan perintah, “Siagakan beberapa pengawal yang dapat dipercaya. Kita akan mengelilingi Tanah Perdikan Matesih ini untuk memberi kesan kepada para pengikut Trah Sekar Seda Lepen bahwa Perdikan Matesih masih ada dan akan tetap ada selama pemerintahan Mataram masih berdiri tegak.”
Demikianlah, perintah Ki Gede itu merupakan suatu perintah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sejenak kemudian pertemuan para bebahu itu pun telah selesai dan mereka segera kembali ke tempat tugas masing-masing.
Dalam pada itu, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan serta Glagah Putih yang mendapat tugas menyelidiki keberadaan Perguruan Sapta Dhahana dari lereng sebelah barat telah mendapat pesan dari Ki Rangga untuk mengamat-amati kediaman Ki Gede Matesih. Tanpa menarik perhatian mereka berjalan di antara ramainya lalu-lalang para pejalan kaki serta pedati-pedati yang sarat mengangkut hasil bumi. Sesekali mereka juga berpapasan dengan orang-orang yang berkuda.
“Guru, mengapa sejauh ini kita tidak melihat para pengawal Perdikan Matesih sedang meronda?” bertanya Glagah Putih yang berjalan di samping gurunya. Sementara beberapa langkah di belakang mereka, tampak Ki Bango Lamatan berjalan sambil menundukkan kepalanya.
“Entahlah Glagah Putih,” jawab gurunya, “Mungkin mereka merasa Perdikan ini sudah begitu aman, terutama di siang hari.”
“Kejahatan tidak mengenal waktu,” tanpa sadar Glagah Putih berdesis perlahan seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri.
“Engkau benar Glagah Putih,” sahut Gurunya, “Memang kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat, akan tetapi lebih tepatnya, kejahatan pun memperhitungkan tempat dan waktu, karena seseorang yang akan melakukan sebuah tindak kejahatan juga mempunyai perhitungan-perhitungan.”
Glagah Putih mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan gurunya itu. Tanpa sadar dia kemudian berpaling ke belakang. Tampak Ki Bango Lamatan sedang berjalan sambil menundukkan kepalanya.
“Orang itu telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam dirinya,” berkata Glagah Putih dalam hati sambil kembali memandang ke depan, “Aku masih ingat peristiwa di tepian kali Opak. Ki Bango Lamatan saat itu berada di pihak Panembahan Cahya Warastra dan sekarang tiba-tiba telah menjadi orang kepercayaan Pangeran Pati,” angan-angan Glagah Putih berhenti sejenak. Kemudian sambil tersenyum sekilas dia melanjutkan angan-angannya, “Semua itu berkat jasa Kanjeng Sunan.”
Tanpa terasa langkah mereka telah mendekati regol halaman rumah Ki Gede Matesih.
Ketiga orang itu pun kemudian berjalan sebagaimana orang-orang yang lain. Namun ketika mereka lewat tepat di depan regol, Glagah Putih telah menyempatkan diri untuk berpaling sekilas.
Tampak kening Glagah Putih berkerut. Apa yang dilihatnya hanya sekilas itu ternyata sangat berkesan. Diujung tangga pendapa dia sempat melihat seorang gadis cantik yang sedang beranjak dewasa tampak sedang bercakap-cakap dengan seseorang.
“Ratri,” tanpa sadar bibir Glagah Putih menyebut sebuah nama.
Ki Jayaraga yang berjalan di sampingnya terkejut. Sambil berpaling dia bertanya, “Siapa Glagah Putih?”
“O,” Glagah Putih tergagap. Setelah menarik nafas panjang barulah Glagah Putih menjawab, “Guru, aku tadi melihat seorang gadis yang sedang beranjak dewasa di tangga pendapa kediaman Ki Gede. Mungkin itu Ratri, putri satu-satunya Ki Gede Matesih.”
Ki Jayaraga mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, “Mungkin Glagah Putih. Gadis yang telah terpikat oleh seorang pria dewasa, yang mengaku sebagai Trah Sekar Seda Lepen.”
“Tentu Ratri telah terbuai oleh angan-angan dan janji-janji dari Raden Surengpati,” sahut Glagah Putih, “Jika perjuangan Trah Sekar Seda Lepen itu berhasil, dia akan ikut menikmati hasilnya. Hidup di kalangan istana, berlimpah ruah dengan harta benda, serta disuyuti dan dihormati oleh kawula seluruh negeri.”
“Ah,” Ki Jayaraga tertawa pendek mendengar ucapan Glagah Putih. Bahkan Ki Bango Lamatan yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka pun ikut tersenyum.
Tanpa terasa langkah mereka telah semakin jauh dari regol halaman Ki Gede. Ketika mereka kemudian menjumpai sebuah jalan simpang, tiba-tiba Glagah Putih telah menghentikan langkahnya.
“Ada apa Glagah Putih?” bertanya Ki Jayaraga yang juga ikut berhenti. Sementara Ki Bango Lamatan yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka telah memperlambat langkahnya.
“Guru, kita mengambil jalan ke kanan,” jawab Glagah Putih kemudian.
“Glagah Putih, jalan menuju ke Gunung Tidar adalah lurus ke depan,” tiba-tiba Ki Bango Lamatan yang telah ikut berhenti menyahut.
“Ki Bango Lamatan benar,” berkata Ki Jayaraga ikut menimpali, “Sebaiknya kita mengambil jalan lurus.”
Sejenak Glagah Putih ragu-ragu. Namun entah mengapa, seraut wajah cantik gadis putri ki Gede Matesih itu tidak mau hilang dari benaknya, walaupun beberapa saat tadi dia hanya melihatnya sekilas.
Setelah menarik nafas dalam-dalam, barulah Glagah Putih mengutarakan kegelisahannya.
“Guru,” berkata Glagah Putih kemudian, “Entah mengapa begitu melihat putri ki Gede tadi, rasa-rasanya aku telah mengkhawatirkan keselamatannya.”
Kedua orang tua itu sejenak saling pandang. Mereka segera menyadari, Glagah Putih agaknya telah tertarik dengan putri Matesih itu, apapun alasannya.
“Glagah Putih,” berkata Ki Jayaraga kemudian setelah melihat Ki Bango Lamatan yang tersenyum dan mengangguk-angguk, “Engkau tertarik pada putri Ki Gede itu memang sudah sewajarnya. Engkau masih muda dan putri Matesih itu pun seorang gadis yang sedang mekar-mekarnya. Namun sejauh manakah ketertarikanmu itu yang harus dipertanyakan.”
“Ah,” Glagah Putih berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rona merah segera saja menghiasi wajahnya, namun dengan cepat segera saja Glagah Putih berusaha menghilangkan kesan itu dari wajahnya. Katanya kemudian, “Guru, aku menyadari bahwa aku adalah laki-laki yang sudah beristri. Aku hanya memikirkan bagaimana nasib putri Matesih itu jika dia benar-benar terjebak dalam jeratan orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu.”
Untuk beberapa saat kedua orang tua itu justru telah terdiam. Memang akan saat mengenaskan nasib putri Matesih yang masih hijau itu jika dia sampai terperangkap jebakan Raden Mas Harya Surengpati.
“Ah, sudahlah,” akhirnya Ki Jayaraga berkata memecah kesunyian setelah sejenak mereka terdiam, “Kita hanya bisa mendoakan masa depan yang baik bagi putri Ki Gede itu.”
Ki Bango Lamatan mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar ucapan Ki Jayaraga, namun Glagah Putih justru mengerutkan keningnya dalam-dalam.
Ki Jayaraga yang melihat muridnya termenung telah menarik nafas panjang. Tanyanya kemudian, “Ada apa lagi Glagah Putih?”
“Maafkan aku Guru dan juga Ki Bango Lamatan,” jawab Glagah Putih kemudian, “Marilah kita bicarakan dengan sungguh-sungguh permasalahan ini”
Selesai berkata demikian Glagah Putih segera mempersilahkan kedua orang tua itu untuk berjalan menepi dan duduk di bawah sebatang pohon peneduh yang tumbuh di kanan jalan.
Setelah ketiganya menempatkan diri duduk di bawah bayangan pohon yang teduh itu, barulah Glagah Putih meneruskan kata-katanya, “Guru, aku mempunyai perhitungan bahwa saat ini Ki Wiyaga tentu telah melaporkan kejadian pagi tadi kepada Ki Gede Matesih.”
Serentak bagaikan telah berjanji, kedua orang tua itu mendongakkan wajahnya ke langit.
“Sudah hampir wayah tengange,” desis Ki Jayaraga
“Ya Ki Jayaraga,” sahut Ki Bango Lamatan, “Tentu Ki Gede sudah mendapat laporan dari Ki Wiyaga.’
“Nah Glagah Putih,” berkata Ki Jayaraga selanjutnya, “Apa hubungannya dengan Ratri, putri Ki Gede?”
“Guru,” jawab Glagah Putih kemudian. Tampak wajahnya bersungguh-sungguh sehingga kedua orang itu pun telah menaruh perhatian sepenuhnya, “Aku mempunyai dugaan bahwa apa yang telah dilaporkan oleh Ki Wiyaga kepada Ki Gede sedikit banyak akan diketahui oleh Raden Surengpati.”
Kedua orang tua itu saling pandang sejenak. Ki Jayaraga lah yang menanggapi, “Bagaimana mungkin, Glagah Putih? Ki Wiyaga tentu tidak gegabah dalam memberikan laporannya.”
“Benar, guru,” sahut Glagah Putih cepat, “Akan tetapi bagaimana dengan keluarga Ki Gede sendiri? Apakah tidak menutup kemungkinan Ratri mendengar walaupun hanya sekilas-sekilas dan kemudian menyampaikannya kepada Raden Surengpati.”
Kini kedua orang tua itu termenung. Memang hal itu sangat mungkin terjadi.
“Jadi apa rencanamu sekarang Glagah Putih?’ bertanya Ki Bango Lamatan kemudian.
Sejenak Glagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun baru saja Glagah Putih akan menjawab pertanyaan Ki Bango Lamatan, tiba-tiba dari kejauhan Glagah Putih melihat seseorang mendatangi tempat itu.
“Penjual dawet serabi,” desis Glagah Putih kemudian. Serentak kedua orang tua itu pun mengikuti arah pandang Glagah Putih.
“Apakah engkau haus Glagah Putih?” bertanya Ki Jayaraga kemudian sambil tersenyum.
Glagah Putih tidak segera menjawab. Pandangan matanya justru mengarah kepada Ki Bango Lamatan.
Ki Bango Lamatan pun lantas tertawa pendek. Katanya kemudian, “Alangkah segarnya minum dawet serabi di siang hari yang terik seperti ini.”
Ki Jayaraga dan Glagah Putih pun akhirnya ikut tertawa.
Demikianlah sejenak kemudian mereka bertiga telah memanggil penjual dawet serabi yang lewat di depan mereka.
Penjual dawet serabi itu pun segera berhenti dan menurunkan dagangannya. Dengan cekatan dilayaninya para pembelinya itu satu persatu.
“Ki Sanak,” berkata Glagah Putih kemudian setelah dia menyelesaikan minumnya lebih cepat dari kedua orang tua itu, “Kelihatannya mangkukku ini lebih kecil dibanding dengan mangkuk yang lainnya.”
“Ah,” penjual dawet itu tertawa, “Apakah engkau bermaksud menambah lagi, anak muda?”
Glagah Putih pun mengangguk sambil tertawa. Sementara Ki Jayaraga sambil menyenduk minumannya telah berkata kepada Glagah Putih, “Lain kali engkau membawa wadah sendiri saja, tempayan atau genthong barangkali.”
Yang mendengar kelakar Ki Jayaraga itu pun telah tertawa.
“Ki Sanak,” tiba-tiba penjual dawet itu berkata sambil memandang satu-persatu pembelinya, “Rasa-rasanya aku belum pernah melihat kalian. Dari manakah Ki Sanak semua ini?”
Sejenak mereka bertiga saling berpandangan. Ki Jayaraga lah yang akhirnya menjawab sambil mengembalikan mangkuknya yang telah kosong.
“Kami berasal dari Sangkal Putung,” jawab Ki Jayaraga sekenanya, “Dan kami sedang menuju ke Padukuhan Paran-paran.”
Penjual dawet ini mengerutkan keningnya. Tanyanya kemudian, “Di manakah letak Padukuhan Paran-paran itu Ki Sanak?”
Ki Jayaraga tersenyum. Jawabnya kemudian, “Padukuhan Paran-paran terletak di antara lembah Gunung Sindara dan Sumbing.”
“O,” penjual dawet itu tampak mengangguk-anggukkan kepalanya walaupun sebenarnya dia tidak mengetahui dengan pasti letak padukuhan itu.
“Terima Kasih Ki Sanak,” berkata penjual dawet itu kemudian ketika Ki Jayaraga membayar harga empat mangkuk dawet serabi, “Semoga perjalanan kalian menyenangkan.”
“Terima kasih,” jawab mereka bertiga hampir bersamaan.
“Semoga sekembalinya kami dari Paran-paran, kita dapat berjumpa kembali,” tambah Glagah Putih.
“O, tentu, tentu ki Sanak,” jawab penjual dawet itu sambil mengangkat pikulannya dan kemudian menaruh di pundaknya, “Hampir setiap hari aku melewati jalan ini.”
“Tapi engkau jangan lupa membawa tempayan,” sahut Ki Jayaraga sambil menggamit Glagah Putih yang segera saja disambut dengan gelak tawa.
Demikianlah setelah penjual dawet serabi itu pergi, Glagah Putih pun segera menyampaikan rencananya.
“Guru,” berkata Glagah kemudian, “Sebaiknya perjalanan kita ke Gunung Tidar kita tunda sebentar. Siang ini sampai nanti menjelang sore kita coba untuk mengamati kediaman Ki Gede. Barangkali putri Ki Gede akan keluar menemui Raden Surengpati untuk menyampaikan berita yang telah dibawa oleh Ki Wiyaga.”
Ki Jayaraga mengerutkan keningnya sambil memandang Ki Bango Lamatan. Agaknya guru Glagah Putih itu meminta pertimbangan untuk menyetujui rencana Glagah Putih.
Untuk sejenak Ki Bango Lamatan termenung. Namun tiba-tiba saja Ki Bango Lamatan berdesis perlahan, “Bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Raden Surengpati itu yang menemui Ratri di kediaman Ki Gede?”
Sekarang giliran Glagah Putih yang tertegun. Kemungkinan itu memang ada, namun menilik tanggapan Ki Gede yang tidak menginginkan putri satu-satunya itu menjalin hubungan dengan orang yang mengaku sebagai Trah Sekar Seda Lepen itu, kemungkinannya sangat kecil jika Ki Gede mengijinkan Raden Surengpati menemui putrinya.
Maka jawab Glagah Putih kemudian, “Kemungkinan itu sangat kecil, Ki Bango Lamatan. Aku justru cenderung hubungan mereka berdua itu masih sebatas sembunyi-sembunyi. Aku yakin mereka berdua belum berani berterus terang justru karena Ki Gede telah memperlihatkan sambutan yang kurang ramah atas kehadiran para pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu di perdikan Matesih.”
“Engkau benar Glagah Putih,” berkata ki Jayaraga kemudian setelah sejenak berpikir, “Memang sebaiknya kita mengamati kediaman Ki Gede siang ini sampai sore nanti. Semoga apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi.”
Demikianlah sejenak kemudian ketiga orang itu segera meneruskan perjalanan. Mereka mengambil jalan yang berbelok ke kanan, jalan yang terlihat lebih kecil dari jalan sebelumnya.
“Agaknya jalan ini sangat jarang dilewati orang,” berkata Ki Jayaraga sambil mengayunkan langkahnya.
“Kelihatannya memang demikian, Ki,” sahut Ki Bango Lamatan sambil mengamat-amati pohon-pohon perdu liar yang tumbuh di sepanjang jalan, “Jalan ini sepertinya sebuah jalan pintas.”
“Aku juga mengira demikian,” kembali Ki Jayaraga berkata sambil ikut mengamati tanah pategalan yang kelihatannya sudah tidak terurus.
Sejenak kemudian jalan yang mereka lewati itu semakin lama menjadi semakin menyempit dan hanya tinggal jalan setapak saja yang terlihat menjelujur di antara rumput-rumput dan ilalang yang tumbuh liar di sana sini.
Selagi mereka berjalan sambil merenungi semak belukar yang semakin lebat, tiba-tiba saja pendengaran mereka yang tajam lamat-lamat telah mendengar langkah seseorang yang terdengar sangat tergesa-gesa dari arah kanan jalan. Memang masih cukup jauh, namun suara langkah itu begitu jelas terdengar di antara suara daun-daun yang tersibak dan ranting-ranting kecil yang berpatahan.
Untuk beberapa saat ketiga orang itu tidak tahu harus berbuat apa untuk menyikapi suara langkah yang terdengar semakin dekat itu. Namun ketika Ki Jayaraga kemudian menganggukkan kepalanya, serentak mereka bertiga pun segera bersembunyi di balik perdu-perdu yang banyak berserakan di tempat itu.
Sambil menahan nafas, mereka bertiga mencoba mengintip dari sela-sela dedaunan untuk melihat siapakah yang akan muncul dari pategalan di kanan jalan yang sudah tak terurus lagi itu.
Semakin lama suara langkah itu terdengar semakin keras. Sejenak kemudian dari balik sebatang pohon sawo kecik, muncul seraut wajah yang sangat dikenal oleh Glagah Putih.
“Ratri?” desis Glagah Putih dengan suara yang bergetar.
Kedua orang tua itu terkejut mendengar desis Glagah Putih sehingga telah berpaling ke arahnya.
“O, jadi itukah Ratri? Pantas!” bisik Ki Bango Lamatan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.
“Maksud Ki Bango Lamatan?” tanya Glagah Putih sambil berpaling.
Ki Bango Lamatan berpaling sekilas sambil tersenyum. Jawabnya kemudian, “Gadis yang bernama Ratri itu sangat cantik. Tentu banyak laki-laki yang ingin menyuntingnya.”
“Termasuk Ki Bango Lamatan barangkali,” sahut Ki Jayaraga
“Ah,” Ki Bango Lamatan hampir saja tidak dapat menahan tawanya, namun yang menjadi merah mukanya justru Glagah Putih.
“Lihatlah,” berkata Ki Jayaraga kemudian mengalihkan pembicaraan, “Putri Ki Gede itu memotong jalan dan memasuki pategalan di sebelah kiri jalan.”
“Kita ikuti,” sahut Glagah Putih cepat sambil berdiri dan kemudian melangkah menuju ke tempat putri Matesih itu menghilang.
Kedua orang tua itu sejenak saling berpandangan. Sambil menahan senyum akhirnya kedua orang tua itu pun berdiri dan melangkah mengikuti Glagah Putih.
Bukanlah sebuah pekerjaan yang sulit bagi ketiga orang itu untuk mengikuti jejak Ratri. Putri Ki Gede Matesih itu hanyalah seorang gadis kebanyakan yang tidak pernah diperkenalkan pada olah kanuragan sejak kecil.
Semakin lama ketiga orang itu semakin jauh memasuki pategalan yang sudah berubah menjadi seperti hutan kecil itu. Setelah melalui jalan setapak yang nyaris tak terlihat dan kemudian menurun, terlihat sebuah parit yang airnya mengalir bening.
“Parit ini mungkin digunakan sebagai pengairan ketika pategalan-pategalan ini masih digarap,” berkata Ki Jayaraga dalam hati sambil meloncati batang pohon yang tumbang karena lapuk dimakan usia.
Beberapa saat kemudian ketiga orang itu melihat Ratri telah berhenti di sepetak tanah yang ditumbuhi rumput. Di tanah sepetak itu kelihatannya dulu pernah didirikan sebuah gubuk untuk tempat beristirahat.
Sejenak Ratri terlihat masih berdiri termangu-mangu. Tampaknya dia sedang menunggu seseorang. Dengan raut wajah yang terlihat gelisah dia kemudian duduk di atas batu yang menjorok di sebelah parit yang airnya mengalir dengan bening.
Dalam pada itu di salah satu jalan di sebelah barat perdikan Matesih, tampak dua orang penunggang kuda, Eyang guru dan Raden Surengpati sedang memacu kudanya dengan sedikit kencang.
“Eyang guru,” berkata Raden Surengpati, “Di depan ada simpang tiga. Sebelum kita meneruskan perjalanan melalui jalan yang membelok ke kiri, ijinkan aku untuk menemui Ratri terlebih dahulu.”
“Raden,” jawab Eyang guru, “Apakah pertemuan itu dapat ditunda? Kita sebaiknya sampai di Tidar sebelum Matahari tergelincir jauh ke barat. Banyak hal yang harus kita bicarakan sehubungan dengan kedatangan Ki Rangga Agung Sedayu.”
“Aku paham Eyang guru,” jawab Raden Surengpati kemudian, “Namun sekarang ini adalah waktunya aku bertemu Ratri di tempat yang sudah kita sepakati. Mungkin Ratri membawa berita yang penting.”
Eyang guru menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, “Baiklah Raden. Kalau begitu aku menunggu saja di persimpangan. Aku tidak ingin mengganggu keasyikan kalian berdua.”
“Ah,” desah Raden Surengpati, “Ratri adalah gadis yang masih lugu. Dia selalu membawa kawan jika bertemu denganku.”
“He?!” terkejut Eyang guru mendengar keterangan Raden Surengpati.
Sambil berpaling sekilas, Eyang guru pun kemudian bertanya, “Apakah teman Ratri itu dapat dipercaya?”
“Ya, Eyang guru,” jawab Raden Surengpati mantap, “Kawannya itu adalah pemomongnya sejak kecil, jadi sudah dianggap seperti biyungnya sendiri. Apalagi sejak Nyi Gede meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, pemomongnya itu seolah-olah telah dianggap sebagai pengganti biyungnya.”
Eyang guru menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Tak terasa derap langkah kaki-kaki kuda mereka telah mendekati simpang tiga.
“Aku akan menunggu di sini,” berkata Eyang guru kemudian sambil meloncat turun dan kemudian menambatkan kudanya pada sebatang pohon di pinggir jalan. Sementara Raden Surengpati masih belum turun dari kudanya.
“Apakah Raden akan berkuda?” bertanya Eyang guru sambil mengambil duduk di bawah sebatang pohon besar yang akar-akarnya tampak menonjol keluar.
Sejenak Raden Surengpati termenung. Namun akhirnya dia pun menjawab, “Aku akan berkuda saja Eyang guru. Tempatnya memang agak jauh dari sini.”
“Pergilah!” berkata Eyang guru sambil merebahkan dirinya bersandaran pada batang pohon itu.
“Terima kasih Eyang guru,” jawab Raden Surengpati kemudian, “Aku pergi dulu.”
Tanpa menunggu lagi, Raden Surengpati pun kemudian segera menghentak perut kudanya agar berlari maju.
Jarak antara simpang tiga dengan tempat yang biasa dijadikan pertemuan Raden Surengpati dengan Ratri memang cukup jauh. Setelah melalui jalan yang menurun, barulah Raden Surengpati membelokkan kudanya menyusuri jalan setapak memasuki sebuah pategalan.
Ketika jalan setapak itu telah menghilang tertutup rumput-rumput liar dan ilalang yang tumbuh rapat berjajar-jajar, Raden Surengpati pun segera menghentikan kudanya dan meloncat turun.
Sejenak Raden Surengpati menarik nafas panjang untuk memenuhi rongga dadanya dengan udara segar siang hari itu. Entah mengapa setiap akan berjumpa dengan Ratri, jantungnya selalu berdebar. Sebenarnyalah bagi Raden Surengpati bukan sekali ini saja dia berhubungan dengan perempuan, namun terhadap Ratri, dia mempunyai tujuan tersendiri.
“Ratri harus bisa membujuk dan meyakinkan ayahnya bahwa perjuangan Trah Sekar Seda Lepen ini memerlukan dukungan penuh dari perdikan Matesih,” berkata Raden Surengpati dalam hati sambil menambatkan tali kekang kudanya pada sebuah batang pohon, “Dengan direstuinya hubungan kami berdua, aku berharap Ki Gede akan legawa untuk melintirkan Perdikan Matesih ini kepadaku sehingga perdikan Matesih akan menjadi tumpuan utama dalam berjuang melawan Mataram.”
Sekali lagi Raden Surengpati menarik nafas panjang. Kemudian dengan langkah yang mantap dia mulai menuruni tanah yang agak miring menuju ke sebuah parit yang sudah tampak dari tempatnya berdiri.
Setelah sampai di tepi parit yang airnya mengalir bening, Raden Surengpati pun menyusuri parit itu mendekati tempat Ratri menunggu dari arah barat. Sementara Ki Jayaraga dan kawan-kawannya telah menempatkan diri di tempat yang agak jauh di sebelah timur dari tempat Ratri menunggu.
Dalam pada itu, Ratri yang sedang menunggu kedatangan Raden Surengpati itu menjadi semakin gelisah. Sesekali dia berdiri dari duduknya dan berjalan mondar-mandir. Namun ketika dirasakan kakinya menjadi penat, dia pun duduk kembali.
“Mengapa aku tadi tidak menunggu mbok Pariyem saja,” berkata Ratri dalam hati sambil sesekali mendongakkan kepalanya ke arah barat, “Tapi mbok Pariyem pergi dari pagi dan belum kembali, sedangkan berita ini sangat penting bagi Raden Mas Harya Surengpati.”
Teringat akan Raden Surengpati, tiba-tiba saja wajah Ratri menjadi cerah. Sebuah senyum manis tersungging di bibirnya yang merah menawan. Gadis putri satu-satunya Ki Gede itu sedang beranjak dewasa bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Mengalami masa-masa remaja yang ingin selalu dipuja dan dimanja, dan agaknya Raden Surengpati telah paham akan hal itu. Pengalaman panjangnya bergaul dengan perempuan telah membuat Ratri menjadi mabuk kepayang.
Tiba-tiba Ratri yang sedang termenung itu mendengar langkah-langkah mendekat dari arah barat. Dengan segera dia berpaling sambil bangkit dari duduknya.
“Raden…” desis Ratri dengan suara yang riang penuh kegembiraan begitu mengetahui siapa yang datang.
Yang datang itu memang Raden Surengpati. Sejenak langkahnya tertegun. Dia tidak melihat kawan Ratri yang biasanya selalu setia menemani.
“Engkau sendiri, Ratri?” bertanya Raden Surengpati kemudian dengan pandangan nanar merayapi sekujur tubuh Ratri.
“Ya, Raden,” jawab Ratri sambil menundukkan wajahnya. Jauh di lubuk hatinya dia telah menyesali ketergesa-gesaannya untuk datang ke tempat itu tanpa mbok Pariyem.
“Nah, berita apakah yang engkau bawa kali ini, Ratri?” bertanya Raden Surengpati kemudian sambil berjalan mendekat.
Sejenak Ratri mengangkat wajahnya. Ketika sepasang matanya memandang ke wajah Raden Surengpati, tiba-tiba saja dadanya berdesir tajam. Wajah itu tidak menampakkan sebagaimana biasanya yang ramah dan lembut. Wajah itu tampak mengerikan, merah membara dengan sepasang mata yang liar menelusuri lekuk-lekuk sekujur tubuhnya.
Dengan segera Ratri menundukkan wajahnya kembali. Sambil berusaha menguasai degup jantungnya yang melonjak-lonjak, dia menjawab pertanyaan Raden Surengpati dengan suara bergetar, “Raden, tadi pagi ayah telah mengadakan pertemuan dengan para bebahu perdikan Matesih.”
“O,” desis Raden Surengpati sambil menarik nafas panjang. Darah di sekujur tubuhnya telah mendidih. Dengan langkah satu-satu, orang yang mengaku trah Sekar Seda Lepen itu berjalan semakin dekat.
“Apa yang mereka bicarakan, Ratri?” terdengar suara Raden Surengpati berbisik di dekat telinganya. Begitu dekatnya sehingga Ratri dengan jelas dapat mendengar desah nafasnya yang memburu.
Seketika gemetar sekujur tubuh putri Matesih itu. Berbagai dugaan muncul dalam benaknya. Ada perasaan takut yang menyergap hatinya begitu menyadari apapun bisa terjadi selagi mereka hanya berdua saja di tempat yang sepi itu.
Menyadari bahaya yang setiap saat dapat saja menerkamnya, Ratri segera berusaha menghindar dari tempat itu. Katanya kemudian sambil melangkah surut, “Maaf Raden, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Setiap saat ayah akan memerlukan aku. Aku harus segera kembali ke bilikku.”
“Tidak Ratri,” tiba-tiba terdengar suara Raden Surengpati itu mirip lolong seekor serigala lapar di telinga Ratri, “Akulah yang sekarang memerlukanmu disini. Tidak ada seorang pun yang akan menggangu. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu, justru aku akan membahagiakanmu dan sekaligus memberikan sebuah pengalaman yang belum pernah engkau rasakan seumur hidup,” Raden Surengpati berhenti sebentar untuk sedikit meredakan dadanya yang seakan-akan mau meledak. Lanjutnya kemudian, “Inilah kesempatan bagiku untuk membuat Ki Gede menyerah dan menuruti segala kemauanku.”
STSD Jilid 4
SELESAI berkata demikian, dengan langkah satu-satu Raden Surengpati
pun kemudian melangkah semakin dekat. Sementara Ratri benar-benar
bagaikan melihat seekor serigala lapar dengan sepasang mata merah
menyala serta gigi-gigi runcing menyeringai mengerikan.
Ada sebersit penyesalan yang menyelinap di dalam hati anak perempuan satu-satunya Ki Gede Matesih itu. Jika dia sedikit bersabar menunggu kedatangan mbok Pariyem, mungkin Raden Surengpati akan bersikap lain.
“Raden,” berkata Ratri kemudian mencoba untuk mengalihkan perhatian Raden Surengpati, “Menurut berita yang aku dengar, kelima orang yang bermalam di banjar padukuhan Klangon itu telah lolos.”
“Persetan dengan segala macam tetek bengek itu!” geram Raden Surengpati, “Aku sudah tidak peduli lagi kepada mereka. Yang ada sekarang ini adalah antara engkau dan aku!”
Selesai berkata demikian, Raden Surengpati maju selangkah lebih dekat. Penalarannya benar-benar telah gelap. Di dalam benaknya hanya ada satu keinginan, menguasai Ratri dengan sepenuhnya kalau perlu dengan paksaan.
Namun putri Matesih itu belum menyerah. Dengan menguatkan hatinya, Ratri pun akhirnya berkata dengan nada sedikit memelas, “Raden, kasihanilah aku. Aku harus cepat kembali, dan Raden pun tentu mempunyai kepentingan lain yang tidak dapat ditunda -tunda. Ijinkanlah aku pergi, Raden.”
Suara Ratri yang terdengar memelas itu di telinga Raden Surengpati bagaikan sebuah rengekan manja dari seorang gadis yang haus akan cinta. Darah di sekujur tubuhnya pun bagaikan mendidih dan kemudian menggelegak menelusuri segenap urat-urat nadinya.
“Ratri,” terdengar suara Raden Surengpati yang bergetar hebat menahan gejolak yang sudah menghanguskan jantungnya, “Engkau begitu cantik dan menawan. Aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk menikmati tubuhmu sejengkal demi sejengkal. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu walau hanya seujung rambutmu. Engkau akan kubawa ke alam keindahan dan kenikmatan yang belum pernah terbayangkan dalam seumur hidupmu.”
Mulut Ratri benar-benar sudah terkunci, tidak mampu lagi untuk berkata-kata maupun berteriak. Kengerian yang sangat telah menjalar ke sekujur tubuhnya sehingga tubuhnya telah kaku seperti sebuah tonggak kayu. Bahkan hanya untuk menggerakkan ujung ibu jari kakinya pun dia sudah tidak mampu lagi.
Ketika salah satu tangan Raden Surengpati yang kekar itu kemudian merengkuh pundaknya, hanya terdengar sebuah jeritan kecil dari mulutnya yang mungil. Sejenak kemudian segalanya terlihat gelap dalam rongga matanya dan Ratri pun jatuh pingsan dalam pelukan Raden Surengpati.
Melihat mangsanya ternyata telah jatuh pingsan, Raden Surengpati pun bagaikan menjadi kalap. Dengan kedua tangan yang gemetar menahan nafsu yang bergejolak, dicobanya untuk membuka pakaian bagian atas putri Matesih itu.
Namun belum sempat dia melakukannya, tiba-tiba telinganya mendengar suara seseorang bergumam tidak seberapa jauh di depannya.
Ketika Raden Surengpati kemudian mengangkat wajahnya, tampak seorang anak muda dengan wajah yang merah padam berdiri beberapa langkah saja di hadapannya dengan kaki renggang dan kedua tangan bersilang di depan dada.
“Iblis!” geram Raden Surengpati kemudian sambil menurunkan tubuh Ratri perlahan-lahan dan kemudian membaringkannya di atas t anah. Sambil maju dua langkah, Raden Surengpati pun kemudian membentak keras, “Siapa yang berani mengganggu kesenangan Raden Surengpati, he?!”
Namun Raden Surengpati menjadi heran sendiri. Pemuda yang berdiri di hadapannya itu tidak menampakkan rasa gentar sedikit pun mendengar dia menyebut nama serta gelar kebangsawanannya. Bahkan sambil mengurai kedua tangannya yang bersilang di depan dada, tangan kanan Pemuda itu justru telah menunjuk ke arah wajahnya sambil membentak tak kalah kerasnya, “Surengpati, namamu yang selama ini menghantui Perdikan Matesih akan berakhir hari ini. Sebelum Matahari terbenam di langit sebelah barat, aku jamin mayatmu akan terbujur di pategalan ini sebagai tumbal tanah Perdikan Matesih untuk menemukan masa depannya kembali.”
“Tutup mulutmu! ” bentak Raden Surengpati kemudian dengan wajah membara, “Sebut namamu sebelum aku membunuhmu! ”
Pemuda itu melangkah setapak ke depan. Sambil membusungkan dada, dia pun kemudian berteriak lantang, “Dengarkan baik-baik. Aku Glagah Putih dari Prambanan yang akan mengakhiri petualanganmu hari ini.”
Belum sempat Glagah Putih menutup mulutnya dengan sempurna, terpaan angin yang keras terasa mendahului serangan Raden Surengpati yang telah meluncur dengan deras menyambar dagunya.
Namun Glagah Putih bukanlah anak kemarin sore yang baru saja berlatih loncat-loncatan dalam olah kanuragan. Dengan tangkasnya dia bergeser selangkah ke samping kiri. Kemudian dengan bertumpu pada tumit salah satu kakinya, kaki yang lainnya berputar menyambar lambung lawannya yang terbuka.
Raden Surengpati yang menyadari sambaran kaki lawannya mengarah ke lambung segera menggeliat. Tumit Glagah Putih pun lewat hanya sejengkal dari lambungnya.
Demikian lah sejenak kemudian kedua orang itu segera bertempur dengan sengitnya. Kedua-duanya masih muda dan berdarah panas, sehingga keduanya segera saja telah merambah pada tingkat ilmu mereka yang semakin tinggi.
Dalam pada itu, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan diam-diam menjadi semakin berdebar-debar melihat tandang Glagah Putih. Dari tempat persembunyian mereka, terlihat Glagah Putih bertempur dengan segenap tenaga dan terlihat sedikit menuruti gejolak dalam dadanya.
“Ki Jayaraga, mengapa Glagah Putih terlihat begitu bernafsu untuk segera menjatuhkan lawannya?” bisik Ki Bango Lamatan kepada Ki Jayaraga yang berada di sampingnya.
Ki Jayaraga tersenyum sambil menggeleng. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu. Mungkin terdorong kemarahan yang membakar jantungnya melihat putri satu-satu Ki Gede Matesih itu dalam bahaya.”
Ki Bango Lamatan mengerutkan keningnya mendengar jawaban Ki Jayaraga. Katanya kemudian, “Seharusnya Glagah Putih mengekang diri. Jika terjadi kesalahan tangan sehingga Raden Surengpati terbunuh, apakah tidak akan membahayakan para kawula tanah Perdikan Matesih ini?”
“Maksud Ki Bango Lamatan, Raden Wirasena sebagai saudara kandung Raden Surengpati pasti akan membalas dendam?”
“Benar, Ki,” jawab Ki Bango Lamatan, “Dan tidak menutup kemungkinan Raden Wirasena akan meminta bantuan perguruan Sapta Dhahana untuk membuat Perdikan Matesih menjadi karang abang.”
Sekarang giliran Ki Jayaraga yang mengerutkan keningnya. Namun sambil tertawa lirih Ki Jayaraga pun kemudian berkata, “Jika memang itu yang kemudian terjadi, sekali lagi kita harus menyembunyikan mayatnya agar untuk sementara orang-orang pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu tidak mengetahuinya.”
Ki Bango Lamatan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam mendengar jawaban Ki Jayaraga. Pandangan matanya kembali melihat ke arah medan pertempuran kedua anak muda itu yang semakin lama semakin sengit.
Pangeran Pati tampak tersenyum sambil
mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, “Ki Rangga, semua yang
kita bicarakan tadi masih bersifat rahasia. Belum ada yang mengetahui
rencana ini kecuali tiga orang, Ayahanda Prabu, Eyang Buyut Mandaraka
dan aku sendiri. Sengaja hal ini aku sampaikan agar hatimu telah siap
sejak awal terutama tentang Rara Anjani,” Pangeran Pati berhenti
sejenak. Lanjutnya kemudian, “Bicarakanlah masalah ini dengan istrimu
dari hati ke hati. Jangan hanya menurutkan hawa nafsu saja. Ingat,
laki-laki memang diciptakan untuk mengatur perempuan namun bukan berarti
kita berhak untuk memaksakan sebuah kehendak.”
Sejenak suasana menjadi sepi. Berbagai
tanggapan telah muncul dalam benak Ki Rangga. Namun akhirnya Ki Rangga
hanya dapat berpasrah diri kepada Yang Maha Mengetahui apapun yang
akan terjadi esok hari.
“Ki Rangga,” berkata Pangeran Pati kemudian memecah sepi, “Apakah Ki Rangga masih mempunyai persoalan yang ingin disampaikan?”
Ki Rangga tidak segera menjawab. Sejenak
ingatannya tiba-tiba saja kembali ke peristiwa pertempuran Lemah Cengkar
beberapa saat yang lalu.
“Ampun Pangeran,” segera Ki Rangga
menghaturkan sembah sambil bertanya, “Jika memang hamba diperkenankan
untuk mengetahui, siapakah orang tua yang pernah bersama Pangeran di
Lemah Cengkar beberapa saat yang lalu?”
Pangeran Pati tidak segera menjawab.
Untuk beberapa saat dipandangi Ki Rangga yang duduk di hadapannya. Namun
setelah menarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu, akhirnya justru
terlontar sebuah pertanyaan dari Pewaris tahta Mataram itu, “Mengapa Ki
Rangga ingin mengetahui jati diri orang tua itu?”
Dengan cepat Ki Rangga menyembah sambil
menjawab, “Mohon ampun Pangeran, hamba rasa-rasanya pernah mengenal
orang tua itu, namun hamba kurang yakin akan pengamatan hamba pada saat
itu.”
Pangeran Pati tersenyum. Jawabnya
kemudian, “Orang tua itu bernama Ki Tanpa Aran, atau kadang-kadang orang
memanggilnya kakek Tanpa Aran. Beliau adalah murid dan juga sekaligus
sahabat dari Kanjeng Sunan.”
Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Ki
Rangga. Segera saja ingatan Ki Rangga melayang pada selembar kain
gringsing yang ditinggalkan oleh orang yang menyebut dirinya Panembahan
Panjer Bumi di Padukuhan Merjan.
“Mungkinkah..?” bertanya Ki Rangga dalam hati. Namun pertanyaan itu hanya disimpannya saja di dalam hati.
“Mohon ampun Pangeran. Di manakah Ki Tanpa Aran itu tinggal?” bertanya Ki Rangga kemudian.
“Sekarang Ki Tanpa Aran tinggal di Ndalem
Kapangeranan atas permintaanku,” jawab Pangeran Pati, “Sebenarnya Ki
Tanpa Aran menolak untuk tinggal di sini, namun atas perkenan Kanjeng
Sunan, Ki Tanpa Aran diminta untuk membimbing aku dalam kawruh lahir
maupun batin sehingga mau tidak mau harus tinggal di Ndalem
Kapangeranan.”
Dada Ki Rangga terasa bergemuruh begitu
mendengar Ki Tanpa Aran itu ternyata sekarang ini tinggal di Ndalem
Kapangeranan. Maka katanya kemudian, “Ampun Pangeran, jika diperkenankan
suatu saat hamba ingin mengenal Ki Tanpa Aran itu lebih dekat.”
“O, silahkan Ki Rangga,” jawab Pangeran
Pati dengan serta merta, “Namun agak sulit untuk menemui orang tua itu.
Walaupun sudah disediakan sebuah bilik khusus baginya, namun bilik itu
lebih sering kosong.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam.
Panggraitanya yang tajam sedikit banyak mulai dapat meraba jati diri
orang yang menyebut dirinya Ki Tanpa Aran itu.
“Nah, Ki Rangga,” berkata Pangeran Pati kemudian, “Apakah masih ada permasalahan lagi yang ingin engkau sampaikan?”
“Hamba kira sudah cukup Pangeran,” jawab Ki Rangga, “Jika diperkenankan hamba segera mohon diri.”
“Silahkan Ki Rangga,” jawab Pangeran Pati
sambil bangkit berdiri yang segera diikuti oleh Ki Rangga, “Sampaikan
salamku kepada Ki Waskita dan Ki Jayaraga serta Glagah Putih. Ingat, apa
yang kita bicarakan tadi hanya sebatas pengetahuan untuk diri Ki Rangga
saja.”
“Hamba Pangeran,” jawab Ki Rangga sambil membungkuk dalam-dalam.
Demikianlah akhirnya Ki Rangga pun segera
minta diri. Setelah diantar oleh Pelayan Dalam sampai ke regol depan,
Ki Rangga pun memilih melanjutkan perjalanannya kembali ke Istana
Kepatihan seorang diri.
“Apakah Ki Rangga memerlukan kawan?” bertanya prajurit jaga Ndalem Kapangeranan yang menjemputnya tadi.
“O, tidak. Terima kasih,” jawab Ki Rangga
sambil tersenyum, “Aku sudah tahu jalannya. Jika aku nanti tersesat,
aku bisa bertanya kepada para prajurit yang berada di gardu penjagaan
sepanjang jalan menuju istana Kepatihan.”
“Atau kalau ragu-ragu, Ki Rangga dapat
kembali ke penjagaan ini untuk bertanya,” jawab prajurit itu yang
disambut dengan gelak tawa.
Demikianlah, sejenak kemudian Ki Rangga pun telah menyusuri jalan yang menuju ke istana Kepatihan.
Dalam pada itu, malam telah melewati
puncaknya. Angin malam yang dingin bertiup lembut mengusap tubuh Ki
Rangga yang sedikit basah oleh keringat. Suara binatang malam yang
terdengar bersahut-sahutan dalam irama ajeg menambah suasana malam yang
sepi itu menjadi semakin ngelangut.
Namun baru beberapa puluh langkah
meninggalkan Ndalem Kapangeranan, tiba-tiba saja pendengaran Ki Rangga
yang tajam telah mendengar suara yang asing di antara nyanyian binatang
malam. Ketajaman panggraitanya telah memberitahukan kepadanya bahwa
suara itu bukan suara yang berasal dari sejenis binatang malam.
Suara itu sedikit berbeda dengan suara
binatang-binatang yang lain. Suara itu sesekali terdengar bagaikan desis
seekor ular namun dengan nada yang berubah-ubah. Kadang meninggi tajam
seperti jeritan seekor bilalang, namun tiba-tiba dengan cepat menurun
seperti derik seekor jengkerik.
Dengan segera Ki Rangga menghentikan
langkahnya. Dengan aji sapta pangrungu dicobanya untuk mengetahui arah
sumber suara itu. Tiba-tiba dada Ki Rangga menjadi berdebar-debar.
Sumber suara itu berasal dari arah belakang Ndalem Kapangeranan.
Untuk beberapa saat Ki Rangga menjadi
ragu-ragu. Seumur hidup Ki Rangga memang belum pernah mendengar suara
isyarat semacam itu kecuali yang pernah diperagakan oleh gurunya pada
waktu itu. Suara yang dia dengar itu adalah semacam isyarat dari sebuah
perguruan yang pernah berjaya di masa Kerajaan Majapahit, perguruan
Windujati. Bahkan menurut cerita gurunya, beberapa perguruan lain yang
masih sealiran dengan perguruan Windujati juga telah menggunakan
isyarat semacam itu untuk kepentingan bersama.
Sebagai murid orang bercambuk, tentu saja
Ki Rangga juga mendapat pengetahuan tentang bahasa isyarat itu dari
gurunya. Namun sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh gurunya, isyarat
semacam itu hampir tidak pernah dijumpai lagi semenjak pemerintahan
Demak lama berpindah ke Pajang dan kemudian sampai Mataram berdiri.
Kini pada saat Ki Rangga berada di dekat Ndalem Kapangeranan justru telah mendengar suara isyarat semacam itu.
“Ki Tanpa Aran?” tiba-tiba terlintas
sebuah nama di dalam benak Ki Rangga, “Mungkinkah Ki Tanpa Aran yang
telah melontarkan isyarat itu untuk memanggilku?”
Berpikir sampai disitu, tiba-tiba saja
sekujur tubuh Ki Rangga menjadi gemetar. Dugaan sementara tentang orang
tua yang menyebut dirinya Ki Tanpa Aran itu memang mengarah kepada
gurunya, Kiai Gringsing yang tidak pernah diketahui tempat kuburnya.
Dengan mengerahkan kemampuannya untuk
menyerap segala bunyi yang dapat ditimbulkan oleh gesekan pergerakan
tubuhnya dengan alam sekitarnya, Ki Rangga pun segera bergeser mendekati
ke arah sumber bunyi tersebut.
Setelah meloncati beberapa pagar
rumah-rumah yang berada di sekitar Ndalem Kapangeranan, Ki Rangga
berusaha untuk semakin dekat dengan sumber bunyi itu.
Namun begitu Ki Rangga telah semakin
dekat dengan sumber bunyi itu, ternyata sumber bunyi itu justru mulai
bergeser menjauh. Agaknya orang yang dengan sengaja telah melontarkan
isyarat itu mengetahui bahwa seseorang telah tertarik dengan isyaratnya
dan sedang berusaha mendekat ke arahnya.
Sejenak kemudian sumber bunyi itu
ternyata telah bergerak semakin menjauhi Ndalem Kapangeranan. Ki Rangga
harus meloncati pagar dan menyeberangi halaman beberapa rumah untuk
mengikuti sumber bunyi itu sebelum akhirnya sampai di dinding yang
membatasi Kota Mataram sebelah utara. Sumber bunyi itu agaknya
memperhitungkan juga keadaan di sekitarnya dan tidak ingin mendapat
kesulitan dengan para prajurit yang sedang meronda sehingga memilih
jalur di luar kewajaran.
Untuk beberapa saat Ki Rangga justru diam
membeku di bawah dinding. Ada sedikit keragu-raguan yang menyelinap di
dalam dadanya. Tidak menutup kemungkinan bahaya sedang mengintainya di
balik dinding.
Namun anggapan itu segera ditepisnya
sendiri. Dengan mengetrapkan aji sapta pangrungu, Ki Rangga mencoba
meraba apa yang sedang terjadi di balik dinding. Sementara sumber bunyi
itu justru telah berhenti dan tidak terdengar lagi.
Dengan dada yang berdebaran Ki Rangga
semakin mempertajam pengetrapkan aji sapta pangrungunya untuk menelisik
keadaan di balik dinding. Namun yang terjadi kemudian sungguh diluar
dugaan Ki Rangga. Pendengarannya yang sangat tajam justru menangkap
langkah-langkah yang sangat halus nyaris tak terdengar dari arah
belakangnya.
Dengan segera Ki Rangga menghilang di balik sebuah gerumbul perdu yang banyak tumbuh di sekitar dinding.
“Ki Waskita,” desis Ki Rangga dalam hati
begitu melihat bayangan seorang tua yang berjalan mendekati dinding.
Hampir saja Ki Rangga menampakkan dirinya, namun dengan segera niat itu
diurungkannya.
Untuk beberapa saat Ki Waskita masih
termangu-mangu di bawah dinding. Namun setelah yakin tidak ada suatu
gerakan pun yang didengarnya dari balik dinding, Ki Waskita pun segera
bergerak meloncatinya.
Sejenak kemudian bayangan ayah Rudita itu pun segera menghilang di balik dinding.
“Agaknya Ki Waskita pun mengenali isyarat
itu,” berkata Ki Rangga dalam hati sambil perlahan-lahan muncul dari
balik gerumbul. Dengan tetap mengetrapkan aji sapta pangrungunya, Ki
Rangga pun akhirnya memutuskan untuk menyusul Ki Waskita.
Demikianlah, dengan tanpa sepengetahuan
orang yang telah dianggap sebagai gurunya selain Kiai Gringsing itu, Ki
Rangga mengikuti langkah-langkah Ki Waskita menyusuri sebuah bulak yang
cukup panjang. Sementara sumber bunyi itu sudah terdengar lagi namun
sudah cukup jauh di depan.
Untuk beberapa saat Ki Rangga harus
berjalan di bawah tanggul di kiri jalan. Tanggul itu cukup tinggi
sehingga jika dengan tiba-tiba Ki Waskita berpaling ke belakang, ada
kesempatan bagi Ki Rangga untuk melekatkan dirinya di dinding tanggul.
“Apakah tidak sebaiknya aku menampakkan
diriku saja?” berkata Ki Rangga dalam hati, “Tidak sepatutnya aku
bersembunyi dari Ki Waskita, orang yang telah memberiku kesempatan untuk
membaca dan mempelajari kitabnya.”
Berpikir sampai disitu, Ki Rangga segera
mempercepat langkahnya dengan tanpa menyembunyikan lagi bunyi yang
ditimbulkan dari gerakan tubuhnya.
Agaknya Ki Waskita pun segera mendengar
langkah tergesa-gesa di belakangnya. Ketika Ki Waskita pun kemudian
berpaling ke belakang, seraut wajah yang sudah sangat dikenalnya telah
tersenyum sambil mempercepat langkah menuju ke tempatnya.
“Engkau ngger?” sapa Ki Waskita juga sambil tersenyum.
“Ya Ki Waskita,” jawab Ki Rangga sambil menjajari langkah Ki Waskita, “Agaknya kita mempunyai tujuan yang sama.”
“Ya ngger,” jawab Ki Waskita, “Suara itu
sangat menarik perhatian. Dulu aku pernah melakukan hal yang serupa dan
ternyata dugaanku benar, gurumu sangat tertarik dengan suara isyaratku
itu dan telah mendatangi ke tempat aku menunggu.”
Ki Rangga mengerutkan keningnya. Gurunya
tidak pernah bercerita tentang peristiwa itu. Maka tanyanya kemudian,
“Bagaimana Ki Waskita bisa mengetahui tentang isyarat itu? Bukankah Ki
Waskita dan guru bukan berasal dari satu sumber?”
“Engkau benar ngger,” jawab Ki Waskita,
“Kami memang bukan saudara seperguruan, namun isyarat itu memang telah
digunakan bersama oleh orang-orang yang berkepentingan dalam menegakkan
Demak sepeninggal Majapahit.”
Tak terasa langkah mereka berdua hampir
mencapai tengah-tengah bulak ketika tiba-tiba saja suara desis yang
mirip dengan desis seekor ular itu berhenti.
“Suara itu berhenti, Ki,” bisik Ki Rangga sambil memperlambat langkahnya.
“Ya, ngger. Suara itu telah berhenti,”
jawab Ki Waskita. Kemudian sambil menunjuk ke depan, Ki waskita
melanjutkan, “Lihatlah, di depan ada seseorang yang sedang menunggu
kita.”
Pandangan mata Ki Rangga yang tajam
segera saja mengenali seseorang yang berperawakan tinggi sedang berdiri
di tengah jalan sambil bertolak pinggang beberapa puluh tombak di depan
mereka.
Dalam pada itu di Ndalem Kapangeranan,
Rara Anjani telah keluar dari biliknya. Dengan tergesa-gesa dia menuju
ke dapur. Namun alangkah terkejutnya Rara Anjani, begitu dia membuka
pintu dapur yang terhubung dengan ruang tengah, tampak pelayan tua itu
sedang duduk terkantuk-kantuk di bibir amben bambu yang terletak di
sudut dapur.
“Mbok,” sapa Rara Anjani, “Mengapa belum tidur?”
Perempuan tua itu terkejut dan berpaling.
Sambil mengusap kedua matanya dia menyahut, “O, Rara kiranya. Aku
menunggu titah Pangeran jika ada sesuatu yang diperlukan.”
Rara Anjani tersenyum. Katanya kemudian,
“Tidurlah mbok. Malam telah larut. Aku kira Pangeran Pati tidak
membutuhkan apa-apa lagi.”
Sejenak pelayan tua itu memandangi Rara
Anjani tanpa berkedip. Katanya kemudian, “Nah, Rara sendiri mau kemana
malam-malam begini?”
“Aku akan ke pakiwan sebentar, mbok?”
“Mengapa tidak memakai pakiwan yang ada di dalam?”
“Aku terbiasa dengan pakiwan yang berada di halaman belakang mbok,” jawab Rara Anjani sambil melangkah menuju pintu keluar.
“Bawalah dlupak Rara, diluar sangat gelap.”
“Tidak mbok, terima kasih. Aku sudah terbiasa melihat dalam gelap.”
Pelayan tua itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil memandangi bayangan Rara Anjani yang hilang di balik pintu.
Dalam pada itu, begitu Rara Anjani
melangkah keluar pintu, kegelapan yang pekat segera menyergapnya. Namun
Rara Anjani bukanlah perempuan kebanyakan. Dengan menajamkan indera
penglihatannya, Rara Anjani tanpa ragu-ragu segera mengayunkan
langkahnya menuju ke sebelah Pakiwan, ke sebuah pohon nangka yang tumbuh
menjulang tinggi.
“Untung aku tadi menggunakan pakaian
rangkap,” desis Rara Anjani dalam hati sambil tersenyum kecil, “Sekarang
aku dapat dengan bebas mencegat Ki Rangga dengan memakai pakaian
khususku.”
Namun sebelum Rara Anjani sempat
melepaskan pakaian luarnya, tiba-tiba pandangan matanya yang tajam
menangkap sesuatu yang aneh sedang bergerak di dahan rendah dari pohon
nangka itu.
Sejenak Rara Anjani mengerutkan
keningnya. Bayangan hitam itu mirip seekor kera yang cukup besar sedang
bergelantungan di dahan yang rendah. Dengan tenangnya bayangan itu
berayun-ayun tanpa menimbulkan suara. Seolah-olah bayangan itu terpisah
dari alam sekitarnya.
Rara Anjani masih terdiam di tempatnya.
Dia benar-benar tidak mengerti sedang berhadapan dengan makhluk apa.
Ketika dia sedang berusaha mempertajam pandangan matanya, tiba-tiba saja
makhluk itu menjatuhkan dirinya ke tanah dan menggelinding ke arahnya.
Hampir saja Rara Anjani menjerit. Untung
kesadaran masih menguasai nalarnya. Dengan gerak naluriah, Rara Anjani
pun bergerak mundur beberapa langkah untuk mengambil jarak.
Sejenak makhluk yang aneh itu diam
melingkar di atas tanah yang lembab. Tidak terlihat gerakan sama sekali
kecuali hanya terdengar samar-samar tarikan nafas yang halus dan
teratur.
“Siapa?” bertanya Rara Anjani menguatkan
hatinya. Seumur hidup Rara Anjani memang belum pernah melihat atau pun
bertemu hantu. Namun kali ini penalarannya yang sedikit buram telah
mengarah kesana.
Tidak terdengar jawaban dari benda yang
lebih mirip dengan sebongkah batu padas itu. Ketika dengan memberanikan
diri Rara Anjani mencoba maju selangkah, benda itu pun segera berguling
menjauh dengan jarak yang sama.
Rara Anjani benar-benar menjadi tidak
sabar. Ada sedikit rasa gusar yang menyelinap di dalam dadanya. Dia
merasa dipermainkan oleh seseorang yang barangkali ingin menggagalkan
rencananya untuk mencegat Ki Rangga Agung Sedayu.
“Siapapun Ki Sanak, aku merasa tidak
punya urusan,” geram Rara Anjani. Sebagai perempuan yang telah
mempelajari olah kanuragan jaya kawijayan, harga dirinya merasa terusik.
Lanjutnya kemudian dengan suara sedikit membentak, “Pergilah! Atau aku
akan menyingkirkan ujudmu yang sangat tidak menarik ini dari hadapanku
secara paksa!”
Agaknya kali ini ujud yang mirip
sebongkah batu padas itu menanggapi kata-kata Rara Anjani. Tiba-tiba
ujud itu terlihat melunak dan melumer menjadi sebentuk seperti selembar
kain panjang yang teronggok begitu saja di atas tanah. Namun sebelum
Rara Anjani menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, tiba-tiba saja
makhluk aneh itu melenting tinggi dan kemudian hilang dalam rimbunnya
pepohonan di halaman belakang Ndalem Kapangeranan.
Jantung Rara Anjani benar-benar hampir
terlepas dari tangkainya. Ketika baru saja dia menarik nafas lega,
tiba-tiba terdengar suara tertawa lirih hanya selangkah di belakangnya.
Dengan cepat Rara Anjani segera memutar
tubuhnya. Tampak hanya selangkah di hadapannya berdiri seorang yang
sangat pendek dan berwajah tua bangka.
Berdesir dada Rara Anjani. Dengan cepat
dia segera mengambil jarak mundur beberapa langkah. Walaupun dia adalah
salah satu perempuan perkasa yang menguasai olah kanuragan jaya
kawijayan, namun menghadapi seseorang yang sangat aneh di malam yang
pekat itu, tidak urung membuat jantungnya bergetar juga.
“Maafkan aku Rara,” terdengar makhluk
pendek itu bersuara mirip suara kanak-kanak, “Sengaja aku mengganggumu
malam ini, karena terdorong oleh rasa tanggung jawabku sebagai pemomong
para trah Mataram sejak Panembahan Senapati masih bergelar Mas Ngabehi
Loring Pasar sampai dengan saat ini cucunda Raden Mas Rangsang telah
diwisuda sebagai Pangeran Pati.”
Degub di dalam dada Rara Anjani semakin
kencang. Menurut pengenalannya selama ini di Ndalem Kapangeranan, tidak
pernah ditemui pemomong Pangeran Pati yang berujud seperti yang sekarang
ini berdiri di hadapannya. Maka jawabnya kemudian, “Ki Sanak jangan
ngayawara. Aku mengetahui seluruh penghuni Ndalem Kapangeranan ini
sampai para pekatik dan jajar, emban dan pelayan,” Rara Anjani berhenti
sejenak. Lanjutnya kemudian, “Tidak ada penghuni Ndalem Kapangeranan
yang mempunyai ujud seperti Ki sanak ini. Apakah maksud Ki sanak yang
sebenarnya?”
Tiba-tiba makhluk pendek itu mengambil
ujudnya seperti batu kembali dan menggelinding menjauh. Katanya kemudian
sambil tertawa lirih, “Aku adalah pemomong para calon Raja Mataram
sejak Raden Sutawijaya masih muda. Karena pada saat itu aku merasa
ajalku sudah dekat, aku kemudian minta ijin untuk bertapa di lereng
Merapi. Ternyata permohonanku dikabulkan dan aku menjadi mrayang dan diberi gelar Kiai Dandang Wesi yang bertugas memomong dan menjangkungi calon pewaris tahta Mataram turun temurun.”
Rara Anjani mengerutkan keningnya
dalam-dalam. Cerita makhluk itu sama sekali tidak mengena di hatinya.
Maka katanya kemudian, “Aku tidak mengerti dengan cerita Ki Sanak dan
aku juga tidak melihat adanya hubungan antara diriku pribadi dengan
cerita Ki Sanak.”
Makhluk yang sekarang mengambil ujud
seperti batu padas itu terdengar tertawa. Jawabnya kemudian, “Rara
adalah selir dari Pangeran Pati. Apakah aku masih harus menjelaskan
hubungannya dengan tugasku?”
Kembali Rara Anjani mengerutkan
keningnya. Jawabnya kemudian, “Memang benar aku adalah selir Pangeran
Pati. Namun Ki sanak adalah pemomong Pangeran Pati jika memang pengakuan
Ki Sanak dapat dipercaya,” Rara Anjani berhenti sebentar. Lanjutnya
kemudian, “Nah, silahkan Ki Sanak mengurusi momongan Ki sanak dan jangan
ikut campur dengan urusanku, karena kita sama sekali tidak ada sangkut
pautnya.”
Selesai berkata demikian Rara Anjani
sudah bersiap melangkah pergi kalau saja tidak didengarnya makhluk itu
berkata perlahan namun telah membuat sekujur tubuh Rara Anjani
menggigil.
“Apa tanggapan orang jika selir dari momonganku telah bertemu dengan laki-laki lain di tempat dan waktu yang tidak sewajarnya?”
Bagaikan disambar petir di siang bolong,
Rara Anjani pun terperanjat bukan alang kepalang. Ternyata makhluk aneh
itu telah mengetahui rencana rahasianya untuk menemui Ki Rangga Agung
Sedayu.
“Rara,” kembali terdengar makhluk itu
berbicara, namun kini terdengar nada suaranya sangat sareh, “Rara telah
bersuami. Apapun yang terjadi, hargailah suami Rara. Betapapun Rara
masih mencintai laki-laki itu, namun Rara sudah menjadi milik suami
Rara, Pangeran Pati yang suatu saat nanti jika waktunya telah tiba akan
menggantikan kedudukan Ayahandanya sebagai Raja Mataram.”
Jika saja ada batu-batu padas yang
berguguran dari lereng bukit dan menimpa dadanya satu persatu, niscaya
tidak akan sedahsyat rasa sakit yang mendera dadanya saat itu begitu
mendengar kata-kata makhluk aneh itu yang secara langsung telah
menyadarkan dirinya akan kedudukannya sekarang ini.
“Nah, kembalilah ke bilikmu Rara,”
kembali makhluk aneh itu berkata dengan suara yang berat dan dalam, “Apa
kata Pangeran Pati nantinya jika mendapatkan bilikmu kosong?”
Kalimat terakhir dari makhluk aneh itu
benar-benar telah membuka penalaran Rara Anjani yang semula buram
sedikit demi sedikit menjadi terang.
“Terima kasih Ki Sanak,” jawab Rara
Anjani lirih hampir tak terdengar, “Ki Sanak telah berhasil menyadarkan
aku akan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh perempuan yang
sudah bersuami.”
Terdengar sebuah tarikan nafas yang berat
dari makhluk itu sebelum akhirnya dia melenting tinggi dan hilang di
dalam rimbunnya dedaunan.
Sepeninggal makhluk aneh itu, Rara Anjani
pun dengan kepala tunduk telah berjalan kembali memasuki Ndalem
Kapangeranan melalui pintu dapur.
Dalam pada itu, langkah Ki Waskita dan
Ki Rangga telah menjadi semakin dekat dengan orang yang berperawakan
tinggi itu. Sekilas Ki Rangga segera dapat menarik kesimpulan bahwa
orang yang sedang mereka ikuti itu bukanlah Ki Tanpa Aran.
“Ki Tanpa Aran memiliki bentuk tubuh yang
mirip dengan guru, sedang-sedang saja.” berkata Ki Rangga dalam hati,
“Sedangkan orang ini berperawakan tinggi dan cenderung agak kurus.”
Sedangkan Ki Waskita yang telah banyak
makan asam garamnya kehidupan, samar-samar mempunyai gambaran tentang
orang yang berperawakan tinggi itu, walaupun masih penuh keraguan.
“Sepertinya bentuk tubuh itu tidak begitu
asing bagiku,” berkata Ki Waskita dalam hati, “Walaupun di Mataram ini
banyak orang yang mempunyai bentuk tubuh yang hampir sama, namun hanya
sedikit yang mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Apalagi
kemampuan dalam melontarkan isyarat khusus ini.”
Berbekal keyakinan itulah, Ki Waskita pun mulai menilai setiap gerak dan tingkah orang berperawakan tinggi itu.
Semakin dekat mereka dengan orang itu,
dada Ki Waskita dan Ki Rangga pun menjadi semakin berdebaran. Ternyata
orang itu telah menutupi sebagian wajahnya dengan secarik kain hitam
agar sulit untuk dikenali.
Sebenarnyalah Ki Rangga telah mencoba
mengetrapkan aji sapta pandulu untuk melihat dengan jelas wajah orang
itu. Namun agaknya orang itu pun dengan sengaja telah mengetrapkan
sebuah ilmu yang dapat untuk menyamarkan jati dirinya sehingga
pengamatan Ki Rangga melalui aji sapta pandulu pun mengalami kesulitan.
“Akan aku coba untuk mengenalinya dengan
aji sapta panggraita,” berkata Ki Rangga dalam hati. Namun apa yang
telah dikenali oleh Ki Rangga melalui aji sapta panggraita itu justru
telah membuat jantung Ki Rangga semakin berdebaran.
“Menurut bentuk wadag dan pengenalanku
melalui aji sapta panggraita, memang dugaan itu mengarah kesana,”
berkata Ki Rangga dalam hati, “Namun semua itu masih harus tetap
dibuktikan.”
Demikianlah akhirnya kedua orang itu pun berhenti hanya beberapa langkah saja di hadapan orang yang berperawakan tinggi itu.
“Hem,” tiba-tiba orang itu mendengus
keras. Katanya kemudian dengan nada yang rendah dan dalam, “Mengapa
kalian mengikuti aku, he?!”
Untuk sejenak Ki Waskita dan Ki Rangga
justru telah terdiam. Mereka berdua tidak menduga akan mendapatkan
pertanyaan seperti itu.
“Maaf Ki Sanak,” Ki Waskita lah yang
akhirnya menjawab sambil maju selangkah, “Justru kami berdua yang
seharusnya mengajukan pertanyaan itu kepada Ki sanak. Untuk apa Ki Sanak
melontarkan isyarat itu kepada kami berdua?”
“Gila!” umpat orang itu sambil menunjuk
ke arah Ki Waskita dan Ki Rangga ganti berganti. Kali ini nada suaranya
terdengar melengking aneh. Lanjutnya kemudian sambil membentak, “Kalian
kira, kalian ini siapa, he?! Aku tidak pernah mengenal kalian berdua.
Apalagi mengundang kalian dengan bahasa isyarat khusus ini. Ketahuilah,
isyarat ini hanya diketahui oleh perguruan-perguruan besar semasa Demak
lama masih berdiri. Kami para murid perguruan yang mempunyai kepentingan
bersama untuk menegakkan Demak sebagai penerus kerajaan besar Majapahit
telah bersepakat dengan isyarat ini. Kalian tentu saja tidak akan
memahami,” orang itu berhenti sebentar. Lanjutnya kemudian, “Pergilah
dari tempat ini sebelum orang yang aku panggil dengan isyarat ini
datang. Jika orang itu telah datang, aku tidak akan bertanggung jawab
terhadap apa yang akan terjadi kemudian.”
Hampir bersamaan Ki Waskita dan Ki Rangga
menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sadar kedua orang itu saling
berpandangan sejenak. Sangat sulit untuk mengenali orang berperawakan
tinggi itu hanya dari nada suaranya. Dengan sengaja dia telah
mengubah-ubah nada suaranya. Namun yang pasti, baik Ki Waskita maupun Ki
Rangga telah mulai dapat menduga siapakah orang itu dari bentuk tubuh
dan gerak-geriknya.
“Ki Sanak,” Ki Rangga akhirnya membuka
suara, “Ki Sanak tidak usah ingkar. Apapun alasan Ki Sanak, namun yang
jelas Ki Sanak telah berusaha memancing persoalan dengan kami,” Ki
Rangga berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Nah, lebih baik Ki Sanak
segera membuka penutup wajah Ki sanak serta mengatakan apa sebenarnya
tujuan Ki Sanak melontarkan isyarat ini?”
Orang berperawakan tinggi itu sejenak
terdiam. Namun tiba-tiba terdengar suara tawanya yang meledak. Katanya
kemudian di antara derai tawanya, “O, alangkah menakutkan jika harus
berurusan dengan senapati agul-agulnya Mataram, Ki Rangga Agung Sedayu?
Siapa yang tak kenal namanya yang harum di seluruh penjuru tanah ini
dari ujung ke ujung bahkan sampai ke seberang lautan,” orang itu
berhenti sejenak. Kemudian sambil menggeram dia melanjutkan, “Akan
tetapi aku tidak gentar. Apa yang aku takutkan dengan ilmu cambuk anak
gembala di padang-padang perdu itu? Atau ilmu kakang kawah adi wuragil
yang tak lebih dari permainan semu yang menjemukan? Atau ilmu lewat
sorot matamu yang mampu meluluh lantakkan bukit dan mengeringkan lautan?
Atau ilmumu yang mana lagi yang akan engkau banggakan di hadapanku he?”
Bagaikan disengat kalajengking kedua
orang itu terutama Ki Rangga Agung Sedayu mendengar perkataan orang
berperawakan tinggi itu. Namun dengan demikian secara tidak sengaja
orang itu telah sedikit banyak membuka jati dirinya sendiri. Orang itu
pasti sudah mengenal secara pribadi kepada Ki Rangga Agung Sedayu,
sehingga dugaan Ki Waskita dan Ki Rangga semakin mendekati kenyataan.
Ki Waskita yang merasa lebih banyak
berpengalaman dibanding dengan Ki Rangga segera maju selangkah lebih
dekat sambil berkata, “Baiklah Ki Sanak. Sebenarnya kami bukanlah
segolongan orang yang senang dengan keributan. Akan tetapi agaknya Ki
Sanak sendiri yang memang sengaja sedang mencari perkara dengan kami.”
Sejenak orang itu tampak mengerutkan
kening. Jawabnya kemudian sambil menggeram, “Silahkan! Majulah
bersama-sama agar sebelum terang tanah pekerjaan ini sudah dapat aku
tuntaskan.”
Kembali Ki Waskita dan Ki Rangga saling
berpandangan. Hanya satu sebenarnya yang mereka berdua perlukan untuk
mengungkap jati diri orang itu, nada suara aslinya. Namun agaknya sampai
saat ini orang itu masih mampu menyembunyikannya.
Akhirnya kesabaran Ki Rangga pun ada
batasnya. Maka katanya kemudian sambil mengurai cambuknya, “Baiklah Ki
Sanak, ternyata kita memang terpaksa harus bersilang jalan. Kami memang
tidak yakin akan dapat menandingi ilmu Ki Sanak. Namun setidaknya suara
ledakan cambukku ini akan memancing para prajurit yang sedang meronda
untuk mendatangi tempat ini dan membantu kami bersama-sama untuk
menangkap Ki Sanak.”
Selesai berkata demikian Ki Rangga segera
mengangkat cambuknya dan memutarnya di atas kepala. Siap untuk
meledakkan cambuknya dengan sebuah lecutan sendal pancing.
“Tunggu dulu!” tiba-tiba orang itu
berteriak sambil mengangkat tangannya. Agaknya orang itu terpengaruh
oleh permainan Ki Rangga sehingga tanpa sadar telah mengeluarkan nada
suara aslinya.
Begitu mendengar orang itu telah berkata
dengan nada suara aslinya, Ki Rangga pun segera menurunkan cambuknya dan
menyimpannya kembali di balik bajunya. Sementara Ki Waskita telah
menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya
kemudian sambil membungkukkan badannya dalam-dalam diikuti oleh Ki
Rangga, “Mohon ampun, Ki Patih. Jika kami berdua telah mengganggu
permainan Ki Patih. Sungguh kami berdua hanya mengikuti bunyi isyarat
itu tanpa mengetahui maksud yang sebenarnya.”
Tampak orang itu termangu-mangu sejenak.
Tiba-tiba terdengar orang itu tertawa kecil sambil merenggut secarik
kain yang menutupi sebagian wajahnya. Katanya kemudian, “Sudahlah Ki
Waskita, Ki Rangga. Permainan ini kelihatannya memang kurang menarik
bagi kalian berdua. Namun sesungguhnya aku memang sedang berusaha
menarik perhatian seseorang untuk hadir di tempat ini.”
Hampir bersamaan Ki Waskita dan Ki Rangga
telah menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepala
mereka. Dugaan mereka berdua memang tepat. Orang berperawakan tinggi
yang menutupi sebagian wajahnya dengan secarik kain itu memang Ki Patih
Mandaraka.
“Ampun Ki Patih,” berkata Ki Waskita
kemudian begitu Ki Patih melangkah mendekat, “Siapakah sebenarnya yang
Ki Patih kehendaki untuk hadir memenuhi panggilan isyarat itu?”
Ki Patih tersenyum sambil melangkah.
Jawabnya kemudian, “Marilah kita berbincang sambil berjalan. Agaknya
sudah lama sekali aku tidak berjalan-jalan menghirup udara dini hari
yang begitu segar ini.”
Kedua orang itu tidak menyahut. Hanya tampak kepala mereka yang terangguk-angguk sambil mengiringi langkah Ki Patih.
“Nah, aku akan memulai sebuah cerita yang
cukup menarik,” berkata Ki Patih selanjutnya sambil mengayunkan
langkahnya perlahan-lahan, “Cerita ini bermula saat Kanjeng Sunan
menyerahkan Ki Bango Lamatan sebagai pengawal pribadi Pangeran Pati,” Ki
Patih berhenti sejenak. Dihirupnya udara dini hari yang sejuk untuk
memenuhi rongga dadanya. Lanjutnya kemudian, “Selain Ki Bango Lamatan,
ternyata Kanjeng Sunan juga menyarankan seseorang yang menyebut dirinya
Ki Tanpa Aran untuk menjadi penasehat dan sekaligus pembimbing Pangeran
Pati dalam hal kawruh lahir maupun batin yang berhubungan dengan
kehidupan bebrayan.”
Kedua orang itu tampak
mengangguk-anggukkan kepala mereka. Ki Rangga lah yang kemudian
bertanya, “Ampun Ki Patih, siapakah sebenarnya orang yang menyebut
dirinya Ki Tanpa Aran itu?”
“Itulah yang aku sendiri juga belum
mengetahuinya,” jawab Ki Patih, “Sejauh yang aku ketahui, menurut
keterangan Pangeran Pati, dia adalah murid dan juga sekaligus sahabat
Kanjeng Sunan.”
Mendengar jawaban Ki Patih, Ki Rangga
hanya dapat menarik nafas panjang dengan wajah kecewa. Keterangan itu
juga yang dia dapatkan dari Pangeran Pati, tidak lebih dan tidak kurang.
“Ampun Ki Patih,” sekarang giliran Ki
Waskita yang mengajukan pertanyaan, “Apakah Ki Patih pernah bertemu muka
dengan Ki Tanpa Aran itu?”
Ki Patih menggeleng. Jawabnya kemudian,
“Dia selalu menghindar untuk bertemu muka denganku. Pernah suatu saat
aku perintahkan Pangeran Pati menghadap dengan membawa serta Ki Tanpa
Aran itu. Namun selalu saja ada alasan darinya untuk menghindari
pertemuan denganku.”
Hampir bersamaan Ki Waskita dan Ki Rangga
mengangguk-anggukkan kepala. Bertanya Ki Rangga kemudian, “Ampun Ki
Patih. Apakah Ki Patih mempunyai sebuah dugaan tentang diri orang yang
bernama Ki Tanpa Aran itu?”
Ki Patih menarik nafas dalam-dalam
sebelum menjawab pertanyaan Ki Rangga. Dipandanginya langit yang
terlihat bersih tanpa awan selembar pun. Berjuta bintang tampak
berkerlap-kerlip menghiasi langit.
“Aku hanya menduga-duga saja,” akhirnya
Ki Patih menjawab pertanyaan Ki Rangga, “Namun dugaanku ini belum
berdasar. Maka untuk itulah aku mencoba memancingnya dengan isyarat
khusus ini,” Ki Patih berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Aku masih
ingat pada saat terjadi pertentangan Pajang dengan Jipang. Telah muncul
orang yang mengaku bernama Kiai Pager Wesi dari goa susuhing angin di
sebelah utara gunung Merbabu yang berpihak kepada Kadipaten Jipang dan
mengancam akan membunuh Adipati Pajang. Perguruan-perguruan yang
mendukung Pajang pun telah bersiap untuk menghadapinya. Kita telah
sepakat menggunakan sebuah isyarat khusus dalam menyusun kekuatan.
Bukankah Ki Waskita juga mengenal isyarat khusus ini walaupun agak
sedikit berbeda?”
KI Waskita tersenyum sambil
mengangguk-angguk mendengar pertanyaan Ki Patih. jawabnya kemudian,
“Sendika Ki Patih. Memang pada saat itu perguruan-perguruan yang
mendukung Pajang telah bersepakat untuk menghadapi bersama jika para
penghuni Goa susuhing angin di sebelah utara gunung Merbabu itu akan
melaksanakan ancamannya,” Ki Waskita berhenti sejenak. Lanjutnya
kemudian, “Dan ternyata Raden Pamungkas dari perguruan Windujati lah
yang terlebih dahulu bertindak sehingga Kiai Pager Wesi dan para
pengikutnya menarik diri dari perselisihan itu.”
Ki Rangga yang mendengar perguruan
Windujati disebut telah berpaling ke arah Ki Waskita. Sengaja Ki Waskita
menggunakan nama Raden Pamungkas agar muridnya itu tidak mengetahui
bahwa Kiai Gringsing lah yang dimaksud oleh Ki Waskita.
Ki Patih tersenyum mendengar Ki Waskita
menyebut nama Raden Pamungkas. Tanpa sadar Ki Patih berpaling ke arah Ki
Rangga yang hanya dapat mengerutkan keningnya dalam-dalam.
“Aku menduga Ki Tanpa Aran ini adalah
tokoh sakti di masa lalu,” lanjut Ki Patih kemudian, “Entah dia berasal
dari masa Demak lama atau pada saat Pajang mengalami benturan dengan
Jipang. Semoga saja kehadirannya di masa kini akan memberikan manfaat
kepada Mataram di masa mendatang.”
Kembali Ki Waskita dan Ki Rangga
mengangguk-anggukkan kepala mereka. Bagi Ki Rangga cerita masa lalu itu
hanya diketahuinya sepotong-sepotong, tidak utuh dan runut.
Pengetahuannya tentang jati diri gurunya pun sangat terbatas. Sesuai
dengan kitab peninggalan gurunya, bahwa ilmu yang mereka warisi adalah
bersumber pada sebuah perguruan yang pernah mempunyai nama besar di
akhir masa pemerintahan kerajaan Majapahit, perguruan Windujati.
Untuk sejenak suasana menjadi sunyi.
Hanya terdengar langkah-langkah ketiga orang itu menapaki jalan tanah
berbatu-batu. Tanpa terasa langkah mereka telah mendekati gerbang kota.
Beberapa oncor yang dipasang di kanan kiri gerbang sinarnya tampak
menerangi jalan masuk yang dijaga ketat oleh beberapa prajurit.
Agaknya para prajurit jaga itu telah
melihat ketiga orang yang berjalan perlahan-lahan menuju ke arah pintu
gerbang. Serentak beberapa prajurit segera berloncatan menghadang jalan.
Namun alangkah terkejutnya para prajurit
itu begitu mengenali salah satu dari ketiga orang yang sedang berjalan
menuju ke pintu gerbang itu adalah ki Patih Mandaraka.
“Segera laporkan kepada Ki Lurah Adiwaswa,” bisik salah seorang prajurit itu kepada kawannya.
Tanpa diperintah dua kali, prajurit itu
pun segera meloncat dan berlari ke arah gardu penjagaan yang berada di
sisi dalam gerbang.
“Ada apa?” bertanya Ki Lurah Adiwaswa yang sedang duduk di dalam gardu sambil menikmati jenang alot dan wedang sere hangat.
“Ki Lurah,” berkata prajurit itu dengan nafas setengah memburu, “Ki Patih Mandaraka!”
“He?!” bagaikan tersengat kalajengking
sebesar ibu jari kaki, Ki Lurah terloncat dari tempat duduknya sambil
membentak, “Jangan main-main. Mana ada Ki Patih dini hari begini datang
ke gerbang kota?”
“Mereka bertiga,” jawab prajurit itu sambil menunjuk ke arah jalan yang membujur di luar gerbang.
Malam memang masih cukup gelap walaupun
sudah mendekati fajar. Namun pandangan tajam Ki Lurah Adiwaswa segera
melihat bayangan tiga orang yang berjalan dengan perlahan menuju
gerbang kota.
“Dari mana Ki Patih sepagi ini?” gumam Ki Lurah sambil bergegas mengayunkan langkahnya.
Setibanya di depan gerbang, ki Lurah segera memimpin para prajurit jaga untuk berbaris menyambut kehadiran Ki Patih.
Ki Patih yang melihat kesiap-siagaan para
prajurit penjaga gerbang kota tersenyum. Begitu mereka bertiga tinggal
tiga langkah saja dari pintu gerbang, Ki Lurah pun segera memberi
aba-aba penghormatan.
“Terima kasih,” jawab Ki Patih sambil
tersenyum. Sementara Ki Rangga yang mengenal Ki Lurah Adiwaswa telah
mengerutkan keningnya.
“Ki Lurah bertugas di sini?” bertanya Ki Rangga.
“Ya Ki Rangga,” jawab Ki Lurah, “Sepulang dari Lemah Cengkar, aku dipindah-tugaskan untuk menjaga keamanan kota Raja.”
Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya.
Sedangkan Ki Patih yang tidak begitu mengenal Ki Lurah justru telah
bertanya, “Di mana Ki Lurah tinggal?”
“Ampun Ki Patih, hamba masih tinggal di barak prajurit,” jawab Ki Lurah sambil membungkuk hormat.
“He?” hampir bersamaan ketiga orang itu berseru heran.
“Berapa umur Ki Lurah?” Ki Patih bertanya kemudian.
Untuk sejenak lidah ki Lurah bagaikan kelu. Namun pertanyaan Ki Patih itu pun akhirnya dijawab, “Hampir tiga puluh, Ki Patih.”
Ki Patih tertawa pendek. Katanya
kemudian, “Sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah keluarga,” Ki
Patih berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Apakah Ki Lurah belum
mempunyai calon.”
Mendapat pertanyaan seperti itu Ki Lurah
hanya dapat menundukkan kepalanya. Sementara para prajurit yang berada
di pintu gerbang itu tampak dengan sekuat tenaga berusaha untuk menahan
senyum mereka.
Ki Patih agaknya menyadari hal itu. Maka
katanya kemudian sambil menepuk pundak ki Lurah, “Bersabarlah dan
berdoalah. Semoga Yang Maha Agung segera memberikan jodoh Ki Lurah
seorang perempuan yang cantik dan setia.”
“Dari keluarga yang terpandang dan kaya raya,” tambah Ki Rangga sambil tersenyum.
“Anak tunggal yang tidak punya saudara,” Ki Waskita yang sedari tadi diam saja telah ikut bicara.
“Yang kedua orang tuanya sudah tua renta, sehingga warisan segera jatuh ke tangannya,” Ki Patih menambahkan.
Seketika meledaklah tawa di tempat itu.
“Sudahlah,” berkata Ki Patih kemudian setelah tawa mereka mereda, “Lanjutkan tugas kalian. Kami akan kembali ke Kepatihan.”
“Sendika Ki Patih,” berkata Ki Lurah
kemudian. Begitu Ki Patih melangkah meninggalkan pintu gerbang, dengan
sigap Ki Lurah segera memberi aba-aba para prajurit jaga untuk
melaksanakan penghormatan.
Demikianlah mereka bertiga segera
berjalan kembali ke Kepatihan. Di sepanjang jalan sesekali mereka masih
membicarakan jati diri Ki Tanpa Aran. Namun dalam pembicaraan itu Ki
Patih sama sekali tidak menyinggung nama Kiai Gringsing dalam
hubungannya dengan Ki Tanpa Aran, karena Ki Patih memang belum pernah
bertemu muka dengan penasehat dan sekaligus pembimbing Pangeran Pati
itu.
Dalam pada itu malam terasa semakin
mendekati ujungnya. Ketika terdengar ayam jantan berkokok untuk yang
terakhir kalinya. Barulah Ki Rangga dan Ki Waskita menyempatkan sejenak
untuk berbaring setelah menunaikan kewajiban mereka sebagai hamba yang
selalu bersyukur kepada Tuhannya.
Ketika seorang pelayan kemudian memberitahukan kepada mereka untuk bersiap makan pagi, keempat orang itu pun segera berkemas.
Ternyata Ki Bango Lamatan telah terlebih
dahulu hadir di ruang tengah kepatihan. Setelah menunggu beberapa saat,
Ki Patih pun berkenan hadir dan bersama-sama dengan para tamunya untuk
menikmati makan pagi.
“Memang masih terlalu pagi,” berkata Ki
Patih sambil menyenduk nasi putih yang masih hangat, “Aku juga kurang
terbiasa makan terlalu pagi. Namun karena kalian akan berangkat pagi
ini, aku menyempatkan diri untuk menemani kalian makan pagi.”
“Terima kasih Ki Patih,” hampir bersamaan mereka menjawab.
“Kuda-kuda kalian telah disiapkan,”
berkata Ki Patih kemudian, “Dengan berkuda, diharapkan perjalanan akan
ditempuh lebih cepat,” Ki Patih berhenti sejenak untuk mengunyah
makanan. Lanjutnya kemudian, “Sesampainya di Tanah Perdikan Matesih,
kalian dapat berhubungan dengan salah satu petugas sandi yang berada di
sana. Titipkan kuda-kuda kalian sebelum mendaki lereng gunung Tidar
sebelah barat.”
Mereka berlima hanya dapat
mengangguk-anggukkan kepala mereka. Perintah ki Patih memang sudah
sangat jelas. Mereka harus dapat memutus hubungan antara perguruan Sapta
Dhahana dengan orang yang menyebut dirinya sebagai Trah Sekar Seda
Lepen tanpa ada kesan keterlibatan Mataram.
Demikianlah setelah jamuan makan pagi itu
selesai, Ki Patih telah mengantarkan tamu-tamunya ke halaman kepatihan.
Di halaman telah menunggu lima ekor kuda yang terlihat biasa-biasa
saja, bukan kuda yang besar dan tegap.
Untuk sejenak Ki Rangga dan
kawan-kawannya justru telah termangu-mangu di tlundak pendapa sambil
mengamati-amati kelima ekor kuda yang terlihat agak kecil.
Ki Patih tertawa melihat keragu-raguan
yang tersirat di wajah kelima orang itu. Katanya kemudian, “Sengaja aku
perintahkan untuk menyiapkan kuda-kuda ini agar tidak terlalu menarik
perhatian di sepanjang perjalanan kalian,” Ki Patih berhenti sebentar.
Kemudian sambil menuruni tlundak pendapa dan menghampiri salah satu kuda
itu, Ki Patih meneruskan kata-katanya, “Kuda-kuda ini terlihat agak
kecil namun cukup kuat untuk mengantar kalian sampai ke gunung Tidar.
Jika kalian meragukan kemampuannya, kalian dapat mengambil istirahat di
tepian kali Krasak sebelum meneruskan perjalanan.”
Mereka berlima tampak
mengangguk-anggukkan kepala. Ki Rangga selaku pemimpin rombongan segera
menjawab, “Sendika Ki Patih. Memang sebaiknya kami memberi kesempatan
kuda-kuda ini nantinya untuk beristirahat di tepian kali Krasak.”
Ki Patih tersenyum sambil mengangguk.
Katanya kemudian, “Nah apakah masih ada sesuatu yang ingin kalian
sampaikan sebelum berangkat?”
Sejenak kelima orang itu saling
berpandangan. Kembali Ki Rangga yang menjawab, “Ampun Ki Patih,
kelihatannya kami sudah siap untuk berangkat,” Ki Rangga berhenti
sejenak untuk menarik nafas. Lanjutnya kemudian, “Kami berlima segera
mohon diri.”
“Silahkan,” jawab Ki Patih, “Semoga Yang
Maha Agung senantiasa melindungi hambaNYa dalam setiap langkah dan usaha
untuk menciptakan kedamaian di bumi Mataram ini.”
Demikianlah sejenak kemudian lima ekor
kuda segera berderap dengan kecepatan sedang meninggalkan regol istana
Kepatihan. Kuda-kuda itu berderap di jalan-jalan kota yang sudah mulai
ramai. Sesekali mereka berpapasan dengan pedati-pedati yang sarat memuat
hasil bumi dari luar kota menuju pasar besar yang terletak di dekat
alun-alun. Tak jarang mereka juga bertemu dengan para prajurit yang
sedang menjaga sudut-sudut jalan untuk mencegah segala sesuatu yang
tidak diinginkan terjadi.
“Mengapa para prajurit itu disiagakan di
sudut-sudut jalan?” bertanya Ki Waskita yang berkuda di sebelah Ki
Rangga, “Apakah tidak cukup menempatkan mereka di gardu-gardu penjagaan
saja? Sedang di malam hari mereka memang dibutuhkan untuk meronda ke
seluruh sudut kota.”
Ki Rangga tersenyum mendapat pertanyaan
Ki Waskita. Sambil berpaling sekilas dia menjawab, “Prajurit-prajurit
yang bersiaga di sudut-sudut jalan itu selain memberikan rasa aman
kepada kawula Mataram, mereka juga mengawasi setiap gerak-gerik orang
yang lalu lalang di jalan. Beberapa saat yang lalu memang telah tumbuh
kelompok-kelompok anak muda yang meresahkan dan mengganggu keamanan.
Mereka menamakan kelompok-kelompok itu dengan nama yang menyeramkan
seperti, Sidat macan, Kelabang Ireng dan lain-lain. Mereka sering
membuat onar dengan tingkah yang aneh-aneh. Walaupun perbuatan mereka
itu masih dapat digolongkan sebagai kenakalan anak-anak muda, namun jika
dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan mereka akan
terjerumus dalam perbuatan yang mengarah pada tindak kejahatan.”
Orang-orang yang mendengar keterangan Ki
Rangga itu tampak mengangguk-angguk. Sedangkan Glagah Putih yang berkuda
di samping Ki Jayaraga hanya tersenyum- senyum saja.
Tanpa terasa perjalanan mereka telah
mencapai pintu gerbang kota sebelah utara. Karena Ki Rangga dan Glagah
Putih tidak mengenakan pakaian keprajuritan, tanpa menarik perhatian
mereka segera keluar melalui pintu gerbang untuk kemudian berpacu di
bulak panjang yang menghubungkan kota Mataram dengan padukuhan terdekat.
Dalam pada itu di Ndalem Kapangeranan, seorang pelayan dalam dengan sangat hati-hati telah mengetuk pintu bilik Pangeran Pati.
“Siapa?” terdengar suara Pangeran Pati dari dalam bilik.
“Hamba Pangeran, pelayan dalam,” jawab pelayan dalam itu dengan suara rendah.
Sejenak kemudian terdengar
langkah-langkah kaki mendekat sebelum akhirnya terdengar selarak pintu
diangkat dan pintu bilik itupun terbuka.
“Ada apa sepagi ini engkau menghadap?” bertanya Pangeran Pati yang berdiri di tengah-tengah pintu bilik.
“Ampun Pangeran,” jawab pelayan itu, “KI Tanpa Aran mohon menghadap.”
Sejenak Pangeran Pati mengerutkan
keningnya. Adalah bukan kebiasaan Ki Tanpa Aran menghadap di saat
seperti itu. Jika Pangeran Pati dan Ki Tanpa Aran akan membicarakan
sesuatu hal yang berhubungan dengan kawruh kehidupan, biasanya mereka
akan bertemu ketika waktu menjelang sepi uwong.
“Di manakah Ki Tanpa Aran?” bertanya Pangeran Pati itu kemudian.
“Ampun Pangeran, Ki Tanpa Aran menunggu di pringgitan.”
Pangeran Pati mengangguk-anggukkan
kepalanya. Katanya kemudian, “Sampaikan kepadanya untuk menunggu
sebentar. Aku akan berbenah.”
“Sendika Pangeran,” jawab pelayan dalam itu sambil menyembah dan kemudian mengundurkan diri.
Beberapa saat kemudian, Pangeran Pati pun telah hadir di pringgitan untuk menemui Ki Tanpa Aran.
Setelah menanyakan keselamatan dan
kesehatan masing-masing, Pangeran Pati pun mulai menanyakan keperluan Ki
Tanpa Aran menghadap pagi itu.
“Ampun Pangeran,” berkata Ki Tanpa Aran
kemudian, “Untuk beberapa hari ke depan, mungkin satu atau dua pekan,
hamba mohon ijin untuk mengurus sebuah keperluan. Jika Pangeran
memerlukan hamba dalam waktu dekat ini, mungkin hamba tidak ada di
tempat.”
Untuk beberapa saat Pangeran Pati
termenung. Hampir saja Pangeran Pati menanyakan apa keperluan Ki Tanpa
Aran, namun pertanyaan yang sudah ada di ujung lidahnya itu segera
ditelannya kembali. Maka jawabnya kemudian, “KI Tanpa Aran tinggal di
Ndalem Kapangeranan ini adalah atas permintaanku, sehingga jika Ki Tanpa
Aran mempunyai keperluan khusus dan akan bepergian untuk beberapa hari
kedepan, aku tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah apalagi
melarang.”
“Ah,” desah Ki Tanpa Aran, “Ampun
Pangeran, bukan maksud hamba untuk memaksakan kehendak, namun karena
suatu urusan pribadi yang sangat penting, hamba mohon ijin meninggalkan
Ndalem Kapangeranan untuk beberapa hari saja.”
Pangeran Pati tersenyum. Jawabnya
kemudian, “Silahkan Ki, semoga urusan pribadi Ki Tanpa Aran segera
selesai dan kembali dengan selamat ke Ndalem Kapangeranan,” Pangeran
Pati berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Apakah Ki Tanpa Aran akan
menempuh perjalanan bersama Ki Rangga Agung Sedayu dan kawan-kawannya?
Mereka rencananya pagi ini akan berangkat dari Istana Kepatihan menuju
ke gunung Tidar.”
Tiba-tiba wajah Ki Tanpa Aran yang
biasanya tenang dan sareh itu berubah tegang. Namun perubahan itu hanya
sekejap. Dengan tertawa Ki Tanpa Aran pun kemudian menjawab, “Tentu
tidak Pangeran. Hamba mempunyai keperluan yang berbeda dengan mereka.”
Pangeran Pati mengangguk-anggukkan
kepalanya. Walaupun hanya sekejap, perubahan wajah Ki Tanpa Aran itu
sempat ditangkap oleh pewaris Trah Mataram itu.
“Baiklah Ki,” berkata Pangeran Pati
kemudian, “Silahkan mengurus keperluan pribadi Ki Tanpa Aran. Semoga
segala sesuatunya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita.”
“Terima kasih Pangeran. Hamba mohon diri,” berkata Ki Tanpa Aran kemudian.
“Kapan Ki Tanpa Aran akan berangkat?” bertanya Pangeran Pati sambil bangkit dari duduknya diikuti oleh Ki Tanpa Aran.
“Hari ini juga Pangeran,” jawab Ki tanpa Aran.
”Hari ini juga?” bertanya Pangeran Pati dengan wajah keheranan, “Begitu tergesa-gesa?”
“Hamba Pangeran. Hamba berharap semakin cepat hamba mengurus keperluan pribadi ini, akan semakin cepat pula urusan ini selesai.”
“Baiklah, Ki,” berkata Pangeran Pati
kemudian sambil berjalan ke arah pintu pringgitan, “Semoga Yang Maha
Agung selalu melindungi perjalanan Ki Tanpa Aran.”
“Terima kasih Pangeran,” jawab Ki Tanpa
Aran sambil mengikuti langkah Pangeran Pati menuju pintu yang membatasi
pringgitan dengan pendapa.
Dalam pada itu, Matahari telah memanjat
semakin tinggi di langit sebelah timur. Sinarnya yang garang terasa
mulai menggatalkan kulit. Lima ekor kuda berderap dengan kencang
melintas di jalan tanah yang berbatu-batu dan meninggalkan debu
berhamburan yang membumbung tinggi ke udara.
“Apakah kita akan beristirahat sejenak di
Kali Krasak, ngger?” bertanya Ki Waskita kepada Ki Rangga yang
berkuda di sebelahnya.
Untuk sejenak Ki Rangga terdiam.
Pandangan matanya terlempar jauh ke depan, ke titik-titik di kejauhan.
Kenangannya pun terlempar ke beberapa saat yang lalu ketika menghadap
Pangeran Pati di Ndalem Kapangeranan.
“Tumenggung Ranakusuma,” desis Ki Rangga
dalam hati, “Dan Putri Triman itu. Aku benar-benar belum siap untuk
mendapatkan kedua-duanya.”
“Bagaimana Kakang?” tiba-tiba Glagah Putih yang berkuda di belakangnya bertanya sehingga membuyarkan lamunannya.
Sejenak Ki Rangga Agung Sedayu berpaling
sekilas ke belakang. Jawabnya kemudian, “Sesuai pesan Ki Patih, ada
baiknya kita beristirahat sebentar di tepian kali Krasak untuk sekedar
memberi waktu kuda-kuda minum dan merumput,” Ki Rangga Agung Sedayu
berhenti sebentar. Sambil berpaling ke penunggang di sebelahnya dia
melanjutkan, “Ki Waskita, ada baiknya kita memasuki Perdikan Matesih
sebelum senja agar tidak banyak menarik perhatian.”
Ki Waskita tidak menjawab. Hanya
kepalanya saja yang tampak mengangguk-angguk. Sementara di belakangnya
Glagah Putih, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan tampak ikut
mengangguk-anggukkan kepala mereka.
Demikianlah ketika jalan yang mereka
lalui mulai menurun dan menikung tajam, mereka pun segera menyadari
bahwa tepian kali Krasak telah semakin dekat. Dengan segera mereka
memperlambat laju kuda-kuda mereka. Ketika tanah di bawah kaki kuda-kuda
mereka itu mulai bercampur pasir dan bau khas air sungai serta gemuruh
arus air mulai lamat-lamat terdengar , mereka pun segera menghentikan
kuda-kuda mereka dan meloncat turun.
“Kita mencari tepian yang landai dan teduh,” berkata Ki Rangga sambil menuntun kudanya.
“Dan yang banyak batu-batu besarnya,” sahut Glagah Putih beberapa langkah di belakang Ki Rangga.
Ki Bango Lamatan yang berada di belakang Glagah Putih sejenak mengerutkan kening. Tanya Ki Bango Lamatan kemudian, “Untuk apa?”
Ki Jayaraga yang mendengar pertanyaan Ki Bango Lamatan itu segera menyahut, “Untuk apa lagi kalau bukan untuk alas tidur?”
Mereka yang mendengar jawaban Ki Jayaraga
itu tertawa kecuali Ki Bango Lamatan. Dia hanya menarik nafas
dalam-dalam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang Ki Bango
Lamatan masih memerlukan waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan
mereka.
Demikianlah ketika mereka menemukan
tempat yang benar-benar nyaman untuk sekedar melepaskan lelah, kuda-kuda
mereka pun sengaja di lepas agar dapat minum sepuas-puasnya serta
merumput di tepian.
Glagah Putih yang melihat ada sebuah batu
besar yang sedikit menjorok ke air segera meloncat ke atasnya. Sejenak
kemudian anak laki-laki Ki Widura itu pun segera merebahkan dirinya dan
mulai dibuai oleh rasa kantuk yang tak tertahankan.
Ketika rasa kantuk itu hampir saja
membuatnya jatuh tertidur, tiba-tiba saja pendengarannya yang sangat
terlatih telah mendengar sayup-sayup suara derap beberapa ekor kuda.
Pada awalnya Glagah Putih mengira suara
derap kaki-kaki kuda itu berada di dalam alam mimpinya. Namun ketika
suara derap kaki-kaki kuda itu terdengar semakin keras, Glagah Putih pun
perlahan-lahan mulai menemukan kesadarannya kembali.
Dengan perlahan-lahan Glagah Putih
bangkit dan kemudian duduk bersila. Ketika pandangan matanya menyapu ke
sekitar tepian, tampak Ki Rangga dan yang lainnya masih tetap pada sikap
mereka semula.
Ki Rangga masih tetap duduk di bawah
sebatang pohon yang rindang ditemani Ki Waskita. Keduanya tampak sedang
membicarakan sesuatu hal dengan sungguh-sungguh. Sementara Ki Jayaraga
justru sedang bermain mul-mulan dengan Ki Bango Lamatan. Mereka membuat
garis-garis di atas tanah sebagai bidang permainan serta menggunakan
batu-batu kecil sebagai alat bermain.
Glagah Putih tersenyum. Orang-orang tua
kadang bersikap seperti kanak-kanak kembali, bermain mul-mulan bahkan
sesekali untuk mengurangi kejenuhan mereka juga senang bermain engklek
bersama anak-anak di bawah siraman Bulan purnama.
Untuk beberapa saat Glagah Putih tidak
tahu harus berbuat apa. Sementara suara derap kaki-kaki kuda itu semakin
keras dan akhirnya dari tanggul seberang sungai yang cukup tinggi,
muncul tiga ekor kuda dengan penunggangnya.
Sejenak ketiga penunggang kuda itu segera
mengekang tali kendali kuda masing-masing. Tanpa turun dari kuda,
mereka mengamat-amati Ki Rangga dan kawan-kawannya yang sedang
duduk-duduk melepaskan lelah di seberang tepian.
“Orang-orang miskin,” geram seorang yang bertubuh besar dan berjambang lebat.
“Belum tentu kakang,” jawab orang yang di
sebelahnya, bertubuh pendek tapi terlihat sangat kekar, “Kelihatannya
saja mereka miskin. Kuda yang kecil dan cenderung kurus, pakaian yang
lusuh dan wajah-wajah tak bergairah. Namun siapa tahu mereka justru
menyimpan kepingan uang emas serta keris-keris yang berpendok emas dan
bertretes berlian.”
“Ah, macam kau!” geram orang yang
dipanggil kakang itu, “Engkau selalu bermimpi yang muluk-muluk setiap
kali kita bertemu dengan calon mangsa. Ingat, di saat terakhir kita
menjumpai seorang pengembara tua itu, engkau bermimpi dia membawa emas
berlian di balik baju kumalnya. Ternyata yang kita jumpai benar-benar
seorang gelandangan yang hampir mati kelaparan.”
Orang ketiga yang sedari tadi diam saja
telah tertawa. Sementara orang yang berperawakan pendek itu hanya dapat
mendengus sambil bersungut-sungut.
“Sudahlah. Lupakan saja,” berkata orang berjambang itu sambil bergerak menghela kudanya menjauhi tanggul.
“Kakang tunggu,” tiba-tiba orang yang
pendek itu berbisik, “Lihatlah timang yang dipakai orang yang sedang
bermain mul-mulan itu.”
Orang berjambang yang sudah memutar
kudanya itu tertegun. Tanpa sadar dia menghela kudanya mendekati tanggul
kembali. Ketika matanya yang tajam itu kemudian melihat ke arah
pinggang Ki Bango Lamatan, hati orang berjambang itupun berdesir tajam.
Timang itu tampak berkilat-kilat tertimpa sinar Matahari yang sesekali
menerobos rimbunnya dedaunan.
“Gila!” umpat orang berjambang itu
kemudian, “Engkau benar. Mereka kelihatannya memang orang-orang kaya
yang sedang berpura-pura miskin. Marilah. Ini kesempatan kita untuk
mendapatkan hasil yang banyak dan akan semakin menambah kepercayaan Ki
Lurah kepada kita.”
“Dan di lain kesempatan kita akan dipercaya untuk melaksanakan tugas yang lebih menantang,” sahut orang yang ketiga.
Orang berjambang yang sudah menggerakkan
kendali kudanya itu sejenak tertegun. Sambil berpaling kearah orang itu
dia bertanya, “Apa maksudmu dengan tugas yang lebih menantang?”
Orang itu tersenyum. Jawabnya kemudian,
“Aku sudah bosan menjadi penyamun. Mungkin sesekali kita diberi tugas
untuk merampok rumah Ki Gede Matesih barangkali dan menculik anak
gadisnya yang cantik itu.”
“Dan besoknya kepalamu akan dipenggal oleh Raden Mas Harya Surengpati,” geram orang berjambang itu.
Selesai berkata demikian orang berjambang
itu segera memutar kudanya menjauhi tanggul. Sedangkan kedua kawannya
sejenak masih termangu-mangu sebelum akhirnya .bergerak ikut menuruni
tanggul.
Dalam pada itu, Glagah Putih yang sedari
tadi mengawasi ketiga orang berkuda itu dengan sudut matanya telah
menarik nafas dalam-dalam sambil memalingkan wajahnya ke arah kakak
sepupunya. Namun tampaknya Ki Rangga dan Ki Waskita tidak memperhatikan
keadaan di sekelilingnya karena sedang terlibat pembicaraan yang
bersungguh-sungguh.
Glagah Putih yang tadi sempat
mengetrapkan aji sapta pangrungu telah mendengar pembicaraan mereka
dengan jelas. Ketiga orang berkuda itu kemungkinannya sedang mencari
tanggul yang landai untuk mendekat ke arah mereka.
“Siapakah mereka itu?” bertanya Glagah
Putih dalam hati sambil meluruskan kedua kakinya, “Mereka tidak mungkin
hanya perampok kecil yang bernyali terlalu besar. Kelihatannya mereka
tidak berdiri sendiri. Salah satu telah menyebut nama Ki Lurah dan
seorang pemimpin yang agaknya sangat mereka segani, Raden Mas Harya
Surengpati.”
Ada keinginan dari Glagah Putih untuk
memberi tahu yang lain. Namun niat itu segera ditepisnya. Keempat orang
itu adalah orang-orang yang linuwih, tentu mereka sudah mengetahui dan
menyadari serta memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi.
“Di sebelah timur itu agaknya ada tanggul
sungai yang agak rendah dan kelihatannya memang sudah menjadi jalur
jalan selama ini,” berkata Glagah Putih dalam hati kemudian sambil
mengawasi tanggul sebelah timur yang berjarak sekitar lima puluh tombak,
“Kemungkinannya mereka akan lewat dari tanggul yang rendah itu.”
Ternyata dugaan Glagah Putih tidak
meleset. Sejenak kemudian, ketiga penunggang kuda itupun telah muncul
dari balik tanggul yang rendah dan segera menghela kuda-kuda mereka
untuk menyeberangi kali Krasak yang airnya hanya setinggi lutut orang
dewasa.
Ketika kaki-kaki kuda itu mulai menapak
tanah berpasir di tepian, Glagah Putih pun sudah tidak dapat menahan
diri lagi. Dengan cepat dia segera meloncat turun dari batu besar yang
didudukinya.
“Mereka telah tertarik dengan timang emas
yang dipakai Ki Bango Lamatan,” berkata Glagah Putih dalam hati,
“Mungkin timang itu hadiah dari Pangeran Pati karena Ki Bango Lamatan
telah diangkat menjadi pengawal pribadinya.”
Untuk beberapa saat Glagah Putih masih
melihat kuda-kuda itu berderap dengan lambat di atas tepian yang
berpasir, namun ketiga penunggangnya dengan keras telah melecutnya.
Sedangkan kuda-kuda Ki Rangga dan kawan-kawannya justru telah meringkik
keras-keras begitu kuda-kuda ketiga orang itu telah melangkah semakin
dekat.
Ki
Jayaraga yang duduk membelakangi arah datangnya kuda-kuda itu telah
berpaling ke belakang. Sedangkan Ki Bango Lamatan yang sedari tadi sudah
melihat kedatangan kuda-kuda itu segera berdiri dari tempat duduknya
sambil mengibas-kibaskan kain panjangnya yang kotor terkena pasir di
tepian.
Ketika
jarak kuda yang paling depan hanya tinggal lima langkah saja, barulah
dengan malasnya Ki Jayaraga bangkit berdiri sambil memutar tubuhnya.
“Selamat
siang,” berkata orang yang berjambang itu sambil melompat turun dari
kudanya dan diikuti oleh kedua kawannya, “Maaf jika kedatangan kami di
tempat ini telah mengganggu istirahat Ki Sanak semuanya.”
Glagah
Putih yang mendengar cara orang berjambang itu berbicara telah
mengerutkan keningnya. Tingkah laku maupun nada suara orang berjambang
itu cukup sopan dan mengenal unggah-ungguh. Padahal sewaktu di atas
tanggul tadi, apa yang didengarnya sangatlah jauh berbeda. Mereka datang
ke tempat itu hanyalah bertujuan untuk merampas barang-barang berharga
yang dimiliki oleh Ki Rangga dan kawan-kawannya.
“O,
tidak-tidak,” Ki Jayaraga lah yang menyahut sambil tersenyum lebar,
“Marilah, silahkan duduk. Kami sudah terbiasa berbagi tempat. Demikian
juga jika Ki Sanak sekalian membutuhkan bekal, kami juga ada. Kami
membawa juadah bakar, ketela rebus yang dicampur dengan santan dan gula
kelapa,” Ki Jayaraga berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Tentu saja
kuah santan gula kelapanya dibuat kental agar mudah membawanya.”
Orang
berjambang itu tidak segera menjawab. Sekilas dia berpaling ke arah
kawan-kawannya. Ketika orang yang pendek kekar itu menganggukkan
kepalanya, orang berjambang itupun segera menjawab, “Terima kasih Ki
Sanak. Kedatangan kami ke tempat ini bukan untuk beristirahat. Kami
telah cukup beristirahat di padukuhan Salam tadi,” orang berjambang itu
berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Kedatangan kami adalah untuk
mengajak kalian semua menyadari apa sebenarnya yang telah dan sedang
terjadi di tanah ini, tanah tercinta kita ini.”
Dalam
pada itu, Ki Rangga dan Ki Waskita agaknya mulai tertarik dengan
percakapan itu sehingga keduanya telah berdiri dan berjalan mendekat.
“Ki
Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian sesampainya di samping Ki Jayaraga,
“Kami sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan Ki Sanak. Menurut
hemat kami, di tanah ini tidak sedang terjadi apa-apa? Sejak kami
dilahirkan kemudian menjadi setua ini, di tanah kita yang tercinta ini
keadaannya tidak pernah ada bedanya. Dari hari ke hari, minggu menjadi
minggu. Bahkan telah bertahun tahun kami menjelajahi tanah ini dari
ujung ke ujung, kami sama sekali tidak melihat adanya banyak perubahan.”
Untuk
sejenak orang berjambang itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil
memandang tajam ke arah Ki Rangga, dia pun bertanya, “Siapakah kalian
ini sebenarnya?”
“Kami
adalah pedagang wesi aji dan perhiasan dari Prambanan,” sahut Ki
Waskita yang juga telah berdiri di samping Ki Jayaraga, “Kami
menjelajahi padukuhan-padukuhan untuk menawarkan barang dagangan kami,”
Ki Waskita berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Namun kami juga siap
untuk membeli barang-barang berharga yang sekiranya menarik minat kami
dari siapapun.”
Sejenak
mata ketiga orang itu berbinar begitu mengetahui bahwa calon mangsa
yang berdiri di hadapan mereka kali ini adalah pedagang weji aji dan
barang-barang berharga.
“Ki
Sanak,” berkata orang berjambang itu kemudian, “Kami adalah anggota
dari sekelompok orang-orang yang menginginkan perubahan. Wahyu keprabon
di tanah ini seharusnya tetap tegak lurus dari Trah Majapahit. Namun
pada kenyataannya wahyu keprabon sekarang telah dicuri oleh keturunan
pidak pedarakan yang berasal dari Sela,” orang itu berhenti sebentar.
Lanjutnya kemudian, “Apakah Ki Sanak pernah mendengar sebuah cerita
tentang buah kelapa milik Ki Ageng Giring? Nah, sudah waktunya wahyu
keprabon saat ini kembali kepada yang berhak.”
Dengan nada sedikit ragu-ragu Ki Jayaraga pun kemudian bertanya, “Siapakah sebenarnya yang berhak atas wahyu keprabon itu?”
Orang
berjambang itu tidak segera menjawab. Sebuah senyum menghiasi wajahnya.
Jawabnya kemudian, “Siapa lagi kalau bukan keturunan Pangeran Sekar
Seda Lepen?”
Ki
Rangga dan kawan-kawannya sejenak tertegun. Ternyata pengaruh Trah
Sekar Seda Lepen itu telah jauh menyebar dan agaknya orang-orang semacam
inilah yang telah berusaha dengan tak mengenal lelah untuk menyebar
luaskan pengaruh itu.
“Maaf
Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian setelah beberapa saat mereka
terdiam, “Bukankah Harya Penangsang sebagai keturunan Sekar Seda Lepen
telah gugur di pinggir Bengawan Sore? Sedangkan Harya Mataram telah
hilang dan tidak ketahuan lagi rimbanya?”
“Itu
bukan urusan Ki Sanak,” jawab orang berjambang itu, “Sekarang yang
perlu kami ketahui adalah, apakah Ki Sanak mendukung Trah Sekar Seda
Lepen untuk kembali menduduki tahta atau tetap mendukung keturunan para
petani dari Sela itu?”
Untuk
beberapa saat Ki Rangga dan kawan-kawannya hanya dapat diam termangu.
Sementara Glagah Putih yang masih berdiri bersandaran pada batu sebesar
kerbau itu tidak ingin ikut campur. Dia telah percaya sepenuhnya kepada
Ki Rangga dan orang-orang tua itu.
“Ki
Sanak,” akhirnya orang berjambang itu berkata untuk memecah kesunyian,
“Kalian tidak harus bergabung dengan barisan kami jika memang ingin
mendukung Trah Sekar Seda Lepen untuk menduduki Tahta kembali. Ki Sanak
cukup menyumbangkan benda-benda berharga yang Ki Sanak miliki. Kami
memerlukan dana yang sangat besar untuk mewujudkan tanah ini kembali
gemah ripah loh jinawi sebagaimana di masa kejayaan Majapahit dahulu.”
Hampir
bersamaan Ki Rangga dan kawan-kawannya menarik nafas dalam-dalam.
Ternyata itulah pokok permasalahan sebenarnya yang ingin disampaikan
oleh orang berjambang itu, pengumpulan dana baik secara suka rela maupun
paksaan untuk mewujudkan cita-cita kelompok mereka.
Selagi
Ki Rangga berpikir untuk menyelesaikan persoalan itu tanpa menimbulkan
kekerasan, tiba-tiba Ki Waskita telah maju dua langkah sambil kedua
tangannya mengangsurkan sebuah keris berpendok emas dan bertretes
berlian. Kata Ki Waskita kemudian, “Inilah Ki Sanak. Mungkin aku tidak
bisa membantu dengan tenagaku yang sudah tua renta ini. Semoga keris ini
akan bermanfaat bagi perjuangan kalian.”
Ketiga
orang itu terkejut begitu melihat keris berpendok emas dan bertretes
berlian di tangan Ki Waskita. Sementara Ki Rangga dan kawan-kawannya
telah mengerutkan kening mereka dalam-dalam, namun itu hanya terjadi
sesaat. Sejenak kemudian tampak kepala mereka terangguk-angguk.
Dengan
cepat orang berjambang itu meraih keris di tangan Ki Waskita. Katanya
kemudian, “Terima kasih. Bantuan Ki Sanak tidak akan pernah kami
lupakan,” orang itu berhenti sejenak. Katanya kemudian sambil
mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling, “Bagaimana dengan Ki Sanak
yang lain? Apakah tidak ingin menyumbangkan harta benda kalian demi
sebuah perjuangan suci ini?”
Mendengar
pertanyaan itu Ki waskita segera tanggap. Sambil berjalan menghampiri
kawan-kawannya kecuali Glagah Putih, Ki Waskita pun berkata, “Tentu,
tentu Ki Sanak. Dengan senang hati kawan-kawan kami akan ikut berderma
untuk perjuangan ini.”
Segera
saja di tangan Ki Waskita terkumpul beberapa benda berharga, sebuah
timang emas, tiga buah cincin emas bermata merah delima dan beberapa
batu permata.
Dengan
sebuah senyum lebar orang berjambang itu menerima barang-barang
tersebut dari tangan Ki Waskita. Kemudian katanya kepada kawannya yang
bertubuh pendek kekar, “Masukkan semua ke dalam kantong di pelana
kudamu. Hari ini kita benar-benar sangat beruntung.”
Kawannya
segera maju untuk menerima barang-barang itu dan selanjutnya
menyimpannya ke dalam sebuah kantong besar yang disangkutkan di pelana
kudanya.
“Nah,
Ki sanak semua,” berkata orang berjambang itu kemudian, “Kami sangat
berterima kasih atas semua bantuan kalian. Semua ini akan aku laporkan
kepada Ki Lurah. Kelak jika perjuangan kami berhasil, kalian semua pasti
akan ikut menikmatinya. Sebuah Kerajaan baru akan lahir dibawah
pemerintahan seorang Raja yang adil dan bijaksana sehingga akan tercipta
sebuah negri yang gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja.”
Ki Rangga dan kawan-kawannya tidak menyahut. Hanya kepala mereka saja yang terlihat terangguk-angguk.
“Nah, aku mohon diri. Semoga hari kalian menyenangkan.”
Selesai
berkata demikian, tanpa menunggu jawaban, orang berjambang itu segera
meloncat ke punggung kudanya dan diikuti oleh kawan-kawannya. Sejenak
kemudian mereka segera menghela kuda masing-masing untuk berbalik arah
dan kemudian berderap meninggalkan tempat itu.
Untuk
beberapa saat ketiga kuda itu masih tampak menyeberangi kali Krasak
yang airnya hanya setinggi lutut orang dewasa. Setelah kuda-kuda itu
naik ke tepian dan kemudian hilang di balik tanggul yang rendah, barulah
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, “Ternyata Ki
Waskita masih senang bermain-main dengan bayangan semu. Kita harus
segera meninggalkan tepian ini sebelum mereka menyadari apa sebenarnya
yang telah terjadi.”
“Marilah
ngger,” sahut Ki Waskita kemudian, “Untung mereka tidak tertarik dengan
kuda-kuda kita. Ternyata perhitungan Ki Patih Mandaraka benar.”
“Bukankah
Ki Waskita juga mampu membuat bayangan semu seekor kuda atau bahkan
lebih, seribu kuda barangkali?” bertanya Ki Jayaraga sambil melangkah
mendekati kudanya.
“Membuat
yang tidak ada menjadi seolah-olah ada, itulah ilmu bayangan semu yang
sebenarnya tidak lebih dari sebuah permainan kanak-kanak,” Ki Waskita
berhenti sebentar sambil membenahi pelana kudanya. Lanjutnya kemudian,
“Namun jika sudah ada lima ekor kuda dan kemudian aku harus membuat
bayangan semu lima ekor kuda yang lain, bagaimana aku harus
menyembunyikan lima ekor kuda yang sebenarnya dari penglihatan mereka?”
Mereka
yang mendengar keterangan Ki Waskita itu tampak mengangguk-anggukkan
kepala. Demikian juga Glagah Putih yang sedang sibuk mempersiapkan
kudanya. Sementara Ki Bango Lamatan yang selama kejadian itu hanya
berdiam diri saja, telah semakin mengerti dan mendalami akan kemampuan
kawan-kawan seperjalanannya.
“Selama
ini aku memang ibarat seekor katak dalam tempurung,” berkata Ki Bango
Lamatan dalam hati, “Ternyata Mataram memiliki sekumpulan orang-orang
yang pilih tanding dan ngedab edabi,” Ki Bango Lamatan berhenti sejenak.
Sambil berpaling sekilas ke arah Glagah Putih yang berkuda di sebelah
Ki Jayaraga, dia kembali berkata dalam hati, “Anak muda itupun
kelihatannya bukan anak muda sembarangan. Sorot matanya terlihat begitu
meyakinkan serta gerak-geriknya penuh dengan kepercayaan diri yang
tinggi.”
Demikianlah,
sejenak kemudian kelima ekor kuda itupun segera menyeberangi kali
Krasak yang airnya cukup dangkal untuk kemudian berpacu di bulak panjang
yang menuju ke padukuhan Ngadiluwih.
“Ngger,”
berkata Ki Waskita kemudian sambil berpaling kepada Ki Rangga yang
berkuda di sebelahnya, “Sebaiknya sebelum mencapai hutan kecil di depan,
kita mengambil jalan ke kiri menuju ke padukuhan Gesik. Setelah itu
kita menyusuri tepian kali Praga sampai memasuki padukuhan Klangon.
Sebaiknya kita menghindari padukuhan Salam.”
“Ki
Waskita benar,” jawab Ki Rangga, “Ketiga orang tadi menyebut-nyebut
padukuhan Salam dan agaknya sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke
sana. Kemungkinannya mereka memang bersarang di sana.”
Ki Waskita mengangguk-anggukkan kepalanya diikuti oleh yang lainnya.
“Apakah angger mempunyai dugaan siapakah
yang dimaksud dengan Raden Mas Harya Surengpati?” bertanya Ki Waskita
kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Sewaktu masih di atas tanggul
tadi, orang berjambang itu telah menyebut namanya.”
Ki Rangga menggeleng. Jawabnya kemudian,
“Mungkin banyak orang yang mengaku masih kerabat dekat dengan Sekar Seda
Lepen dan bergabung dengan kelompok itu. Namun aku yakin bahwa mereka
masing-masing mempunyai pamrih pribadi yang lebih kuat dibanding dengan
apa yang mereka sebut sebagai sebuah perjuangan itu.”
Kembali Ki Waskita mengangguk-anggukkan kepalanya dan diikuti oleh yang lainnya.
“Kita harus membuat hubungan terlebih
dahulu dengan para petugas sandi sebelum memasuki Perdikan Matesih,”
berkata Ki Rangga selanjutnya, “Kita tidak tahu apakah pengaruh kelompok
orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu
telah merambah sampai ke Perdikan Matesih.”
“Kemungkinan itu ada ngger,” sahut Ki
Waskita, “Tanah Perdikan Matesih letaknya tidak jauh di sebelah barat
Gunung Tidar. Tidak menutup kemungkinan ada sebagian penduduk terutama
para pemudanya yang menjadi murid Perguruan Sapta Dhahana.”
“Dan Perguruan Sapta Dhahana menurut
keterangan para petugas sandi telah menjalin hubungan dengan Trah Sekar
Seda Lepen,” Ki Jayaraga yang berkuda di belakang Ki Rangga menyahut.
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam.
Katanya kemudian, “Menilik pengaruh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen
sudah sampai di padukuhan Salam dan sekitarnya, kuat dugaanku Perdikan
Matesih pun tidak luput dari pengaruh itu.”
“Jadi bagaimana kakang?” Glagah Putih
yang sedari tadi hanya diam saja tidak mampu lagi menahan hati, “Apakah
kita akan tetap bermalam di Perdikan Matesih?”
“Seperti yang telah aku katakan tadi,
kita membuat hubungan dengan para petugas sandi terlebih dahulu,” jawab
Ki Rangga kemudian, “Petugas sandi yang terdekat berada di padukuhan
Klangon.”
Glagah Putih mengangguk-anggukkan
kepalanya mendengar keterangan kakak sepupunya itu. Sementara yang
lainnya pun telah ikut mengangguk-angguk pula.
Demikianlah sejenak kemudian mereka
segera memacu kuda masing-masing menyusuri bulak yang cukup panjang itu
sebelum mencapai hutan kecil di pinggir padukuhan Ngadiluwih.
Dalam pada itu, orang berjambang dan
kedua kawannya sedang memacu kuda-kuda mereka keluar pintu gerbang
padukuhan Ngadiluwih. Setelah melewati sebuah bulak pendek, mereka akan
memasuki sebuah padukuhan kecil yang selama ini mereka pergunakan
sebagai tempat tinggal sementara, Padukuhan Salam.
Perjalanan itu hanya memerlukan waktu
yang sangat pendek. Ketika pintu gerbang padukuhan yang sangat sederhana
telah mereka lalui, orang berjambang beserta kedua kawannya itu segera
mengambil jalur ke kanan menyusuri sebuah jalan setapak.
Tidak banyak yang memperhatikan jalan
setapak itu. Sebuah jalan setapak yang menembus pategalan yang sangat
luas. Di kanan kiri jalan setapak itu tumbuh beberapa jenis pepohonan
yang berkayu keras. Beberapa gerombol pohon pisang juga tampak tumbuh di
beberapa tempat di sepanjang jalur jalan setapak itu.
“Ki Lurah pasti akan terkejut melihat
hasil kerja kita hari ini,” berkata orang berjambang itu kepada kedua
kawannya yang berkuda di belakangnya, “Matahari baru mendekati
puncaknya, namun kita sudah pulang dengan membawa hasil yang sedemikian
banyaknya.”
Kedua kawannya tidak menyahut dan hanya
mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tanpa sadar salah seorang telah
mendongakkan wajahnya ke langit. Di sela-sela rimbunnya dedaunan, tampak
Matahari memang belum sampai pada puncaknya.
Untuk beberapa saat mereka masih
menyusuri jalan setapak di pinggir pategalan yang tidak terurus itu.
Kelihatannya pemilik pategalan itu sudah lama tidak menengoknya dan
dibiarkan saja semak belukar tumbuh subur di pategalan itu. Namun ketiga
orang itu sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap keadaan di
sekeliling mereka. Masing-masing sedang berangan-angan untuk
mendapatkan hadiah dari pemimpin mereka serta di masa mendatang akan
lebih dipercaya untuk melaksanakan tugas yang lebih besar.
Semakin lama jalan setapak yang mereka
lalui semakin sempit sehingga mereka harus berkuda berurutan. Setelah
melewati sebuah pohon randu yang batangnya sebesar hampir dua pelukan
orang dewasa, mereka pun kemudian berbelok ke kiri dan melalui jalan
setapak yang mulai menurun.
“Kita hampir sampai,” berkata orang
berjambang itu sambil berpaling sekilas ke belakang, “Aku tidak bisa
membayangkan wajah Ki Lurah yang akan terheran-heran melihat hasil kerja
kita hari ini.”
Kawannya yang bertubuh pendek dan berkuda
tepat di belakangnya tersenyum mendengar angan-angan orang berjambang
itu. Tanpa sadar tubuhnya agak membungkuk ke depan sambil tangan kirinya
meraba kantong besar yang tersangkut di pelana kudanya.
Namun alangkah terkejutnya orang yang
bertubuh pendek itu. Jantungnya bagaikan berhenti berdetak dengan
tiba-tiba. Tangan kirinya yang meraba kantong itu tidak menemukan
sesuatu apapun. Dicobanya sekali lagi untuk meremas-remas kantong itu,
namun hasilnya tetap sama. Kantong itu sama sekali kosong dan tidak ada
isinya.
“Kakang..!” terdengar suaranya gemetar memanggil orang berjambang di depannya.
Orang berjambang itu mengerutkan keningnya sambil menoleh. Tanyanya kemudian, “Ada apa?”
“Kantong itu..” orang bertubuh pendek itu
tidak mampu menyelesaikan kata-katanya. Dadanya rasa-rasanya telah
pepat seolah tertimbun bebatuan yang longsor dari puncak bukit.
Kembali orang berjambang itu mengerutkan
keningnya. Sekarang dia tidak hanya menoleh, namun telah menghentikan
kudanya. Katanya kemudian setengah membentak, “Ada apa, he?!”
Orang yang bertubuh pendek itu sekarang
benar-benar telah menggigil seperti orang kedinginan. Sambil gemetaran
tangannya meraih kantong yang terikat di pelana kudanya dan kemudian
diangkatnya. Katanya kemudian dengan suara yang memelas, “Kakang,
barangnya tidak ada. Kantong ini kosong.”
“He?” bagaikan disambar petir di siang
bolong orang berjambang itu berteriak sambil meloncat turun dari
kudanya. Dengan tergesa-gesa dia segera melangkah mendekat.
Orang yang pendek dan orang yang satunya
segera ikut meloncat turun. Sementara orang yang bertubuh pendek itu
segera melepas tali yang mengikat kantong itu di pelana kudanya.
Tanpa menunggu waktu lagi orang
berjambang itu segera menyambar kantong yang diangsurkan kepadanya.
Dengan menggeram marah dibongkarnya kantong itu yang ternyata memang
kosong melompong tidak ada isinya.
“Gila..!” umpat orang berjambang itu
sambil membanting kantong itu ke tanah. Sejenak matanya yang memerah
darah menatap tajam ke arah orang yang bertubuh pendek yang berdiri di
hadapannya dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba saja tangan kirinya
mencengkeram leher orang itu.
“Kau? Kau?” geram orang berjambang itu
dengan suara menggelegar, “Pengkhianat busuk! Di mana kau sembunyikan
barang-barang itu, he?!”
Orang yang bertubuh pendek itu
benar-benar telah kehilangan nyali. Nyawanya rasa-rasanya sudah berada
di ubun-ubun, siap untuk meloncat keluar dari raganya. Sementara
wajahnya pucat pasi dengan sekujur tubuh yang telah basah kuyup oleh
keringat dingin.
“Aaku.. tidak tahu Kakang..” jawab orang itu terbata-bata.
“Bohoong..! Kau memang pantas mampus!”
umpat orang berjambang itu sambil mengangkat tangan kanannya
tinggi-tinggi. Siap menghancurkan kepala orang yang bertubuh pendek itu.
“Kakang tunggu!” tiba-tiba orang ketiga
yang sedari tadi hanya berdiri terpaku melihat peristiwa itu segera
berteriak sambil meloncat maju, “Pendek belum tentu bersalah. Aku sedari
tadi berkuda di sampingnya dan kemudian di belakangnya. Aku tidak
melihat dia menyentuh kantong itu kecuali beberapa saat tadi. Aku yakin,
Pendek tidak akan mengkhianati perjuangan kita.”
Untuk beberapa saat orang berjambang itu
masih tetap pada sikapnya. Namun tiba-tiba cengkeramannya di leher orang
bertubuh pendek itu semakin keras sambil berteriak, “Kalian sengaja
bersekongkol untuk menipu aku, he? Kalian akan mengangkangi
barang-barang itu berdua saja dan menipu aku! Sebaiknya kalian berdua
aku bunuh saja!”
Selesai berkata demikian, kembali tangan
kanan orang berjambang itu terangkat tinggi-tinggi siap menghancurkan
kepala orang yang selama ini telah menjadi kawan seperjuangannya.
“Kakang, ampun..kakang. Aku benar-benar
tidak melakukannya..” rengek orang bertubuh pendek itu dengan suara
memelas. Sementara orang yang satunya hanya dapat memandang peristiwa
itu dengan wajah yang sangat tegang.
Tiba-tiba di saat yang menegangkan itu terdengar sebuah tawa terbahak-bahak memenuhi tempat itu.
Serentak ketiga orang itupun segera berpaling ke arah mana suara tawa itu berasal.
“Ki Lurah,” hampir bersamaan ketiga orang itu berseru tertahan.
Orang yang dipanggil Ki Lurah itu
tersenyum sambil melangkah mendekat. Sambil memberi isyarat kepada orang
yang berjambang itu dia berkata, “Jambang, lepaskan si Pendek.”
Dengan segera orang yang berjambang itu
melepaskan cengkeramannya kepada Pendek. Begitu cengkeraman itu terlepas
dari lehernya, Pendek segera menarik nafas dalam-dalam sambil melangkah
mundur. Agaknya dia tidak ingin bermasalah lagi dengan si Jambang itu.
“Aku dapat menduga apa sebenarnya yang
telah terjadi pada kalian,” berkata Ki Lurah kemudian, “Kalian telah
menjadi korban permainan dari orang-orang yang berilmu tinggi. Namun
dengan demikian kita akan menjadi lebih waspada.”
Ketiga orang itu sejenak saling pandang.
Orang berjambang itu yang akhirnya bertanya mewakili kawan-kawannya,
“Maaf Ki Lurah. Kami tidak mengerti maksud Ki Lurah. Kami merasa tidak
pernah bertemu atau bahkan bertempur dengan orang-orang yang berilmu
tinggi.”
“Kalian memang terlalu bodoh!” geram Ki
Lurah, “Bukankah seseorang telah memberikan sesuatu yang menurut kalian
itu merupakan barang-barang berharga?”
“Benar Ki Lurah,” serempak mereka
menjawab. Sementara si Jambang segera meneruskan, “Kami bertemu lima
orang di tepian kali Krasak. Ketika aku menjelaskan kepada mereka
tentang perjuangan kami, dengan serta merta salah seorang dari mereka
yang terlihat paling tua telah menyerahkan sebuah keris yang berpendok
emas dan bertretes berlian.”
“Itulah,” sahut Ki Lurah sambil
menggeleng-gelengkan kepalanya, “Orang tua itu pasti tukang sihir, dan
kalian telah disihirnya,” Ki Lurah berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian,
“Apakah orang-orang yang lainnya juga menyerahkan barang-barang
berharga mereka?”
Kembali ketiga orang itu saling
berpandangan. Seingat mereka, orang-orang yang lainnya memang hanya
berdiam diri saja. Orang yang paling tua itulah yang mengambil
barang-barang berharga dari mereka dan kemudian menyerahkannya.
“Tidak Ki Lurah,” jawab si Jambang yang
kini mulai menyadari kebodohannya, “Memang kita mendapat tambahan
beberapa barang berharga lagi, namun orang tua itulah yang mengambil
dari masing-masing orang dan menyerahkannya kepadaku.”
Ki Lurah mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berdesis perlahan, “Kemanakah sebenarnya tujuan orang-orang itu?”
Sejenak suasana menjadi sunyi. Masing-masing tenggelam dalam angan-angan tentang peristiwa yang baru saja mereka alami.
“Ki Lurah,” tiba-tiba orang yang bertubuh
pendek itu membuka suara, “Apakah tidak sebaiknya kita mengejar
orang-orang yang telah mempermainkan kami itu?”
Ki Lurah menggeleng sambil tersenyum
masam. Jawabnya kemudian, “Tidak ada gunanya. Mereka tentu sudah jauh
dan jika kita dapat menemukan mereka, aku tidak yakin kekuatan kita akan
mampu untuk menghadapi mereka.”
Ketiga orang itu mengangguk-anggukkan
kepala mereka mendengar jawaban Ki Lurah. Memang segala sesuatunya harus
dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum bertindak.
“Sudahlah,” berkata Ki Lurah kemudian,
“Kalian dapat beristirahat sebentar. Aku akan ke Perdikan Matesih untuk
melaporkan kejadian ini kepada Raden Mas Harya Surengpati.”
Ketiga orang itu tidak menjawab dan hanya
melangkah sambil menuntun kuda-kuda mereka mengikuti Ki Lurah menuju ke
sebuah bangunan yang terletak tidak jauh dari tempat itu.
Tidak banyak yang memperhatikan bangunan
itu. Sebuah bangunan yang dindingnya terbuat dari bambu dan beratap
ilalang. Sebuah bangunan yang lebih cocok disebut sebuah gubuk dari pada
sebuah rumah. Di gubuk itulah orang yang dipanggil Ki Lurah itu tinggal
bersama mereka.
Dalam pada itu Ki Rangga dan
kawan-kawannya telah sampai di Padukuhan Gesik, sebuah padukuhan kecil
dan sepi. Mereka berlima sengaja tidak melewati jalan satu-satunya yang
berada di padukuhan itu, namun mereka lebih senang menyusuri sebuah
jalan setapak di pinggir hutan yang cukup lebat. Hutan itu melingkari
Padukuhan Gesik dari sebelah selatan kemudian membujur ke arah sisi
barat padukuhan.
Beberapa saat kemudian rombongan berkuda
itu telah memasuki sebuah padang rumput yang luas di pinggir hutan
sebelah barat Padukuhan Gesik. Rombongan itu pun segera keluar dari
jalur jalan setapak yang menjelujur di pinggir hutan itu. Kuda-kuda itu
pun kemudian dapat berpacu dengan cepat di sela-sela gerumbul-gerumbul
perdu yang banyak tersebar di padang rumput itu.
Sesekali mereka tampak mendongakkan wajah
mereka ke langit. Awan yang gelap mulai tampak bergerombol dan
berarak-arak di cakrawala langit sebelah barat. Kelihatannya musim
kemarau akan segera berakhir dan sudah saatnya hujan turun membasahi
bumi yang kering.
“Mungkin ini akan menjadi hujan yang pertama yang akan turun,” desis Ki Waskita yang berkuda di samping Ki Rangga.
Ki Rangga mendongakkan wajahnya sekilas. Jawabnya kemudian, “Semoga sebelum hujan kita sudah memasuki Padukuhan Klangon.”
Yang mendengar kata-kata Ki Rangga itu
pun telah mengangguk-anggukkan kepala. Mereka memang berharap tidak
sampai kehujanan di tengah perjalanan.
Ketika hutan di sebelah barat padukuhan
itu menjadi semakin tipis dan pohon-pohon yang besar telah berganti
dengan tanaman perdu serta semak belukar, padang rumput yang mereka
lalui itu pun telah menyempit. Sejenak kemudian di hadapan mereka telah
terbentang tanah persawahan yang luas. Jalan setapak di pinggir hutan
itu pun telah tersambung dengan sebuah bulak panjang. Di sepanjang
bulak, banyak pepohonan yang tumbuh atau memang sengaja ditanam di kiri
kanan jalan. Sementara di langit awan hitam mulai bergerak menutupi
sinar Matahari sehingga pemandangan di sepanjang bulak itu terlihat
mulai remang-remang.
Sambil memperlambat laju kuda-kuda
mereka, Ki Rangga dan kawan-kawannya pun kemudian membelokkan arah
kuda-kuda mereka ke bulak yang sangat panjang dan sekarang terlihat
agak gelap. Angin yang dingin dan basah mulai bertiup sedikit kencang
menggugurkan daun-daun yang sudah menguning dari tangkainya. Di langit
sesekali halilintar mulai bersabung. Suaranya terdengar menggelegar
memekakkan telinga.
“Kelihatannya para petani sudah mulai
mempersiapkan tanah mereka untuk digarap,” berkata Ki Jayaraga yang
berkuda di belakang Ki Rangga sambil mengamati orang-orang yang sedang
bekerja di sawah. Sebagian tampak sedang memperbaiki tanggul, sebagian
lainnya tampak sedang mencangkul.
“Ya, Ki Jayaraga,” sahut Ki Rangga sambil berpaling sekilas, “Apakah Ki Jayaraga tertarik untuk membantu?”
“Ah,” Ki Jayaraga tertawa pendek. Lanjut Ki Jayaraga kemudian, “Aku lupa membawa cangkul, Ki Rangga.”
Kali ini semua orang yang berada di dalam
rombongan itu tertawa cukup keras sehingga membuat orang-orang yang
bekerja di sawah itu telah berpaling.
Demikianlah rombongan berkuda itu pun
kemudian tanpa berusaha menarik perhatian telah berpacu kembali di bulak
panjang. Dari kejauhan tampak debu yang mengepul tinggi di belakang
rombongan berkuda itu.
Ketika rombongan itu telah melewati
tengah-tengah bulak, dari kejauhan mereka melihat seseorang tampak
sedang duduk terkantuk-kantuk di bawah sebatang pohon di sebelah kiri
jalan, hanya beberapa puluh tombak saja dari regol padukuhan Klangon.
Orang itu terlihat duduk bersila dengan
kedua tangan bersilang di dada serta kepala yang tertunduk dalam-dalam.
Sebuah caping di atas kepalanya telah menutupi sebagian wajahnya.
Terasa dada Ki Rangga berdesir, demikian
juga Glagah Putih. Sebagai prajurit mereka cukup mengenal tanda-tanda
yang ditunjukkan oleh orang yang sedang beristirahat di tepi jalan itu.
Ki Rangga segera memberi isyarat untuk
memperlambat kuda-kuda mereka begitu rombongan itu mendekati tempat
orang bercaping itu duduk.
Ki Waskita sejenak mengerutkan keningnya
dalam-dalam sambil berpaling ke arah Ki Rangga. Ketika Ki Rangga
kemudian mengangguk, barulah Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam
sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara Glagah Putih yang
berkuda di samping gurunya telah berkata dengan suara yang sedikit
lantang, “Angin timur atau angin barat kah yang bertiup membawa hujan
kali ini?”
Tidak terdengar suara jawaban sama
sekali. Bahkan ketika rombongan berkuda itu telah tepat berhenti di
depannya, orang bercaping itu tetap pada sikapnya semula, menunduk
dengan caping menutupi sebagian wajahnya.
Sejenak Ki Rangga menjadi ragu-ragu.
Namun segala sesuatunya harus segera diyakinkan. Maka dengan cepat Ki
Rangga segera meloncat turun dari kudanya dan bergegas menghampiri
orang itu.
Ketika jarak Ki Rangga dengan orang itu
tinggal selangkah, jantung Ki Rangga pun bagaikan berhenti berdetak. Ki
Rangga melihat sesuatu yang janggal telah terjadi pada diri orang itu.
Orang itu bagaikan sebuah patung yang diletakkan begitu saja di bawah
pohon, sama sekali tidak bergerak. Bahkan gerakan tubuh yang menandakan
bahwa dia masih bernafas pun tidak terlihat.
Tanpa meninggalkan kewaspadaan, dengan
gerak cepat Ki Rangga maju selangkah sambil membungkuk. Ketika tangan
Ki Rangga kemudian terjulur untuk membuka caping itu, alangkah
terkejutnya Ki Rangga. Terlihat sebuah paser kecil telah menancap
dalam-dalam di leher orang itu.
“Gila!” geram Ki Rangga sambil berusaha
meraba detak nadi di leher dan kedua pergelangan tangan orang itu. Namun
Ki Rangga tidak menemukan apa yang dicarinya.
Perlahan Ki Rangga mengembalikan caping
itu di atas kepala orang itu sambil menarik nafas dalam-dalam untuk
melonggarkan dadanya yang berdebaran. Ketika Ki Rangga kemudian
menegakkan tubuhnya dan berbalik, yang pertama-tama dilakukannya adalah
menggeleng sambil berdesis, “Orang itu telah mati.”
“Mati?” hampir serentak mereka yang masih
berada di atas punggung kuda itu mengulang. Dengan bergegas mereka pun
kemudian segera berloncatan turun dari atas punggung kuda masing-masing.
Sejenak kemudian kelima orang itupun
telah mengerumuni orang bercaping yang telah menjadi mayat dalam keadaan
duduk dibawah sebatang pohon itu.
“Paser beracun,” desis Ki Waskita sambil mengamat-amati paser yang menancap dalam-dalam di leher orang itu.
“Ya Ki Waskita,” sahut Ki Rangga,
“Kelihatannya seseorang dengan sengaja telah melontarkan paser kecil itu
melalui sebuah sumpit,” Ki Rangga berhenti sejenak sambil mengedarkan
pandangan matanya ke sekelilingnya. Lanjutnya kemudian, “Hanya orang
yang mempunyai kemampuan tinggi yang mampu melakukan semua ini.”
Yang mendengar keterangan Ki Rangga telah
mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tentu diperlukan tenaga yang sangat
kuat untuk dapat melontarkan paser kecil itu sehingga menancap hampir
seluruhnya di leher orang itu.
“Bagaimana kakang,” bertanya Glagah Putih
kemudian, “Menilik ciri-cirinya, dia adalah petugas sandi Mataram.
Apakah kita akan menguburkannya?”
Mendengar pertanyaan Glagah Putih, Ki
Rangga segera menyingkap baju orang itu untuk melihat timang ikat
pinggangnya. Dan apa yang diduga oleh Glagah Putih memang benar. Timang
itu bagi orang kebanyakan memang tidak akan banyak berarti, namun bagi
sesama petugas sandi atau prajurit Mataram, tanda yang berada di
lempengan timang itu mengandung arti tersendiri.
“Seharusnya memang demikian,” jawab Ki
Rangga kemudian sambil berpaling ke arah adik sepupunya itu, “Namun kita
harus mencari tempat yang layak dan tidak begitu banyak menarik
perhatian orang.”
“Baik kakang,” sahut Glagah Putih kemudian sambil maju mendekat untuk mengangkat tubuh yang sudah tak bernyawa itu.
Namun sebelum Glagah Putih menyentuh
tubuh itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan riuh rendah
yang berasal dari arah regol padukuhan Klangon.
Serentak mereka berpaling. Tampak
berpuluh-puluh orang sedang berlari-larian dari arah regol padukuhan
Klangon menuju ke tempat mereka berkerumun.
“Tangkap pembunuh..!” teriak beberapa orang dengan senjata yang teracu.
STSD Jilid 2
Bagian 1
“TANGKAP pembunuh..!!” yang lainnya pun ikut berteriak sambil mengangkat senjata di tangan kanan mereka tinggi-tinggi.
Untuk beberapa saat Ki Rangga dan
kawan-kawannya justru telah membeku. Mereka tidak tahu apa yang harus
dilakukan dan hanya diam di tempat saja sambil menunggu.
Sejenak kemudian orang-orang yang
berlari-larian itu telah sampai di tempat Ki Rangga dan kawan-kawannya
berdiri. Dengan segera mereka berkerumun sambil mengacu-acukan senjata
mereka.
Sekilas Ki Rangga dan kawan-kawannya
segera melihat bahwa mereka adalah sekumpulan orang-orang padukuhan
yang masih lugu, dilihat dari jenis senjata yang mereka bawa. Kebanyakan
dari mereka membawa parang pembelah kayu, linggis dan bahkan sabit
rumput serta dua orang justru telah membawa cangkul.
Agaknya mereka begitu tergesa-gesa atau
bahkan tidak menutup kemungkinan mereka sedang dalam perjalanan ke
sawah atau ke pategalan dan kemudian seseorang telah mempengaruhi
mereka.
“Ki Sanak semua,” berkata Ki Waskita
kemudian dengan suara sareh sambil maju selangkah, “Apakah sebenarnya
yang telah terjadi, sehingga Ki Sanak semua telah berbondong-bondong
menuju ke tempat ini?”
“Tidak usah berpura-pura kakek tua!”
geram seorang yang berperawakan tegap dan masih cukup muda sambil
melangkah ke depan, “Kalian berlima akan kami bawa ke banjar padukuhan
untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan kalian.”
“Sebentar Ki Sanak,” berkata Ki Waskita tetap dengan nada yang sareh, “Perbuatan apakah yang harus kami pertanggung-jawabkan?”
“Kalian telah membunuh orang itu!” bentak
orang bertubuh kekar itu sambil menunjuk orang yang duduk di bawah
pohon dan telah menjadi mayat.
“Kalian salah sangka,” jawab Ki Waskita, “Kami berlima justru terheran-heran mendapatkan orang itu telah menjadi mayat.”
“Bohong!” kembali orang berperawakan
tegap itu membentak, “Ada seseorang yang telah memberitahu kami bahwa
kalian lah yang telah membunuh orang itu.”
Ki Waskita mengerutkan keningnya sejenak.
Katanya kemudian, “Siapakah diantara kalian yang melihat kami telah
membunuh orang itu?”
Serentak orang-orang yang berkerumun itu
saling pandang sambil mencoba mengenali orang-orang yang berada di dekat
mereka. Agaknya mereka sedang mencari seseorang diantara mereka.
“Dimana dia?” geram orang berperawakan tegap itu sambil menebarkan pandangannya ke sekeliling.
“Ya, mana orang tadi?” seseorang yang lain telah menyahut.
“Siapa?” yang lain justru balik bertanya
“Orang yang memberitahu kita bahwa di bulak telah terjadi rajapati,” sahut yang lain.
Segera saja terdengar suara bergeremang
di antara mereka. Ternyata orang yang sedang mereka cari itu justru
tidak ada di antara mereka.
“Gila!” kembali orang tegap itu menggeram, “Kemana perginya orang itu, he? Dia harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini.”
“Maaf Ki Sanak,” kali ini Ki Rangga yang
berkata, “Sesungguhnya kami berlima bermaksud untuk menanyakan sesuatu
kepada orang itu. Namun kami menjadi curiga begitu orang itu sama sekali
tidak menjawab bahkan terlihat tidak bergerak sama sekali,” Ki Rangga
berhenti sebentar. Lanjutnya kemudian, “Kami menyangka orang itu sedang
mengalami kesulitan atau menderita sakit. Maka kami memberanikan diri
untuk mendekat dan memeriksanya. Ternyata orang itu telah meninggal.”
Beberapa orang tampak menarik nafas
sambil mengangguk-angguk. Sedangkan orang berperawakan tegap itu masih
mengerutkan keningnya dalam-dalam. Bertanya orang itu kemudian dengan
nada yang mulai menurun, “Siapakah sebenarnya Ki Sanak berlima ini?”
“Kami dari Prambanan dan sedang dalam
perjalanan menuju ke tanah Perdikan Matesih,” jawab Ki Waskita, “Kami
sangat jarang melakukan perjalanan jauh. Sehingga kami sering berhenti
di suatu tempat dan menanyakan kembali arah perjalanan kami untuk
meyakinkan bahwa kami tidak tersesat.”
Orang bertubuh tegap itu tampak
ragu-ragu. Namun sebelum dia bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar
langkah-langkah beberapa orang yang sedang berlari-larian menuju ke
tempat itu Sejenak kemudian beberapa orang tampak muncul dari regol
padukuhan.
“Ki Jagabaya!” hampir setiap mulut menyebut nama itu kecuali Ki Rangga dan kawan-kawannya.
Memang yang datang itu adalah Ki
Jagabaya, perangkat padukuhan Klangon yang bertanggung jawab atas
keselamatan dan keamanan padukuhan.
“Ada apa Ki Senggi?” bertanya Ki Jagabaya sesampainya dia di hadapan orang yang bertubuh tegap itu.
“Maaf Ki Jagabaya, kita sedang mengusut
sebuah rajapati yang baru saja terjadi di bulak ini,” jawab orang
bertubuh tegap itu yang ternyata bernama Ki Senggi.
Sejenak Ki Jagabaya mengerutkan keningnya
sambil mengedarkan pandangan matanya ke wajah-wajah yang ada di
sekelilingnya. Katanya kemudian, “Aku baru saja diberi tahu tentang
rajapati ini. Nah, di mana jasad orang itu? Aku ingin melihatnya.”
Segera saja kerumunan itu menyibak dan
memberi jalan Ki Jagabaya. Dengan langkah lebar Ki Jagabaya pun kemudian
mendekati jasad orang yang masih terlihat duduk di bawah pohon itu.
Sambil membungkuk Ki Jagabaya mencoba membuka caping itu. Sejenak kerut merut yang dalam terlihat menghiasi kening Ki Jagabaya.
“Sebuah paser,” desis Ki Jagabaya
perlahan sambil mengamat-amati sebuah paser yang menancap dalam-dalam di
leher orang itu, “Tentu sebuah paser yang sangat beracun.”
Beberapa orang yang mendengar desis Ki
Jagabaya itu mencoba mendekat. Dengan berdesak-desakan mereka mencoba
melihat keadaan orang itu.
“Sudahlah,” berkata Ki Jagabaya kemudian
sambil menegakkan tubuhnya dan berbalik, “Angkat jasad ini dan bawa ke
banjar padukuhan. Kita harus segera menyelenggarakan pemakaman baginya
sebelum hujan turun.”
Mendengar kalimat terakhir Ki Jagabaya,
serentak mereka yang hadir mendongakkan kepala mereka ke langit. Mendung
sudah sedemikian tebalnya serta angin yang bertiup keras terasa telah
membawa titik-titik air.
“Bagaimana dengan Ki Sanak berlima ini,
Ki Jagabaya?” bertanya Ki Senggi begitu melihat Ki Jagabaya tampak
memperhatikan Ki Rangga dan kawan-kawannya yang berdiri termangu-mangu
sambil memegang kendali kuda masing-masing.
Ki Jagabaya berpaling sekilas mendengar pertanyaan Ki Senggi. Bertanya Ki Jagabaya kemudian, “Siapakah mereka?”
“Maaf Ki Jagabaya,” Ki Waskita lah yang
mendahului menjawab sambil melangkah mendekat dengan tetap memegangi
kendali kudanya, “Kami berlima berasal dari Prambanan dan sedang dalam
perjalanan menuju ke Perdikan Matesih,” Ki Waskita berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian, “Beberapa saat tadi kami menemukan orang itu sudah
dalam keadaan tidak bernyawa di bawah pohon.”
Ki Jagabaya tidak segera menanggapi
kata-kata Ki Waskita. Sepasang matanya yang mirip sepasang mata burung
hantu itu menatap tajam ke wajah Ki Waskita.
Agaknya Ki Waskita dapat menjajagi isi
hati Ki Jagabaya. Maka katanya kemudian sambil balas menatap mata Ki
Jagabaya, “Apakah Ki Jagabaya meragukan keterangan kami?”
Ki Jagabaya terkejut. Sepasang mata Ki
Waskita yang balik menatapnya itu bagaikan menyala dan telah membuat
sepasang matanya menjadi pedas bahkan mulai berair.
“Gila!” geram Ki Jagabaya dalam hati
sambil melemparkan pandangan matanya ke arah Ki Senggi. Katanya
kemudian, “Ada hubungan apakah mereka berlima dengan peristiwa rajapati
ini?”
Ki Senggi beringsut setapak. Jawabnya
kemudian, “Seseorang telah memberitahukan kepada kami bahwa mereka
berlima itulah pembunuh yang sebenarnya.”
Untuk ke sekian kalinya Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Tanyanya kemudian, “Di mana orang itu sekarang?”
“Dia tidak ada di sini, Ki Jagabaya.”
Merah padam wajah Ki Jagabaya. Katanya kemudian dengan suara sedikit keras, “Panggil orang itu ke sini sekarang juga!”
“Aku tidak mengenalnya, Ki Jagabaya.”
“He?” seru Ki Jagabaya keheranan, “Bagaimana mungkin? Bukankah Ki Senggi mengenal hampir semua penghuni padukuhan Klangon ini?”
“Ya, Ki Jagabaya,” jawab Ki Senggi cepat,
“Namun kami tidak sempat menanyakan jati diri orang itu, karena berita
rajapati itu telah mengejutkan kami.”
“Ki Senggi benar Ki Jagabaya,” sahut yang
lain, “Pada saat kami akan berangkat ke sawah, di tengah perjalanan
seseorang telah memberitahu kami tentang rajapati ini.”
“Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang mengenal orang itu?’ sela Ki Jagabaya cepat.
Hampir bersamaan orang-orang padukuhan Klangon yang hadir di tempat itu menggeleng.
Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam
sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sambil menatap satu-satu wajah
yang tertunduk itu Ki Jagabaya pun kemudian bertanya, “Atas dasar apa
kalian seenaknya saja menuduh Ki Sanak berlima ini sebagai pelakunya?”
Wajah-wajah lugu penghuni padukuhan Klangon itupun semakin tertunduk dalam-dalam.
“Untunglah seseorang telah memberitahu
aku tentang peristiwa di depan regol padukuhan ini, sehingga
kesalah-pahaman ini dapat dihindarkan,” berkata Ki Jabagaya kemudian
setelah sejenak mereka terdiam. Lanjut Ki Jagabaya kemudian, “Marilah
kita segera menyelenggarakan jasad orang itu. Siapapun dia sebenarnya,
karena dia telah meninggal di padukuhan Klangon, maka sudah menjadi
kewajiban kita untuk menyelenggarakan pemakamannya.”
Setiap kepala yang hadir di tempat itu pun tampak terangguk-angguk.
Kemudian kepada Ki Rangga dan
kawan-kawannya, Ki Jagabaya berkata, “Marilah Ki Sanak, kami persilahkan
Ki Sanak berlima untuk sekedar mampir di padukuhan Klangon. Kalian
dapat bermalam di banjar padukuhan karena sebentar lagi kelihatannya
hujan akan turun, dan sebaiknya Ki Sanak mencari tempat berteduh.”
Hampir bersamaan Ki Rangga dan
kawan-kawannya saling pandang. Segera saja mereka memaklumi ajakan Ki
Jagabaya itu. Walaupun tidak secara langsung orang yang bertanggung
jawab atas keamanan padukuhan Klangon itu mencurigai mereka, namun
ajakan untuk bermalam di padukuhan Klangon itu perlu diwaspadai. Secara
tidak langsung ajakan itu mengisyaratkan bahwa Ki Rangga berlima masih
dalam pengawasan atas peristiwa rajapati itu.
“Terima kasih Ki Jagabaya,” akhirnya Ki
Waskita lah yang menjawab mewakili yang lain, “Kami sangat bersyukur
mendapat tempat bermalam di padukuhan Klangon. Semoga kehadiran kami
tidak merepotkan para penghuni padukuhan.”
“O, tidak..tidak,” jawab Ki Jagabaya
dengan serta merta, “Marilah kita berangkat sebelum hujan benar-benar
turun,” Ki Jagabaya berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Apakah kami
dapat meminjam salah satu kuda kalian untuk membawa jasad orang itu?”
“O, tentu..tentu,” dengan tergopoh-gopoh
Ki Waskita segera menyerahkan kendali kudanya, “Kami akan berjalan kaki
bersama-sama kalian ke banjar padukuhan.”
“Terima kasih,” jawab Ki Jagabaya sambil menerima kendali kuda.
Sejenak kemudian, salah satu penghuni
padukuhan Klangon segera menaikkan jasad itu ke atas punggung kuda Ki
Waskita. Setelah menerima kendali kuda dari Ki Jagabaya, dengan perlahan
kuda itu pun dihelanya maju. Sementara dua orang menjaga di kiri kanan
jasad yang terlelungkup di atas punggung kuda itu.
Demikianlah iring-iringan itu pun segera
bergerak menuju ke banjar padukuhan Klangon. Sepanjang jalan hampir
tidak ada seorang pun yang berbicara. Masing-masing sedang sibuk dengan
angan-angan mereka sendiri-sendiri. Sementara di langit sesekali
terdengar petir bersabung disertai dengan air hujan yang mulai turun
menetes satu persatu.
Rombongan itu segera mempercepat langkah
mereka. Ketika titik-titik hujan mulai terasa semakin deras, beberapa
orang bahkan telah mulai berlari-lari kecil.
Untunglah banjar padukuhan itu sudah
mulai terlihat di ujung kelokan jalan. Begitu mereka mencapai pendapa
banjar padukuhan, jasad itu segera diangkat dan kemudian diletakkan di
tengah-tengah pendapa. Sejenak kemudian, hujan pun turun bagaikan
dicurahkan dari langit.
“Marilah Ki Sanak sekalian,” berkata Ki
Jagabaya kemudian kepada Ki Waskita, “Biarlah kuda-kuda kalian dirawat
oleh penjaga banjar ini,” Ki Jagabaya berhenti sejenak. Lanjutnya
kemudian, “Bukankah kalian sudah mengambil perbekalan masing-masing?”
“Sudah Ki Jagabaya,” jawab Ki Waskita
sambil menunjukkan buntalan pakaian di tangan kirinya diikuti oleh yang
lainnya, “Jika diijinkan kami akan membersihkan diri terlebih dahulu
sebelum berganti pakaian.”
“Silahkan, silahkan,” sahut Ki Jagabaya
cepat, “Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, kalian dapat
beristirahat di ruang dalam banjar. Aku akan mempersiapkan pemakaman
jenazah sambil menunggu hujan reda.”
Demikianlah kelima orang itu segera
memasuki banjar padukuhan Klangon. Seorang yang berpakaian serba hitam
dengan rambut yang sudah mulai memutih telah menunjukkan ruang dalam
tempat mereka untuk beristirahat.
Untuk beberapa saat mereka masih menunggu
hujan agak mereda untuk pergi ke pakiwan secara bergantian. Kesempatan
itu digunakan oleh Ki Rangga untuk membicarakan rencana mereka
selanjutnya.
“Kelihatannya sekarang ini kita diterima
sebagai tamu,” berkata Ki Rangga memulai pembicaraan, “Namun aku merasa
kita selalu diawasi sehingga kita ini seperti menjadi tawanan saja.”
“Angger benar,” sahut Ki Waskita, “Aku
tadi sempat melihat beberapa pengawal padukuhan Klangon telah
berdatangan bersamaan dengan turunnya hujan.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam
sambil memandang ke arah Glagah Putih. Agaknya Glagah Putih pun tanggap
dengan maksud kakak sepupunya itu. Maka katanya kemudian sambil bangkit
berdiri, “Aku akan melihatnya kakang.”
“Berhati-hatilah,” hampir bersamaan Ki Rangga dan Ki Jayaraga berpesan.
“Ya Guru,” jawab Glagah Putih sambil melangkah ke pintu.
Begitu bayangan Glagah Putih hilang di balik pintu, Ki Rangga pun segera meneruskan kata-katanya.
“Malam ini kita akan membagi tugas untuk
menyelidiki padukuhan ini,” Ki Rangga berhenti sejenak. Lanjutnya
kemudian, “Kita ingin mengetahui, sejauh mana padukuhan ini telah
terpengaruh oleh bujukan orang-orang yang mengaku Trah Sekar Seda
Lepen.”
“Kemungkinan itu memang ada. Ngger,”
berkata Ki Waskita menanggapi, “Terbukti salah satu petugas sandi
Mataram telah menjadi korban.”
“Agaknya mereka juga senang bermain-main dengan racun,” Ki Jayaraga memberikan pendapatnya.
Sejenak Ki Rangga terdiam. Tanpa sadar
dia berpaling ke arah Ki Bango Lamatan yang terlihat hanya menundukkan
kepalanya dalam-dalam.
“Apakah Ki Bango Lamatan mempunyai sebuah
gagasan?,” tiba-tiba Ki Rangga mengajukan sebuah pertanyaan yang
membuyarkan lamunan Ki Bango Lamatan.
Untuk sejenak Ki Bango Lamatan masih
menarik nafas dalam sambil menegakkan punggungnya. Jawabnya kemudian,
“Ki Rangga, kedudukanku dalam kelompok ini hanyalah sebagai pelengkap.
Aku dititipkan oleh Pangeran Pati atas persetujuan KI Patih Mandaraka.
Sehingga apapun rencana Ki Rangga, aku akan mengikutinya.”
“Ah,” desah Ki Rangga sambil tertawa
pendek, “Aku ditunjuk sebagai pemimpin kelompok ini bukan berarti aku
mempunyai kekuasan mutlak untuk menjalankan rencana sesuai dengan hasil
pemikiranku sendiri. Setiap anggota di dalam kelompok ini berhak untuk
mengajukan pendapatnya.”
“Ki Rangga benar,” sahut Ki Jayaraga
cepat, “Setiap orang dalam kelompok ini dapat mengusulkan sebuah rencana
yang disesuaikan dengan keadaan. Rencana manakah yang akan kita pakai
nantinya, tergantung dari hasil kesepakatan kita.”
Semua yang hadir di ruangan itu mengangguk-anggukkan kepala mereka tak terkecuali Ki Bango Lamatan.
Pembicaraan itu terhenti ketika terdengar
pintu berderit dan Glagah Putih muncul dari balik pintu. Sementara
hujan di luar kelihatannya sudah mulai mereda. Bunyi air hujan yang
memukul-mukul atap banjar padukuhan sudah tidak sekeras dan sesering
seperti beberapa saat tadi.
“Masuklah,” berkata Ki Rangga begitu
melihat adik sepupunya itu masih termangu-mangu di tengah-tengah pintu,
“Apakah engkau melihat sesuatu yang perlu mendapat perhatian?”
“Jenazah itu akan diberangkatkan,” jawab
Glagah Putih sambil melangkah mendekat dan kemudian duduk di sebelah
gurunya, “Banjar ini rasa-rasanya telah terkepung dari segala penjuru.
Aku melihat banyak pengawal yang berjaga-jaga di seputar banjar.”
“Apakah tidak sebaiknya kita ikut mengantarkan jenazah itu, ngger?” sela Ki Waskita sambil berpaling ke arah Ki Rangga.
Sejenak Ki Rangga termenung. Namun
jawabnya kemudian, “Aku kira tidak perlu Ki Waskita. Kita tidak usah
menunjukkan kedekatan kita dengan orang yang sudah meninggal itu.
Sebaiknya kita tetap di banjar ini.”
Hampir bersamaan mereka yang hadir di ruangan itu telah menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk.
Untuk sejenak mereka yang berada di dalam
ruang itu terdiam. Sementara bunyi titik-titik air hujan yang menimpa
atap banjar padukuhan sudah tidak terdengar lagi. Berkata Ki Rangga
kemudian, “Nah, hujan sudah benar-benar reda. Siapakah yang akan ke
pakiwan terlebih dahulu?”
Tanpa menunggu jawaban yang lainnya,
ternyata Glagah Putih telah berdiri kembali. Sambil melangkah ke pintu
dia berkata, “Aku akan menimba air terlebih dahulu. Silahkan jika ada
yang akan membersihkan diri.”
“Benar-benar anak yang baik,” sahut Ki Jayaraga yang disambut gelak tawa oleh yang lainnya.
Demikianlah ketika Glagah Putih kemudian
membuka pintu butulan dan turun ke halaman belakang, secara tidak
mencolok tampak beberapa pengawal duduk-duduk bergerombol di teritisan
sebelah kiri sambil bersenda-gurau. Di hadapan mereka tampak beberapa
mangkuk minuman panas dan penganan.
Glagah Putih pura-pura tidak
memperhatikan mereka. Diayunkan langkahnya menuju ke perigi. Setelah
melepas tali senggot yang diikatkan pada sebatang bambu yang ditancapkan
di sebelah perigi, sejenak kemudian Glagah Putih pun telah tenggelam
dalam keasyikannya menimba air.
Dalam pada itu, di pendapa banjar
padukuhan jenazah petugas sandi Mataram itu telah diberangkatkan.
Beberapa orang penghuni padukuhan Klangon tampak ikut mengantar jenazah
itu ke tanah pekuburan bersama dengan beberapa pengawal padukuhan.
Selain pengawal padukuhan Klangon, Ki Jagabaya pun tampak ikut berjalan
di antara mereka.
Tiba-tiba seseorang yang rambutnya sudah
putih semua dengan memakai ikat kepala yang agak rendah tanpa menarik
perhatian telah berjalan menjajari langkah Ki Jagabaya.
“Ki Jagabaya,” bisik orang itu, “Apakah benar ada lima orang yang bermalam di banjar sekarang ini?”
Ki Jagabaya terkejut. Dengan cepat dia
segera berpaling. Sejenak Ki Jagabaya ragu-ragu, dia hampir tidak
mengenali orang itu. Namun ketika orang itu kemudian tersenyum ke
arahnya, barulah Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam.
“Benar Ki Gede,” jawab Ki Jagabaya kemudian juga dengan berbisik sambil mengiringi langkah orang yang dipanggilnya Ki Gede itu.
Orang yang dipanggil Ki Gede itu tampak
mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil memandang ke titik-titik di
kejauhan dia berdesis, “Usahakan untuk mengetahui jati diri mereka.
Agaknya mereka itu orang-orang yang sedang menyamar. Tidak menutup
kemungkinan mereka adalah para petugas sandi Mataram. Aku memerlukan
datang ke sini untuk bisa bertemu dengan mereka. Mudah-mudahan dugaanku
ini tidak keliru, namun jangan sampai menimbulkan kesan kepada para
pengikut Raden Mas Harya Surengpati yang banyak tersebar di padukuhan
ini.”
“Akan aku usahakan, Ki Gede,” sahut Ki
Jagabaya, “Namun aku tidak yakin jika mereka itu para petugas sandi
Mataram yang sedang menyamar. Jika mereka adalah para prajurit sandi
Mataram, beberapa di antaranya sudah terlalu tua untuk disebut sebagai
seorang prajurit.”
Orang yang dipanggil Ki Gede itu tertawa
pendek sehingga orang-orang yang berjalan di depannya telah berpaling
sekilas. Namun Ki Gede tidak mempedulikan mereka. Lanjutnya kemudian,
“Mungkin yang tua-tua itu adalah para prajurit yang sudah purna namun
tenaganya masih dibutuhkan sehingga tidak menutup kemungkinan mereka
diperbantukan dalam tugas rahasia ini,” Ki Gede berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian, “Apakah para penghuni padukuhan Klangon ini ada yang
dapat mengenali aku?”.
Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Sambil
mengedarkan pandangan matanya ke sekitarnya, dengan nada sedikit ragu
dia menjawab, “Sejauh ini belum ada yang mengenali dan memperhatikan Ki
Gede. Dalam pakaian yang sangat sederhana ini, kemungkinannya sangat
kecil untuk mengenal Ki Gede. Kecuali orang-orang terdekat yang sudah
terbiasa bergaul dengan Ki Gede.”
Orang yang dipanggil Ki Gede itu
mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan Ki Jagabaya. Dalam
hati dia membenarkan pendapat Ki Jagabaya itu. Betapapun sempurnanya dia
melakukan penyamaran, namun orang-orang terdekatnya terutama istri dan
kedua anaknya tentu dapat mengenali dari bentuk tubuh, gerak-gerik serta
hal-hal lain yang tidak pernah terbaca oleh orang lain kecuali hanya
keluarga terdekatnya saja.
Untuk beberapa saat mereka berdua
terdiam. Masing-masing tenggelam dalam angan-angan tentang kelima orang
asing itu. Sementara langkah-langkah mereka telah semakin mendekati
tanah pekuburan.
“Usahakan mereka tidak keluar dari banjar
malam ini,” berkata Ki Gede kemudian ketika iring-iringan jenazah itu
sudah memasuki gerbang tanah pekuburan, “Apapun yang akan terjadi, aku
akan menemui mereka. Aku sudah muak dengan segala tingkah polah para
pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu.”
Ki Jagabaya yang berjalan di samping Ki
Gede tampak mengerutkan keningnya. Jawabnya kemudian, “Bagaimana jika
dugaan Ki Gede justru sebaliknya? Mereka ternyata justru utusan Raden
Wirasena yang selama ini belum pernah kita lihat? Atau bahkan tidak
menutup kemungkinan justru salah satu dari mereka itu adalah Raden
Wirasena sendiri.”
Berdesir jantung Ki Gede. Kemungkinan itu
memang ada. Dan jika kemungkinan itulah yang akan terjadi, tentu
lehernya sendiri yang akan menjadi taruhannya.
Untuk beberapa saat kedua orang itu
kembali terdiam sambil berjalan di antara sela-sela batu nisan. Ketika
iring-iringan itu kemudian berhenti di depan liang lahat yang telah
disediakan, kedua orang itu pun segera menepi dan berdiri di bawah
sebatang pohon Kamboja.
“Apakah kita akan mendekat, Ki Gede?” bertanya Ki Jagabaya kepada Ki Gede yang berdiri di sebelahnya.
“Tidak perlu,” jawab Ki Gede, “Aku
khawatir jika terlalu dekat dengan mereka, mungkin salah satu dari
mereka akan ada yang mengenaliku.”
Ki Jagabaya tersenyum. Katanya kemudian,
“Sudah aku katakan tadi, penyamaran Ki Gede cukup sempurna. Namun jika
Ki Gede berbicara, tentu orang akan dapat mengenali Ki Gede dari suara
itu.”
Ki Gede tersenyum, betapapun masamnya.
Katanya kemudian, “Untuk itulah kita tidak perlu mendekat. Jika
seseorang kemudian bertanya sesuatu kepadaku, walaupun tanpa kesengajaan
dan maksud tertentu, tentu aku akan mengalami kesulitan untuk
menyembunyikan suaraku yang asli.”
Ki Jagabaya kembali tersenyum. Sambil
melemparkan pandangan matanya ke arah kerumunan orang di seputar liang
lahat itu, dia kemudian bergumam perlahan seolah-olah ditujukan kepada
dirinya sendiri, “Siapakah sebenarnya orang itu? Dia mati tanpa
meninggalkan ciri-ciri yang dapat dijadikan sebagai pancadan untuk
menelusuri jati dirinya.”
Ki Gede yang mendengar gumam Ki Jagabaya
telah menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya kemudian, “Tentu bukan
pengikut Trah Sekar Seda Lepen. Aku justru cenderung menduga dia adalah
salah satu dari petugas sandi yang telah disebar oleh Mataram.
Kemungkinannya orang itu ada hubungannya dengan kedatangan kelima orang
yang sekarang berada di banjar.”
Ki Jagabaya mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar dugaan Ki Gede. Namun semua dugaan itu masih harus dibuktikan.
Demikianlah ketika liang lahat itu telah
selesai ditimbun tanah dan seseorang yang dianggap sesepuh padukuhan
Klangon telah selesai memanjatkan doa, orang-orang yang hadir di tanah
pekuburan itu pun segera membubarkan diri.
“Marilah Ki Gede,” berkata Ki Jagabaya kemudian sambil melangkahkan kakinya, “Sebaiknya kita ikut meninggalkan tempat ini.”
Ki Gede mengangguk sambil melangkahkan
kakinya. Ketika pandangan matanya melihat beberapa pengawal padukuhan
yang berjalan beriringan sambil bersenda gurau, Ki Gede pun segera
membisikkan sebuah pertanyaan kepada Ki Jagabaya.
“Mengapa begitu banyak pengawal yang
datang melayat? Aku tadi juga sempat melihat banyak pengawal yang
bersiaga di banjar padukuhan. Apakah ini ada hubungannya dengan
kedatangan kelima orang itu?”
Ki Jagabaya menggeleng. Jawabnya
kemudian, “Aku tidak tahu, Ki Gede. Mungkin Ki Dukuh telah mendapat
laporan dan menyuruh para pengawal padukuhan untuk bersiaga.”
Ki Gede menarik nafas panjang. Bertanya
Ki Gede kemudian, “Apakah Ki Dukuh Klangon masih sering mengadakan
hubungan dengan pengikut Trah Sekar Seda Lepen?”
K Jagabaya mengangguk sambil berdesis,
“Orang yang mengaku bernama Raden Mas Harya Surengpati itulah yang
sering mengunjungi Ki Dukuh dan kemudian membuat hubungan kerja sama dan
janji-janji dengan mengatas-namakan kakaknya, Raden Wirasena.”
Ki Gede kembali menarik nafas dalam-dalam
sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya kemudian, “Agaknya Ki
Dukuh Klangon telah termakan janji-janji dari Raden Mas Harya
Surengpati.”
“Kemungkinannya memang demikian Ki Gede,” sahut Ki Jagabaya.
“Apakah semua perangkat padukuhan telah terpengaruh?” bertanya Ki Gede selanjutnya.
Ki Jagabaya menggeleng, “Aku tidak tahu
Ki Gede. Yang jelas aku tetap bersetia kepada Mataram. Namun hal ini
tidak aku tunjukkan dengan semata-mata. Aku masih memikirkan keselamatan
keluargaku.”
Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya.
Pertimbangan yang sangat berat adalah permasalahan yang menyangkut
keluarga. Bagaimanapun juga jika keluarga terancam keselamatannya, tentu
akan berpikir seribu kali untuk menentang pengaruh para pengikut Trah
Sekar Seda Lepen itu.
Tak terasa langkah mereka telah sampai di persimpangan jalan. Kedua orang itu pun kemudian memutuskan untuk segera berpisah.
“Kita bertemu lagi saat sirep uwong,”
berkata Ki Gede, “Aku akan berusaha memasuki banjar lewat belakang. Aku
akan menunggu di dekat perigi. Lontarkanlah sebuah isyarat jika memang
kelima orang itu berada di pihak kita. Namun jika ternyata kelima orang
itu justru orang-orangnya Raden Mas Harya Surengpati, aku harus segera
menyelamatkan diri.”
“Baik Ki Gede,” jawab Ki Jagabaya.
Demikianlah akhirnya kedua orang itu pun
kemudian segera berpisah. Ki Gede dengan langkah yang tergesa-gesa telah
mengambil jalur jalan yang lurus untuk meninggalkan tempat itu,
sementara dengan langkah satu-satu Ki Jagabaya mengambil jalur jalan
yang satunya untuk kembali menuju ke banjar padukuhan.
Dalam pada itu, walaupun hujan telah
berhenti, namun di langit masih menyisakan mendung yang bergelayutan.
Matahari tidak menampakkan sinarnya sama sekali. Walaupun hari belum
menjelang petang, namun suasananya benar-benar sudah seperti menjelang
malam.
Di banjar padukuhan, Ki Rangga dan
kawan-kawannya telah selesai membersihkan diri dan berganti pakaian.
Mereka pun kemudian segera berkumpul kembali di ruang dalam, ruang yang
diperuntukkan bagi mereka untuk bermalam.
“Sebentar lagi Matahari akan terbenam,”
berkata Ki Rangga kemudian sambil membetulkan letak duduknya, “Selepas
makan malam sebaiknya kita menyusun rencana.”
“Ya ngger,” jawab Ki Waskita, “Aku
menyarankan sebagian dari kita duduk-duduk saja di pendapa. Siapa tahu
Ki Jagabaya berkenan hadir dan menemani kita berbincang.”
“Ya, aku setuju,” sahut Ki Jayaraga,
“Sementara sebagian dari kita berbincang di pendapa, yang lainnya
melakukan penyelidikan di padukuhan Klangon ini.”
“Tepatnya di sekitar rumah Ki Dukuh Klangon,” dengan serta-merta Glagah Putih mengajukan sebuah usul.
Semua orang menengok ke arah suami Rara Wulan itu. Ki Rangga lah yang kemudian bertanya, “Apa pertimbanganmu Glagah Putih?”
Glagah Putih menggeser duduknya
sejengkal. Jawabnya kemudian, “Aku mempunyai dugaan, jika padukuhan ini
telah terpengaruh oleh orang-orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda
Lepen, tentu dimulai dari pemimpinnya , dalam hal ini adalah Ki Dukuh.”
Mereka yang hadir mengangguk-anggukkan
kepala pertanda setuju dengan pendapat Glagah Putih kecuali Ki Bango
Lamatan. Berkata Ki Bango Lamatan kemudian, “Belum tentu Ki Dukuh telah
terpengaruh oleh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen. Bisa saja Ki Dukuh
sedang dalam tekanan dan ancaman orang-orang terdekatnya yang telah
terpengaruh terlebih dahulu. Jika hal ini yang terjadi, kita harus
melindungi Ki Dukuh.”
Kembali mereka mengangguk-angguk. Berkata
Ki Rangga kemudian, “Kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan
sebaiknya kita memang mengadakan penyelidikan di sekitar rumah Ki Dukuh
Klangon.”
“Benar, ngger,” Ki Waskita menambahi,
“Namun harus tetap kita usahakan jangan sampai jati diri kita terungkap.
Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai apa yang terjadi nantinya di
padukuhan Klangon ini akan membangunkan perguruan Sapta Dhahana yang
selama ini masih belum menyadari akan kehadiran kita.”
Untuk beberapa saat mereka terdiam.
Memang sasaran mereka yang utama adalah memutus hubungan antara
perguruan Sapta Dhahana dengan orang-orang yang menyebut dirinya Trah
Sekar Seda Lepen. Namun agaknya pengaruh itu sudah cukup meluas sehingga
telah sampai di padukuhan Klangon tempat mereka bermalam.
“Marilah,” tiba-tiba Ki Waskita berkata
memecah kesunyian, “Matahari sudah terbenam dan sudah terdengar
panggilan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Yang Maha Agung.”
Hampir bersamaan mereka
mengangguk-angguk. Secara bergantian mereka pun kemudian memerlukan
pergi ke pakiwan untuk mensucikan diri sebelum menunaikan kewajiban
sebagai tanda syukur atas nikmat dan karunia dari Sang Maha Pencipta.
Dalam pada itu Ki Gede yang sedang
menyusuri bulak panjang yang menghubungkan padukuhan Klangon dengan
Tanah Perdikan Matesih telah dikejutkan oleh kehadiran seseorang di atas
tanggul.
Pada awalnya Ki Gede menduga orang itu
hanyalah seorang petani yang sedang melepaskan lelah sehabis membenahi
sawahnya. Musim hujan memang telah datang dan agaknya para petani sudah
mulai ancang-ancang untuk menggarap sawah mereka kembali.
“Mungkin hanya seorang petani yang
kebetulan belum pulang dari sawahnya,” berkata Ki Gede dalam hati sambil
memandang bayangan hitam yang berdiri di atas tanggul sebelah kiri
beberapa puluh tombak di depan. Matahari memang baru saja terbenam namun
karena langit masih menyisakan mendung yang bergelayutan, sehingga
suasana pun terlihat cukup gelap.
“Mengapa akhir-akhir ini aku menjadi
cepat berprasangka buruk terhadap seseorang.?” bertanya Ki Gede dalam
hati sambil terus mengayunkan langkah, “Mungkin kehadiran orang-orang
yang mengaku pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu yang membuatku selalu
bercuriga.”
Ketika langkah Ki Gede semakin dekat
dengan orang yang berdiri di atas tanggul itu, jantung Ki Gede pun
berdentang semakin keras. Orang itu tidak tampak sebagaimana petani
biasanya yang memanggul cangkul di pundaknya dan menyelipkan sabit di
pinggangnya. Orang itu justru telah berdiri sambil bertolak pinggang dan
terlihat dengan sengaja memang sedang menunggu kedatangannya.
“Apa boleh buat,” geram Ki Gede dalam
hati sambil meraba pinggangnya. Ketika tangan kanannya menyentuh sebuah
keris pusaka turun-temurun kebanggaan Tanah Perdikan Matesih yang
terselip di pinggang kanannya, hatinya pun menjadi sedikit tenang.
Dengan langkah satu-satu Ki Gede berjalan
terus tanpa meninggalkan kewaspadaan. Malam yang baru saja mulai itu
terasa sangat sepi. Hanya terdengar suara binatang-binatang malam yang
mulai memperdengarkan nyanyian dalam irama ajeg. Sementara di langit
yang kelam kelelawar dan burung-burung malam mulai beterbangan hilir
mudik mencari mangsa.
Semakin dekat jarak Ki Gede dengan orang
di atas tanggul itu, jantung Ki Gede pun rasa-rasanya telah berpacu
semakin kencang. Betapa pun Ki Gede berusaha menepis syak wasangka di
dalam hatinya, namun sikap orang di atas tanggul itu memang terasa
sangat mendebarkan.
Ternyata apa yang menjadi dugaan Ki Gede
itu benar adanya. Ketika jarak mereka berdua tinggal beberapa langkah
lagi, tiba-tiba terdengar suara tawa perlahan dan tertahan-tahan dari
orang yang berdiri di atas tanggul itu. Agaknya itu adalah sebuah
isyarat bahwa orang di atas tanggul itu memang sengaja menunggu Ki Gede.
Maka Ki Gede pun segera menghentikan langkahnya.
Sejenak suasana menjadi sunyi. Sudah
tidak terdengar lagi suara tawa yang memuakkan itu. Masing-masing
terlihat saling menahan diri dan menunggu apa yang akan terjadi
selanjutnya. Diam-diam Ki Gede telah menggeser kedudukan keris pusakanya
ke depan. Tangan kanannya pun telah menggenggam hulu keris itu, siap
untuk menghadapi segala kemungkinan.
Suasana benar-benar sangat mencekam.
Masing-masing mencoba menilai keadaan, namun tidak ada yang berani
mengambil keputusan untuk bergerak terlebih dahulu. Masing-masing hanya
menunggu dan menunggu.
Tiba-tiba suasana yang mencekam itu telah
dipecahkan kembali oleh suara tawa orang yang berdiri di atas tanggul
itu. Suara tawa yang terdengar dalam nada rendah dan berkepanjangan.
Benar-benar sebuah tawa yang terdengar sangat memuakkan di telinga Ki
Gede.
“Diam!” tiba-tiba Ki Gede yang sudah tidak dapat menahan hatinya itu telah membentak dengan suara yang menggelegar.
Orang di atas tanggul itu tampak terkejut
dan segera menghentikan tawanya. Untuk beberapa saat dia hanya dapat
berdiri diam termangu-mangu.
“Apakah Ki Gede merasa terganggu?” tiba-tiba orang di atas tanggul itu bertanya. Suaranya terdengar sangat berat dan dalam.
Berdesir dada Ki Gede mendengar
pertanyaan itu. Orang itu agaknya telah mengenal dirinya. Jantung Ki
Gede pun menjadi semakin berdebaran.
Ki Gede tidak segera menjawab. Dicobanya
untuk mengenali bayangan yang berdiri bertolak pinggang di atas tanggul
itu. Namun kegelapan yang menyelimuti tempat itu telah menghalangi Ki
Gede untuk melihat wajahnya dengan jelas, walaupun Ki Gede telah
mengerahkan kemampuannya untuk menajamkan pandangan matanya.
“Bagaimana Ki Gede?” kembali terdengar
suara orang di atas tanggul itu, “Mengapa Ki Gede diam saja?” orang itu
berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Ki Gede tidak perlu menghunus
pusaka kebesaran Tanah Perdikan Matesih. Tidak akan banyak berarti
bagiku.”
“Sombong!” sergah Ki Gede dengan serta
merta. Namun dalam hati Ki Gede mengakui ketajaman mata orang itu. Maka
katanya kemudian sambil melepaskan pegangan pada hulu kerisnya dan
menunjuk ke arah orang itu, “Turunlah! Jangan menjadi pengecut yang
hanya berani bertempur dari atas tanggul. Jika Ki Sanak tetap bertahan,
jangan salahkan aku jika aku akan memaksamu turun dengan caraku.”
“O?” terdengar orang itu kembali tertawa,
tawa yang memuakkan, “Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa aku
untuk turun dari tanggul ini. Ki Gede Matesih pun tidak,” orang itu
berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Kalau Ki Gede tidak percaya,
silahkan! Aku berjanji tidak akan menggerakkan tubuhku untuk melawan
atau pun menghindar, walaupun hanya ujung ibu jari kakiku.”
Kata-kata itu benar-benar telah membuat
darah Ki Gede mendidih. Rasa-rasanya kemarahan Ki Gede telah sampai ke
ubun-ubun. Sebuah penghinaan yang luar biasa telah dengan sengaja
ditujukan kepada dirinya, penguasa tertinggi Tanah Perdikan Matesih.
Dengan menggeram marah Ki Gede segera
memusatkan segenap nalar dan budinya untuk mengungkapkan puncak ilmu
warisan turun-temurun leluhur Perdikan Matesih. Sebuah ilmu yang
bersumber dari perguruan Pandan Alas dari cabang Gunung Kidul. Namun
dalam perkembangannya, sepeninggal Ki Demang Sarayudha, murid pertama Ki
Ageng Pandan Alas, ilmu cabang Perguruan Ki Pandan Alas itu telah
mengalami kemunduran yang cukup memprihatinkan.
Segera saja Ki Gede bergeser ke samping
setapak. Wajahnya terangkat dan matanya menjadi redup setengah terpejam.
Disalurkan segala tenaganya yang dilambari dengan pemusatan pikiran
untuk kemudian meletakkan satu tangannya di atas dada, sedangkan tangan
lainnya menjulur ke depan lurus-lurus. Itulah suatu sikap untuk
melepaskan ilmunya yang dahsyat, ilmu pamungkas Cundha Manik dari
Perguruan Pandan Alas.
Orang di atas tanggul itu terkejut begitu
menyadari Ki Gede telah mengungkapkan ilmu pamungkasnya. Namun
sebagaimana janji yang telah diucapkan sebelumnya, orang di atas tanggul
itu tidak akan menggerakkan tubuhnya untuk melawan atau pun menghindar,
walaupun hanya ujung ibu jari kakinya.
Sejenak kemudian terdengar teriakan
menggelegar dari Ki Gede. Tubuhnya melesat bagaikan tatit yang meloncat
di udara. Tangan kanan yang terjulur lurus itu dengan kekuatan penuh
menghantam dada orang yang berdiri di atas tanggul itu.
Akibatnya sangat dahsyat. Tubuh Ki Gede
bagaikan membentur dinding baja setebal satu jengkal. Kekuatan yang
tersalur pada telapak tangan kanannya membalik membentur dadanya sendiri
sehingga tubuhnya terpental ke belakang dan melayang jatuh terjerembab
di tanah yang berdebu. Terdengar sebuah keluhan pendek sebelum akhirnya
Ki Gede jatuh pingsan.
Sedangkan orang yang berdiri di atas
tanggul itu sejenak bagaikan membeku di tempatnya. Walaupun kekuatan aji
Cunda Manik itu tidak mampu menggetarkan tubuhnya, namun untuk beberapa
saat jalan nafasnya terasa bagaikan telah tersumbat.
“Sayang,” desis orang itu sambil menarik
nafas dalam-dalam untuk melonggarkan dadanya, “Aji Cunda Manik ini
tinggal kulitnya saja. Seandainya Ki Gede mampu mendalami dan
mematangkannya, menghadapi orang yang menyebut dirinya Raden Mas Harya
Surengpati itu bukanlah suatu hal yang menakutkan.”
Dengan perlahan orang itu pun kemudian melangkahkan kakinya menuruni tanggul.
“Seandainya Ki Ageng Pandan Alas masih
hidup dan beliau sendiri yang melontarkan Aji Cunda Manik ini, aku tidak
yakin kalau aku akan mampu bertahan,” gumam orang itu kemudian sambil
melangkah ke tempat Ki Gede terbaring.
Sesampainya orang itu di sebelah tubuh Ki
Gede, segera saja dia mengambil tempat di sebelah kirinya dan kemudian
duduk bersila di atas tanah yang berdebu.
Untuk beberapa saat orang itu masih
merenungi tubuh Ki Gede yang terbujur diam. Kemudian dengan perlahan
dirabanya pergelangan tangan Ki Gede, kemudian berpindah ke dada dan
terakhir orang itu memiringkan tubuh Ki Gede untuk meraba punggungnya.
“Untung hanya pingsan saja,” desis orang
itu, “Tidak ada luka dalam. Semoga ini menjadi pelajaran bagi Ki Gede
untuk memacu semangatnya dalam mendalami dan menyempurnakan ilmu
kebanggaan Perguruan Pandan Alas ini.”
Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya,
orang itu pun kemudian mulai memijat tengkuk Ki Gede. Sejenak kemudian,
terdengar keluhan tertahan yang keluar dari mulut Ki Gede.
“Ki Gede,” desis orang itu perlahan
ketika melihat Ki Gede mulai membuka kedua matanya, “Tidak ada yang
perlu dirisaukan. Anggap saja apa yang baru saja terjadi ini adalah
bentuk dari perkenalan kita.”
Ki Gede yang belum menemukan kesadarannya
secara utuh itu tidak menjawab. Pendengaran dan penglihatannya belum
pulih dan bekerja sebagaimana biasa. Sementara dadanya terasa nyeri dan
tulang-tulang rusuknya bagaikan berpatahan.
“Duduklah Ki Gede,” bisik orang itu sambil membantu menyangga punggung Ki Gede.
Ki Gede masih berusaha memperjelas
penglihatan kedua matanya. Dengan mengerjap-kerjapkan kelopak kedua
matanya beberapa kali, akhirnya penglihatan Ki Gede pun menjadi semakin
terang dan jelas.
Begitu kesadarannya mulai pulih kembali,
tanpa sadar Ki Gede telah berpaling. Namun alangkah terkejutnya Ki Gede.
Darahnya bagaikan tersirap sampai ke ubun-ubun begitu kedua matanya
menatap wajah orang yang berada di sebelah kirinya itu.
Kalau saja Ki Gede tidak menguatkan
hatinya, tentu dia sudah berteriak ketakutan melihat raut wajah orang
yang berada di sebelahnya itu. Seraut wajah yang rata, tidak tampak
adanya sepasang mata, hidung atau pun mulut. Seraut wajah yang
benar-benar tampak mengerikan.
Namun Ki Gede bukanlah anak kemarin sore
yang ketakutan seperti melihat orang-orangan pengusir burung di sawah.
Menurut dugaannya, orang itu pasti menggunakan sejenis topeng tipis dari
kulit binatang yang disamak dengan halus sehingga terlihat seperti
kulit wajah manusia. Berpikir sampai disitu, dengan mengendapkan hatinya
yang sempat bergejolak, Ki Gede pun segera bergerak meraih topeng yang
menutupi wajah orang itu.
Namun sebelum tangan Ki Gede sempat
meraih wajah orang itu, tiba-tiba saja dirasakan sekujur tubuhnya
menjadi lemas tak bertenaga. Tulang-belulangnya pun bagaikan terlepas
dari persendian. Bersamaan dengan itu, terasa telapak tangan orang
bertopeng itu mengusap tengkuknya.
Sejenak kemudian, Ki Gede merasakan
kantuk yang luar biasa beratnya dan tak tertahankan.. Namun sebelum Ki
Gede jatuh tertidur, terdengar orang bertopeng itu membisikkan sesuatu
di telinganya.
Demikianlah akhirnya, Ki Gede yang telah
siuman dari pingsannya itu telah tak sadarkan kembali, namun kali ini Ki
Gede merasakan ketenangan yang luar biasa dalam tidurnya.
Ketika Ki Gede kemudian terbangun dari
tidur nyenyaknya, dia mendapatkan dirinya sedang terbaring di bawah
sebatang pohon di sebelah perigi.
“He?” desis Ki Gede sambil bangkit dan bertelekan pada kedua tangannya, “Di mana aku? Apa sebenarnya yang telah terjadi?”
Perlahan-lahan Ki Gede mencoba merangkai
ingatannya kembali. Segera saja ingatan Ki Gede tertuju pada seraut
wajah yang mengerikan, wajah yang tampak rata tak berbentuk bagaikan
sebuah dinding batu saja.
“Mengapa orang bertopeng itu membawaku
kemari?” bertanya Ki Gede dalam hati sambil memperbaiki duduknya, “Orang
yang aneh, namun kesaktiannya benar-benar ngedab-edabi,” Ki Gede
berhenti berangan-angan sejenak. Kemudian lanjutnya, “Atau aku saja yang
terlalu malas untuk mendalami Aji Cunda Manik?”
Berpikir sampai disitu, tiba-tiba saja
terbesit niat di dalam hati Ki Gede untuk menjalani laku yang sudah
ditentukan dalam menyempurnakan puncak ilmunya.
“Namun guru sudah lama meninggal,”
kembali Ki Gede berangan-angan, “Aku tidak berani menjalani laku
terakhir itu tanpa bimbingan seorang guru.”
Niat yang sudah menggebu-gebu di dalam
hatinya itu tiba-tiba saja surut kembali bagaikan sinar sebuah dlupak
yang kehabisan minyak.
“Ah, sudahlah,” desah Ki Gede kemudian,
“Itu akan aku pikirkan kemudian. Kelihatannya sekarang sudah mendekati
waktu sepi uwong. Aku telah berjanji dengan Ki Jagabaya untuk bertemu di
banjar.”
Sambil berpegangan pada sebatang pohon
sawo kecik di sebelahnya, Ki Gede pun kemudian mencoba untuk bangkit.
Diedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya sambil mengibas-kibaskan
kain panjangnya yang menjadi sedikit kotor. Hujan memang telah berhenti
sejak sore tadi, namun tanah tempat Ki Gede terbaring masih terasa
basah.
“Hem,” desah Ki Gede sambil
mengamat-amati lampu dlupak yang disangkutkan di teririsan. Tampak
beberapa orang pengawal sedang tidur silang melintang. Bahkan ada yang
bersandaran tiang di teritisan itu.
“Banjar padukuhan Klangon,” desis Ki Gede
dalam hati dengan jantung yang berdebaran begitu mengenali tempat itu,
“Para pengawal itu seharusnya berjaga-jaga, namun mengapa mereka justru
telah tertidur?”
Dengan tetap tidak meninggalkan kewaspadaan, ki Gede pun mulai melangkahkan kakinya menuju banjar padukuhan.
“Mereka tidur dalam keadaan tidak
sewajarnya,” kembali Ki Gede berkata dalam hati begitu dia sampai di
dekat teritisan, “Sebaiknya aku tidak perlu mengusik mereka. Aku akan
masuk dan menemui kelima perantau itu.”
Dengan sedikit bergegas Ki Gede pun segera membuka pintu butulan dan melangkahkan kakinya memasuki dapur.
Di dalam dapur itu ternyata tidak ada
sebuah dlupak pun yang menyala sehingga suasana benar-benar gelap.
Untunglah Ki Gede bukan orang kebanyakan. Dengan mengerahkan
kemampuannya untuk mempertajam pandangan matanya, Ki Gede pun tidak
mengalami kesulitan sedikit pun untuk melintasi dapur dan menuju ke
ruang tengah.
Begitu Ki Gede membuka pintu yang
menghubungkan dapur dengan ruang tengah, sepercik sinar segera saja
menyambarnya. Ternyata di ruang tengah itu ada sebuah dlupak yang
diletakkan di ajug-ajug. Walaupun sinarnya tidak begitu terang, namun
sudah cukup untuk menerangi ruang tengah yang cukup luas itu.
Demikian Ki Gede melangkah memasuki ruang tengah, lamat-lamat dia mendengar suara orang yang sedang bercakap-cakap.
“Mereka agaknya di pringgitan,” berkata Ki Gede dalam hati sambil mengayunkan langkahnya.
Namun tiba-tiba saja sebuah keragu-raguan telah menyelinap di hatinya sehingga ki Gede telah menghentikan langkahnya.
“Bagaimana jika orang bertopeng itu sengaja menjebakku?” pertanyaan itu telah berputar-putar di benak Ki Gede.
Memang sebelum jatuh tertidur beberapa
saat tadi, Ki Gede sempat mendengar bisikan orang bertopeng itu di
telinganya, “Bergabunglah dengan kelima orang di banjar itu, Ki Gede.
Sesungguhnya mereka orang-orang yang dapat dipercaya.”
Pesan singkat itu memang sangat jelas.
Namun tidak menutup kemungkinan jika yang terjadi kemudian adalah justru
sebaliknya. Mereka adalah para pengikut Trah Sekar Seda Lepen, atau
bahkan salah satu dari mereka adalah Raden Wirasena sendiri.
STSD jilid 2 Bagian 2
Namun ketika lamat-lamat Ki Gede
mendengar suara tawa Ki Jagabaya, keragu-raguan itu pun segera sirna
bagaikan kabut dini hari yang tertimpa sinar Matahari pagi.
“Agaknya Ki Jagabaya mulai akrab dengan
mereka,” berkata Ki Gede dalam hati sambil mengayunkan langkahnya
kembali, “Persoalan yang sedang bergolak di Perdikan Matesih harus
segera dituntaskan.”
Demikianlah, Ki Gede segera membuang
jauh-jauh semua keraguan yang membelit hatinya. Dengan langkah mantap Ki
Gede pun menuju ke pringgitan.
Dalam pada itu, ketika malam telah
melewati sepi uwong dan hampir mencapai tengah malam, tampak seseorang
yang berwajah keras, sekeras batu-batu padas di gerojogan sedang
berjalan mendekati pintu gerbang Tanah Perdikan Matesih.
Beberapa pengawal yang sedang berjaga
segera berloncatan ke tengah-tengah pintu gerbang begitu melihat
bayangan seseorang yang berjalan menuju ke arah mereka.
“Siapa?” bertanya salah seorang pengawal
sambil mengamat-amati wajah keras itu di bawah siraman oncor yang
tersangkut di pojok atas gerbang.
“Aku,” terdengar suara parau mirip suara burung gagak, “Apakah mata kalian sudah lamur sehingga tidak mengenali aku lagi?”
“O, maafkan kami Ki Lurah,” jawab salah
satu pengawal itu sambil memberi isyarat kawan-kawannya untuk memberi
jalan, “Sesuai pesan Raden Mas Harya Surengpati, kita diperintahkan
untuk meningkatkan kewaspadaan. Berita terbunuhnya seseorang yang
diduga telik sandi dari Mataram di Dukuh Klangon sore tadi telah sampai
kemari.”
Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam sambil
mengangguk-angguk. Katanya kemudian, “Aku tadi sempat singgah di
padukuhan Klangon dan telah mendapat laporan dari Ki Dukuh,” Ki Lurah
berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Aku akan menghadap Raden Mas
Harya Surengpati malam ini. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang
ingin aku laporkan.”
Para pengawal itu sejenak saling
berpandangan. Ada keinginan untuk menanyakan berita apakah yang dibawa
oleh Ki Lurah itu? Namun ternyata pertanyaan itu hanya mereka simpan di
dalam hati saja.
“Marilah,” berkata Ki Lurah kemudian
begitu melihat para pengawal itu hanya berdiri termangu-mangu. Lanjutnya
kemudian sambil melangkah, “Berhati-hatilah terhadap segala kemungkinan
yang dapat terjadi. Agaknya Mataram sudah mulai mencium gerakan kita.”
“Baik Ki Lurah,” hampir bersamaan mereka menjawab.
“Apakah Ki Lurah tidak memerlukan kawan?” tiba-tiba salah seorang pengawal itu menyeletuk.
Ki Lurah yang sudah mengayunkan
langkahnya itu berhenti sejenak. Sambil memandang wajah pengawal itu Ki
Lurah tertawa pendek. Jawabnya kemudian, “Aku tahu maksudmu. Bukankah
jalan menuju rumah yang ditempati Raden Mas Harya Surengpati ini
melewati rumahmu?”
“Ah,” terdengar gelak tawa
kawan-kawannya, namun dengan cepat pengawal itu menyahut, “Barangkali Ki
Lurah memerlukan kawan untuk berbincang sekalian menjaga segala
kemungkinan di perjalanan?”
“Terima kasih, aku dapat menjaga diriku sendiri,” jawab Ki Lurah sambil kembali mengayunkan langkahnya meninggalkan tempat itu.
Demikianlah, sejenak kemudian Ki Lurah
telah berjalan menyusuri lorong-lorong jalan yang telah sepi. Ki Lurah
harus melewati padukuhan kecil yang merupakan bagian dari Tanah Perdikan
Matesih yang luas sebelum memasuki padukuhan induk. Antara padukuhan
kecil dengan padukuhan induk itu dihubungkan dengan sebuah bulak yang
tidak begitu panjang.
Ketika rumah terakhir telah dilewatinya,
kini di hadapan ki Lurah terhampar tanah persawahan yang cukup luas. Di
tengah-tengah tanah persawahan itu tampak jalur jalan yang menjelujur
dalam keremangan malam.
Tiba-tiba dada Ki Lurah berdesir tajam.
Sebagai orang yang telah kenyang malang-melintang dalam dunia kekerasan,
hatinya seolah-olah telah menerima isyarat tentang bahaya yang mungkin
sedang menghadang di depannya.
“Persetan!” geram Ki Lurah mengeraskan
hatinya, “Aku bukan anak kemarin sore yang baru belajar loncat-loncatan
dalam olah kanuragan. Siapa yang tidak mengenal gegedug dari Dukuh
Salam? Baru menyebut namanya saja orang-orang sudah mati berdiri.”
Dengan berbekal keyakinan itulah, Ki
Lurah pun kemudian meneruskan langkahnya menyusuri jalur jalan yang
terlihat sangat sepi dan mendebarkan.
Ketika Ki Lurah baru saja menempuh
perjalanan beberapa tombak jauhnya, firasatnya mengatakan bahwa ada
seseorang yang sedang mengikuti perjalanannya.
Dengan cepat Ki Lurah berpaling ke
belakang. Namun tidak tampak sesuatu pun di belakangnya selain kegelapan
malam. Dicobanya mengerahkan kemampuan untuk mempertajam
penglihatannya. Namun Ki Lurah benar-benar tidak melihat apapun kecuali
hanya kegelapan.
“Gila!” geram ki Lurah sambil mengayunkan langkahnya kembali, “Mengapa aku sekarang ini menjadi seorang pengecut?”
Dengan tanpa meninggalkan kewaspadaan, Ki Lurah kembali berjalan menyusuri jalur jalan yang terasa sangat ngelangut dan sepi.
Namun baru saja Ki Lurah berjalan lagi
beberapa langkah, kali ini pendengaran ki Lurah dikejutkan oleh suara
orang terbatuk-batuk beberapa langkah saja di belakangnya.
Bagaikan disengat kalajengking sebesar
ibu jari kaki orang dewasa, Ki Lurah pun terlonjak kaget. Dengan cepat
dia segera memutar tubuhnya dan memasang kuda-kuda. Siap untuk
menghadapi segala kemungkinan.
Namun yang terlihat di hadapan Ki Lurah
hanyalah kegelapan malam. Tidak tampak sesuatu pun yang mencurigakan
sehingga Ki Lurah menjadi ragu-ragu sendiri dengan pendengarannya.
“Hantu?” kata itulah yang kini menyelinap di dalam hati Ki Lurah.
“Ah, tidak mungkin. Seumur hidupku aku
belum pernah melihat seekor hantu dan aku memang tidak percaya dengan
keberadaan para hantu itu sendiri,” berkata Ki Lurah dalam hati mencoba
untuk menenangkan hatinya. Namun Ki Lurah tidak dapat memungkiri bahwa
pendengarannya benar-benar telah menangkap suara orang terbatuk-batuk.
Setelah beberapa saat Ki Lurah tidak
melihat sesuatu yang mencurigakan, dengan perlahan-lahan Ki Lurah pun
kemudian memutar tubuhnya.
Namun kali ini jantung ki Lurah bagaikan
terlepas dari tangkainya. Belum sepenuhnya Ki Lurah memutar tubuhnya,
terasa sebuah tangan telah mengusap tengkuknya.
“Iblis!” teriak Ki Lurah sekeras-kerasnya
sambil meloncat menjauh. Begitu sepasang kakinya menginjak tanah,
dengan cepat Ki Lurah memutar tubuhnya. Sebuah pedang berukuran cukup
besar telah tergenggam di tangan kanannya.
Namun kembali Ki Lurah hanya dapat
mengumpat-umpat dengan umpatan yang sangat kotor. Kembali yang
terbentang di hadapannya hanyalah kegelapan malam yang sepi.
Kali ini hati Ki Lurah benar-benar tinggal semenir. Betapapun Ki Lurah mencoba menyangkal akan keberadaan segala jenis hantu, gendruwo, ilu-ilu banaspati, engklek-engklek balung atandak dan sebangsanya, namun kenyataan yang dihadapinya sekarang ini benar-benar berada diluar jangkauan nalarnya.
“Tidak mungkin seseorang mampu melakukan
ini semua, walaupun orang itu memiliki kesaktian yang tiada taranya. Dia
pasti memerlukan waktu yang cukup untuk menghindar dari pandangan
mataku,” berkata Ki Lurah dalam hati dengan jantung yang berdentangan.
Begitu dahsyatnya suara dentangan itu sehingga dadanya seolah-olah akan
meledak.
Untuk beberapa saat Ki Lurah masih
menunggu. Dicobanya menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sekedar
untuk menurunkan gejolak di dalam dadanya. Namun rasa-rasanya perasaan
takut yang mulai menjalari otaknya telah membuat tubuh ki Lurah menjadi
menggigil kedinginan.
Sambil meningkatkan kemampuan panca
inderanya, Ki Lurah mencoba membaca segala mantra-mantra yang pernah
dipelajarinya. Dulu sewaktu dia berguru pada seseorang yang sakti, yang
dianggap menguasai dunia kasar maupun dunia halus, dia telah diajari
bagaimana caranya menolak segala jenis makhluk halus yang datang
mengganggu.
Sambil meludah tiga kali ke tanah, Ki
Lurah pun kemudian menggores-goreskan ujung pedangnya ke tanah yang
telah basah oleh ludahnya.
“Setan ora doyan demit ora ndulit!”
geram Ki Lurah sambil memutar pedangnya dengan deras di atas kepala.
Seolah-olah Ki Lurah sudah yakin dengan keberadaan lawannya dan akan
segera ditebasnya dengan senjata di tangannya.
Demikianlah dengan teriakan menggelegar,
pedang di tangan kanannya bergerak membabat kesana-kemari tanpa arah
yang jelas. Ki Lurah yakin dengan demikian jika ada sebangsa makhluk
halus yang berada di sekitarnya, mereka akan berlarian tunggang langgang
karena takut terkena sabetan pedang yang telah diberinya mantra.
Namun yang terjadi kemudian justru telah
membuat sekujur tubuh Ki Lurah kaku tak mampu bergerak. Jantungnya kini
benar-benar berhenti berdetak. Sepasang matanya melotot dengan mulut
ternganga lebar-lebar. Wajahnya pucat pasi bagaikan tak dialiri oleh
darah setetes pun.
Memang ketika dengan penuh semangat yang
membara Ki Lurah sedang mengayun-ayunkan senjatanya tadi, tiba-tiba saja
pedang yang berukuran cukup besar di tangan kanannya itu terlepas
begitu saja. Seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa kuatnya menarik
pedang itu. Dan sebagai gantinya, pedang itu sekarang justru telah
bergerak-gerak sendiri dan justru mengancam ke arah dadanya.
Penalaran ki Lurah pun kini benar-benar
telah menjadi buram. Perlahan-lahan kesadarannya pun mulai kabur dan
pandangan matanya mulai gelap. Namun sebelum Ki Lurah benar-benar jatuh
tak sadarkan diri, lamat-lamat dia mendengar sebuah bisikan di
telinganya.
“Tidurlah Ki Lurah,” terdengar bisikan itu sangat dekat sekali di telinga kanannya.
Diantara kesadarannya yang mulai
menghilang, Ki Lurah mencoba mengenali siapa pemilik suara itu dengan
memalingkan wajahnya. Namun sekali lagi terasa sebuah tangan mengusap
tengkuknya dan segala sesuatunya pun menjadi gelap.
Namun sebelum tubuh Ki Lurah benar-benar
terjatuh, tiba-tiba sepasang tangan yang kekar muncul begitu saja dari
dalam kegelapan malam dan menahan tubuh yang sudah hampir menyentuh
tanah itu. Sejenak kemudian, perlahan-lahan dari dalam kegelapan malam
muncul seseorang yang bertubuh tinggi besar sambil sepasang tangannya
menahan tubuh Ki Lurah.
“Dengan memutus jalur ini, semoga orang
yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen itu tidak akan mendengar
berita yang terjadi di padukuhan Klangon,” gumam orang tinggi besar itu
perlahan sambil mengangkat tubuh ki Lurah dan kemudian memanggulnya.
Sejenak kemudian orang tinggi besar itupun segera meninggalkan tempat
itu.
Dengan langkah lebar namun terlihat
ringan, orang tinggi besar itu segera meloncati parit dan kemudian
menyusuri pematang. Batang-batang padi memang belum ditanam karena hujan
memang baru turun sore tadi. Namun para petani telah menyiapkan tanah
garapan mereka dengan sebaik-baiknya.
Beberapa saat kemudian, orang itu telah
mencapai pematang yang paling ujung dari tanah persawahan yang luas itu.
Kini di hadapannya terbentang tebing sebuah sungai yang tidak begitu
curam. Dengan sangat cekatan dan terampil orang itu pun kemudian mulai
menuruni tebing.
Sesampainya di tepian sungai, ternyata seseorang sedang menunggunya sambil duduk di atas sebuah batu.
“Engkau berhasil Ki Bango Lamatan?” bertanya orang itu sambil bangkit dari duduknya.
“Ya, Ki Gede,” jawab orang itu yang
ternyata adalah Ki Bango Lamatan, “Orang ini akan sangat berbahaya jika
sampai melaporkan kedatangan kami kepada orang yang menyebut dirinya
Trah Sekar Seda Lepen itu.”
“Engkau benar Ki,” sahut Ki Gede
memandang sesosok tubuh yang menggelantung di pundak Ki Bango Lamatan.
Kemudian sambil melangkah mendekat, Ki Gede melanjutkan, “Marilah kita
bawa orang ini ke Padukuhan induk Perdikan Matesih. Biarlah dia
ditempatkan di salah satu bilik yang ada di gandhok kanan rumahku. Para
pengawal akan menjaganya siang dan malam.”
Ki Bango Lamatan mengangguk-anggukkan
kepalanya. Namun beberapa saat kemudian kening Ki Bango Lamatan tampak
berkerut merut. Bertanya Ki Bango Lamatan kemudian, “Ki Gede, apakah
para perangkat tanah Perdikan Matesih masih bisa dipercaya?”
Ki Gede menggeleng. Jawabnya kemudian,
“Tidak semuanya bisa dipercaya. Untunglah keluargaku belum terpengaruh
oleh rayuan Raden Mas Harya Surengpati. Namun untuk saat ini yang
menjadi beban pikiranku justru Ratri, anak perempuanku satu-satunya.”
Ki Bango Lamatan menarik nafas
dalam-dalam. Beberapa saat tadi ketika Ki Gede telah bertemu dengan Ki
Rangga dan kawan-kawan di banjar padukuhan Klangon, Ki Gede telah
menyebut permasalahan yang sedang dialaminya itu. Salah satunya adalah
hubungan yang sedang terjalin antara Ratri dengan Raden Mas Harya
Surengpati itu.
“Dunia anak muda memang menggairahkan,
apalagi kalau sudah menyangkut masalah asmara,” berkata Ki Bango Lamatan
dalam hati. Walaupun Ki Bango Lamatan sendiri semasa mudanya tidak
begitu tertarik dengan perempuan, namun di usianya yang sudah mendekati
senja, hati Ki Bango Lamatan justru telah tertarik kepada seorang
perempuan muda yang sangat cantik.
“Rara Anjani,” desah Ki Bango Lamatan
dalam hati menyebut sebuah nama sambil menengadahkan wajahnya. Sekilas
dipandanginya angan gelap yang masih bergelantungan di langit. Terbayang
di rongga matanya seraut wajah perempuan muda cantik jelita yang kini
telah dipersunting oleh Pangeran Pati.
“Aku memang harus tahu diri,” berkata Ki
Bango Lamatan kembali dalam hati, “Tidak sepantasnya aku memendam
keinginan gila ini di dalam hatiku. Apa yang diajarkan oleh Ki Ajar
Mintaraga beberapa saat yang lalu seharusnya telah mengendapkan hatiku
ini dari segala keinginan duniawi.”
Ki Bango Lamatan menarik nafas panjang,
panjang sekali. Kemudian dihembuskannya kuat-kuat melalui kedua lobang
hidungnya. Seolah-olah ingin dibuangnya segala keinginan yang ngayawara itu bersama dengan hembusan nafasnya.
“Buwenging bawana gung mung kacekan lepasing wardaya,” gumam
Ki Bango Lamatan dalam hati sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.
Memang wejangan Ki Ajar Mintaraga itu sangat membekas di hatinya.
Luasnya dunia ini sesungguhnya masih lebih luas dari hati sanubari yang
tak bertepi.
Sejenak kemudian mereka berdua telah
menyusuri tepian sungai yang tidak begitu lebar. Keduanya berjalan
sambil berdiam diri. Masing-masing sedang asyik tenggelam dalam dunia
angan-angan.
Sambil mengayunkan langkahnya, beberapa
kali Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Ingatannya kembali ke beberapa
saat yang lalu ketika waktu sudah memasuki sirep uwong. Dengan berbekal
keyakinan akan pesan singkat yang diterimanya dari orang bertopeng itu,
Ki Gede pun tanpa ragu-ragu melangkahkan kakinya memasuki pringgitan.
“Silahkan Ki Gede,” sambut Ki Jagabaya
pada saat itu sambil tersenyum dan bangkit berdiri. Orang-orang yang
berada di ruangan itu pun ikut berdiri.
Sejenak kemudian, satu-persatu secara
bergantian orang-orang yang hadir di ruangan itu menyalami Ki Gede.
Sambutan yang ramah itu terasa menyejukkan hati Ki Gede yang pada
awalnya sempat dihinggapi sepercik keragu-raguan.
“Ki Gede,” berkata Ki Jagabaya kemudian
setelah semuanya kembali duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih
bersih, “Sebelumnya aku akan memperkenalkan para sahabat kita dari
Prambanan ini.”
Mendengar Ki Jagabaya menyebut Prambanan,
tampak kening Ki Gede berkerut merut. Namun segera saja sebuah senyum
menghiasi bibirnya begitu Ki Jagabaya meneruskan kata-katanya,
“Setidaknya itulah pengakuan mereka, para perantau yang berasal dari
daerah sekitar Prambanan.”
Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya.
Sementara Ki Rangga dan kawan-kawannya hanya dapat saling berpandangan
sambil menahan nafas.
“Ki Gede,” berkata Ki Jagabaya
selanjutnya, “Di sebelah kanan Ki Gede adalah Ki Waskita, kemudian Ki
Sedayu, Ki Jayaraga, dan yang termuda diantara mereka bernama Glagah
Putih. Sedangkan yang terakhir adalah Ki Bango Lamatan.”
Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya
sambil memandangi satu persatu orang-orang yang disebut Ki Jagabaya.
Dalam hati Ki Gede mulai menduga-duga. Mungkinkah orang bertopeng yang
menemuinya sore tadi itu adalah salah satu dari mereka?
Namun pertanyaan itu masih disimpannya
saja di dalam hati. Suatu saat nanti jika waktunya telah tiba, segala
sesuatunya pasti akan terungkap.
Ketika pandangan mata Ki Gede menatap
wajah Ki Rangga Agung Sedayu, sejenak Pemimpin tertinggi Tanah Perdikan
Matesih itu mengerutkan keningnya. Ada sebuah kesan tersendiri begitu ki
Gede Menatap mata Ki Rangga, sepasang mata yang terlihat sangat
meyakinkan, penuh percaya diri namun tidak tersirat sedikit pun sifat adigang, adigung, adiguna.
Sedangkan Ki Rangga yang menyadari
dirinya sedang di perhatikan menjadi berdebar-debar. Apakah Ki Gede
mencurigainya? Ki Rangga memang sengaja memperkenalkan dirinya sebagai
Ki Sedayu, nama dirinya yang sebenarnya tanpa menyertakan pangkat
keprajuritannya.
“Ki Gede,” berkata Ki Jagabaya kemudian
membuyarkan lamunan Ki Gede, “Para sahabat kita ini bersedia untuk
membantu Ki Gede dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di
Perdikan Matesih.”
Untuk sejenak Ki Gede masih terlihat
ragu-ragu. Entah apa yang terlintas di dalam benaknya. Namun akhirnya Ki
Gede pun berkata, “Ki Sanak berlima. Aku tidak peduli siapakah Ki sanak
berlima ini sebenarnya. Jika Ki sanak berlima ini ternyata adalah para
petugas sandi dari Mataram, aku malah bersyukur. Tanah Perdikan Matesih
memang sedang menghadapi sebuah permasalahan yang besar. Aku katakan
masalah ini sangat besar karena menyangkut masa depan Tanah Perdikan
Matesih ini sendiri,” Ki Gede berhenti sebentar untuk mengambil nafas.
Lanjutnya kemudian, “Aku menganggap permasalahan ini besar karena jika
Mataram telah mengetahui kegiatan di Perdikan Matesih dan dari pihak
Mataram kurang mendapatkan keterangan yang memadai, Perdikan Matesih ini
akan dianggap sedang mempersiapkan diri dalam sebuah kegiatan makar
terhadap Mataram.”
Hampir bersamaan mereka yang hadir di
ruangan itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Perbuatan makar terhadap
sebuah pemerintahan yang syah akan dapat mengakibatkan hancurnya masa
depan Tanah Perdikan Matesih itu sendiri.
Namun lamunan Ki Gede itu menjadi
terputus ketika tiba-tiba saja terdengar Ki Bango Lamatan yang sedang
berjalan di sebelahnya itu bertanya, “Ki Gede, sungai ini sudah mulai
menyempit. Apakah tidak sebaiknya kita naik ke tanggul?”
Ki Gede tidak segera menjawab.
Diamat-amatinya pohon Lo yang tumbuh di tebing sungai sebelah kiri.
Pohon Lo itu tumbuh menjulang tinggi dan terlihat bagaikan raksasa yang
sedang berdiri di tengah kegelapan malam.
“Setelah pohon Lo ini, beberapa puluh
langkah lagi sungai akan membelok ke kanan,” jawab Ki Gede kemudian,
“Kita akan naik ke atas tanggul setelah melewati kelokan itu.”
Ki Bango Lamatan tampak mengangguk-angguk. Keduanya pun kemudian segera meneruskan langkah mereka.
Demikianlah, setelah melewati sebuah
kelokan sungai yang tidak begitu tajam, mereka berdua segera mendaki
tanggul sebelah kanan sungai yang cukup landai. Begitu mereka muncul di
atas tanggul, beberapa ratus tombak di hadapan mereka telah terbentang
padukuhan induk Tanah Perdikan Matesih. Dalam kegelapan malam, tampak
padukuhan induk Tanah Perdikan Matesih itu bagaikan raksasa yang sedang
tidur lelap.
“Marilah,” berkata Ki Gede kemudian,
“Kita berjalan agak melingkar untuk menghindari para peronda. Dalam
keadaan seperti ini, kita belum tahu mana yang bisa menjadi kawan dan
mana yang justru akan menjadi lawan.”
Ki Bango Lamatan tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
Dalam pada itu, malam telah mencapai
puncaknya. Para peronda di gardu-gardu telah memukul kentongan dengan
nada dara muluk. Sementara itu di banjar padukuhan Klangon, Ki Waskita
tampak masih bercakap-cakap dengan Ki Rangga Agung Sedayu di pringgitan.
Sedangkan Ki Jayaraga dan Glagah Putih telah masuk ke ruang dalam untuk
beristirahat.
“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian
setelah meneguk wedang sere yang sudah dingin, “Ki Gede Matesih memang
sedang dalam bahaya, bahaya yang mengancam Tanah Perdikannya maupun
bahaya yang mengancam keluarganya.”
Sejenak Ki Rangga termenung. Berbagai
pertimbangan sedang hilir-mudik dalam benaknya. Tugas yang diemban
mereka berlima dari Ki Patih Mandaraka ternyata tidak sesederhana
seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Walaupun mereka menyadari,
tugas menggempur perguruan Sapta Dhahana tentu memerlukan perhitungan
yang cermat serta kekuatan yang memadai. Namun ternyata permasalahan itu
sudah berkembang sedemikian jauhnya. Pengaruh orang-orang yang menyebut
dirinya Trah Sekar Seda Lepen itu sudah menyebar sampai di Tanah
Perdikan Matesih dan padukuhan-padukuhan sekitarnya.
“Ki Waskita,” akhirnya Ki Rangga membuka
suaranya, “Menurut pertimbanganku. Apakah tidak sebaiknya kita langsung
saja menghancurkan sumber masalah itu? Sebagaimana yang telah kita
pertimbangkan sebelumnya, kita secara diam-diam akan memasuki Perguruan
Sapta Dhahana dan kemudian memancing para pemimpinnya untuk berperang
tanding. Terutama pemimpin perguruan Sapta Dhahana yang memang merasa
mempunyai urusan denganku.”
“Memang demikian sebaiknya ngger,” jawab
Ki Waskita, “Aku percaya jika Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan berdua
akan mampu menebarkan sirep yang sangat tajam sehingga tidak akan banyak
murid-murid perguruan Sapta Dhahana yang akan terlibat,” Ki Waskita
berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Dengan demikian kita akan
berurusan hanya dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan. Namun yang
menjadi persoalannya sekarang adalah, kita tidak tahu kapan mereka semua
akan berkumpul di padepokan Sapta Dhahana, terutama orang yang menyebut
dirinya Trah Sekar Seda Lepen itu. Seperti yang telah disampaikan oleh
Ki Gede Matesih beberapa saat yang lalu, adik orang yang mengaku Trah
Sekar Seda Lepen itu sekarang bertempat tinggal di Perdikan Matesih.
Sedangkan Raden Wirasena sendiri menurut keterangan Ki Gede belum pernah
menampakkan dirinya sama sekali sampai saat ini.”
Kembali Ki Rangga termenung. Jika
memungkinkan memang sebaiknya mereka menggempur padepokan Sapta Dhahana
itu pada saat semua orang yang berkepentingan sedang berkumpul, walaupun
dengan demikian kekuatan mereka akan menjadi diluar dugaan.
“Ki Waskita,” berkata Ki Rangga kemudian,
“Apakah tidak sebaiknya kita mengikuti saja saran ki Gede Matesih
sambil menunggu perkembangan selanjutnya?”
Sejenak ki Waskita menarik nafas
dalam-dalam. Memang beberapa saat tadi ketika Ki Gede Matesih dan Ki
Jagabaya membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, mereka
mengusulkan Ki Rangga dan kawan-kawan sebaiknya bertempat di kediaman Ki
Gede saja. Mereka akan mengaku sebagai kerabat Ki Gede dari daerah
sekitar Prambanan dan sedang ada keperluan keluarga. Namun dengan
demikian secara tidak langsung mereka berlima telah menyatakan diri
mereka dan siap berhadapan dengan para pengikut Trah Sekar Seda Lepen.
“Ngger,” jawab Ki Waskita kemudian
setelah sejenak menimbang, “Bukankah salah satu pengikut Trah Sekar Seda
Lepen itu pernah berurusan dengan Angger? Dengan demikian tidak menutup
kemungkinan dia akan mengenal angger dengan baik. Benturan langsung pun
tidak dapat dihindarkan dan penyamaran kita akan dengan mudah
tersingkap.”
Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya.
Katanya kemudian, “Aku menyadari itu Ki Waskita. Jika orang yang
disebut Eyang Guru itu ada diantara mereka, tentu dengan mudah akan
mengenali aku. Selain itu kita tidak akan dapat melaksanakan pesan Ki
Patih untuk tidak melibatkan Mataram dalam persoalan ini.”
“Tetapi jika keadaan ternyata telah berkembang diluar perhitungan kita, apa boleh buat,” sahut Ki Waskita.
Ki Rangga mengerutkan keningnya mendengar
kata-kata Ki Waskita. Jawabnya kemudian, “Akan tetapi harus ada bukti
nyata bahwa mereka telah memberontak terhadap pemerintahan yang sah,
yaitu Mataram,” Ki Rangga berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian,
“Sementara ini Tanah Perdikan Matesih yang diharapkan akan menjadi
tumpuan perjuangan mereka, ternyata masih belum menentukan sikap secara
terang-terangan. Bahkan kita mendengar sendiri beberapa saat tadi,
sewaktu Ki Gede Matesih hadir di sini, dia telah menyatakan sikapnya
untuk tetap setia kepada Mataram.”
Ki Waskita mengangguk-anggukkan
kepalanya. Memang persoalannya menjadi semakin rumit. Jika
terang-terangan para pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu sudah melakukan
sebuah gerakan yang mengarah pada sebuah pemberontakan, tentu Ki Rangga
akan segera mengirim Glagah Putih untuk melaporkan hal itu kepada Ki
Patih. Dengan demikian Ki Rangga sebagai Senapati pasukan khusus yang
berkedudukan di Menoreh akan dapat menggerakkan pasukan segelar sepapan
untuk menumpas pemberontakan itu.
“Trah Sekar Seda Lepen itu baru mulai
menanamkan pengaruh mereka,” tanpa sadar Ki Waskita bergumam, “Mereka
mencoba mempengaruhi para penghuni Tanah Perdikan Matesih, terutama para
perangkatnya. Sedangkan Ki Gede agaknya terlalu sulit untuk
dipengaruhi.”
“Untuk itulah Raden Mas Harya Surengpati
mencoba melunakkan hati Ki Gede melalui putri satu-satunya Ki Gede,”
sahut Ki Rangga dengan serta merta.
Sejenak Ki Waskita mengerutkan keningnya
dalam-dalam. Entah mengapa, tiba-tiba saja dada ayah Rudita itu berdesir
tajam mendengar Ki Rangga menyebut hubungan yang sedang dijalin oleh
Raden Mas Harya Surengpati dengan putri satu-satunya Ki Gede itu.
“Ngger,” akhirnya Ki Waskita berkata
setelah gejolak di dalam dadanya mereda, “Aku mempunyai panggraita
tentang hubungan kedua orang itu. Panggraitaku mengatakan bahwa orang
yang bernama Raden Mas Surengpati itu belum tentu dengan hati yang tulus
menjalin hubungan dengan putri Ki Gede. Aku justru mencurigai adanya
pamrih tersembunyi di balik semua itu.”
Untuk sejenak Ki Rangga tertegun
mendengar kata-kata Ki Waskita. Berbagai tanggapan telah muncul dalam
benaknya, namun Ki Rangga masih berdiam diri dan hanya menyimpannya saja
di dalam hati.
Melihat Ki Rangga hanya diam
termangu-mangu, Ki Waskita pun melanjutkan kata-katanya, “Sebaiknya kita
terima saja saran Ki Gede untuk berkunjung ke kediaman Ki Gede sebagai
tamu atau kerabat jauh. Selain kita memang punya rencana tersendiri,
kita juga berkewajiban melindungi keluarga Ki Gede jika terjadi sesuatu
yang tidak diharapkan,” Ki Waskita berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian,
“Namun sebaiknya yang datang berkunjung cukup tiga orang saja. Ki
Jayaraga, Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih.”
“Bagaimana dengan kita berdua?” bertanya Ki Rangga dengan serta merta.
Ki Waskita tidak segera menjawab. Hanya senyumnya saja yang tampak mengembang di bibirnya.
Agaknya Ki Rangga tanggap dengan maksud
Ki Waskita. Maka katanya kemudian, “Kita berdua memang tidak perlu
menampakkan diri. Dengan demikian jika orang yang disebut Eyang Guru itu
sekarang ini sedang berada di Perdikan Matesih, aku akan luput dari
pengamatannya.”
“Demikianlah ngger,” berkata Ki Waskita
kemudian, “Sementara itu kita berdua akan mengadakan penyelidikan di
sekitar padepokan Sapta Dhahana dan juga rumah yang dijadikan tempat
tinggal oleh Raden Mas Surengpati di Perdikan Matesih.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam
sambil mengangguk-angguk. Namun di dalam hati kecilnya, terasa ada suatu
yang kurang pada tempatnya sehubungan dengan rencana yang disampaikan
oleh Ki Waskita. Maka katanya kemudian, “Ki Waskita, Kita datang ke
padukuhan Klangon ini berlima, sedangkan yang akan berkunjung ke
kediaman Ki Gede Matesih hanya bertiga. Apa kata Ki Dukuh Klangon nanti
jika dia mendapat laporan tentang hal ini?”
“O, masalah itu sudah aku pikirkan,
ngger,” jawab Ki Waskita, “Besuk pagi-pagi sekali kita berdua harus
sudah meninggalkan tempat ini. Akan ada seseorang yang menjemput kita
karena ada keluarga kita di Prambanan yang sedang sakit.”
“Siapakah yang akan menjemput kita berdua
besuk pagi-pagi sekali?” tiba-tiba pertanyaan itu terlontar begitu saja
dari bibir Ki Rangga.
Mendapat pertanyaan itu, Ki Waskita kembali tidak menjawab. Hanya senyumnya saja yang kembali menghiasi bibirnya.
Melihat ayah Rudita itu hanya tersenyum
ke arahnya, Ki Rangga menjadi berdebar-debar. Secara samar Ki Rangga
dapat meraba maksud Ki Waskita. Tentu dengan mengetrapkan bayangan semu,
Ki Waskita akan mempengaruhi para pengawal yang berjaga di gardu depan
sehingga mereka berdua akan dapat lolos dari banjar padukuhan Klangon
besuk pagi-pagi sekali.
“Jika tidak ada perubahan rencana, Ki
Jagabaya akan datang bersama utusan dari Ki Gede Matesih besuk pagi
menjelang pasar temawon,” berkata Ki Waskita kemudian membuyarkan
lamunan Ki Rangga.
Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya.
Katanya kemudian sambil bangkit dari tempat duduknya, “Marilah, Ki
Waskita. Kita bergabung dengan yang lainnya di ruang dalam. Kita perlu
menyampaikan rencana kita kepada mereka.”
“Ya, ngger,” jawab Ki Waskita sambil
bangkit berdiri dan kemudian mengikuti Ki Rangga yang telah melangkah
meninggalkan pringgitan.
Setibanya mereka berdua di ruang dalam,
ternyata ki Jayaraga dan Glagah Putih belum tidur. Mereka berdua tampak
sedang berbincang-bincang.
“Silahkan,” berkata Ki Jayaraga sambil
menggeser duduknya, “Kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak
sewajarnya yang ada di ruangan ini.”
“Apakah itu, Ki?” hampir bersamaan Ki Rangga dan Ki Waskita bertanya.
Ki Jayaraga tersenyum terlebih dahulu
sebelum menjawab. Katanya kemudian sambil menunjuk ke arah dinding
sebelah utara, “Lihatlah. Di sudut dinding sebelah utara itu ada sebuah
lubang yang kelihatannya memang sengaja dibuat.”
Hampir bersamaan Ki Rangga dan Ki Waskita
berpaling ke arah yang ditunjukkan oleh Ki Jayaraga. Dengan bergegas
keduanya pun segera menghampiri tempat itu. Benar saja, sebuah lubang
yang tidak begitu besar agaknya dengan sengaja telah dibuat di sudut
dinding sebelah utara itu.
“Lubang ini kelihatannya belum lama
dibuat,” desis Ki Waskita sambil mengamat-amati lubang di sudut dinding
itu, “Mungkin lubang ini dibuat pada saat kita di pringgitan bersama Ki
Gede dan Ki Jagabaya.”
“Dugaanku juga demikian Ki,” sahut Ki
Jayaraga yang kemudian juga ikut mendekat dan mengamat-amati lubang itu,
“Namun apakah tujuan sebenarnya?”
“Untuk membunuh kita,” jawab Ki Rangga yang membuat semua orang terperanjat. Glagah Putih pun ikut berdiri dan mendekat.
“Ya, untuk membunuh kita atau paling
tidak salah satu dari kita,” berkata Ki Rangga selanjutnya begitu
melihat orang-orang itu hanya berdiri diam termangu-mangu.
“Paser beracun,” tiba-tiba hampir bersamaan terdengar mereka berdesis perlahan.
“Ya, paser beracun,” berkata Ki Rangga.
Kemudian sambil tangannya menunjuk lubang di sudut dinding itu Ki Rangga
melanjutkan, “Dari lubang inilah sumpit itu akan dimasukkan. Sementara
kita sedang tertidur lelap, sebuah paser beracun akan mematuk dada salah
satu dari kita, atau bahkan mungkin orang itu akan meniup sumpitnya
berkali-kali untuk menghabisi kita semua.”
“Curang!” geram Glagah Putih, “Ini pasti
pekerjaan orang yang telah membunuh petugas sandi kita di bulak siang
tadi. Kita harus membuat perhitungan.”
Orang-orang tua yang mendengar Glagah
Putih menggeram telah tersenyum. Mereka bisa memaklumi perasaan Glagah
Putih. Kematian salah satu petugas sandi dari Mataram itu agaknya telah
membuat Glagah Putih waringuten.
“Sebaiknya kita segera tidur,” berkata Ki
Rangga sambil memberi isyarat kepada kawan-kawannya. Kemudian sambil
melangkah ke tengah-tengah ruangan dia melanjutkan, “Aku akan berbaring
di sisi paling utara. Silahkan yang lainnya menyesuaikan.”
Agaknya orang-orang itu segera memahami
maksud Ki Rangga. Mereka sengaja memancing kehadiran orang itu. Maka
sejenak kemudian orang-orang itu pun mulai menempatkan diri untuk tidur
berjajar-jajar di tengah-tengah ruangan itu. Tidur hanya dengan
beralaskan tikar.
Glagah Putih yang tidur di paling ujung
berseberangan dengan kakak sepupunya masih sempat menggerutu sebelum
membaringkan tubuhnya.
“Orang-orang padukuhan Klangon memang
keterlaluan,” geram suami Rara Wulan itu sambil menyelimuti tubuhnya
dengan kain panjang, “Tidak ada amben, tidur hanya beralaskan tikar
usang, banyak nyamuknya lagi!”
Mereka yang mendengar gerutu Glagah Putih
hanya dapat menahan senyum. Sementara Ki Rangga yang berbaring di sisi
paling utara bersebelahan dengan Ki Waskita segera menyilangkan kedua
tangannya di depan dada.
Sejenak kemudian ruang dalam itu pun
segera menjadi sunyi. Yang terdengar kemudian hanyalah suara tarikan
nafas yang teratur diselingi oleh suara dengkuran Glagah Putih.
Dalam pada itu malam telah jauh
meninggalkan pusatnya. Angin yang berhembus terasa dingin menusuk
tulang. Sesekali di langit terdengar petir bersabung di udara. Agaknya
hujan akan turun lagi karena sisa mendung yang bergelayutan di langit
terlihat semakin hitam menggumpal.
Ketika tetes-tetes air hujan satu-persatu
mulai berjatuhan, sesosok bayangan tampak berjalan mengendap-endap
mendekati dinding ruang dalam sebelah utara yang bersebelahan dengan
longkangan.
Semua orang yang berada di dalam ruang
dalam itu dengan jelas dapat mendengar desir langkah seseorang di balik
dinding sebelah utara yang bersebelahan dengan longkangan. Namun
ternyata Ki Rangga Agung Sedayu mendengar desir yang lain yang sangat
lembut hampir tidak tertangkap oleh pendengaran, walaupun dengan
mengetrapkan aji sapta pangrungru sekalipun.
Ki Rangga menjadi berdebar-debar. Orang
kedua yang datang kemudian ini benar-benar luar biasa. Ki Rangga yakin,
kemampuan orang ini tentu ngedab-edabi.
“Siapakah orang yang datang kemudian ini?” berkata Ki Rangga dalam hati, “Apakah yang lain juga mendengar desir yang kedua ini?”
Untuk meyakinkan, Ki Rangga segera mengirim aji pameling kepada Ki Waskita yang berbaring di sebelahnya.
“Ki Waskita,” berkata Ki Rangga dalam aji
pamelingnya, “Apakah Ki Waskita mendengar desir langkah yang lain
selain orang yang pertama?”
“Aku tadi juga sempat mendengar sekilas,
ngger,” jawab Ki Waskita juga dalam aji pameling, “Namun sekarang desir
itu telah menghilang. Aku tidak mampu lagi untuk memantaunya.”
Berdesir tajam dada Ki Rangga mendengar
jawaban Ki Waskita. Ternyata dugaannya benar. Orang yang datang kemudian
ini mempunyai kemampuan yang ngedab-edabi.
Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang sekilas
juga sempat mendengar desir langkah yang lain setelah orang yang pertama
ternyata juga telah kehilangan jejak.
“Gila!” geram Ki Jayaraga dalam hati,
“Aku tidak mampu memantaunya lagi. Semoga Ki Waskita atau Ki Rangga
mampu memantau kedatangan orang yang kedua ini. Kalau yang aku dengar
tadi adalah benar-benar desir langkah seseorang, alangkah dahsyatnya
kemampuan orang itu?”
Ketika Ki Jayaraga kemudian mencoba
mengetrapkan aji pameling kepada muridnya, ternyata Glagah Putih sama
sekali tidak mendengar desir langkah yang datang kemudian.
“Yang mana guru?” bertanya Glagah Putih
juga dengan aji pameling, “Aku tidak mendengar desir langkah kecuali
orang yang sedang bersembunyi di balik dinding itu.”
Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam.
Kemampuan olah kanuragan muridnya itu memang sudah tinggi, namun jiwanya
masih sangat muda. Glagah Putih masih belum mampu menguasai gejolak
jiwa mudanya sehingga ketajaman mata hatinya memang masih perlu untuk
diasah.
Untuk beberapa saat suasana menjadi sunyi
dan mencekam. Orang yang berada di balik dinding itu agaknya sedang
mengintip suasana di ruang dalam melalui lubang di sudut dinding itu.
Dengan jelas orang-orang yang berada di dalam ruangan itu mendengar
sesuatu sedang dimasukkan melalui lubang di sudut dinding itu.
“Orang itu agaknya sedang memasukkan
sumpit melalui lubang di sudut dinding itu,” semua orang di dalam
ruangan itu berkata dalam hati. Namun mereka tetap berusaha bersikap
wajar, sebagaimana sewajarnya orang yang sedang tidur nyenyak.
“Siapakah yang akan menjadi sasaran yang
pertama?” hampir setiap dada bertanya-tanya menunggu paser pertama yang
akan meluncur ke arah salah satu dari mereka.
Dalam pada itu Ki Rangga yang sedang
memantau keberadaan orang yang datang kemudian itu pada akhirnya
ternyata juga telah kehilangan jejak, walaupun Ki Rangga telah
mengetrapkan aji sapta pangrungu setinggi-tingginya.
“Luar biasa,” berkata Ki Rangga dalam
hati. Sepercik kegelisahan mulai merayapi jantungnya. Berbagai dugaan
telah muncul dalam benaknya.
“Siapakah orang kedua itu? Mungkinkah
Eyang Guru itu telah mengetahui keberadaanku, atau mungkin Raden
Wirasena sendiri, ataukah yang lainnya?” menduga Ki Rangga dengan
jantung yang berdebaran.
Tiba-tiba Ki Rangga teringat akan Ki Bango Lamatan yang sedang mengantar Ki Gede pulang ke tanah Perdikan Matesih.
“Mungkin Ki Bango Lamatan,” berkata Ki
Rangga dalam hati. Namun dugaan itu segera ditepisnya sendiri. Jika yang
datang itu Ki Bango Lamatan, tentu Ki Rangga tidak akan kehilangan
jejak, demikian juga dengan Ki Waskita dan Ki Jayaraga.
“Walaupun Ki Bango Lamatan mengetrapkan
aji halimunannya, pada dasarnya wadagnya masih ada dan tidak menghilang
sepenuhnya,” berkata Ki Rangga dalam hati, “Dia hanya bersembunyi saja
dan aku sudah tahu bagaimana cara memecahkan ilmu itu.”
Namun Ki Rangga tidak berputus asa.
Dengan mengetrapkan aji sapta panggraita, Ki Rangga pun mulai meraba
alam sekitarnya tidak dengan meningkatkan kemampuan panca inderanya,
namun dengan meningkatkan ketajaman mata hatinya.
Demikianlah akhirnya, lambat laun Ki
Rangga mulai mampu meraba keberadaan orang kedua itu kembali. Walaupun
orang yang datang kemudian itu berusaha mengaburkan keberadaannya dengan
cara mengetrapkan ilmu yang mampu menyerap segala bunyi yang berada di
sekitarnya. Namun kemampuan ilmu orang itu tidak mampu mengelabuhi
ketajaman mata hati Ki Rangga.
Dengan semakin meningkatkan getar-getar
isyarat yang mengalir melalui detak jantungnya, Ki Rangga segera
mengetahui keberadaan orang kedua itu. Ternyata orang itu sudah berada
hanya beberapa langkah saja di belakang orang yang datang pertama kali.
Sementara orang yang sedang memasang sumpitnya itu agaknya tidak
menyadari akan kehadiran orang lain yang tepat berada di belakangnya.
Dengan asyiknya dia telah memasang sebuah paser beracun di sumpitnya dan
siap untuk membidik sasaran yang pertama.
Sejenak kemudian kembali suasana mencekam
dirasakan oleh orang-orang yang berada di ruang dalam itu. Seolah-olah
mereka sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati saja, namun tidak tahu,
siapakah yang akan terlebih dahulu menerima hukuman itu.
Namun ke empat orang yang berada di dalam
ruang dalam itu diam-diam menjadi heran. Setelah beberapa saat
menunggu, ternyata belum terjadi sesuatu apa pun. Bahkan kini mereka
tidak mendengar lagi desah nafas tertahan-tahan dari orang yang
bersembunyi di balik dinding itu.
Sedangkan Ki Rangga yang telah berhasil
memantau keberadaan orang yang datang kemudian itu menjadi
berdebar-debar. Dalam rabaan mata hatinya, orang yang datang kemudian
itu ternyata telah menggerakkan kedua tangannya dari arah belakang untuk
menyumbat jalan pernafasan orang pertama dengan cara mencekik lehernya.
Hampir saja Ki Rangga terpancing dan
meloncat bangun untuk menolong orang yang sedang dalam bahaya itu, namun
naluri keprajuritannya telah mencegahnya. Ki Rangga belum tahu pasti,
berdiri di pihak manakah orang yang datang kemudian itu.
Tidak ada kesempatan bagi orang yang
sedang mengarahkan sumpitnya itu untuk meronta maupun melawan.
Cengkeraman itu begitu kuatnya dan datang dengan tiba-tiba sehingga
telah menyumbat jalan nafasnya dan sekaligus mematahkan lehernya.
“Benar-benar iblis!” geram Ki Rangga
dalam hati. Panggraitanya masih dapat meraba gerakan orang itu setelah
mencekik korbannya. Agaknya orang itu telah bergeser mundur dengan cepat
sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu.
Ketika tiba-tiba saja terdengar
tetes-tetes air hujan yang turun dengan derasnya memukul-mukul atap
banjar padukuhan, Ki Rangga pun ternyata telah kehilangan pengamatan
atas kepergian orang itu. Perhatian Ki Rangga telah terpecah dengan
turunnya hujan yang bagaikan dicurahkan dari langit.
“Orang itu telah pergi,” perlahan Ki
Rangga berdesis sambil menarik nafas dalam-dalam dan mengurai sepasang
tangannya yang bersilang di dada. Dengan bertelekan pada kedua
tangannya, Ki Rangga pun kemudian bangkit dan duduk bersila.
Yang lain pun segera mengikuti Ki Rangga
untuk bangkit dan duduk bersila. Kini mereka berempat telah duduk
melingkar di atas tikar yang usang.
“Orang itu seperti nya telah mati
tercekik,” berkata Glagah Putih, “Aku sempat mendengar desah nafasnya
yang tiba-tiba saja telah terputus. Mungkin telah terjadi sesuatu dengan
orang itu. Tetapi siapakah yang telah membunuhnya?”
“Benar ngger,” Ki Waskita lah yang
kemudian menjawab, “Seseorang yang mempunyai kemampuan linuwih telah
membunuhnya. Beberapa saat tadi aku memang telah kehilangan jejak akan
keberadaan orang yang datang kemudian itu. Namun di saat dia mencekik
orang yang pertama, agaknya dia lupa menyembunyikan suara yang
ditimbulkan akibat gesekan tangannya dengan leher orang yang pertama
itu. Di saat itulah aku mampu memantau kembali keberadaannya.”
Orang-orang yang berada di ruangan itu
pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sementara Ki Rangga justru telah
termenung sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang
sedang merisaukan hatinya, namun Ki Rangga merasa enggan untuk
mengungkapkannya.
“KI Rangga,” berkata Ki Jayaraga kemudian, “Apakah tidak sebaiknya kita melihat keadaan orang di balik dinding itu?”
KI Rangga memandang ke arah Ki Waskita
untuk meminta pertimbangan. Ketika Ki Waskita kemudian mengangguk, Ki
Rangga pun akhirnya menarik nafas dalam-dalam sambil bangkit dari
duduknya. Katanya kemudian, “Marilah kita lihat orang itu. Barangkali
kita akan mendapatkan sebuah petunjuk.”
Yang lain pun segera bangkit dan mengikuti langkah Ki Rangga yang telah berjalan terlebih dahulu keluar dari ruang dalam.
Ketika mereka telah keluar lewat pintu
butulan yang terdapat di lorong tengah, dengan bergegas mereka pun
segera berbelok ke kanan dan memasuki longkangan. Apa yang mereka
dapatkan kemudian adalah sangat mengejutkan. Sesosok tubuh tampak
meringkuk dengan kepala yang terkulai. Sementara ketika Ki Rangga
kemudian membungkuk untuk mencoba mengamati lebih teliti lagi, tampak
sebuah paser menancap dalam-dalam di leher mayat itu.
“Mengapa?” pertanyaan itu muncul di benak mereka masing-masing.
“Agaknya orang itu ingin memberikan kesan
bahwa orang ini telah mengalami kejadian yang sama dengan petugas sandi
Mataram itu, mati karena paser beracun,” berkata Ki Rangga kemudian
sambil menegakkan tubuhnya.
“Ya, ngger,” sahut Ki Waskita, “Agaknya memang itulah kesan yang ingin ditunjukkan oleh pembunuh orang yang malang ini.”
“Dan sumpit orang itu pun ternyata juga
telah lenyap,” seru Glagah Putih agak sedikit keras sambil mencari-cari
sumpit yang akan digunakan orang itu, namun Glagah Putih tidak
menemukan apa yang dicarinya.
Hampir berbareng mereka telah menarik
nafas dalam-dalam. Untuk beberapa saat kemudian orang-orang itu tampak
masih merenungi sesosok mayat yang meringkuk di longkangan itu.
“Ki Rangga,” tiba-tiba suara Ki Jayaraga
membuyarkan lamunan mereka, “Apakah langkah kita selanjutnya? Besuk pagi
pasti akan terjadi kegemparan lagi karena sekali lagi telah terjadi
rajapati di padukuhan Klangon ini. Dan tempatnya justru di banjar
padukuhan, di balik dinding tempat kita menginap.”
Tanpa sadar mereka telah mengangkat
kepala dan saling pandang begitu mendengar pertanyaan Ki Jayaraga.
Setiap dada yang ada di longkangan itu pun telah berdesir. Tidak menutup
kemungkinan tuduhan pembunuhan itu akan kembali diarahkan kepada
mereka.
“Apakah tidak sebaiknya kita menyingkir saja, ngger?” bertanya Ki Waskita kemudian kepada Ki Rangga yang terlihat termenung.
Sejenak Ki Rangga menimbang-nimbang.
Namun akhirnya Ki Rangga pun menjawab, “Ki Waskita, pada awalnya kita
akan menerima tawaran ki Gede untuk tinggal di kediamannya dengan dalih
kita adalah tamu-tamu yang masih terhitung kerabat jauh dari Prambanan,”
Ki Rangga berhenti sebentar. Lanjutnya kemudian, “Kemudian timbul
pemikiran untuk memecah kekuatan kita. Ki Jayaraga, Ki Bango Lamatan dan
Glagah Putih saja yang akan berangkat ke Tanah Perdikan Matesih.
Sedangkan kita berdua seolah-olah pulang kembali ke Prambanan karena
suatu kepentingan. Namun ternyata keadaan telah berkembang semakin
rumit, dan jika kita menyingkir dari tempat ini, bagaimana dengan
keselamatan Ki Gede Matesih dan keluarganya? Para pengikut Trah Sekar
Seda Lepen pasti akan menangkap Ki Gede dan keluarganya serta menyandera
mereka sebagai alat untuk memaksa kita menyerahkan diri.”
Sejenak mereka menjadi bimbang. Namun di
tengah-tengah ketidak-pastian itu, tiba-tiba saja Ki Waskita berdesis
perlahan, “Marilah kita singkirkan saja mayat ini jauh-jauh dan jangan
sampai ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya kita.”
Bagaikan baru saja tersadar dari sebuah
mimpi buruk, Ki Rangga pun segera berkata, “Glagah Putih, angkatlah
mayat ini. Mari kita bawa mayat ini ke hutan kecil di sebelah barat
padukuhan Klangon. Kita akan menguburkannya di sana.”
“Baik Kakang,” jawab Glagah Putih sambil bersiap untuk mengangkat mayat yang meringkuk di longkangan itu.
Namun belum sempat Glagah Putih menyentuh
mayat itu, tiba-tiba saja pendengaran mereka yang tajam telah mendengar
langkah-langkah yang menuju ke tempat itu.
Segera saja suasana menjadi tegang
kembali. Namun agaknya Ki Rangga telah mengenal langkah-langkah itu,
maka katanya kemudian sambil tersenyum, “Sepertinya Ki Bango Lamatan
telah selesai mengantar Ki Gede.”
“Oh,” yang mendengar kata-kata Ki Rangga
itu pun telah menarik nafas dalam-dalam sambil menggeleng-gelengkan
kepala. Ternyata hati mereka terlalu tegang dengan adanya peristiwa
pembunuhan itu.
Demikianlah sejenak kemudian terdengar
langkah itu semakin jelas mendekati bangunan induk banjar padukuhan dari
arah samping kiri.
“Kami di sini Ki Bango Lamatan,” desis Ki
Rangga perlahan memberi-tahukan keberadaan mereka begitu
langkah-langkah itu semakin jelas terdengar.
STSD jilid 2 Bagian 3
Ki Bango Lamatan yang sedang berjalan
dalam gelapnya malam menuju ke pintu butulan samping itu telah tersenyum
mendengar bisikan Ki Rangga. Segera saja diayunkan langkahnya menuju ke
longkangan.
Namun alangkah terkejutnya Ki Bango
Lamatan begitu menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di
longkangan itu. Ki Rangga dan yang lainnya tampak sedang mengerumuni
seseorang yang sedang meringkuk tak bergerak di dalam longkangan itu.
“Apa yang terjadi?” bertanya Ki Bango Lamatan kemudian sesampainya dia di hadapan Ki Rangga.
“Seseorang telah mati di longkangan ini,”
jawab Ki Rangga, “Lebih baik segera kita singkirkan saja mayat ini
sebelum ada orang yang mengetahuinya.”
“Aku akan mengambil cangkul di dapur
dulu,” sela Glagah Putih kemudian sambil setengah berlari menuju ke
ruang tengah melalui pintu butulan.
“Biarlah Glagah Putih aku kawani,” berkata Ki Bango Lamatan kemudian sambil mengangkat mayat itu di pundaknya.
“Ki Bango Lamatan,” dengan serta merta Ki Rangga mencoba untuk mencegah, “Biar Glagah Putih saja yang membawa mayat ini.”
Ki Bango Lamatan tersenyum sambil menggeleng. Jawabnya kemudian, “Tidak Ki Rangga, Glagah Putih biar membawa peralatan saja.”
“Aku ikut,” tiba-tiba saja Ki Jayaraga menyela, “Aku sudah tidak bisa tidur lagi di sisa malam ini.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam.
Entah mengapa sejak tadi panggraitanya telah mengisyaratkan sesuatu,
namun Ki Rangga belum mampu menguraikannya.
Melihat kebimbangan Ki Rangga, Ki Waskita pun segera berbisik, “Apakah angger merasakan sesuatu yang mengkhawatirkan?”
Sejenak Ki Rangga ragu-ragu. Namun
akhirnya Ki Rangga pun menjawab, “Entahlah Ki Waskita. Mungkin hanya
kekhawatiran yang tidak beralasan.”
Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam
sambil mengangguk-angguk. Sebagai orang yang menimba ilmu pada sumber
yang sama, Ki Waskita segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada
diri Ki Rangga sehubungan dengan ilmu yang sedang di pelajari dan
disempurnakannya, aji pengangen-angen. Maka katanya kemudian, “Sebaiknya
biarlah Ki Jayaraga saja yang menemani Ki Bango Lamatan dan Glagah
Putih. Aku dan Ki Rangga masih ada urusan yang harus diselesaikan di
banjar ini.”
Ki Rangga akhirnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia segera maklum dengan maksud Ki Waskita.
Demikianlah begitu Glagah Putih telah
muncul dengan sebuah cangkul di pundaknya, mereka bertiga pun kemudian
dengan penuh kewaspadaan telah menyelinap ke halaman belakang banjar dan
kemudian keluar lewat pintu butulan yang terdapat di dinding bagian
belakang banjar.
“Para pengawal itu kelihatannya masih tertidur nyenyak,” desis Ki Jayaraga sambil membuka pintu butulan itu.
“Ya, Ki,” jawab Ki Bango Lamatan sambil
sedikit membungkuk agar mayat yang dipanggulnya tidak tersangkut pintu
butulan yang agak rendah. Lanjutnya kemudian sambil melangkahi tlundak,
“Tadi sewaktu aku mengantar Ki Gede lewat halaman belakang ini, mereka
juga tampak tertidur pulas. Ki Gede sempat bercerita kepadaku sewaktu Ki
Gede datang ke tempat ini, mereka pun sudah tertidur pulas. Agaknya
telah terjadi sesuatu yang tidak wajar pada mereka.”
Ki Jayaraga mengangguk-anggukkan
kepalanya, sementara Glagah Putih masih sempat berpaling sekilas ke
teritisan tempat para pengawal itu tertidur silang melintang sebelum
menutup pintu itu kembali dan kemudian menghilang ditelan kegelapan
malam.
Dalam pada itu, hujan deras yang sempat turun beberapa saat tadi
telah berhenti dan hanya menyisakan titik-titik air hujan yang sesekali
masih menetes dari langit. Sepeninggal ketiga orang itu, Ki Waskita dan
Ki Rangga pun segera kembali ke dalam banjar.“Ngger,” berkata ki Waskita kemudian begitu mereka berdua telah duduk bersila kembali di ruang dalam, “Sedari tadi aku merasakan sepertinya ada sebuah kegelisahan yang sedang membebani pikiranmu.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam sambil membetulkan letak duduknya. Jawabnya kemudian dengan setengah berbisik, “Ki Waskita, aku mempunyai firasat, sepertinya orang itu akan kembali lagi.”
Ki Waskita mengerutkan keningnya. Juga sambil berbisik, Ki Waskita pun kemudian bertanya, “Mengapa angger mempunyai dugaan seperti itu?”
“Entahlah Ki Waskita,” jawab Ki Rangga sambil menggeleng perlahan, “Namun ada baiknya jika aku mencoba untuk melacak keberadaannya lagi.”
“Ya, ngger,” sahut Ki Waskita cepat, “Mumpung malam masih panjang. Sebaiknya angger mengetrapkan aji pengangen-angen untuk melacak keberadaan orang itu.”
Untuk sejenak Ki Rangga tertegun. Tanyanya kemudian, “Apakah itu perlu Ki Waskita?”
“Ya ngger,” jawab Ki Waskita mantap, “Dengan demikian angger tidak hanya melacak keberadaan pembunuh itu, namun jika memungkinkan angger sekalian dapat melumpuhkannya.”
Sejenak Ki Rangga termangu-mangu. Mengetrapkan aji pengangen-angen bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pemusatan nalar dan budi sampai ke titik yang tertinggi. Selain itu, selama Ki Rangga dalam puncak semedinya, raganya akan sangat lemah, selemah selembar daun yang tergeletak di atas tanah.
Agaknya Ki Waskita dapat membaca keragu-raguan Ki Rangga. Maka katanya kemudian sambil tersenyum, “Jangan khawatir, ngger. Selama engkau dalam puncak samadimu, aku akan menjaga ragamu dengan taruhan nyawaku sendiri.”
Ki Rangga tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
Demikianlah, sejenak kemudian Ki Rangga segera membaringkan dirinya di atas tikar yang terbentang di tengah-tengah ruangan itu. Kedua tangannya segera bersilang diatas dada. Beberapa saat kemudian, terdengar aliran nafas Ki Rangga semakin lama semakin halus dan pelan. Ki Rangga pun telah memasuki puncak samadinya. Sementara Ki Waskita dengan sabar dan penuh kewaspadaan duduk bersila berjaga di samping Ki Rangga.
Dalam pada itu, begitu hujan reda, seseorang tampak bangkit dari duduknya di bawah sebatang pohon yang rindang. Pohon itu terletak di pinggir jalan menuju banjar padukuhan. Kira-kira diperlukan waktu sepemakan sirih untuk berjalan dari tempat itu sampai ke banjar padukuhan Klangon.
“Semoga saja berita yang aku terima dari Raden Wirasena itu benar,” berkata orang itu dalam hati sambil menegakkan tubuhnya. Ditengadahkan wajahnya untuk melihat langit yang kelam. Lanjutnya kemudian, “Salah satu dari kelima orang yang bermalam di banjar itu adalah Senapati pasukan khusus Mataram yang berkedudukan di Menoreh, Ki Rangga Agung Sedayu.”
Untuk beberapa saat orang itu tampak termenung. Dilemparkan pandangan matanya ke kejauhan yang tampak hitam kelam tanpa batas.
“Jika apa yang aku dengar selama ini memang benar, tentu orang yang bernama Ki Rangga Agung Sedayu itu pasti mengetahui kehadiranku beberapa saat tadi,” gumam orang itu kemudian sambil melangkahkan kakinya, “Namun jika apa yang diberitakan orang-orang selama ini ternyata terlalu dilebih-lebihkan, agul-agulnya Mataram itu pasti akan kebingungan mendapatkan orang di balik dinding itu tiba-tiba saja sudah tak bernyawa.”
Sambil mengayunkan langkahnya, tampak bibir orang itu menyunggingkan sebuah senyuman, senyum yang menandakan kemenangan yang seolah-olah sudah berada di dalam genggaman tangannya.
“Tidak perlu Raden Wirasena sendiri yang turun tangan,” kembali orang itu berangan-angan, “Cukup Ki Kebo Mengo yang akan mrantasi semua penghalang.”
Namun tiba-tiba panggraita orang yang bernama Ki Kebo Mengo itu merasakan akan kehadiran seseorang di tempat itu.
Dengan segera dia menghentikan langkahnya. Dalam sekejap Ki Kebo Mengo telah memusatkan nalar dan budinya dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Sejenak kemudian, panggraitanya telah menangkap bayangan seseorang yang sedang berdiri melekat pada sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan hanya beberapa langkah saja dari tempatnya berdiri.
“Keluarlah Ki Sanak,” berkata Ki Kebo Mengo kemudian dengan suara yang berat dan dalam sambil mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada, “Tidak ada gunanya Ki Sanak bersembunyi lagi. Aku tidak pernah mengampuni para pengecut yang beraninya hanya main petak umpet. Aku lebih senang membunuh dari pada berbantah yang tidak ada ujung pangkalnya.”
Namun jantung Ki Kebo Mengo itu bagaikan tersulut bara api dari tempurung kelapa. Bayangan yang melekat pada sebatang pohon itu sama sekali tidak bergerak. Seakan-akan tidak menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Ki Kebo Mengo.
“Hem,” geram Ki Kebo Mengo sambil berusaha menajamkan pandangan matanya. Untuk beberapa saat Ki Kebo Mengo menjadi ragu-ragu sendiri dengan pengamatannya.
“Siapa berani mempermainkan Ki Kebo Mengo, he?!” teriak Ki Kebo Mengo dengan suara menggelegar. Untunglah jalan yang menuju ke banjar padukuhan itu keadaannya sangat sepi. Beberapa rumah letaknya berjauhan serta tempat Ki Kebo Mengo berhenti itu adalah tanah kosong yang membujur sepanjang jalan dan belum didirikan sebuah bangunan pun di atasnya.
Ketika melihat bayangan itu sama sekali tidak bergerak, Ki Kebo Mengo menjadi gusar. Dengan segera diayunkan langkahnya mendekat.
Ketika jarak Ki Kebo Mengo dengan pohon tempat bayangan itu berdiri tinggal tiga langkah, tiba-tiba bayangan itu hilang begitu saja bagaikan sinar sebuah dlupak yang padam karena tertiup angin kencang.
“Iblis!” teriak Ki Kebo Mengo sambil meloncat ke depan. Tangannya terayun deras menghantam batang pohon sebesar pelukan orang dewasa itu.
Akibatnya adalah sangat dahsyat. Pohon itu memang tetap berdiri tegak, hanya batangnya saja yang tampak bergetar hebat. Namun seluruh daun-daunnya telah rontok dan berguguran jatuh ke tanah bagaikan baru saja dilanda angin puting beliung.
“Aji rog-rog asem,” tiba-tiba terdengar suara perlahan beberapa langkah saja di belakang Ki Kebo Mengo yang sedang asyik menikmati hasil kedahsyatan ilmunya.
Bagaikan disengat seribu kalajengking, Ki Kebo Mengo pun terlonjak kaget. Dengan cepat dia segera memutar tubuhnya. Tampak seseorang yang berperawakan sedang namun tegap telah berdiri beberapa langkah saja di hadapannya.
Sejenak Ki Kebo Mengo bagaikan membeku di tempatnya, namun itu hanya sekejap. Sesaat kemudian terdengar tawanya yang berderai-derai memecah kesunyian malam.
“O, alangkah sombongnya,” katanya kemudian disela-sela suara tertawanya, “Seseorang telah dengan deksura mencoba mempermainkan Ki Kebo Mengo. Hanya orang-orang yang mempunyai nyawa rangkap tujuh sajalah, yang berani mempermainkan Ki Kebo Mengo.”
Namun jawaban bayangan itu justru sangat menyakitkan. Berkata bayangan itu kemudian, “Ki Sanak benar, aku memang mempunyai nyawa rangkap tujuh. Namun aku hanya memerlukan satu nyawa saja untuk menangkap orang yang bernama Kebo Mengo.”
“Tutup mulutmu!” bentak Ki Kebo Mengo dengan muka merah padam, “Jangan hanya bersembunyi di balik bayangan semu, tidak akan ada artinya bagiku. Keluarlah, kita akan bertempur secara jantan.”
Namun jawaban bayangan itu kembali terdengar menyakitkan di telinga Ki Kebo Mengo, “Sudah aku katakan Ki Sanak, aku hanya memerlukan satu nyawa saja untuk menangkap Ki Kebo Mengo, dan inilah yang aku sebut dengan satu nyawaku itu. Aku tidak perlu menghadirkan wadagku untuk sekedar menangkap seekor kerbau!”
“Gila!” kembali Ki Kebo Mengo membentak, “Untuk apa aku melayani sebuah bayangan semu yang tak berarti? Aku tahu Ki Sanak sedang bersembunyi di sekitar tempat ini dan aku akan menemukanmu. Hanya membutuhkan waktu tidak lebih lama dari mijet wohing ranti untuk menemukan persembunyianmu.”
Selesai berkata demikian Ki Kebo Mengo segera menyilangkan kedua tangannya di depan dada sambil menundukkan wajahnya. Namun yang terjadi kemudian adalah sangat mengejutkan Ki Kebo Mengo itu sendiri. Panggraitanya telah menemukan getaran orang yang dicarinya itu berada tidak jauh di hadapannya.
“Hem!” geram Ki Kebo Mengo sambil mengurai kedua tangan dan mengangkat wajahnya. Dipandangi bayangan semu yang berdiri beberapa langkah di hadapannya itu dengan raut wajah yang terheran-heran. Menurut panggraitanya, yang berdiri di hadapannya sekarang ini bukanlah hanya sebuah bayangan semu belaka, namun benar-benar seseorang dalam ujud yang sebenarnya.
“Aneh,” berkata Ki Kebo Mengo dalam hati, “Seumur hidup aku belum pernah menjumpai ilmu sejenis ini. Namun aku yakin, sebenarnya ini hanya sejenis ilmu untuk bersembunyi sebagaimana ilmu halimunan atau sejenisnya. Aku pasti akan dapat menemukan kelemahannya.”
Berpikir sampai disitu, Ki Kebo Mengo segera maju selangkah. Katanya kemudian, “Baiklah Ki Sanak, kita akan bertempur. Aku tidak peduli lagi berapa nyawa yang akan Ki Sanak pergunakan untuk melawanku. Namun yang jelas, aku telah mengetahui kelemahan ilmumu ini, sebuah ilmu untuk bersembunyi. Di mana pun Ki Sanak bersembunyi, aku pasti akan menemukannya.”
Bayangan itu tampak menarik nafas dalam-dalam. Entah apa yang sedang ada dalam benaknya. Namun yang jelas bayangan itu segera mundur selangkah sambil berkata, “Ki Kebo Mengo, sebenarnya aku bukan orang yang suka dengan keributan. Aku menghadang Ki Kebo Mengo di tempat ini hanya untuk menuntut pertanggung-jawaban Ki Kebo Mengo atas rajapati yang baru saja terjadi.”
Terkejut Ki Kebo Mengo mendengar ucapan bayangan itu. Sebenarnya bukan kebiasaan Ki Kebo Mengo untuk berlama-lama berbantah. Dia tidak peduli siapa orang yang akan dibunuhnya dan atas dasar apa dia melakukan pembunuhan itu. Baginya membunuh itu memang sudah menjadi kebiasaan dan kadang cukup menyenangkan. Namun bayangan itu telah menyebut rajapati yang baru saja terjadi. Dengan demikian Ki Kebo Mengo dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang sekarang berdiri di hadapannya itu, apapun bentuknya tentulah salah satu dari orang yang sedang bermalam di banjar padukuhan Klangon.
Maka dengan suara berat dan dalam, Ki Kebo Mengo pun kemudian berdesis, “Apakah aku sedang berhadapan dengan agul-agulnya Mataram Ki Rangga Agung Sedayu?”
Bayangan itu sejenak termangu-mangu. Ada sedikit keseganan untuk menyebut namanya. Justru karena dia selalu berusaha menghindari kesan yang berlebihan jika seseorang mengetahui jati dirinya.
Namun akhirnya bayangan itu tampak menganggukkan kepalanya.
Berdesir dada Ki Kebo Mengo begitu menyadari sekarang ini dia sedang berhadapan dengan agul agulnya Mataram, walaupun hanya dalam bentuk ujud semu.
“Ujud semu tidak akan mempunyai pengaruh apapun selain menyesatkan pandangan sehingga penalaran pun akan menjadi buram,” berkata Ki Kebo Mengo dalam hati, “Ilmu ini sebenarnya tidak lebih dari permainan kanak-kanak. Manakala aku mampu memecahkan rahasianya, aku akan dapat menemukan tempat persembunyiannya dan sekaligus menghancurkannya.”
Ketika keyakinan itu mulai tumbuh di dalam hatinya, Ki Kebo Mengo pun mulai menggeser kedudukannya, siap untuk melancarkan serangan penjajagan.
Namun tiba-tiba sepercik keragu-raguan muncul kembali di dalam dadanya.
“Bayangan semu tidak akan mampu melukai dan dilukai. Jadi untuk apa aku harus bertempur melawan bayangan semu?” tiba-tiba pertanyaan itu menyelinap di dalam hatinya.
Untuk beberapa saat Ki Kebo Mengo justru hanya berdiri termangu-mangu. Berbagai pertimbangan bergolak di dalam dadanya.
“O,” gumam Ki Kebo Mengo dalam hati. Akhirnya sebuah kesadaran rasa-rasanya telah mengencerkan otaknya yang beku, “Aku tahu maksud Ki Rangga dengan menampilkan bayangan semunya ini. Ki Rangga berharap aku terpancing untuk bertempur sampai tenagaku terkuras habis. Pada saat itulah ujud aslinya akan muncul dan kemudian menangkapku dengan sangat mudahnya.”
Sejenak Ki Kebo Mengo menarik nafas dalam-dalam. Kesimpulan terakhir ini agaknya yang masuk akal. Namun jika memang demikian keadaannya, yang dapat dilakukannya hanyalah menunggu kemunculan ujud asli lawannya.
“Lebih baik aku meneruskan perjalananku ke banjar padukuhan,” berkata Ki Kebo Mengo dalam hati, “Jika aku tidak mampu menemukan persembunyian Ki Rangga di sekitar tempat ini, kemungkinannya dia telah mampu melontarkan ilmu bayangan semunya itu dari jarak jauh, dari banjar padukuhan Klangon.”
Berpikir sampai disitu, tanpa menghiraukan ujud semu lawannya, Ki Kebo Mengo pun segera mengayunkan langkahnya meninggalkan tempat itu.
“Ki Kebo Mengo,” tiba-tiba saja terdengar suara bayangan itu memanggilnya, “Berhentilah! Urusan kita belum selesai. Mengapa engkau begitu tergesa-gesa pergi?”
Namun Ki Kebo Mengo tidak menjawab, bahkan berpaling pun tidak. Tekadnya sudah bulat untuk tidak melayani permainan lawannya. Tujuannya hanya satu, segera sampai di banjar padukuhan Klangon dan membuat perhitungan dengan ujud asli Ki Rangga Agung Sedayu.
“Ki Kebo Mengo!” kembali terdengar bayangan itu berteriak memanggilnya, kali ini lebih keras, “Berhentilah atau aku akan menghentikanmu dengan caraku!”
Namun Ki Kebo Mengo benar-benar sudah bulat tekadnya untuk segera menyingkir dari tempat itu. Dia benar-benar sudah muak dengan permainan yang disangkanya hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang baru saja belajar loncat-loncatan dalam olah kanuragan.
Ketika melihat Ki Kebo Mengo sama sekali tidak mempedulikannya. Dengan sebuah teriakan peringatan, bayangan itu melesat menghantam punggung Ki Kebo Mengo.
Ki Kebo Mengo terkejut bukan buatan ketika merasakan ada sebuah sambaran angin yang cukup deras mengarah ke punggung. Namun semua itu sudah terlambat bagi ki Kebo Mengo untuk memutar tubuh. Yang mampu dilakukan oleh ki Kebo Mengo kemudian adalah dengan tergesa-gesa mengetrapkan ilmu pertahanan dirinya, walaupun tidak sempat sampai ke puncak untuk melindungi punggungnya.
Benturan yang terjadi kemudian memang tidak terlalu keras. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Ki Rangga hanyalah sebatas pengetahuan bagi lawannya, bahwa ujud semu yang sedang dihadapinya bukanlah ujud semu sebagaimana biasanya.
Yang terdengar kemudian adalah sebuah umpatan yang sangat kotor dari mulut Ki Kebo Mengo. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan, walaupun tidak sampai terjatuh. Namun kenyataan yang dihadapinya itulah yang telah membuat jantungnya hampir meledak. Ternyata bayangan semu Ki Rangga mempunyai kemampuan sebagaimana ujud wadag aslinya, mampu menyentuh bahkan melukai sasarannya.
Begitu pengaruh tenaga lontaran lawannya itu telah menghilang, dengan cepat Ki Kebo Mengo berbalik. Sejenak dipandanginya ujud semu Ki Rangga yang hanya berdiri beberapa langkah saja di hadapannya.
“Sebuah ilmu iblis!” geram Ki Kebo Mengo sambil menahan gejolak di dalam dadanya, “Dari mana engkau dapatkan ilmu iblis itu, he?!”
“Sudahlah Ki Kebo Mengo,” jawab bayangan itu, “Bukankah engkau tadi sudah mengatakan tidak suka berbantah? Menyerahlah. Engkau akan aku hadapkan kepada Ki Jagabaya dukuh Klangon untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatanmu.”
“Diam..!” bentak Ki Kebo Mengo dengan raut wajah merah padam, “Tidak seorang pun yang akan mampu menangkap Ki Kebo Mengo, agul-agulnya Mataram pun tidak. Apalagi ki Jagabaya dukuh Klangon. Bersiaplah Ki Rangga, aku akan segera menemukan kelemahan ilmumu. Dan disaat itulah harapanmu untuk menghirup udara esok pagi sudah tidak ada lagi.”
Selesai berkata demikian, tanpa didahului oleh sebuah ancang-ancang, Ki Kebo Mengo begitu saja melontarkan tubuhnya menerjang bayangan semu Ki Rangga.
Namun alangkah terkejutnya Ki Kebo Mengo begitu mendapatkan bayangan lawannya sama sekali tidak bergerak untuk menghindar. Serangannya yang berlandaskan pada kekuatan penuh itu menembus bayangan lawannya bagaikan menerjang angin saja. Ki Kebo Mengo justru telah terdorong oleh kekuatannya sendiri. Sejenak kemudian Ki Kebo Mengo harus menguasai lontaran tubuhnya sendiri yang meluncur dengan deras ke depan.
Disaat tubuh Ki Kebo Mengo itu terhuyung-huyung ke depan karena pengaruh dorongan kekuatannya sendiri, tiba-tiba saja bayangan Ki Rangga dengan cepat berbalik dan kali ini sebuah hantaman yang cukup keras kembali telah melanda punggung Ki Kebo Mengo.
Tubuh Ki Kebo Mengo yang sedang terhuyung ke depan itu bagaikan mendapat dorongan dua kali lipat dari kekuatannya sendiri. Akibatnya benar-benar telah membuat tubuh Ki Kebo Mengo kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya jatuh terjerembab di atas tanah yang mulai basah oleh embun malam.
“Setan, demit, iblis, gendruwo, tetekan!” sumpah serapah pun meluncur dari mulut Ki Kebo Mengo. Sambil berguling ke samping kanan untuk menghindari kemungkinan serangan susulan lawan, dengan sigap Ki Kebo Mengo pun segera melenting berdiri.
Sambil mengusap wajahnya yang penuh dengan debu, terdengar Ki Kebo Mengo menggeram, “Ki Rangga, aku mengakui kedahsyatan ilmumu, namun jangan berbangga dulu. Rahasia ilmu petak umpetmu ini sebentar lagi akan kau temukan dan kebesaran nama Ki Rangga Agung Sedayu, agul-agulnya Mataram hanya akan tinggal nama saja.”
Tampak bayangan itu seolah menarik nafas panjang. Berkata bayangan itu kemudian, “Terima kasih atas pujian Ki Kebo Mengo. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu Ki Kebo Mengo menemukan rahasia ilmuku.”
“Tutup mulutmu!” bentak Ki Kebo Mengo sambil kembali melontarkan serangan. Namun kali ini Ki Kebo Mengo tidak ingin mengulangi kesalahannya. Serangannya yang meluncur deras itu hanya sekedar sebagai pancingan saja.
Diam-diam dalam hati Ki Kebo Mengo tersenyum gembira begitu melihat bayangan lawannya diam tak bergerak. Dengan demikian Ki Kebo Mengo berharap kejadian sebelumnya akan berulang. Serangannya hanya akan menembus bayangan kosong. Pada saat tubuhnya meluncur ke depan, begitu kakinya menginjak tanah, dia sudah berencana untuk melenting ke samping sehingga jika bayangan lawannya itu balik menyerangnya, dia sudah siap untuk membenturkan ilmunya.
“Bayangan semu Ki Rangga akan menampakkan kekuatannya jika dia menyerang,” demikian Ki Kebo Mengo mengambil kesimpulan di dalam hati, “Jika aku ingin menyentuhnya sebagaimana menyentuh bentuk wadagnya, aku harus membenturkan kekuatanku justru pada saat dia menyerang.”
Berbekal keyakinan itulah Ki Kebo Mengo tidak mengerahkan kekuatan penuh pada saat dia menyerang. Kakinya yang terjulur lurus mengarah dada itu meluncur tanpa kekuatan penuh.
Namun yang terjadi kemudian kembali membuat Ki Kebo Mengo harus mengumpat dengan umpatan sekotor-kotornya. Agaknya bayangan lawannya itu mampu mengetahui kekuatan yang tersimpan dalam serangannya berdasarkan desir angin yang mendahuluinya. Dengan mengerahkan kekuatan yang cukup besar, bayangan Ki Rangga itu justru telah membenturkan kekuatannya dengan menyilangkan kedua tangannya di depan dada.
Akibatnya serangan Ki Kebo Mengo bagaikan membentur dinding baja setebal satu jengkal. Tubuh Ki Kebo Mengo pun terlempar ke belakang dan melayang bagaikan selembar daun kering yang tertiup angin puyuh, sebelum akhirnya jatuh bergulingan di atas tanah.
Entah sudah untuk ke berapa kalinya Ki Kebo Mengo mengeluarkan umpatan yang sangat kasar. Dadanya rasa-rasanya bagaikan meledak mendapatkan dirinya menjadi bulan-bulanan lawannya. Sambil melenting berdiri dan kemudian berdiri di atas kedua kakinya yang renggang, Ki Kebo Mengo mulai menilai kekuatan ilmu lawannya yang ternyata sangat ngedab-edabi itu.
“Hem,” desah Ki Kebo Mengo dalam hati sambil mencoba menguasai gejolak di dalam dadanya, “Ternyata ilmu Ki Rangga benar-benar ngedab-edabi. Jika dalam waktu dekat aku belum bisa menemukan kelemahannya, aku hanya akan menjadi bulan-bulanan saja seperti seekor tikus pithi di tangan seekor kucing yang garang.”
Untuk beberapa saat Ki Kebo Mengo tidak tahu harus berbuat apa. Dari pengalamannya melakukan serangan sebanyak dua kali, semuanya berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, apa yang telah terjadi itu merupakan aib yang akan mencoreng nama besarnya.
“Pantas bayangan Ki Rangga ini hanya menunggu serangan,” kembali Ki Kebo Mengo berkata dalam hati, “Disitulah letak kunci rahasianya. Dia hanya menunggu lawan untuk menyerangnya dan kemudian dia akan menjebak lawannya dengan kemampuan ilmunya yang mampu mengelabuhi itu.”
Dalam pada itu, selagi Ki Kebo Mengo masih menduga-duga rahasia di balik aji pengangen-angen Ki Rangga Agung Sedayu, dua pasang mata tampak sedang mengawasi mereka dari tempat yang cukup jauh.
“Raden,” bisik seseorang yang tampak sudah sangat tua renta namun terlihat sangat sehat dan kuat, “Aku pernah menghadapi dan merasakan langsung kedahsyatan ilmu Ki Rangga Agung Sedayu itu. Ilmu itu kelihatannya merupakan perkembangan dari ilmu bayangan semu. Sudah sangat jarang orang yang mampu menguasai ilmu itu untuk saat ini. Selama ini memang pernah ada cerita tentang kesaktian tokoh-tokoh di masa lalu. Mereka itu dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Namun apakah mereka itu juga mempunyai kekuatan yang sama dengan ujud aslinya, itu yang belum pernah aku dengar.”
Orang yang berdiri di sebelahnya tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, “Cerita itu memang pernah aku dengar, salah satunya adalah Maha Patih Gajah Mada. Bahkan menurut cerita yang tidak jelas sumbernya, Panembahan Senapati juga mampu melakukan hal itu walaupun kebenarannya sangat meragukan.”
“Raden benar,” sahut orang tua itu, “Memang pernah tersebar cerita tentang Panembahan Senapati yang mampu berada di beberapa tempat di saat yang bersamaan. Namun aku cenderung menganggap itu cerita ngayawara dari orang-orang Mataram sendiri yang sengaja ingin membesar-besarkan nama Panembahan Senapati.”
Sejenak kedua orang itu terdiam. Perhatian mereka kembali tertuju kepada Ki Kebo Mengo yang tampak mulai mempersiapkan diri untuk kembali menyerang bayangan semu Ki Rangga Agung Sedayu. Namun kali ini Ki Kebo Mengo tampak masih berputar-putar saja dan belum mulai menyerang. Agaknya dia sedang membuat perhitungan-perhitungan dengan mencoba untuk memancing lawannya agar menyerang terlebih dahulu.
“Ki Kebo Mengo hanya membuang-buang waktu saja,” desis orang tua renta itu kemudian begitu melihat Ki Kebo Mengo mulai bergerak berputar-putar.
“Eyang Guru,” berkata orang yang di sebelahnya itu kemudian, “Dimana kah sebenarnya kelemahan ilmu Ki Rangga itu?”
“Raden,” jawab orang tua renta yang ternyata adalah Eyang Guru, “Sangat sulit untuk mengalahkan sebuah bayangan semu. Jika ingin menghancurkan ilmu itu, kita harus menghancurkan sumbernya.”
Orang yang dipanggil Raden itu mengerutkan keningnya. Dengan nada sedikit ragu dia kemudian bertanya, “Maksud Eyang Guru, kita langsung menyerang ujud asli Ki Rangga? Tapi bukankah kita tidak tahu di mana dia sekarang ini sedang bersembunyi?”
Eyang Guru tersenyum menanggapi pertanyaan orang yang dipanggilnya Raden itu. Jawabnya kemudian, “Memang agak rumit dan membutuhkan waktu untuk melacak keberadaan ujud asli Ki Rangga. Harus melalui benturan ilmu yang berkali-kali. Namun sekarang kita tidak perlu melakukan itu. Kita dapat langsung mencari ujud asli Ki Rangga dan langsung membunuhnya.”
Kembali orang yang dipanggil Raden itu memandang ke arah Eyang Guru dengan sorot mata ragu-ragu.
Agaknya Eyang Guru tidak mau berteka-teki terlalu lama. Maka katanya kemudian, “Marilah kita menuju ke banjar padukuhan Klangon. Aku yakin bayangan semu itu dipancarkan dari arah sana. Bukankah menurut berita telik sandi kita, ada lima orang asing yang sedang bermalam di banjar padukuhan Klangon?” Eyang Guru berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Aku yakin Ki Rangga sekarang ini sedang dalam puncak samadinya. Jika kawan-kawannya yang lain mungkin melindunginya, itu menjadi tugasku untuk menyingkirkan mereka. Sementara Raden dapat membunuh Ki Rangga dengan sangat mudahnya. Tubuh Ki Rangga akan sangat lemah tanpa perlindungan sama sekali ketika sedang dalam puncak samadinya.”
Orang yang dipanggil Raden itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika dilihatnya Eyang Guru mulai melangkahkan kakinya meninggalkan tempat ini, dengan bergegas dia pun segera mengikuti langkah orang tua itu.
“Kita berjalan agak melingkar agar tidak terpantau oleh Ki Rangga,” berkata Eyang Guru kemudian sambil menyusup gerumbul liar di sisi jalan.
“Bagaimana dengan Ki Kebo Mengo?” bertanya orang yang dipanggil Raden itu sambil ikut berjalan merunduk-runduk.
Sejenak Eyang Guru menegakkan tubuhnya untuk melihat keadaan Ki Kebo Mengo yang terlihat mulai terlibat dalam pertempuran. Jawabnya kemudian, “Biarlah untuk sementara Ki Kebo Mengo meladeni bayangan semu Ki Rangga. Dengan demikian Ki Rangga akan lengah dan tidak menyadari bahwa bahaya sedang menuju ke tempat samadinya.”
“Eyang Guru,” bertanya kembali orang yang dipanggil Raden itu, “Apa yang akan terjadi jika Ki Rangga menyadari bahwa bahaya sedang mengancam jiwanya?”
“Dia akan menghentikan samadinya sehingga kita akan berhadapan langsung dengan wadag Ki Rangga, dan itu akan sama berbahayanya dengan bayangan semunya itu,” sahut Eyang Guru cepat.
Orang yang dipanggil Raden itu mengerutkan keningnya sambil mengikuti kembali langkah Eyang Guru. Agaknya masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Maka tanyanya kemudian, “Bayangan semu Ki Rangga memang tidak dapat tersentuh, namun ujud wadagnya berbeda, kita dapat menyentuh bahkan melukainya. Apa sebenarnya yang perlu kita takutkan?”
Eyang Guru sekilas berpaling ke belakang sambil tertawa perlahan. Jawabnya kemudian, “Raden Surengpati, dalam ujud aslinya Ki Rangga memiliki ilmu kebal yang sangat sulit untuk ditembus. Selain itu Ki Rangga telah menguasai ilmu kakang pembarep dan adi wuragil yang hampir sempurna. Maksudku, kedua ujud semunya itu akan mempunyai kekuatan yang sama dengan aslinya sehingga jika Ki Rangga mengetrapkan ilmu itu, kita akan bertempur seperti melawan tiga orang Ki Rangga sekaligus.”
Berdesir dada Raden Mas Harya Surengpati. Begitu dahsyatnya ilmu-ilmu yang tersimpan dalam diri Ki Rangga Agung Sedayu itu.
“Pantas Ki Rangga menjadi agul-agulnya Mataram,” berkata Raden Surengpati dalam hati, “Jika Eyang Guru saja menghindari bertemu langsung dengan Ki Rangga, siapa lagi di antara kita yang akan mampu menahan agul-agulnya Mataram itu?”
Tiba-tiba Raden Mas Harya Surengpati teringat akan Kakandanya yang sampai saat ini masih belum hadir di antara para pengikutnya.
“Kakangmas Wirasena sedang membuat hubungan dengan perguruan Sapta Dhahana,” berkata Raden Surengpati dalam hati sambil terus berjalan mengikuti langkah Eyang Guru, “Jika perguruan Sapta Dhahana tidak berkeberatan membantu perjuangan kami, tentu Kiai Damar Sasangka pemimpin perguruan Sapta Dhahana akan mampu mengimbangi kemampuan Ki Rangga Agung Sedayu.”
Sejenak kemudian kedua orang itu harus berjalan menjauhi lingkaran pertempuran antara Ki Rangga melawan ki Kebo Mengo. Sesekali mereka berdua harus meloncati pagar halaman yang cukup tinggi dan melintasi halaman-halaman yang sepi.
“Eyang Guru,” berkata Raden Surengpati kemudian sambil terus mengikuti langkah Eyang Guru, “Selain berita dari telik sandi sore tadi, aku juga menerima berita dari orang-orangnya gegedug Dukuh Salam yang biasa dipanggil dengan sebutan Ki Lurah itu,” Raden Surengpati berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Menurut orang-orangnya Ki Lurah, salah satu dari kelima orang itu ada yang mempunyai kemampuan bermain sihir. Kejadian itu mereka alami ketika mereka sedang mengumpulkan derma di sekitar Kali Krasak. Salah satu dari kelima orang itu telah menyumbangkan berbagai perhiasan emas dan sebuah keris berpendok emas. Namun ternyata mereka telah menjadi korban permainan sihir.”
Eyang Guru tidak menjawab. Sambil berjalan terbungkuk-bungkuk dia dengan cepat melintasi halaman sebuah rumah yang tampak kosong, tidak ada seberkas sinar pun yang terlihat menembus keluar dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari bambu itu.
“Eyang Guru?” Raden Mas Harya Surengpati mengulangi pertanyaannya dengan suara sedikit keras.
“Aku sudah dengar, Raden!” sahut Eyang Guru dengan nada sedikit kesal tanpa menghentikan langkahnya, “Aku tidak peduli siapa kelima orang itu, dan sampai setinggi apa kemampuan mereka, kecuali Ki Rangga Agung Sedayu. Permainan sihir bagiku tak lebih dari sebuah permainan kanak-kanak.”
Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan detak jantung di dalam dadanya yang tiba-tiba saja melonjak-lonjak. Sebenarnya dia ingin menyampaikan sesuatu yang menurut pertimbangannya sangat penting. Namun agaknya Eyang Guru sama sekali tidak peduli. Sifat orang yang disebut Eyang Guru itu memang agak aneh. Karena usianya yang sudah sangat tua, kadang-kadang dia menjadi sedikit pikun dan mudah tersinggung serta menjengkelkan.
Tidak terasa kedua orang itu sudah cukup jauh meninggalkan medan pertempuran antara Ki Kebo Mengo melawan Ki Rangga Agung Sedayu. Ketika kedua orang itu telah melintasi sebuah halaman yang cukup luas dari sebuah rumah yang cukup bagus, keduanya pun kemudian memutuskan untuk kembali ke jalur jalan Padukuhan Klangon kembali.
“Eyang Guru,” bertanya Raden Surengpati kemudian sekali lagi untuk menyampaikan sesuatu yang membebani hatinya, “Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang di banjar padukuhan itu? Mereka berlima dan kita hanya berdua saja.”
Eyang Guru menghentikan langkahnya sebelum mencapai regol halaman rumah itu. Jawabnya kemudian sambil memutar tubuhnya, “Raden, sudah aku katakan sedari tadi. Aku tidak peduli dengan kelima orang itu, kecuali Ki Rangga Agung Sedayu. Bagiku tidak ada kekuatan orang-orang Mataram yang perlu diperhitungkan kecuali hanya Ki Rangga Agung Sedayu.”
“Bagaimana dengan Ki Juru Mertani?” desak Raden Surengpati.
Untuk sejenak Eyang Guru justru terdiam. Hanya sepasang matanya saja yang menatap tajam ke arah Raden Surengpati. Namun pada akhirnya Eyang Guru itu pun menjawab juga, “Ki Juru Mertani dikenal karena olah pikirnya saja yang sangat cerdas. Perhitungan-perhitungannya selalu berdasarkan atas penalaran serta pengalaman yang diperolehnya sehingga menjadi sangat tajam dan terpercaya. Namun kemampuan ilmu olah kanuragannya sendiri aku tidak yakin sedahsyat dan sebanding dengan Mas Karebet yang kemudian menjadi Sultan di Pajang, walaupun dapat dikatakan mereka pernah menimba ilmu dari sumber yang sama.”
Sekarang giliran Raden Surengpati yang termenung. Berbagai pertimbangan telah bergolak di dalam dadanya. Namun akhirnya Raden Surengpati pun menyampaikan juga apa yang selama ini membebani hatinya, “Eyang Guru, aku justru mencurigai salah satu dari mereka adalah Ki Juru Mertani sendiri.”
“He?!” bagaikan disengat ribuan kalajengking Eyang Guru terperanjat mendengar kata-kata Raden Surengpati, “Apa pertimbangan Raden?”
Raden Mas Harya Surengpati menarik nafas dalam-dalam sambil melemparkan pandangan matanya ke kejauhan. Jawabnya kemudian dengan perlahan, “Aku hanya menduga-duga saja sesuai dengan cerita orang-orangnya Ki Lurah gegedug dukuh Salam. Di antara kelima orang itu ada seseorang yang tampak sudah sangat tua namun terlihat masih kuat dan sehat. Orang tua itulah yang dikatakan mampu bermain sihir. Mungkin saja orang tua itu adalah Ki Juru Mertani.”
Sejenak Eyang Guru bagaikan membeku di tempatnya. Bagaimana pun juga, dugaan akan kehadiran Ki Juru Mertani di antara kelima orang itu harus diperhitungkan. Jika semula dia menganggap hanya Ki Rangga yang perlu mendapat perhatian, kini dugaan adanya Ki Juru Mertani yang ikut bermalam di banjar padukuhan Klangon itu telah membuat jantung tuanya berdetak semakin cepat.
“Apa boleh buat!’ geram Eyang Guru pada akhirnya, “Kita akan melihat kekuatan mereka terlebih dahulu. Jika memang orang tua dari Sela yang tak tahu diri itu ada di antara mereka, kita harus segera membuat hubungan dengan Kiai Damar Sasangka dan Raden Wirasena.”
Raden Surengpati mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Segala kemungkinan memang harus diperhitungkan agar jangan sampai justru mereka sendiri yang akan terjebak dalam lingkaran kekuatan yang tidak mampu mereka atasi.
“Marilah,” berkata Eyang Guru kemudian sambil memutar tubuhnya, “Kita akan melihat kekuatan kelima orang itu terlebih dahulu sebelum menentukan langkah kita selanjutnya.”
Raden Mas Harya Surengpati tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk sambil melangkah mengikuti Eyang Guru.
Sejenak kemudian mereka berdua segera meneruskan langkah mendekati regol halaman yang terlihat diselarak dari dalam. Setelah mengangkat selarak pintu regol itu terlebih dahulu, keduanya pun segera mendorong pintu regol dan melangkahkan kaki mereka keluar menuju ke jalur jalan padukuhan Klangon.
Namun alangkah terkejutnya mereka berdua. Jantung kedua orang itu bagaikan terlepas dari tangkainya begitu kaki mereka melangkah ke jalur jalan padukuhan Klangon. Beberapa tombak di hadapan mereka, tampak bayangan seseorang dengan sengaja sedang berdiri menunggu sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada.
STSD 02_25
“Ki Rangga Agung Sedayu?” hampir bersamaan kedua orang itu berdesis perlahan namun terdengar suara mereka bergetar seiring dengan degup jantung mereka yang tiba-tiba saja telah melonjak-lonjak tak terkendali.“Bagaimana mungkin?” terdengar Eyang Guru kembali berdesis sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam, “Apakah Ki Kebo Mengo sedemikian mudahnya dapat ditundukkan oleh Ki Rangga?”
“Belum tentu,” sergah Raden Surengpati dengan dada berdebaran. Pandangan matanya tak pernah lepas dari ujud bayangan Ki Rangga yang berdiri beberapa tombak di depannya, “Ki Kebo Mengo adalah orang kepercayaan Kakangmas Wirasena. Aku yakin ujud bayangan semu Ki Rangga lah yang melarikan diri.”
“Melarikan diri?” ulang Eyang Guru dengan nada keheranan, “Melarikan diri karena kalah beradu ilmu dengan si Kerbau bodoh itu?”
Sejenak merah padam wajah Raden Surengpati. Namun dengan cepat kesan itu dihapus dari wajahnya. Katanya kemudian, “Maksudku, Ki Rangga mungkin mengetahui gerak-gerik kita dan memutuskan untuk mengejar kita berdua.”
Eyang Guru sejenak tertegun. Jika memang benar Ki Rangga telah mengetahui gerak-gerik dirinya dan Raden Surengpati, tentu agul-agulnya Mataram itu telah mencapai tingkat yang nyaris sempurna dalam menguasai panggraitanya untuk melacak keberadaan seseorang.
Namun selagi kedua orang itu menduga-duga apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Ki Kebo Mengo, tiba-tiba saja bayangan semu Ki Rangga perlahan-lahan menghilang bagaikan asap yang tertiup angin kencang.
“He?!” hampir bersamaan keduanya berseru tertahan. Detak jantung mereka yang semula mulai tenang kini melonjak-lonjak kembali.
“Apakah sebenarnya yang telah terjadi?” bertanya Raden Surengpati dengan kening yang berkerut-merut. Sementara Eyang Guru yang berdiri di sebelahnya segera menundukkan kepalanya serta menyilangkan kedua tangannya di depan dada.
Eyang Guru hanya memerlukan waktu sekejab untuk menilai keadaan di sekelilingnya. Sejenak kemudian, Eyang Guru pun telah mengangkat wajahnya serta mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada.
“Ki Rangga telah pergi,” desis Eyang Guru kemudian sambil menarik nafas panjang.
Raden Surengpati yang berada di sebelahnya berpaling. Dengan nada sedikit ragu-ragu, Raden Surengpati pun kemudian bertanya, “Pergi? Mengapa?”
Kembali Eyang Guru menarik nafas dalam. Jawabnya kemudian, “Entahlah. Aku tidak dapat menduga permainan apakah yang sedang ditunjukkan oleh Ki Rangga? Namun yang jelas, ilmu Ki Rangga dari hari ke hari rasa-rasanya semakin tinggi dan mumpuni. Aku khawatir, jika tidak segera dihentikan, cita-cita Trah Sekar Seda Lepen hanya akan tinggal mimpi belaka.”
Berdesir dada Raden Surengpati. Namun di dalam hatinya masih ada sepercik harapan. Jika Kakandanya mampu menarik Kiai Damar Sasangka untuk bergabung, mereka akan mempunyai kekuatan yang setara bahkan mungkin lebih tinggi dibanding dengan kekuatan Mataram.
“Sudahlah,” berkata Eyang Guru kemudian membuyarkan lamunan Raden Surengpati, “Lebih baik kita kembali saja. Aku mempunyai rencana untuk pergi ke gunung Tidar selepas tengange. Ada yang harus segera kita bicarakan dengan Raden Wirasena dan para penghuni perguruan Sapta Dhahana itu.”
Selesai berkata demikian tanpa menunggu tanggapan Raden Surengpati, Eyang Guru segera melangkahkan kaki kembali menuju ke Perdikan Matesih. Sementara Raden Surengpati dengan tergesa-gesa segera mengikuti di belakangnya.
Demikianlah akhirnya, kedua orang itu telah memutuskan untuk kembali ke Tanah Perdikan Matesih. Agaknya Eyang Guru telah memperhitungkan untung ruginya jika harus berhadapan dengan kelima orang yang sedang bermalam di dukuh Klangon itu. Jika dugaan Raden Surengpati benar bahwa Ki Juru Mertani ada di antara kelima orang itu, Trah Sekar Seda Lepen harus benar-benar berhitung cermat dalam mengukur kekuatan mereka.
Sejenak kemudian kedua orang itu telah menyusuri jalan dukuh Klangon yang sepi. Kali ini mereka tidak melewati halaman-halaman rumah yang sepi serta meloncati pagar-pagar yang tinggi. Mereka menyusuri jalan sebagaimana biasanya, tidak harus dengan cara sembunyi-sembunyi.
Namun belum ada sepenginang sirih mereka berdua berjalan, pendengaran Eyang Guru yang lebih tajam dibanding Raden Mas Harya Surengpati telah menangkap desir lembut dari arah yang berlawanan sedang menuju ke tempat mereka.
Segera saja Eyang Guru menghentikan langkahnya.
“Ada apa?” bertanya Raden Surengpati sambil ikut menghentikan langkahnya.
Eyang Guru tidak segera menjawab. Langkah itu memang masih cukup jauh, namun pendengaran Eyang Guru yang luar biasa tajamnya telah mampu menangkapnya.
“Eyang Guru,” kembali Raden Surengpati bertanya, “Apakah Eyang Guru melihat sesuatu yang mencurigakan?”
Eyang Guru menarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu sebelum menjawab. Katanya kemudian setengah berbisik, “Yang datang kemudian ini menurut pengamatanku juga termasuk orang yang mumpuni menilik desir langkahnya yang sangat lembut. Namun aku yakin ini bukan bayangan semu Ki Rangga. Sebuah bayangan semu tidak dapat dikenali desir langkahnya, karena dia hanya berupa sebuah bayangan.”
“Karena itulah kehadiran bayangan semu Ki Rangga beberapa saat tadi tidak dapat diketahui oleh Eyang Guru,” sahut Raden Surengpati.
“Benar Raden,” jawab Eyang Guru, “Aku dapat mengenalinya jika bayangan itu sudah berujud. Namun jika dia menghilang, aku yakin tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk melacaknya. Itulah sebabnya ilmu Ki Rangga itu benar-benar tidak ada duanya. Jika Ki Rangga mampu mematangkannya, seorang diri saja dia akan mampu menggulung jagad.”
Raden Surengpati mengangguk-anggukkan
kepalanya. Sementara suara desir langkah itu telah menjadi semakin dekat
sehingga kini adik orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu pun
sudah mampu mendengarnya.
Sejenak kemudian, pandangan mata Eyang Guru yang melebihi orang
kebanyakan itu segera menangkap dan mengenali sesosok tubuh yang sedang
berjalan dalam kegelapan. Eyang Guru pun menarik nafas dalam-dalam untuk
mengurangi getar di dalam dadanya.“Marilah Raden,” berkata Eyang Guru kemudian, “Kita temui Ki Kebo Mengo. Sekalian kita bicarakan rencana kita untuk ke Padepokan Sapta Dhahana nanti menjelang tengange.”
Raden Surengpati masih ragu-ragu sejenak. Namun ketika pandangan matanya sudah mampu menangkap dan mengenali sesosok tubuh yang berjalan mendekat itu, wajah Raden Surengpati pun menjadi cerah. Sambil tersenyum dan mengangguk-angguk, dia segera mengikuti langkah Eyang Guru.
Dalam pada itu di banjar padukuhan, Ki Rangga yang sedang dalam puncak samadinya itu ternyata telah terganggu oleh sesuatu hal yang belum dimengertinya. Sehingga perlahan-lahan pemusatan nalar dan budi Ki Rangga pun mulai memudar seiring dengan kesadaran yang mulai memenuhi otaknya. Sejenak kemudian Ki Rangga pun telah terjaga dari samadinya dan tersadar sepenuhnya.
“Apa yang sebenarnya telah terjadi, ngger?” pertanyaan itulah yang pertama kali didengar oleh Ki Rangga begitu dia membuka kedua matanya.
Sambil bangkit dan kemudian duduk bersila, Ki Rangga berpaling ke arah Ki Waskita yang duduk di sebelahnya. Jawabnya kemudian, “Ki Waskita, aku merasakan sesuatu yang aneh telah terjadi dalam samadiku.”
Ki Waskita mengerutkan keningnya dalam-dalam. Katanya kemudian, “Angger sedang dalam puncak samadi ketika tiba-tiba saja aku menyadari angger sepertinya mengalami sedikit gangguan dan kemudian samadi angger pun telah badar.”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggeser duduknya menghadap penuh ke arah Ki Waskita, Ki Rangga pun kemudian menceritakan pengalaman yang didapatkannya selama dalam puncak samadinya.
“Ketika aku sedang berhadapan dengan orang yang menyebut dirinya Ki Kebo Mengo,” demikian Ki Rangga memulai ceritanya, “Panggraitaku telah menangkap adanya gerakan dari dua orang yang sedang berada di sekitar tempat itu.”
“Apakah angger mengenali mereka?” potong Ki Waskita dengan nada sedikit tidak sabar.
“Ya, Ki,” jawab Ki Rangga, “Aku mengenal salah satu dari mereka adalah orang yang pernah berselisih denganku di kediaman Ki Gede Menoreh beberapa saat yang lalu.”
Mendengar penjelasan Ki Rangga, Ki Waskita pun segera teringat dengan peristiwa yang terjadi di kediaman Ki Gede Menoreh. Maka tanya Ki Waskita kemudian, “Apakah yang angger maksud itu adalah salah satu pengikut Trah Sekar Seda Lepen yang menyebut dirinya Eyang Guru?”
“Benar, Ki,” sahut Ki Rangga dengan serta merta. Lanjutnya kemudian, “Dan yang satunya adalah orang yang selama ini menghantui tanah Perdikan Matesih, Raden Mas Harya Surengpati.”
Ki Waskita mengerutkan keningnya. Tanya Ki Waskita kemudian, “Bagaimana angger bisa mengetahuinya?”
“Aku mendengar Eyang Guru menyebut namanya,” jawab Ki Rangga, “Namun ternyata mereka berdua tidak ikut melibatkan diri dengan Ki Kebo Mengo. Eyang Guru lebih memilih menuju ke banjar padukuhan.”
Sejenak wajah Ki Waskita menegang. Berbagai tanggapan telah muncul dalam benaknya. Namun sebelum Ki Waskita bertanya lebih jauh, ternyata Ki Rangga segera memberi penjelasan.
“Ki Waskita,” berkata Ki Rangga kemudian, “Ternyata Eyang Guru itu telah mengetahui kelemahan aji pengangen-angen. Dengan sangat yakin Eyang Guru berencana untuk mendapatkan wadagku yang sedang dalam puncak samadi dan kemudian dengan sangat mudahnya dia akan membunuhku.”
Ki Waskita menarik nafas panjang mendengar keterangan Ki Rangga. Untuk beberapa saat ayah Rudita itu termenung. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa dari segala yang berkuasa di muka bumi ini. Aji pengangen-angen pada dasarnya adalah sebuah aji sang sangat ngedab-edabi, namun mempunyai satu kelemahan, yaitu justru terletak pada wadag orang yang menguasai ilmu itu sendiri.
Kembali Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bertanya Ki Waskita selanjutnya, “Apakah angger kemudian memutuskan untuk meninggalkan Ki Kebo Mengo dan mengejar mereka berdua?”
Ki Rangga tidak segera menjawab. Untuk beberapa saat Ki Rangga masih mencoba menilai apa yang telah dilakukannya beberapa saat yang lalu.
STSD Jilid 3
Bagian 1
KETIKA Ki Rangga kemudian mendengar Ki Waskita
terbatuk-batuk kecil, barulah Ki Rangga teringat akan pertanyaan Ki
Waskita itu. Maka jawabnya kemudian, “Ki Waskita, pada awalnya memang
ada niat untuk meninggalkan Ki Kebo Mengo dan kemudian mengejar Eyang
Guru. Namun entah mengapa tiba-tiba saja terbersit di dalam hatiku untuk
mengetrapkan aji kakang pembarep dan adi wuragil sekaligus. Dengan
demikian aku berharap kedua ujud semuku akan dapat menghadapi
lawan-lawanku secara terpisah,” Ki Rangga berhenti sejenak. Lanjutnya
kemudian, “Namun yang terjadi kemudian justru telah membuat aku
benar-benar tidak habis mengerti. Dengan mengetrapkan aji kakang
pembarep dan adi wuragil, pengetrapanku terhadap aji pengangen-angen
menjadi melemah dan akhirnya aku tersadar dari samadiku.”Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan Ki Rangga. Setelah terdiam beberapa saat, barulah dengan suara yang sangat sareh Ki Waksita pun berkata, “Ngger, memang tidak ada ilmu yang sempurna di atas bumi ini. Pada dasarnya aji kakang pembarep dan adi wuragil mempunyai sifat dan watak yang berbeda dengan aji pengangen-angen, walaupun keduanya bertumpu pada ujud semu yang sama,” Ki Waskita berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Aji kakang pembarep adi wuragil menuntut kehadiran wadagmu sedekat mungkin, bahkan menuntut wadagmu untuk ikut dalam setiap keberadaan ujud semu itu. Sedangkan aji pengangen-angen tidak menuntut akan kehadiran ujud wadagmu. Justru aji pengangen-angen akan meninggalkan wadagmu sejauh dapat engkau lakukan, menyeberangi lautan misalnya. Semua itu tergantung dari kekuatan pancaran ilmu dari sumbernya, yaitu wadagmu sendiri.”
Sejenak Ki Rangga termenung. Berbagai tanggapan dan harapan sedang bergolak di dalam dadanya.
“Dalam sebuah kancah pertempuran pasukan segelar sepapan yang sebenarnya, aji pengangen-angen ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain,” berkata ki Waskita selanjutnya, “Kehadirannya mungkin akan sempat membingungkan lawan. Namun jika lawan sempat mengetahui kelemahannya dan menemukan tempat persembunyian ujud wadagnya, tentu akan sangat berbahaya. Demikian juga jika seseorang diminta secara khusus untuk menjaga wadagnya selama dia dalam puncak samadinya, siapakah yang dapat menjamin jika orang yang menjaganya itu tidak akan berkhianat?”
Ki Rangga masih berdiam diri dan belum menanggapi penjelasan Ki Waskita. Angan-angannya sedang menerawang entah ke mana.
“Ngger,” berkata Ki Waskita seterusnya begitu melihat Ki Rangga masih termangu-mangu, “Berbeda dengan aji kakang pembarep dan adi wuragil yang kehadirannya di medan pertempuran yang sebenarnya akan sangat berarti. Lawan akan memperhitungkan keberadaan bentuk semu itu karena engkau telah mampu memancarkan ilmumu melalui kedua ujud semu itu. Sehingga lawan akan mendapatkan perlawanan tiga kali lipat dari kekuatan yang sesungguhnya,” Ki Waskita berhenti sejenak sambil mencoba mengamati raut wajah Ki Rangga. Lanjutnya kemudian, “Jika angger ingin menggabungkan kedua aji itu, tentu diperlukan laku khusus yang tentu akan melibatkan persyaratan dari kedua cabang ilmu itu. Dengan demikian, apabila seseorang telah mampu menguasai gabungan kedua aji tersebut, dia akan benar-benar mampu menjaga wadagnya dengan salah satu bentuk semunya, sedangkan bentuk semu yang lain akan mampu bergerak ke tempat yang sangat jauh, sejauh angan-angan dari manusia itu sendiri.”
Kali ini Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Walaupun tampaknya memang masih ada yang membebani pikirannya.
Agaknya Ki Waskita dapat membaca wajah Ki Rangga yang terlihat sedang menyimpan sebuah beban dalam hatinya itu. Maka katanya kemudian, “Ngger, aku melihat sebuah kegelisahan yang terpancar pada wajah angger. Jika memang aku boleh mengetahuinya, apakah sebenarnya yang masih menjadi beban di hati angger?”
Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu sebelum menjawab. Setelah membetulkan letak duduknya, barulah Ki Rangga menjawab, “Ki Waskita, penggabungan aji kakang pembarep dan adi wuragil dengan aji pengangen-angen itu sebaiknya kita pikirkan di kemudian hari,” Ki Rangga berhenti sejenak untuk sekedar menarik nafas panjang. Lanjutnya kemudian, “Adapun yang masih membebani hatiku sampai saat ini adalah, sejak aku mendalami aji pengangen-angen, aku merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi dalam diriku, terutama panggraitaku. Beberapa kali aku merasakan sepertinya aku mendapatkan firasat tentang sesuatu. Ketika aku menganggapnya itu hanyalah sebagai bentuk kegelisahanku saja, ternyata firasat itu benar-benar terjadi. Namun tidak jarang aku tidak mampu mengurai makna firasat itu sehingga yang terjadi kemudian hanyalah sebuah kegelisahan yang tak berujung pangkal. Aku tidak tahu apakah kejadian dalam diriku ini ada hubungannya dengan usahaku untuk menekuni aji pengangen-angen?”
Untuk beberapa saat Ki Waskita termenung. Setelah menarik nafas dalam-dalam, barulah Ki Waskita menjawab, “Ngger, agaknya angger sedang mengalami keadaan yang sebenarnya wajar bagi angger. Aji pengangen-angen itu pada awalnya adalah suatu bentuk ilmu yang hanya berlandaskan pada sebuah angan-angan. Kemudian dengan memusatkan nalar dan budi serta menyelaraskan ilmu itu dengan pikiran serta persangkaan orang lain, maka akan terciptalah bentuk-bentuk semu sesuai dengan apa yang ada di dalam angan-angan kita,” Ki Waskita berhenti sejenak untuk membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba saja menjadi kering. Lanjutnya kemudian, “Semasa mudaku dulu, aku hanya mampu mempelajari sampai batas ini, walaupun guruku telah memberikan tuntunan sampai sejauh apa yang telah tertulis dalam kitab perguruan kami. Aku memang terlampau puas dengan apa yang telah aku capai waktu itu, tanpa memperhitungkan bahwa ternyata ilmu itu jika disempurnakan dan dikembangkan akan mempunyai kekuatan yang sangat ngedab-edabi.”
Ki Rangga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk. Sementara Ki Waskita meneruskan kata-katanya, “Dalam mendalami ilmu ini, aku pun pada awalnya juga mengalami seperti apa yang sedang engkau alami, ngger. Ketika hal itu aku sampaikan kepada guruku, ternyata aku telah diberi wawasan yang luas bagaimana cara mempelajari dan kemudian mempertajam panggraita kita dalam menyikapi peristiwa itu. Aku pun kemudian justru telah tertarik untuk mengembangkan ilmu dalam mengurai isyarat yang merupakan cabang dari aji pengangen-angen dan telah mengabaikan kelanjutan dari aji pengangen-angen itu sendiri sehingga kemampuanku tidak lebih dari sebuah permainan kanak-kanak,” Ki Waskita berhenti sejenak sambil kembali mencoba mengamati perubahan wajah Ki Rangga. Namun Ki Rangga hanya menundukkan kepalanya saja. Maka Ki Waskita pun melanjutkan kata-katanya, “Ngger, jika memang engkau tertarik dengan ilmu dalam mengurai isyarat ini, usahakan untuk mendalami dan meresapi setiap isyarat yang muncul. Memang kadang-kadang kita salah dalam menafsirkan makna isyarat itu karena memang sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali atas seijin Yang Maha Agung. Oleh karena itu, ngger, semakin kita mendekatkan diri dengan Dzat Yang Maha Mengetahui seluruh alam semesta ini, akan semakin terbukalah cakrawala angan-angan kita sehingga kita akan diijinkan untuk mengetahui sedikit rahasia yang selama ini tersembunyi.”
Kembali Ki Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini hatinya mulai tertata kembali. Tidak ada kegelisahan yang selama ini selalu menggelayuti hatinya. Semuanya yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi adalah di dalam genggamanNYA, di dalam kekuasaanNYA. Jika memang seorang hamba diperkenankan untuk mengetahui sedikit dari apa yang akan terjadi di hari esok, sesungguhnyalah itu adalah sebuah karunia yang tiada taranya.
“Ngger,” tiba-tiba suara Ki Waskita membuyarkan lamunannya, “Jika aku boleh mengetahuinya, sebenarnya isyarat apakah yang sekarang ini sedang angger terima?”
Sejenak Ki Rangga mengerutkan keningnya. Ada sedikit keragu-raguan yang tampak terpancar dari sorot kedua matanya. Namun akhirnya meluncur juga kata-kata dari bibirnya, “Ki Waskita, akhir-akhir ini aku sedang digelisahkan oleh sebuah isyarat yang berhubungan dengan masa depan Kademangan Sangkal Putung sepeninggal Adi Swandaru. Aku sering diperlihatkan sebuah pemandangan yang mengerikan, baik dalam mimpi-mimpiku maupun sebuah firasat yang tiba-tiba saja terasa mencengkam jantungku sehingga telah menggelisahkan hatiku. Namun aku tidak tahu dengan pasti, firasat apakah itu sebenarnya. Yang justru kemudian muncul dalam benakku adalah wajah-wajah yang begitu aku kenal, Sekar Mirah dan Pandan Wangi.”
Sejenak Ki Waskita menahan nafas. Apa yang disampaikan Ki Rangga itu telah menggores jantungnya. Ayah Rudita yang juga diberi karunia untuk menerima isyarat tentang masa depan itu sejenak bagaikan telah membeku.
“Ngger,” berkata Ki Waskita akhirnya sambil menarik nafas dalam-dalam, “Sebagaimana angger, aku juga menerima isyarat yang kurang menyenangkan tentang masa depan Sangkal Putung. Akan tetapi, marilah semua itu kita kembalikan kepada Yang Maha Mengetahui. Kita sebagai hambaNYA hanya dapat berusaha dan berdoa, sekiranya kita dapat membantu Sekar Mirah maupun Pandan Wangi untuk semakin memajukan Sangkal Putung maupun Tanah Perdikan Menoreh.”
Mendengar Ki Waskita menyebut kedua wilayah itu, tiba-tiba saja dada Ki Rangga berdesir tajam. Tanpa sadar Ki Rangga berdesis perlahan, “Siapakah sebenarnya yang berhak atas kedua wilayah itu?”
Ki Waskita hanya menarik nafas panjang mendengar pertanyaan Ki Rangga. Kedua daerah yang subur itu memang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menjadi bahan persengketaan oleh beberapa pihak yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan.
“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Sangkal Putung harus segera mengambil sikap sehubungan dengan niat Pandan Wangi untuk kembali ke Menoreh.”
Untuk kesekian kalinya Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Beberapa hari setelah pemakaman suaminya, Pandan Wangi memang secara khusus telah berbicara dengannya tentang masa depan Bayu Swandana.
“Kakang,” berkata Pandan Wangi pada saat itu ketika mereka berdua saja sedang duduk-duduk di pringgitan, “Sepeninggal kakang Swandaru, rasa-rasanya sudah tidak ada lagi yang dapat mengikatku di Kademangan ini, kakang.”
“Wangi?” terkejut Ki Rangga mendengar ucapan Pandan Wangi, “Mengapa engkau berkata demikian? Bukankah masih ada Ki Demang sebagai mertuamu? Serta Bayu Swandana sebagai penerus Adi Swandaru yang kelak akan memimpin Kademangan Sangkal Putung?”
Pandan Wangi sejenak termangu-mangu. Pandangan matanya jatuh ke tikar tempat duduknya. Seakan-akan Pandan Wangi sedang menghitung helai demi helai anyaman tikar pandan itu di setiap jengkalnya.
“Wangi,” kembali terdengar Ki Rangga bertanya ketika dilihatnya Pandan Wangi hanya tertunduk diam, “Apakah engkau mempunyai keinginan untuk kembali ke Menoreh?”
Kali ini Pandan Wangi mengangkat wajahnya. Ketika dua pasang mata itu saling beradu, alangkah terkejutnya Ki Rangga. Sepasang mata itu terlihat sayu dan penuh air mata. Betapa sepasang mata itu dulu pernah menatapnya seperti itu, berpuluh tahun yang lalu. Masih jelas dalam ingatan Ki Rangga yang pada saat itu menggunakan nama Gupita, dia harus menyampaikan pesan adik seperguruannya, Gupala kepada putri Menoreh itu.
“Sepasang mata yang kecewa, tanpa harapan dan cinta,” desis Ki Rangga dalam hati sambil mencoba menghindari tatapan mata Pandan Wangi. Dilemparkan pandangan matanya jauh keluar pintu pringgitan yang terbuka lebar.
“Kakang,” tiba-tiba terdengar lirih kata-kata Pandan Wangi, “Aku sudah cukup menderita di Sangkal Putung ini, walaupun sebagai istri, aku telah berusaha menjadi istri yang baik. Aku tetap berharap kakang Swandaru dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk memperbaiki hubungan kami sebagaimana dulu pertama kali kita telah berjanji untuk merajut masa depan bersama,” Pandan Wangi berhenti sejenak. Nafasnya menjadi sesak bersamaan dengan air mata yang mulai tumpah membasahi wajahnya. Sambil berusaha menghapus air mata dengan ujung lengan bajunya, Pandan Wangi pun kemudian meneruskan kata-katanya walaupun terdengar timbul tenggelam dalam isak tangisnya, “Kakang, salahkan aku jika aku ingin menghapus kenangan masa laluku yang begitu pahit ini? Aku ingin kembali ke tanah kelahiranku untuk memulai hidup baru sekalian membesarkan anakku serta menunjukkan baktiku kepada orang tuaku yang telah tua dan renta.”
Ki Rangga terdiam. Hanya degup jantungnya saja yang terdengar bertalu-talu.
“Ngger,” tiba-tiba terdengar suara Ki Waskita membangunkan Ki Rangga dari lamunannya, “Sebaiknya memang permasalahan Sangkal Putung segera dibicarakan bersama. Jika Pandan Wangi berkeinginan untuk pulang ke tanah kelahirannya, berarti harus segera ditunjuk Pemangku sementara kademangan Sangkal Putung untuk mendampingi Ki Demang yang sudah sangat sepuh itu.”
“Ki Waskita benar,” jawab Ki Rangga, “Namun siapakah yang berhak untuk menjadi pemangku sementara, sedangkan Bayu Swandana masih terlalu kecil? Sementara Pandan Wangi sebagai istri Adi Swandaru serta ibu Bayu Swandana telah menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Menoreh?”
Ki Waskita tersenyum sekilas. Jawabnya kemudian, “Masih ada saudara sedarah Ki Swandaru yang dapat menjadi pemangku sementara di kademangan Sangkal Putung.”
Ki Rangga mengerutkan keningnya dalam-dalam sambil memandang tajam ke arah Ki Waskita. Katanya kemudian dengan nada yang sedikit ragu-ragu, “Maksud Ki Waskita, Sekar Mirah?”
“Ya, ngger,” jawab Ki Waskita sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, “Sekar Mirah dapat ditunjuk untuk menjadi pemangku sementara sambil menunggu Bayu Swandana dewasa.”
“Tidak, Ki Waskita,” dengan serta-merta Ki Rangga menyela, “Akulah yang berkeberatan jika Sekar Mirah yang akan ditunjuk menjadi pemangku sementara kademangan Sangkal Putung.”
Ki Waskita terkejut mendengar kata-kata Ki Rangga. Orang tua itu sejenak termangu-mangu sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Adalah hal yang diluar kewajaran jika seseorang dengan sadar telah menolak sebuah kedudukan, pangkat dan derajat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.
“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian dengan sareh, “Nyi Sekar Mirah mempunyai hak untuk menerima itu walaupun angger sebagai suaminya juga mempunyai hak untuk menentukan seberapa jauh seorang istri diperbolehkan oleh suaminya untuk berbuat diluar dunianya. Jangan tergesa-gesa untuk memutuskannya sekarang, ngger. Ajaklah istrimu untuk bermusyawarah.”
Untuk beberapa saat Ki Rangga terdiam. Berbagai persoalan sedang bergulat di dalam benaknya.
“Alangkah beruntungnya Bayu Swandana,” berkata Ki Rangga dalam hati, “Dari garis ibunya dia mewarisi Tanah Perdikan Menoreh yang luas, sedangkan dari garis ayahnya, dia adalah pewaris kademangan Sangkal Putung yang subur.”
Tiba-tiba dada Ki Rangga berdesir tajam. Ingatannya melayang kepada anak laki-laki satu-satunya, Bagus Sadewa. Dan tiba-tiba saja hati Ki Rangga telah tersentuh
“Bagus Sadewa,” hampir saja nama itu terloncat dari bibirnya, namun cepat-cepat ki Rangga menelan kembali kata-katanya sendiri yang sudah berada di ujung bibirnya.
“Aku takut seandainya Sekar Mirah ditunjuk menjadi Pemangku sementara Kademangan Sangkal Putung, Bagus Sadewa setelah beranjak dewasa akan mempunyai tanggapan tersendiri atas hak Kademangan Sangkal Putung,” berkata Ki Rangga dalam hati kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam, “Apalagi jika Sekar Mirah sebagai ibu ingin melihat anak laki-laki satu-satunya mempunyai masa depan yang lebih baik, tentu akan timbul pertentangan yang justru berawal dari dalam keluarga sendiri.”
Diam-diam Ki Rangga mengeluh dalam hati. Isyarat yang diterimanya tentang masa depan Sangkal Putung benar-benar telah menggelisahkan hatinya.
“Ngger,” kembali kata-kata Ki Waskita membuyarkan lamunan Ki Rangga, “Biarlah urusan Sangkal Putung kita kesampingkan terlebih dahulu. Sekarang sebaiknya kita bicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan kita lakukan sehubungan dengan telah diketahuinya kehadiran kita di Padukuhan Klangon ini.”
Ki Rangga berpikir sejenak. Jawabnya kemudian, “Ki Waskita, salah satu pengikut Trah Sekar Seda Lepen yang disebut Eyang Guru itu telah mengetahui kehadiranku. Demikian juga dengan orang yang selama ini telah menghantui Perdikan Matesih, Raden Surengpati. Tidak menutup kemungkinan tempat ini akan segera diserbu oleh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen.”
Ki Waskita menarik nafas panjang sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang kemungkinan itulah yang bisa terjadi dalam waktu dekat ini, dan mereka benar-benar harus mempersiapkan diri.
“Kita menunggu Ki Jayaraga dan yang lainnya, ngger,” berkata Ki Waskita kemudian, “Semoga pekerjaan mereka segera selesai dan tidak ada satu aral pun yang melintang dalam perjalanan mereka kembali ke banjar ini.”
Ki Rangga tidak menjawab. Hanya tampak kepalanya saja yang terangguk-angguk.
Dalam pada itu Ki Jayaraga, Ki Bango Lamatan dan Glagah putih telah selesai mengubur mayat orang yang belum diketahui jati dirinya itu. Dengan berjalan sedikit tergesa-gesa, ketiganya pun telah memutuskan untuk segera kembali ke banjar padukuhan.
Namun sesampainya mereka di kelokan jalan yang mengarah ke banjar padukuhan itu, ketiga orang itu telah dikejutkan oleh bayangan seseorang yang tampak berjalan perlahan-lahan di dalam kegelapan malam berlawanan arah dengan mereka.
Agaknya orang itu pun juga melihat Ki Jayaraga dan kawan-kawannya yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa sadar orang itu pun telah menghentikan langkahnya.
“Guru,” desis Glagah Putih yang tampak berjalan di sebelah kiri gurunya sambil memanggul cangkul di pundaknya, “Siapakah orang itu?”
“Aku tidak tahu Glagah Putih,” jawab gurunya, Ki Jayaraga sambil terus melangkah, “Dalam keadaan seperti ini, kita harus berhati-hati dan waspada ketika berhadapan dengan siapapun yang belum kita ketahui jati dirinya.”
Glagah Putih menarik nafas dalam-dalam sambil berpaling ke arah Ki Bango Lamatan. Namun tampaknya Ki Bango Lamatan sedang sibuk mengamati orang yang berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang di tengah jalan itu.
Ketika jarak antara mereka tinggal beberapa tombak, tiba-tiba saja orang yang berdiri tegak itu tanpa membuat sebuah ancang-ancang, demikian saja melontarkan tubuhnya ke samping dan menghilang di antara gerumbul-gerumbul perdu yang banyak berserakan di tepi jalan.
Bagaikan sudah berjanji sebelumnya, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan pun segera meloncat memburu ke tempat orang itu menghilang. Sementara Glagah Putih harus melempar cangkulnya terlebih dahulu ke tepi jalan sebelum menyusul kedua orang tua itu kemudian.
Sejenak kemudian, terjadilah kejar-kejaran di antara keempat orang itu. Ki Jayaraga yang berlari di depan sendiri merasa heran. Guru Glagah Putih itu telah mengerahkan segenap kemampuannya, namun orang itu masih saja berada beberapa langkah di depannya.
Untuk beberapa saat mereka masih berputar-putar di sekitar tempat itu. Memang ada beberapa petak rumah yang telah di bangun di sekitar kelokan jalan itu, namun selebihnya masih berupa gerumbul perdu dan tanah kosong yang ditumbuhi rumput tinggi rapat berjajar-jajar.
Tanpa terasa keempat orang yang sedang bermain kejar-kejaran itu telah merambah pada kemampuan ilmu mereka yang tinggi, baik kemampuan dalam berlari maupun kemampuan untuk menyerap bunyi yang dapat ditimbulkan oleh suara gesekan mereka dengan alam sekitarnya.
Tiba-tiba saja orang yang sedang mereka kejar itu telah mengubah arah larinya. Dia tidak lagi lari berputar-putar, namun telah berlari menjauhi tempat itu menuju ke barat.
Ketika orang itu kemudian menyusup ke dalam rimbunan pohon bambu yang tumbuh membujur di belakang sebuah rumah kecil di tepi jalan, tiba-tiba saja Ki Jayaraga dan kawan-kawannya telah kehilangan jejak.
Serentak mereka bertiga segera menghentikan langkah.
“Kemana perginya orang itu, Guru?” bertanya Glagah Putih kemudian sambil mengatur nafasnya yang sedikit tersengal.
KI Jayaraga tidak menjawab. Disilangkan kedua tangannya di depan dada sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ternyata Ki Bango Lamatan pun telah berbuat serupa.
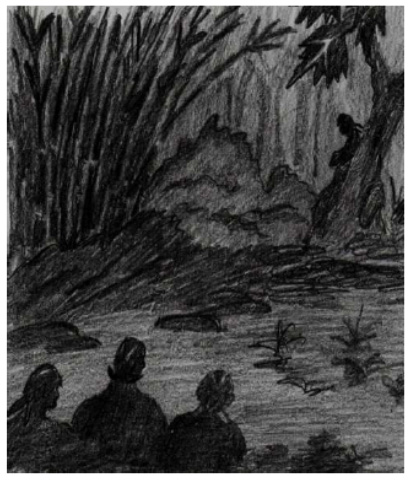
……….“Sudahlah Ki Sanak. Tidak ada gunanya lagi untuk bersembunyi. Lebih baik Ki Sanak segera berterus terang apa maksud Ki Sanak melakukan semua ini?”
Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan hanya memerlukan waktu sekejap untuk mengetahui keberadaan buruannya. Sambil mengangkat kepalanya dan mengurai kedua tangannya, Ki Jayaraga pun kemudian berkata, “Sudahlah Ki Sanak. Tidak ada gunanya lagi untuk bersembunyi. Lebih baik Ki Sanak segera berterus terang apa maksud Ki Sanak melakukan semua ini?”Tidak ada jawaban. Sementara itu Glagah Putih telah mencoba mempertajam penglihatannya dengan lambaran aji sapta pandulu. Segera saja tampak beberapa tombak di depannya, di bawah sebatang pohon keluwih yang tumbuh beberapa langkah dari gerumbul pohon bambu itu, bayangan seseorang sedang berdiri bersandaran pada batang pohon keluwih itu dengan asyiknya.
“Ki Sanak,” Ki Bango Lamatan yang jarang berbicara itu telah maju selangkah, “Apa maksud Ki Sanak melakukan semua ini? Jangan salahkan kami jika Ki Sanak tidak dapat memberikan alasan yang jelas dan masuk akal, kami akan menangkap Ki Sanak.”
Tiba-tiba terdengar bayangan di bawah pohon keluwih itu tertawa perlahan-lahan. Suara tawa yang benar-benar memuakkan.
Berkata bayangan itu kemudian di sela-sela tawanya, “Dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ki Jagabaya Dukuh Klangon? Begitu?”
Ketiga orang itu terkejut. Orang itu telah menyebut Ki Jagabaya Dukuh Klangon. Tentu orang itu telah mengetahui serba sedikit tentang mereka dalam hubungannya dengan Ki Jagabaya Dukuh Klangon.
Namun sebelum Ki Jayaraga menjawab, orang itu telah berkata lagi, “Bagaimana mungkin kalian mau menangkap aku, berlari saja kalian masih seperti kanak-kanak,” orang itu berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Nah, aku akan berlari lagi. Silahkan kalau mau menangkap aku jika kalian merasa mampu.”
Selesai berkata demikian, hampir tidak kasat mata, bayangan itu pun melesat meninggalkan tempat itu menuju ke arah barat.
Ki Jayaraga dan kawan-kawannya merasa tertantang untuk mengejar bayangan itu. Maka sejenak kemudian kejar-kejaran di antara keempat orang itu pun terjadi lagi.
Semakin lama mereka telah semakin jauh meninggalkan padukuhan Klangon dan kini tak terasa mereka telah mendekati tapal batas antara Padukuhan Klangon dengan Tanah Perdikan Matesih sebelah barat.
Sesekali ketiga orang itu kembali kehilangan buruan mereka sehingga ketiga orang itu pun telah menghentikan langkah mereka untuk sejenak. Namun entah mengapa, dengan sengaja orang yang sedang mereka cari itu tiba-tiba saja telah menampakkan diri lagi tidak jauh dari tempat mereka berhenti, sehingga kejar-kejaran itu pun kembali terjadi.
Ketika ketiga orang itu merasakan tanah yang mereka lewati kemudian terasa agak landai, tahulah mereka bahwa sebentar lagi mereka akan mencapai sebuah sungai yang mengalir di sepanjang sisi barat Tanah Perdikan Matesih, kali Praga.
Tiba-tiba saja Ki Jayaraga yang berlari di paling depan telah memperlambat langkahnya. Lamat-lamat Ki Jayaraga mendengar suara aliran air. Sedangkan kedua kawannya yang berlari di belakangnya pun kemudian ikut memperlambat langkah mereka.
“Kita kehilangan jejak kembali,” desis Ki Jayaraga sambil mengatur pernafasannya yang sedikit memburu. Sementara Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih pun telah berbuat serupa.
“Apa maksud orang itu membawa kita ke tepian kali Praga ini?” geram Ki Bango Lamatan sambil menekan lambungnya untuk mengurangi rasa sakit yang tiba-tiba saja terasa menyengat.
“Orang gila,” geram Glagah Putih yang berdiri tersengal-sengal di sebelah Ki Bango Lamatan, “Orang itu berlari seperti setan dan sepertinya memang dengan sengaja dia ingin mempermainkan kita.”
“Sudahlah,” berkata Ki Jayaraga kemudian ketika pernafasannya sudah teratur kembali, “Kita coba untuk turun ke tepian, barangkali di sana ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian.”
Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih tidak menjawab. Hanya kepala mereka saja yang terlihat mengangguk.
Sejenak kemudian ketiga orang itu pun mulai menuruni tebing yang agak curam. Ketika sisi tebing itu mulai landai, mereka pun kemudian mulai berjalan di tepian kali Praga yang berpasir lembut.
Namun baru saja mereka berjalan beberapa langkah, pendengaran mereka yang tajam telah mendengar langkah beberapa orang yang tampak tergesa-gesa menyusuri tepian dari arah yang berlawanan. Memang masih cukup jauh namun ketiga orang itu dengan sangat jelas telah mendengar suara mereka.
Bagaikan sudah berjanji sebelumnya, ketiga orang itu pun segera berloncatan dan bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu yang banyak bertebaran di sisi tebing.
Sejenak kemudian tampak dalam kegelapan malam, beberapa orang muncul dari kelokan sungai. Dengan langkah yang tergesa-gesa mereka menyusuri tepian yang berpasir basah.
“Sebelum ayam jantan berkokok untuk terakhir kalinya, kita sudah harus sampai di banjar Padukuhan Klangon,” berkata seseorang yang berjalan paling depan. Tubuhnya tinggi menjulang dengan sebuah tombak pendek di tangan kanannya, “Perintah Kakang Putut Sambernyawa sudah jelas, kita kepung banjar Padukuhan Klangon tepung gelang agar tidak ada seekor semut pun yang dapat lolos dari pengamatan kita.”
“Kakang Putut Jangkung,” menyela seseorang yang bertubuh gemuk dan pendek yang berjalan di sebelahnya, “Menurut Kakang Putut Sambernyawa tadi, kita sebaiknya membuat hubungan terlebih dahulu dengan Ki Kebo Mengo, orang kepercayaan Raden Wirasena.”
“Persetan dengan Kerbau bodoh itu,” geram Putut Jangkung sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Segera saja terasa bumi di sekitar tempat itu bergetar, “Aku sudah muak sebenarnya dengan orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen beserta para pengikutnya itu. Mereka telah merayu Guru untuk mendukung perjuangan mereka. Dengan berbekal keyakinan seolah-olah wahyu keprabon itu akan menjadi milik mereka, Guru telah dirayu dengan janji-janji yang memabokkan.”
“Apakah janji mereka?” pertanyaan itu dengan serta merta telah terloncat begitu saja hampir dari mulut setiap orang.
Putut Jangkung menarik nafas panjang sebelum menjawab. Sambil mengeluarkan sebuah dengusan dari hidungnya dia menjawab, “Guru dijanjikan akan diangkat menjadi seorang Adipati jika perjuangan mereka berhasil.”
“Sebuah mimpi yang indah,” tiba-tiba saja seseorang yang berjalan di belakang Putut Jangkung terdengar menyahut.
Ki Jangkung berpaling sekilas ke belakang. Katanya kemudian, “Engkau benar, Ki Brukut. Sebuah mimpi yang indah, bahkan terlalu indah jika kita bermimpi ingin menjadi seorang Adipati.”
Ki Brukut menarik nafas panjang. Katanya kemudian, “Kedatanganku ke Padepokan Sapta Dhahana sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala tingkah polah orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pewaris Trah Sekar Seda Lepen itu.”
“Nah, mengapa Ki Brukut ikut rombongan kami?”” sahut orang yang berperawakan gemuk dan pendek yang berjalan di samping Putut Jangkung dengan serta-merta.
Ki Brukut tertawa pendek. Jawabnya kemudian, “Aku datang ke Padepokan Sapta Dhahana sekedar untuk menengok keadaan anakku, Putut Sambernyawa. Anakku lah yang telah meminta aku untuk mengikuti kalian ke Dukuh Klangon, dan memastikan bahwa kalian akan sampai di sana dengan selamat.”
Hampir saja setiap mulut mengumpat mendengar kata-kata Ki Brukut. Namun mereka segera menyadari siapakah Ki Brukut itu. Ayah dari Putut Sambernyawa, Putut tertua dan terpercaya dari Kiai Damar Sasangka, pemimpin tertinggi padepokan Sapta Dhahana.
“Menilik rasa hornat yang diperlihatkan oleh Guru kepada Ki Brukut ini, tentu tingkat ilmunya tidak jauh berbeda dengan Guru,” demikian beberapa orang yang berada dalam rombongan itu berkata dalam hati.
“Atau mungkin keseganan Guru hanya karena Ki Brukut adalah ayah kakang Putut Sambernyawa, bukan tingkat ilmunya,” yang lain justru mempunyai tanggapan yang berbeda.
Tak terasa langkah orang-orang itu pun telah mendekati tempat dimana Ki Jayaraga dan kawan-kawannya sedang bersembunyi.
“Lima belas orang,” berkata Ki Jayaraga dalam hati. Berbagai pertimbangan tengah hilir-mudik dalam benaknya.
Agaknya Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih pun juga telah ikut menghitung jumlah orang-orang yang sedang lewat beberapa langkah di hadapan mereka itu.
“Terlalu banyak dan terlalu berat akibat yang akan ditimbulkan,” berkata Ki Bango Lamatan dalam hati. Memang melawan lima belas orang dengan tingkatan ilmu yang belum mereka ketahui sama saja dengan membunuh diri.
Demikianlah ketika rombongan itu telah berlalu dan tidak tampak lagi bayangannya, ketiga orang yang sedang bersembunyi itu pun berniat untuk keluar dari persembunyiannya. Namun baru saja mereka beringsut setapak, tiba-tiba pendengaran mereka menangkap kembali langkah-langkah mendekati tempat itu. Bahkan sekarang terdengar langkah-langkah itu lebih banyak dari yang pertama.
Segera saja ketiga orang itu membenamkan diri mereka kembali ke dalam gerumbul-gerumbul perdu sambil menahan nafas.
Ternyata yang lewat kemudian adalah serombongan orang yang berjumlah sangat besar, hampir dua kali lipat dari yang pertama. Rombongan yang kedua itu pun kemudian disusul dengan rombongan yang ketiga, keempat dan rombongan kelima adalah rombongan yang terbesar, hampir lima puluh orang.
“Gila!” geram KI Jayaraga perlahan sambil bangkit dari persembunyiannya ketika dirasa sudah tidak ada lagi rombongan yang akan lewat. “Agaknya murid-murid Padepokan Sapta Dhahana telah dikerahkan untuk menutup setiap jalan keluar dari Padukuhan Klangon.”
“Kakang Agung Sedayu dan Ki Waskita pasti akan menemui kesulitan, jika tidak segera diberitahu,” sahut Glagah Putih sambil bangkit berdiri dan mengibas-kibaskan kain panjangnya yang terkena pasir tepian.
Sedangkan Ki Bango Lamatan tampak mengerutkan keningnya dalam-dalam. Katanya kemudian, “Kita harus berterima kasih kepada orang yang telah membawa kita ke tepian ini. Secara tidak langsung dia telah memberitahukan kepada kita, gerakan padepokan Sapta Dhahana yang akan mengepung banjar Padukuhan Klangon.”
Dada Ki Jayaraga dan Glagah Putih berdesir tajam begitu mendengar kata-kata Ki Bango Lamatan. Secara tidak langsung orang itu telah membantu mereka dengan memberitahukan bahaya besar yang akan mengancam jika mereka tetap bertahan di banjar padukuhan.
“Marilah kita segera kembali ke banjar,” berkata Ki Jayaraga kemudian sambil melangkah tergesa-gesa menaiki tebing, “Sesampainya di atas tebing, kita akan berlari kembali sesuai jalur yang telah ditunjukkan oleh orang tadi. Agaknya jalur tadi adalah jalan pintas. Semoga kita dapat mendahului rombongan orang-orang padepokan Sapta Dhahana.”
“Ya, Ki,” sahut Ki Bango Lamatan sambil mengikuti langkah Ki Jayaraga, “Ki Rangga dan Ki Waskita harus segera menyingkir sebelum kedatangan orang-orang itu.”
Glagah Putih yang melihat kedua orang tua itu telah menaiki tebing segera menyusul. Dengan cepat dia segera meloncat di antara batu-batu yang menjorok di lereng untuk menyusul kedua orang tua yang sudah hampir mencapai bibir tebing.
Dalam pada itu di banjar Padukuhan Klangon Ki Rangga dan Ki Waskita masih belum menyadari bahwa bahaya sedang mendekat ke arah mereka. Murid-murid perguruan Sapta Dhahana dari lereng Gunung Tidar secara bergelombang telah memasuki Padukuhan Klangon dari arah barat.
Namun kedua orang yang telah mempelajari ilmu dari sumber yang sama itu ternyata hampir bersamaan panggraita mereka telah menerima getaran-getaran isyarat yang mendebarkan.
Hampir bersamaan keduanya pun segera menyilangkan kedua tangan di depan dada. Sambil menundukkan kepala dalam-dalam dan memejamkan mata, keduanya berusaha memusatkan segenap nalar dan budi untuk memperjelas getaran-getaran isyarat yang mereka terima.
Sejenak kemudian keduanya telah tenggelam dalam pemusatan nalar dan budi. Namun baru beberapa saat berlalu, mereka berdua telah terganggu dengan kedatangan Ki Jayaraga bertiga.
Segera saja Ki Waskita menghentikan usahanya untuk mempertajam panggraitanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam dan mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada, Ki Waskita pun segera menyapa Ki Jayaraga bertiga.
“Bagaimana keadaan kalian bertiga?” bertanya Ki Waskita kemudian sambil mempersilahkan mereka bertiga untuk duduk di atas tikar, “Apakah semuanya dapat berjalan lancar?”
Ketiga orang itu saling pandang sejenak. Perhatian mereka masih tertuju kepada Ki Rangga yang tampak masih mencoba menghentakkan kemampuan panggraitanya untuk memantau keadaan di sekitar Padukuhan Klangon.
Melihat ketiga orang itu tidak menjawab dan justru telah tertarik melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ki Rangga, Ki Waskita pun kemudian berusaha memberikan penjelasan, “Ki Rangga sedang berusaha mempertajam panggraitanya. Agaknya tempat ini sudah tidak nyaman dan aman lagi bagi kita.”
“Benar, Ki Waskita,” tiba-tiba Ki Rangga menyahut sambil membuka kedua matanya dan mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada, “Sepertinya Padukuhan Klangon ini telah kedatangan banyak orang dari arah utara. Aku tidak tahu mereka berasal dari Perdikan Matesih ataukah Gunung Tidar.”
Mendengar Ki Rangga menyebut gunung Tidar, Ki Jayaraga segera beringsut maju. Katanya kemudian, “Ki Rangga, kami bertiga tadi sempat menjumpai murid-murid gunung Tidar sedang berbondong-bondong menuju ke Padukuhan Klangon,” Ki Jayaraga berhenti sebentar sambil memandang ke arah Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih yang tampak mengangguk-angguk. Lanjut Ki Jayaraga kemudian, “Bahkan kami sempat mendengar percakapan mereka. Murid-murid perguruan Sapta Dhahana itu memang sengaja dikirim ke Padukuhan Klangon untuk mengepung serta menutup semua jalan keluar terutama di banjar padukuhan ini.”
Kemudian secara singkat Ki Jayaraga segera menceritakan tentang orang aneh yang telah dengan sengaja menuntun mereka ke tepian kali Praga yang terletak di sebelah barat Perdikan Matesih.
Mendengar cerita Ki Jayaraga, tampak kening Ki Rangga berkerut-merut. Berbagai dugaan telah muncul dalam benaknya tentang orang yang dengan sengaja membawa ketiga orang itu ke tepian Kali Progo.
Namun Ki Rangga benar-benar tidak dapat menduga dengan pasti, siapakah sebenarnya orang itu.
“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian menyadarkan Ki Rangga dari lamunannya, “Apakah tidak sebaiknya kita segera menyingkir?”
Sejenak Ki Rangga memandang ke arah orang-orang yang berada di ruangan itu. Ketika semuanya terlihat mengangguk, Ki Rangga pun segera berkata, “Baiklah, kita segera berkemas. Besok pagi sebelum wayah pasar temawon, salah satu dari kita harus menghubungi Ki Gede Matesih agar membatalkan rencananya untuk mengundang kita.”
Hampir bersamaan yang lainnya telah mengangguk-angguk.
Demikianlah, sejenak kemudian kelima orang itu pun telah berkemas dan meninggalkan tempat itu melalui pintu butulan.
Ketika Ki Rangga sempat melihat para pengawal yang tertidur silang melintang di teritisan, Ki Rangga pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
“Sebuah sirep yang sangat halus,” desis Ki Rangga kemudian sambil berjalan di sebelah Ki Waskita, “Seseorang telah menebarkan sirep yang sangat halus sejak sore tadi. Hampir tidak ada seorang pun dari kita yang menyadarinya.”
“Ya, ngger,” sahut Ki Waskita sambil mendahului melangkahi tlundak pintu butulan di pagar belakang, “Aku hanya merasakan udara begitu sejuk dan sangat nyaman untuk beristirahat sehingga aku tidak menyadari bahwa seseorang telah menebarkan sirep.”
Glagah Putih yang mendengar kata-kata Ki Waskita hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala. Sementara Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan yang mempunyai pengalaman dalam hal ilmu yang dapat membuat orang kehilangan kesadaran itu justru telah tersenyum.
“Diperlukan ketelatenan dalam mengetrapkan sirep sejenis ini,” berkata Ki Jayaraga dalam hati, “Berbeda dengan sirep tajam yang dengan serta merta akan mempengaruhi orang dengan rasa kantuk yang tak tertahankan. Sirep halus ini harus terus menerus ditebarkan di sepanjang waktu dengan kekuatan yang tidak terlalu tajam untuk menyamarkan keberadaan sirep itu sendiri.”
Sedangkan Ki Bango Lamatan yang pernah menebarkan sirep di kediaman Ki Gede Menoreh beberapa waktu yang lalu telah berkata dalam hati, “Aku belum pernah mempelajari sirep jenis ini. Aku lebih senang menebarkan sirep yang langsung dapat membuat orang jatuh pingsan sehingga apa yang menjadi tujuan kita segera dapat tercapai,” Ki bango Lamatan berhenti berangan-angan sejenak. Kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ki Bango Lamatan pun meneruskan angan-angannya, “Namun dengan demikian jika ada seseorang yang mempunyai kemampuan mumpuni akan segera menyadari bahwa seseorang sedang menebarkan sirep.”
Tak terasa langkah-langkah mereka telah semakin jauh meninggalkan banjar Padukuhan Klangon.
Dalam pada itu, ketika ayam jantan telah berkokok untuk terakhir kalinya, banjar padukuhan itu benar-benar telah terkepung rapat dari segala penjuru. Tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari pengamatan murid-murid Padepokan Sapta Dhahana. Namun mereka belum menyadari bahwa buruan mereka telah lolos beberapa saat yang lalu.
Ketika kepungan itu semakin merapat dan mulai mendekati regol banjar, mereka pun mulai melihat sebuah keanehan. Tidak tampak seorang penjaga pun yang sedang berdiri di depan regol.
“He? Kemana perginya para penjaga itu?” geram Putut Jangkung yang memimpin pengepungan itu.
“Apakah mereka belum menyadari akan kehadiran kita?” bertanya kawannya yang bertubuh gemuk dan pendek, “Bukankah kita juga telah mengirimkan para cantrik untuk membantu Ki Dukuh?”
Putut Jangkung tidak menjawab. Sejenak dipicingkan kedua matanya untuk mempertajam penglihatannya. Jarak mereka dengan regol banjar itu hanya tinggal beberapa tombak saja, namun Putut Jangkung masih belum melihat seorang penjaga pun yang berdiri di sebelah menyebelah regol.
“Mereka tentu telah tertidur nyenyak di bawah selimut kain panjang mereka!” geram Putut Jangkung. Kemudian katanya kepada orang yang di sebelahnya, “Putut Pendek, ajak tiga cantrik untuk menemanimu melihat keadaan regol terlebih dahulu.”
“Baik kakang,” jawab Putut Pendek sambil memberi isyarat tiga orang cantrik di dekatnya untuk mengawaninya.
Tanpa meninggalkan kewaspadaan, keempat orang itu pun kemudian segera berjalan mengendap-endap mendekati regol. Masing-masing telah menggenggam tangkai senjata mereka dan setiap saat siap untuk dihunus.
“Sepi,” desis Putut Pendek begitu mereka telah semakin dekat dengan regol.
Salah satu cantrik dengan memberanikan diri telah meloncat ke samping regol. Dengan sangat hati-hati dia mencoba menjengukkan kepalanya ke dalam.
Apa yang dilihatnya kemudian benar-benar telah membuat cantrik itu mengumpat-umpat tak ada habis-habisnya. Di sebelah regol bagian dalam memang ada gardu penjagaan tempat para penjaga regol untuk sekedar melepas lelah. Namun gardu penjagaan itu kini telah dipenuhi oleh para cantrik dan pengawal Padukuhan Klangon yang sedang bertugas malam itu. Mereka terlihat tertidur dengan nyenyak. Ada yang tidur silang melintang di lantai gardu, namun ada juga yang tertidur hanya dengan bersandaran dinding.
Putut Pendek yang melihat cantrik itu justru segera melangkah dengan tergesa-gesa. Namun sebagaimana cantrik itu, Putut Pendek pun telah mengumpat dengan umpatan yang sangat kotor begitu mendapatkan para cantrik dan pengawal yang bertugas menjaga regol justru telah tertidur nyenyak.
“Orang-orang yang tak tahu diri!” geram Putut Pendek kemudian sambil menendang salah satu cantrik yang tertidur sambil bersandaran dinding.
Tentu saja cantrik itu terkejut bukan alang-kapalang merasakan sesuatu telah menghantam pinggulnya dengan keras.
“He?!” teriak cantrik itu sambil terlonjak dari duduknya. Dengan cepat dia segera melenting berdiri.
Namun cantrik itu justru telah membeku begitu menyadari siapa yang sedang berdiri di hadapannya dengan wajah merah padam, Putut Pendek dari perguruan Sapta Dhahana.
“Apa kerja kalian, he?!” terdengar Putu Pendek itu membentuk dengan suara menggelegar. Sementara para cantrik dan pengawal yang lainnya segera tersadar dari tidur nyenyak mereka begitu mendengar suara ribut-ribut.
Dalam pada itu Putut Jangkung yang mendengar suara ribut-ribut di regol segera melangkah mendekat. Yang dilihatnya kemudian adalah para cantrik dan pengawal Padukuhan Klangon yang berdiri dengan kebingungan sementara Putut Pendek telah membentak-bentak mereka tak henti-hentinya.
“Sudahlah, Pendek,” berkata Putut Jangkung kemudian sambil melangkah semakin dekat, “Tentu ada alasannya mengapa mereka telah meninggalkan tugas dan lebih memilih tidur di dalam gardu.”
Putut Pendek menarik nafas panjang untuk meredakan gejolak di dalam dadanya. Katanya kemudian sambil berpaling ke arah Putut Jangkung, “Kakang, tidak ada ampun bagi mereka yang telah melalaikan tugas. Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman yang setimpal, terutama para cantrik padepokan Sapta Dhahana.
Sedang para pengawal Padukuhan Klangon akan kita laporkan kepada Ki Dukuh.”
Putut Jangkung mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya kemudian, “Aku setuju dengan alasanmu itu. Namun kita juga tidak boleh menutup mata sebab musabab yang telah membuat mereka lalai dalam menunaikan tugas.”
“Maaf Kakang Jangkung,” tiba-tiba salah satu cantrik memberanikan diri maju selangkah ke depan, “Kami memang mengakui kesalahan kami. Namun apa yang telah terjadi ini benar-benar diluar kuasa kami. Kami merasakan udara tadi malam memang terasa sangat sejuk. Entah awalnya dari mana, tahu-tahu kami telah dikuasai oleh kantuk yang perlahan–lahan mulai menyergap dan membelenggu kami sejak saat sirep bocah tadi.”
Putut Pendek akan menanggapi kata-kata cantrik itu, namun dengan cepat Putut Jangkung memberi isyarat untuk berdiam diri. Berkata Putut Jangkung kemudian, “Mungkin kalian telah terpengaruh oleh sirep atau sejenisnya yang dapat membuat kalian terserang kantuk tak tertahankan,” Putut Jangkung berhenti sebentar. Lanjutnya kemudian, “Sebelum Matahari terbenam sore tadi, memang Raden Wirasena telah menerima laporan akan kedatangan orang asing di Padukuhan Klangon ini. Untuk itulah Raden Wirasena telah meminta bantuan Guru agar mengutus beberapa murid padepokan Sapta Dhahana untuk menghubungi dan membantu Ki Dukuh. Ternyata Ki Dukuh pun telah menyanggupi dan menyiapkan para pengawal Dukuh Klangon untuk berjaga-jaga bersama para cantrik di banjar padukuhan. Ternyata kalian di sini hanya pindah tidur saja.”
Para cantrik dan pengawal dukuh Klangon itu semakin menundukkan kepala mereka. Entah apa jawab mereka nantinya jika Ki Dukuh menanyakan hal itu.
“Sudahlah,” tiba-tiba Ki Brukut yang telah berada di samping Putut Jangkung menyela, “Yang terpenting sekarang ini adalah keberadaan orang-orang asing itu. Apakah mereka masih berada di dalam banjar?”
Bagaikan disambar halilintar di siang bolong, serentak Putut Jangkung dan Putut Pendek segera meloncat dan berlari menuju ke dalam banjar.
Setelah melewati pendapa yang tidak begitu luas, dengan tergesa-gesa keduanya telah mendorong pintu pringgitan dengan kasar. Ketika keduanya kemudian telah sampai di ruang dalam, yang mereka jumpai hanyalah selembar tikar usang yang terhampar di tengah-tengah ruangan.
“Setan gendruwo, tetekan!” geram Putut Jangkung sambil berjalan mengitari ruangan. Tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk pada sebuah lobang yang tidak seberapa besar yang terdapat di pojok ruangan.
“Lubang ini terlihat masih baru,” desis Putut Jangkung sambil meraba sudut dinding kayu itu, “Seseorang dengan sengaja telah membuat lubang ini dengan suatu tujuan.”
Sedang Putut Pendek dan Ki Brukut yang datang kemudian ternyata lebih memilih menelusuri dapur untuk kemudian lewat pintu butulan ke halaman belakang.
Ternyata di halaman belakang pun kedua orang itu juga dikejutkan oleh para pengawal padukuhan yang terlihat sedang tidur silang melintang di teritisan.
“Sirep,” hampir bersamaan kedua orang itu berdesis.
“Siapakah yang telah menebarkan sirep ini?” tiba-tiba Putut Pendek mengajukan sebuah pertanyaan.
Sejenak Ki Brukut termenung. Jawabnya kemudian, “Tidak menutup kemungkinan orang-orang asing itulah yang telah menebarkan sirep dalam usaha mereka untuk meloloskan diri.”
“Tapi menurut cerita para cantrik dan pengawal yang berjaga di regol depan tadi, mereka merasa di serang kantuk mulai saat sirep bocah,” sela Putut Pendek.
“Entahlah,” akhirnya Ki Brukut menggeleng lemah, “Namun yang jelas kelima orang itu telah pergi dan kita harus memberi jawaban kepada Raden Wirasena dan Kiai Damar Sasangka.”
Berdesir dada Putut Pendek. Jika mereka para cantrik perguruan Sapta Dhahana itu tidak mampu menunaikan tugas karena kelalaian atau ketidak-mampuan mereka, tentu tidak segan-segan guru mereka, Kiai Damar Sasangka, akan memberikan hukuman.
“Sebaiknya kita segera mengirim isyarat,” berkata Putut Pendek kemudian sambil melangkah kembali memasuki bangunan induk banjar.
“Sebaiknya memang demikian,” sahut Ki Brukut sambil mengikuti langkah Putut Pendek, “Dengan demikian Raden Wirasena segera dapat mengambil tindakan dan langkah-langkah berikutnya.”

Ternyata di halaman belakang pun kedua orang itu juga dikejutkan oleh para pengawal padukuhan yang terlihat sedang tidur silang melintang di teritisan.
“Sirep,” hampir bersamaan kedua orang itu berdesis.
STSD-03
Bagian 2
Demikianlah setelah berunding terlebih dahulu dengan Putut Jangkung, Putut Pendek segera memerintahkan seorang cantrik yang membawa busur dan anak panah sendaren untuk segera mengirim isyarat ke Gunung Tidar.
Sejenak kemudian kesunyian dini hari langit Padukuhan Klangon itu pun telah dipecahkan oleh suara panah sendaren yang meraung-raung dua kali berturut-turut.
Dalam pada itu langit di sebelah timur telah menampakkan cahaya semburat kemerahan. Mendung sisa hujan semalam telah tertiup angin dan bergerak berarak-arak ke arah selatan. Mungkin menjelang pasar temawon hujan akan turun di laut selatan.
Di Perdikan Matesih, seorang pengawal yang sedang berjaga di sebuah gardu perondan telah mendengar isyarat itu. Dengan bergegas diambilnya busur dan anak panah sendaren yang disimpan di gardu perondan. Namun sebelum tangannya meraih busur dan anak panah itu, terdengar seseorang bergumam di belakangnya.
Ketika dia kemudian memutar tubuhnya, tampak Kepala pengawal Perdikan Matesih berdiri hanya dua langkah di depannya dengan kedua tangan bertolak pinggang.
“Ki Wiyaga,” desis pengawal itu mencoba menyapa.
Ki Wiyaga, kepala pengawal Perdikan Matesih itu tersenyum hambar. Tanyanya kemudian, “Untuk apa engkau akan mengambil busur dan anak panah sendaren itu?”
Pengawal itu tidak menjawab. Dia belum yakin, di pihak manakah Ki Wiyaga berdiri. Memang keadaan di Perdikan Matesih saat itu tidak menentu, terutama para perangkatnya telah terpecah menjadi dua.
Sebagian telah ikut arus para pengikut Trah Sekar Seda Lepen, sedangkan sisanya masih bersetia kepada Ki Gede Matesih sebagai kawula Mataram.
“Engkau tidak usah termakan janji-janji ngayawara itu, Lajuwit,” terdengar suara ki Wiyaga berat dan dalam, “Mereka adalah segolongan orang-orang yang sedang kalap dan edan kamukten. Apapun akan diterjang demi meraih mimpi mereka tanpa menyadari bahwa hari sudah menjelang siang dan bukan waktunya lagi bagi mereka untuk bermimpi.”
Lajuwit termenung sejenak. Ada sedikit kebimbangan di dalam hati untuk sekedar menyampaikan apa yang menjadi ganjalan hatinya.
Agaknya Ki Wiyaga dapat membaca raut wajah Lajuwit yang gelisah. Maka katanya kemudian, “Lajuwit, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang tersirat di dalam hatimu. Mungkin pandangan kita berbeda. Namun setelah engkau menyampaikan apa yang telah menjadi arah kiblatmu selama ini, kita dapat saling berbagai dan mempelajari, arah manakah sebenarnya yang paling masuk akal untuk kita ikuti?”
Kembali Lajuwit termenung namun hanya sekejap. Katanya kemudian, “Ki Wiyaga, sebenarnya janji-janji yang disampaikan oleh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu terlalu jauh dari kenyataan. Namun jika kita tetap berharap akan adanya perubahan hidup kita dibawah pemerintahan yang sekarang ini, sepertinya itu juga sebuah mimpi. Kedua-duanya bagiku memang hanya sebatas mimpi, namun jika aku mengikuti Trah Sekar Seda Lepen, setidaknya aku telah menggantungkan sebuah harapan, bukan sekedar mimpi sebagaimana yang telah terjadi saat ini.”
Ki Wiyaga menarik nafas dalam-dalam. Dilemparkan pandangan matanya ke jauh ke depan, ke arah tanah pesawahan yang terbentang luas yang mulai digarap.
“Lajuwit,” berkata Ki Wiyaga kemudian sambil tangan kanannya menunjuk jauh ke tanah pesawahan, “Lihatlah tanah pesawahan yang luas itu. Itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah kenyataan yang harus kita garap, kita kelola sehingga pada saatnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Manfaat yang dapat dipetik turun temurun sampai anak cucu kita.”
Namun jawaban Lajuwit sungguh diluar dugaan kepala pengawal Perdikan Matesih itu.
Jawab Lajuwit kemudian, “Maafkan aku Ki Wiyaga. Bagiku tanah pesawahan itu bukan kenyataan lagi, tapi itu mimpi buruk yang akan terus menghantui sampai anak cucu kita nanti. Tanah-tanah itu dulunya milik para petani, namun kini para tuan tanahlah yang menguasai. Di musim kemarau ketika petak-petak sawah tidak dapat menghasilkan lagi, sedangkan para petani mempunyai keluarga dan anak-anak yang mulut mereka harus tetap disuapi setiap hari, mereka pun tidak mempunyai pilihan lagi. Atau membiarkan saja anak dan istri kelaparan dan mati sehingga hidup merekapun tidak akan berarti lagi.”
“Cukup!” bentak Ki Wiyaga, “Tidak usah menggurui aku. Aku tahu para petani telah terlilit hutang sampai mencekik leher mereka sendiri. Akhirnya sepetak sawah sebagai sumber hidup mereka pun kini sudah terjual kepada para tuan tanah itu dan kini mereka menjadi buruh di atas tanah mereka sendiri. Tapi itu semua akibat dari cara hidup mereka sendiri. Disaat panen mereka tidak berusaha berhemat sehingga di saat musim kering tiba, mereka menjadi kelaparan dan akhirnya hanya menggantungkan hutang kepada para tuan tanah itu.”
Lajuwit hanya berdiam diri saja mendengar bentakan Ki Wiyaga. Namun diam-diam dia telah mempersiapkan diri. Apa boleh buat, jika perselisihan tidak dapat dihindarkan lagi, dia telah menyiapkan dirinya lahir maupun batin.
“Nah,” berkata Ki Wiyaga kemudian, “Agaknya memang kita telah berselisih jalan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersetia kepada Ki Gede Matesih sebagai kawula Mataram.”
Mendengar kata-kata terakhir kepala pengawal Perdikan Matesih ini, Lajuwit sudah dapat menduga akhir dari perdebatan itu. Maka katanya kemudian, “Maafkan aku Ki Wiyaga. Aku sudah terlanjur mengikatkan diriku dengan Trah Sekar Seda Lepen. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.”
Selesai berkata demikian Lajuwit segera menggeser kaki kanannya selangkah ke samping. Sedangkan kedua tangannya telah terkepal di kedua sisi lambungnya.
Ki Wiyaga yang melihat Lajuwit telah mempersiapkan diri, tidak ingin ketinggalan. Maka segera saja Ki Wiyaga menekuk lutut salah satu kakinya sambil bergeser setapak ke belakang.
Ternyata Lajuwit tidak ingin membuang-buang waktu. Dia harus segera mengirim panah sendaren untuk menyambung pesan yang telah diterimanya dari Padukuhan Klangon. Maka sambil membentuk keras, serangannya pun telah meluncur mengarah dada.
Tentu saja Ki Wiyaga tidak ingin dadanya rontok mendapat serangan lawan. Dengan sedikit menggeser kakinya ke samping serangan kaki lawannya itu lewat sejengkal dari dadanya. Kemudian dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, tangan kiri Ki Wiyaga pun mencoba menangkap pergelangan kaki Lajuwit.
Menyadari lawannya mencoba menangkap pergelangan kakinya, Lajuwit segera mengubah arah serangannya. Ketika kaki kanannya sedang terjulur lurus, tiba-tiba saja lututnya telah ditekuk. Kemudian dengan bertumpu pada tumit kaki yang lainnya, tubuhnya pun berputar untuk mengarahkan lututnya menghantam dada lawan.
Terkejut Ki Wiyaga mendapat serangan susulan itu. Namun kepala pengawal Perdikan Matesih itu tidak menjadi gugup. Dengan cepat tangannya yang sedianya akan menangkap pergelangan kaki lawan itu segera ditarik dan disilangkan di depan dadanya.
Sejenak kemudian terjadilah benturan yang cukup keras. Kedua-duanya telah meloncat ke belakang untuk mengambil jarak.
Untuk sejenak Ki Wiyaga termangu-mangu. Sebenarnyalah Ki Wiyaga sebagai kepala pengawal Perdikan Matesih merasa sayang. Lajuwit adalah salah seorang pengawal Perdikan Matesih yang dapat diandalkan karena Lajuwit pernah berguru dan menimba ilmu di padepokan Sapta Dhahana. Padepokan yang terletak di lereng Gunung Tidar di sebelah timur Perdikan Matesih.
“Ki Wiyaga,” tiba-tiba terdengar Lajuwit bertanya begitu melihat kepala pengawal itu termangu-mangu sejenak, “Apakah Ki Wiyaga berubah pikiran? Ingat, Perguruan gunung Tidar telah berdiri di belakang perjuangan Trah Sekar Seda Lepen. Aku kira Ki Wiyaga cukup menyadari kekuatan yang tersembunyi di Gunung Tidar. Kekuatan yang aku yakin akan mampu mengimbangi Mataram.”
“Cukup!” kembali Ki Wiyaga membentak, “Kita buktikan dulu semua itu.”
Selesai berkata demikian, Ki Wiyaga segera mempersiapkan serangannya. Bagaikan tatit yang meloncat di udara, tubuh Ki Wiyaga pun melesat ke depan dengan sebuah serangan yang mengarah ke ulu hati.
Demikianlah sejenak kemudian pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya adalah pengawal Perdikan Matesih yang dapat dibanggakan, namun yang ternyata mempunyai kiblat yang berbeda sehingga harus berselisih jalan.
Dalam pada itu, tanpa mereka sadari, beberapa pasang mata sedang mengawasi jalannya pertempuran itu. Orang-orang yang sedang bersembunyi di balik tanggul dekat gardu perondan itu telah melihat dan mendengar semua yang telah terjadi.
“Itulah gambaran keadaan para perangkat Perdikan Matesih sekarang ini,” desis orang yang usianya sudah lewat setengah abad namun masih tampak muda dan gagah, “Ki Gede Matesih benar-benar prihatin dengan keadaan kawulanya. Apalagi para perangkat tanah perdikan sudah banyak yang terpengaruh dengan janji-janji Raden Mas Harya Surengpati.”
“Kakang,” tiba-tiba terdengar seorang yang masih cukup muda menyela, “Bagaimana jika kita datangi saja rumah tempat kediaman Raden Surengpati itu di Matesih dan kita hancurkan?”
“Tidak semudah itu Glagah Putih,” jawab orang itu, “Dengan demikian kita akan memancing para pengikut Trah Sekar Seda Lepen serta para Cantrik perguruan Sapta Dhahana turun berbondong-bondong ke Perdikan Matesih. Kita akan kesulitan untuk melawan mereka semua.”
“Ki Rangga,” tiba-tiba seseorang yang sudah tua menyahut cepat, “Kita harus ikut mencegah berita lolosnya kita dari banjar padukuhan itu sampai ke telinga orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen.”
“Benar Ki Jayaraga,” jawab orang itu yang ternyata Ki Rangga Agung Sedayu, “Aku mempunyai rencana, selagi para murid padepokan Sapta Dhahana dan para pengawal Padukuhan Klangon disibukkan di banjar Padukuhan Klangon, kita dapat bergerak menyelidiki keadaan di Gunung Tidar.”
“Bagaimana rencana kakang?” sela Glagah Putih tidak sabar.
Ki Rangga menarik nafas panjang terlebih dahulu sebelum menjawab. Dilemparkan pandangan matanya kearah pertempuran antara kedua pengawal perdikan Matesih itu. Tampak Ki Wiyaga sedikit demi sedikit mulai tampak menguasai jalannya pertempuran.
“Kita sebaiknya berpencar untuk menghindari kemungkinan adanya pengamatan para telik sandi lawan,” berkata Ki Rangga kemudian, “Kita akan bergerak dalam dua kelompok. Aku akan bersama dengan Ki Waskita bergerak menyusur ke arah timur lereng Gunung Tidar. Sementara Ki Jayaraga, Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih menyusur sebelah barat lereng Gunung Tidar.”
Tampak kepala orang-orang yang berada di situ terangguk-angguk. Agaknya semuanya setuju dengan rencana Ki Rangga.
“Ngger,’ tiba-tiba Ki Waskita berkata setelah mereka terdiam sejenak, “Bagaimana dengan Ki Gede Matesih? Ki Gede telah berencana untuk mengundang kita sebagai tamu-tamunya, namun ternyata keadaan telah berkembang lain. Kita harus memberitahu perkembangan keadaan ini kepada ki Gede.”
Mendengar pertanyaan Ki Waskita itu, tanpa sadar Ki Rangga telah berpaling ke medan pertempuran antara kedua pengawal itu. Agaknya orang-orang itu dapat membaca pikiran Ki Rangga. Maka kata Ki Waskita kemudian, “Sebuah pemikiran yang bagus, ngger. Kita akan meminta Ki Wiyaga untuk memberitahu Ki Gede.”
Yang mendengar kata-kata Ki Waskita itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka.
Demikianlah sejenak kemudian, Ki Wiyaga benar-benar telah menguasai pertempuran. Lajuwit yang berbadan tinggi besar itu tidak mampu mengatasi kelincahan Ki Wiyaga yang berbadan sedikit lebih pendek. Pengalaman serta ketekunan yang dimiliki oleh kepala pengawal Perdikan Matesih itu selama ini ternyata telah menunjukkan hasil yang gemilang. Lajuwit benar-benar sudah hampir tak berdaya.
Ketika sebuah pukulan kembali mendarat di bagian tubuh Lajuwit, salah satu pengawal yang pernah menimba ilmu di Perguruan Sapta Dhahana itu telah terhuyung-huyung ke samping. Dengan menggeretakkan giginya, Lajuwit mencoba memperbaiki kedudukannya. Namun sebelum tubuhnya benar-benar berdiri tegak, ujung tumit kaki Ki Wiyaga telah mendarat di lambungnya.
Terdengar keluhan tertahan dari mulut Lajuwit. Tanpa dapat dikendalikan lagi, tubuhnya pun terdorong beberapa langkah ke belakang sebelum akhirnya jatuh terlentang di atas tanah.
Ki Wiyaga yang melihat lawannya telah terlempar dan jatuh terlentang di atas tanah telah menghentikan serangannya.
Namun yang terjadi kemudian benar-benar diluar dugaan Ki Wiyaga maupun orang-orang yang bersembunyi di balik tanggul itu. Lajuwit yang terlihat sudah tak berdaya itu, tiba-tiba dengan susah payah telah bangkit berdiri. Dengan berdiri sedikit terhuyung-huyung salah satu tangannya telah mengambil sesuatu dari balik bajunya. Belum sempat Ki Wiyaga menyadari apa yang akan dilakukan oleh Lajuwit, tiba-tiba saja dua buah pisau kecil berwarna gelap telah meluncur menyambar dadanya.
Jarak Lajuwit dengan Ki Wiyaga hanya sekitar empat langkah sehingga Ki Wiyaga benar-benar sedang dalam kesulitan. Sambaran pisau yang pertama masih sempat dihindarinya dengan memiringkan tubuhnya, namun pisau yang kedua telah berhasil menyambar pundaknya.
Terdengar Ki Wiyaga berdesis tertahan. Mulutnya tampak menyeringai menahan rasa pedih yang menyengat pundaknya. Luka itu memang tidak terlalu dalam, namun darah yang mengalir dari luka itu berwarna kehitam hitaman.
“Racun!” seru Ki Wiyaga sambil berusaha menekan sekitar luka itu agar racun yang terlanjur memasuki tubuhnya tidak menjalar mengikuti arus darahnya.
Melihat Ki Wiyaga sibuk dengan lukanya, Lajuwit ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat diraihnya lagi sebilah pisau belati dari balik bajunya. Sambil tertawa penuh rasa kemenangan, sekali lagi sebuah pisau meluncur dari tangannya mengarah ke leher Ki Wiyaga.
Namun di saat yang menentukan itu, tiba-tiba saja dari balik tanggul di dekat gardu perondan meluncur sebuah batu sebesar kepalan orang dewasa menyongsong pisau belati yang mengarah ke leher Ki Wiyaga.
Sejenak kemudian terdengar benturan yang cukup keras. Batu sebesar kepalan orang dewasa itu telah menghantam pisau belati itu. Akibatnya adalah diluar dugaan semua orang. Kekuatan lontaran batu yang berlebihan itu ternyata telah menghantam balik pisau belati itu kembali ke pemiliknya. Arah lontaran batu itu memang segaris dengan arah pisau belati itu. Tanpa dapat dicegah lagi, pisau belati itu pun dengan deras berbalik ke pemiliknya dan dengan tepat menghunjam jantungnya.
Lajuwit hanya sempat mengeluh pendek sebelum tubuhnya terdorong selangkah ke belakang. Sejenak tubuh tinggi besar itu masih limbung sebelum akhirnya jatuh terjerembab tidak bernafas lagi.
Dalam pada itu kelima orang yang bersembunyi di balik tanggul itu pun telah terkejut bukan alang kepalang, terutama Ki Rangga Agung Sedayu. Dengan segera mereka pun kemudian berloncatan keluar dari persembunyian mereka dan berlari menuju ke bekas medan pertempuran kedua pengawal itu.
Ki Rangga segera berlari ke tempat Ki Wiyaga yang tampak terjatuh pada kedua lututnya. Wajahnya pucat serta bibirnya bergetar menahan sakit di pundaknya akibat racun yang mulai menjalar di aliran darahnya. Pandangan matanya mulai gelap dan kesadarannya pun perlahan menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang limbung.
Dengan cepat Ki Rangga segera menangkap tubuh ki Wiyaga yang terlihat mulai limbung akan terjatuh. Setelah dibaringkan di atas tanah, dengan cekatan jari-jemari Ki Rangga segera memijat urat-urat nadi yang berada di sekitar pundak Ki Wiyaga agar racun itu tidak menjalar semakin jauh.
“Kakang,” bisik Glagah Putih yang telah ikut berlutut di sisi tubuh Ki Wiyaga, “Ini barangkali dapat membantu kakang.”
Ki Rangga berpaling. Dilihatnya Glagah Putih mengangsurkan sebuah cincin bermata batu yang berwarna kebiru-biruan dengan garis-garis putih di dalamnya.
Sejenak Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam sambil tersenyum. Cincin bermata batu itu mengingatkan Ki Rangga kepada gurunya, Kiai Gringsing.
“Terima kasih Glagah Putih,” berkata Ki Rangga kemudian sambil menerima uluran tangan Glagah Putih. Dengan tanpa membuang waktu lagi, ditempelkannya batu yang terdapat pada cincin itu di luka Ki Wiyaga.
Beberapa saat kemudian, tampak warna garis-garis putih di dalam batu itu berubah menjadi kehitam-hitaman, sedangkan luka yang terdapat di pundak Ki Wiyaga pun berangsur-angsur mulai mengalirkan darah yang berwarna merah segar, tidak lagi kehitam-hitaman.
“Syukurlah,” berkata Ki Rangga kemudian sambil mengangkat cincin itu dari luka ki Wiyaga dan kemudian mengembalikannya kepada Glagah Putih, “Agaknya Yang Maha Agung telah mengabulkan permohonan dan usaha kita.”
“Ya ngger,” terdengar suara Ki Waskita yang telah ikut berlutut di sisi tubuh Ki Wiyaga, “Racun ini sangat kuat dan jahat. Agaknya orang-orang Gunung Tidur memang senang bermain-main dengan racun.”
Ki Rangga menganggukkan kepalanya sambil tangannya sibuk menaburkan sejenis bubuk berwarna kehijau-hijaun di atas luka Ki Wiyaga. Sejenak kemudian luka itu pun telah mampat walaupun masih belum sempurna.
“Glagah Putih,” berkata Ki Rangga kemudian tanpa berpaling, “Tolong carikan air.”
“Baik kakang,” jawab Glagah Putih dengan serta merta sambil bangkit berdiri.
Sepeninggal Glagah Putih, Ki Waskita segera berbisik, “Ngger. Agaknya tenaga lontaranmu terlalu kuat sehingga pisau itu telah berbalik arah dan mengenai orang itu sendiri.”
Ki Rangga menarik nafas panjang sambil mengangkat kepalanya. Dilihatnya Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan sedang melihat keadaan Lajuwit yang telah terbujur menjadi mayat. Ada rasa penyesalan di dalam hati ki Rangga, namun semua itu dilakukan tanpa kesengajaan sama sekali. Ki Rangga tidak menduga bahwa pengawal itu akan berbuat curang selagi Ki Wiyaga lengah.
“Aku betul-betul tidak sengaja, Ki Waskita,” berkata Ki Rangga kemudian sambil membebat luka yang ada di pundak Ki Wiyaga dengan secarik kain yang didapat dari sobekan kain panjang kepala pengawal itu, “Aku benar-benar dicengkam kecemasan yang luar biasa begitu melihat pisau berikutnya itu meluncur ke arah leher Ki Wiyaga yang sedang tak berdaya.”
Ki Waskita tidak menjawab hanya tampak kepalanya saja yang terangguk-angguk. Sementara Glagah Putih telah datang sambil membawa kendi yang penuh berisi air.
“Dari mana engkau dapatkan kendi ini, Glagah Putih?” bertanya Ki Rangga sambil menerima kendi itu dari tangan adik sepupunya itu.
Glagah Putih tersenyum sambil kembali berlutut. Jawabnya kemudian, “Di setiap gardu perondan pasti disiapkan air minum, namun kadang sudah kosong tidak ada isinya. Untunglah kendi ini masih cukup banyak isinya.”
Ki Rangga tersenyum sambil mengambil sebutir obat yang berwarna hijau dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian katanya kepada Glagah Putih, “Bantu aku mengangkat kepalanya.”
Dengan cepat Glagah Putih segera menyangga kepala Ki Wiyaga. Sementara Ki Rangga telah membuka mulut Ki Wiyaga dan memasukkan sebutir obat yang berwarna hijau itu ke dalam mulutnya. Sambil memijat urat leher Ki Wiyaga dengan tangan kirinya, tangan kanan Ki Rangga meraih kendi berisi air itu dan menuangkan isinya perlahan-lahan ke mulut Ki Wiyaga. Sejenak kemudian obat itu pun telah memasuki perut Ki Wiyaga.
“Turunkan,” perintah Ki Rangga kepada Glagah Putih. Dengan perlahan Glagah Putih pun kemudian menurunkan kepala Ki Wiyaga kembali ke atas tanah.
Demikianlah Ki Rangga pun kemudian segera berusaha untuk menyadarkan Ki Wiyaga. Dengan pijatan perlahan di belakang lehernya, Ki Wiyaga pun tampak mulai menunjukkan tanda-tanda kesadarannya.
Ketika sekali lagi Ki Rangga mengusap tengkuknya, Ki Wiyaga pun telah berdesah perlahan sambil menarik nafas panjang dan menggeliat. Ketika Ki Wiyaga pertama kali membuka matanya, yang tampak kemudian hanyalah bayangan kabur beberapa orang yang sedang mengerumuninya.
Setelah mengerjap-kerjapkan matanya beberapa kali, barulah Ki Wiyaga melihat dengan jelas orang-orang yang sedang mengerumuninya, namun tak satu pun dari mereka yang dikenalnya.
“Siapa?’ bertanya Ki Wiyaga kemudian sambil mencoba bangkit berdiri. Ki Rangga pun segera membantu kepala pengawal perdikan Matesih itu untuk duduk.
“Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian setelah melihat Ki Wiyaga duduk dengan sempurna, “Kami berlima adalah para pengembara dari Prambanan yang kebetulan saja sedang lewat di tempat ini dan melihat kalian sedang bertempur.”
Terkejut Ki Wiyaga mendengar pengakuan Ki Rangga. Tanpa sadar diedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Ketika pandangan matanya kemudian tertumbuk pada Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan yang sedang mengangkat jasad Lajuwit untuk dibawa ke gardu, wajah Ki Wiyaga pun telah menegang.
“Apa yang telah mereka lakukan pada Lajuwit?” pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir ki Wiyaga.
“Tenanglah Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian sambil menahan tubuh kepala pengawal itu yang tiba-tiba saja akan bangkit berdiri, “Temanmu itu telah mati terkena pisau beracunnya sendiri.”
“He?” seru Ki Wiyaga seakan tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Sambil berpaling ke arah Ki Rangga, dia melanjutkan pertanyaannya, “Bagaimana itu bisa terjadi?”
Orang-orang yang sedang mengerumuni Ki Wiyaga itu saling pandang sejenak. Ki Rangga lah yang akhirnya menjawab, “Ki Sanak, dia kurang hati-hati mempergunakan pisau belatinya yang sangat beracun itu sehingga telah merenggut nyawanya sendiri.”
Ki Wiyaga mengerutkan keningnya mendengar penjelasan ki Rangga. Pada saat dia sibuk dengan lukanya beberapa saat tadi, dia telah mendengar sebuah benturan. Namun selanjutnya dia sudah tidak ingat lagi.
“Sudahlah Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian sambil membantu Ki Wiyaga ketika kepala pengawal itu mencoba bangkit dari duduknya, “Sekarang sebaiknya segera kita selenggarakan jasad pengawal itu.”
“Ya Ki Wiyaga,” sahut Ki Waskita, “Bukankah nama Ki Sanak, Ki Wiyaga? Kepala pengawal Perdikan Matesih?”
Ki Wiyaga yang sudah berdiri di atas kedua kakinya berpaling ke arah Ki Waskita. Pertanyaan Ki Waskita tidak dijawabnya, justru dia telah balik bertanya, “Dari mana Ki Sanak mengetahuinya?”
Ki Waskita tersenyum. Jawabnya kemudian, “Sedari tadi kami sudah berada di balik tanggul dekat gardu itu.”
Ki Wiyaga termangu-mangu. Berbagai dugaan muncul dalam benaknya tentang kelima orang yang mengaku berasal dari Prambanan itu.
Ketika Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan kemudian berjalan mendekat, Ki Wiyaga pun tiba-tiba telah melangkah mundur sambil berdesis, “Siapakah kalian ini sebenarnya?”
“Ki Wiyaga,” jawab Ki Rangga sambil maju selangkah, “Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ki Waskita tadi, kami berlima adalah pengembara dari Prambanan. Kami tidak akan mengganggu keberadaan Perdikan Matesih, justru kami ingin membantu tanah Perdikan Matesih ini.”
Kepala pengawal perdikan Matesih itu sejenak mengerutkan keningnya. Tentu saja dia tidak dapat mempercayai keterangan Ki Rangga begitu saja. Tanah Perdikan Matesih sedang mengalami goncangan dan setiap orang dapat saja mengaku sebagai kawan atau bahkan lawan.
“Ki Wiyaga,” berkata Ki Rangga selanjutnya begitu menyadari keragu-raguan tampak menyelimuti wajah Ki Wiyaga, “Percayalah, kami berlima tidak mempunyai maksud jelek, jika kami adalah bagian dari orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen itu, tentu kami akan membiarkan saja Ki Wiyaga terluka dan mati direnggut oleh racun yang sangat kuat dan jahat.”
Terkejut Ki Wiyaga mendengar keterangan Ki Rangga. Tanpa sadar dia meraba pundak kirinya yang dibebat dengan sobekan kain panjangnya sendiri. Menyadari akan keterlanjurannya, Ki Wiyaga pun segera maju mendekati Ki Rangga.
“Maafkan akan keterlanjuranku Ki Sanak,” berkata Ki Wiyaga kemudian sambil berjalan memutar dan menjabat tangan kelima orang itu. Ki Rangga dan kawan-kawannya pun kemudian menyambut uluran tangan Ki Wiyaga sambil satu-persatu menyebutkan nama mereka.
“Nah, Ki Sedayu,” berkata Ki Wiyaga kemudian setelah mengetahui nama Ki Rangga, “Apakah yang dapat aku bantu?”
Sejenak Ki Rangga memandang ke arah kawan-kawannya, namun agaknya kali ini terutama Ki Waskita telah menyerahkan purba wasesa kepada Ki Rangga. Maka jawab Ki Rangga kemudian, “Hari telah semakin terang. Sebaiknya jasad pengawal itu segera dikuburkan.”
“Apakah pengawal itu mempunyai keluarga?” tiba-tiba Glagah Putih bertanya.
Ki Wiyaga menggeleng. Jawabnya kemudian, “Sebenarnya Lajuwit bukanlah orang Matesih. Dia datang entah dari mana dan berguru ke padepokan Sapta Dhahana. Selang beberapa saat kemudian setelah dia merasa cukup menimba ilmu, dia telah turun gunung dan menetap di Matesih.”
“Dan kemudian menjadi salah satu pengawal perdikan Matesih,” sahut Glagah Putih.
“Aku lah yang telah mengusulkan kepada Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga dengan serta merta, “Karena aku melihat kemampuannya yang lebih dari cukup untuk membantu menjaga keamanan di Matesih.”
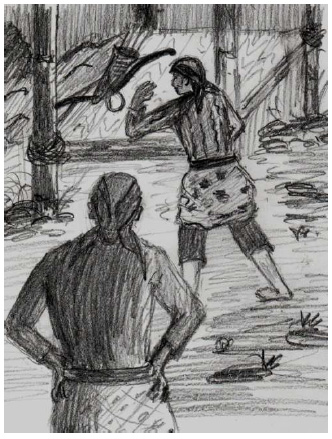
…..Namun sebelum tangannya meraih busur dan anak panah itu, terdengar seseorang bergumam di belakangnya.
Orang-orang yang hadir di tempat itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sebenarnya lah Lajuwit memang masih mempunyai hubungan yang erat dengan Perguruan Sapta Dhahana.“Nah, sekarang bagaimana dengan mayat itu?” sekarang giliran Ki Jayaraga yang bertanya.
Mendapatkan pertanyaan Ki Jayaraga, Ki Wiyaga pun segera berpaling ke arah Ki Rangga.
“Ki Wiyaga,” berkata Ki Rangga kemudian, “Sebaiknya engkau melaporkan kejadian ini terlebih dahulu kepada Ki Gede. Demikian juga dengan keberadaan kami berlima. Sampaikan kepada Ki Gede bahwa Ki Gede tidak usah mengirim utusan untuk menjemput kami di banjar Padukuhan Klangon. Sampaikan kepada Ki Gede bahwa kami berlima telah memutuskan untuk lolos dari banjar karena menjelang dini hari tadi, banjar Klangon telah dikepung oleh murid-murid dari perguruan Sapta Dhahana.”
Terkejut Ki Wiyaga mendengar keterangan Ki Rangga. Dengan segera dia membungkukkan badannya dalam-dalam sambil berkata, “Maafkan aku yang terlalu deksura terhadap kalian berlima. Aku tidak tahu kalau ternyata kalian adalah tamu-tamu Ki Gede. Sesungguhnya aku telah ditugasi oleh Ki Gede untuk menjemput kalian berlima nanti menjelang saat pasar temawon.”
“Sudahlah Ki Wiyaga,” sahut Ki Jayaraga sambil tertawa pendek, “Kami bukan para bangsawan yang harus dihormati dengan berlebihan. Kami memang masih terhitung saudara jauh dari Ki Gede.”
Ki Wiyaga mengangguk-anggukkan kepalanya. Diam-diam dalam hati Ki Wiyaga bersyukur. Agaknya kelima tamu Ki Gede ini yang akan membantu mengurai benang kusut yang sedang terjadi di Perdikan Matesih.
“Nah, sekarang apakah Ki Sanak berlima akan pergi ke kediaman Ki Gede?” bertanya Ki Wiyaga kemudian.
“O, tidak, tidak,” jawab Ki Rangga dengan serta merta, “Kami masih ada urusan yang harus kami selesaikan. Sampaikan kepada Ki Gede, setelah urusan kami selesai, kami pasti akan menghadap.”
Ki Wiyaga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tidak berani bertanya lebih jauh tentang urusan kelima orang itu.
“Sebaiknya jasad pengawal itu disembunyikan terlebih dahulu sambil menunggu arahan Ki Gede,” berkata Ki Rangga kemudian setelah sejenak mereka terdiam.
“Ki Rangga benar,” sahut Ki Waskita, “Ki Wiyaga dapat memohon arahan Ki Gede tentang jasad pengawal itu, dan jika memang harus dikuburkan, Ki Wiyaga dapat meminta bantuan kawan-kawan Ki Wiyaga yang dapat dipercaya.”
Ki Wiyaga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
“Marilah,” berkata Ki Rangga kemudian sambil melangkah mendekati gardu, “Kita sembunyikan jasad pengawal itu di bawah gardu.”
Demikianlah sejenak kemudian orang–orang itu segera menyembunyikan mayat itu di bawah gardu. Glagah Putih telah mencari rumput-rumput kering untuk menimbuni mayat itu agar tidak terlihat apabila ada orang yang lewat di sekitar tempat itu.
Setelah pekerjaan itu selesai, mereka pun segera berpencar, Ki Wiyaga berjalan menuju ke kediaman Ki Gede, sedangkan kelima orang itu pun telah menempuh jalan mereka sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.
Dalam pada itu Matahari telah semakin terang sinarnya. Butir-butir embun yang menebar di atas rerumputan serta bergelayutan di pucuk-pucuk dedaunan telah menguap. Burung-burung pun berkicau tak henti-hentinya menyambut terbitnya Matahari pagi.
Di padepokan Sapta Dhahana, beberapa cantrik tampak sedang berjaga-jaga di regol depan. Mereka bersenda-gurau dengan riangnya seolah-olah tidak ada beban sama sekali sehingga tidak menyadari bahwa seseorang sedang berjalan menuju ke arah mereka.
Ketika jarak orang itu tinggal beberapa langkah saja dari regol, barulah para cantrik itu menyadari atas kelengahan mereka. Segera saja mereka berloncatan ke tengah-tengah regol menghadang orang itu.
“Berhenti!” bentak cantrik tertua diantara mereka, “Kakek tua, engkau harus minta ijin dulu kepada kami jika ingin memasuki padepokan.”
Orang yang mendatangi regol padepokan itu memang seorang yang sudah sangat renta. Tubuhnya kurus kering dan hanya tubuh bagian bawahnya saja yang dibalut dengan selembar kain panjang yang sangat kumal dan lusuh. Sedangkan bagian atas tubuhnya telanjang sehingga terlihat dengan jelas tulang-tulang iganya yang menonjol. Sementara rambutnya yang panjang dan gimbali itu digelung ke atas dan diikat dengan secarik kain usang.
“Kakek!” kembali cantrik tertua itu membentak begitu dilihatnya kakek tua itu tidak menanggapinya justru malah berdiri sambil memejamkan kedua matanya. Tubuhnya tampak bergoyang-goyang mengikuti aliran angin yang bertiup cukup keras pagi itu.
Melihat kakek itu acuh tak acuh, salah satu cantrik yang berbadan tinggi besar segera maju ke depan. Tanpa basa-basi dicengkeramnya leher kakek tua itu dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya mengepal keras dan disorongkannya tepat di depan hidung kakek tua itu.
“Jangan macam-macam gembel tua!” geram cantrik itu kemudian, “Di sini padepokan Sapta Dhahana, tempat orang-orang sakti. Bukan gardu perondan yang dapat engkau singgahi dengan seenaknya!”
Namun yang terjadi kemudian adalah sangat diluar dugaan setiap orang. Tiba-tiba saja kakek tua itu telah membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian menjulurkan lidahnya keluar. Lidah yang panjang itu pun kemudian menjilat pergelangan tangan cantrik itu.
Bagaikan tersentuh bara api dari tempurung kelapa, cantrik itu pun telah menjerit keras sambil meloncat mundur. Dengan tergesa-gesa diperiksanya pergelangan tangan kirinya. Beberapa kawannya pun telah mendekat untuk melihat apa sebenarnya yang telah terjadi.
Sejenak kemudian, setiap jantung orang yang berada di tempat itu pun bagaikan terlepas dari tangkainya. Kulit pergelangan tangan kiri cantrik itu ternyata telah hangus terbakar.
“Gila!” hampir setiap mulut telah mengumpat. Namun kini mereka tidak berani lagi dengan gegabah untuk mendekati kakek aneh itu.
“Kau, pergilah ke dalam,” perintah cantrik tertua itu kemudian kepada cantrik yang pergelangan tangannya terluka, “Laporkan kejadian ini kepada Kakang Putut Sambernyawa, sekalian ke balai pengobatan untuk mengobati lukamu.”
“Baik, kakang,” jawab cantrik itu. Dengan mulut menyeringai menahan sakit dan tangan kanan menekan seputar pergelangan tangan kirinya, cantrik itupun segera bergeser mundur dan kemudian berlari ke dalam padepokan.
Dalam pada itu, kakek aneh itu ternyata tetap pada sikapnya semula. Berdiri tegak sambil memejamkan kedua matanya dengan tubuh yang bergoyang-goyang mengikuti hembusan angin pagi.
Dengan memberi isyarat kepada kawan-kawannya terlebih dahulu, cantrik tertua itupun kemudian segera bergeser mundur selangkah. Kawan-kawannya ternyata telah tanggap dan segera mengikuti bergerak setapak demi setapak sambil berpencar sehingga sejenak kemudian, kakek tua itu telah berada di dalam lingkaran para cantrik.
Untuk beberapa saat suasana benar-benar menegangkan. Para cantrik itu tidak ada yang berani mendahului bergerak. Mereka hanya berusaha menahan kakek tua itu agar tidak meloloskan diri sambil menunggu kedatangan cantrik tertua, Putut Sambernyawa.
Dalam keheningan yang menegangkan itu, tiba-tiba saja kakek tua itu dengan tetap memejamkan keduanya matanya, bibirnya telah mengeluarkan suara siulan yang aneh. Pada awalnya suara siulan itu terdengar seperti desis seekor ular. Namun lama kelamaan suara siulan itu terdengar meninggi mirip seperti suara jeritan seekor burung elang. Sesaat kemudian tiab-tiba saja suara siulan itu menurun dan terdengar menyayat seperti rintihan seekor burung kedasih.
Para cantrik yang mendengarkan suara siulan yang berubah-ubah itu menjadi heran. Mereka tidak mengetahui maksud dari kakek aneh itu. Mereka hanya dapat berdiri termangu-mangu sambil tetap tidak meninggalkan kewaspadaan.
Dalam pada itu, di ruang dalam padepokan, Raden Wirasena yang sedang duduk-duduk ditemani Kiai Damar Sasangka telah dikejutkan oleh suara siulan aneh yang terdengar sangat jelas dari ruang dalam itu.
“Begawan Cipta Hening?” desis Raden Wirasena. Namun terdengar nada suaranya sedikit ragu-ragu.
“He?!” Kiai Damar Sasangka pun tak kalah terkejutnya mendengar Raden Wirasena telah menyebut sebuah nama.
“Tidak mungkin Raden,” berkata Kiai Damar Sasangka kemudian, “Keberadaan Begawan itu sepertinya hanya sebuah dongeng belaka. Jika memang dia itu benar-benar ada dan masih hidup sampai sekarang ini, tentu umurnya telah mencapai ratusan tahun lebih.”
Sejenak Raden Wirasena termenung. Memang Raden Wirasena sendiri belum pernah bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Begawan Cipta Hening itu.
“Aku memang belum pernah bertemu secara pribadi dengan begawan itu,” berkata Raden Wirasena dalam hati, “Sesuai saran Panembahan Cahaya Warastra, sebelum pecah perang di Menoreh, seharusnya aku sudah menghadap Begawan Cipta Hening di puncak pebukitan Menoreh,” Raden Wirasena berhenti berangan-angan. Lanjutnya kemudian, “Namun aku belum sempat dan Panembahan Cahya Warastra ternyata telah terbunuh di Menoreh.”
Seakan masih jelas tergambar dalam ingatan Raden Wirasena, ketika suatu hari dia sedang mengunjungi padepokan Cahya Warastra. Panembahan Cahya Warastra pada saat itu sedang mempersiapkan penyerbuan ke Menoreh dan berpesan untuk meminta bantuan dan dukungan kepada Begawan Cipta Hening yang sedang bertapa di pucak pebukitan Menoreh. Namun belum sempat Raden Wirasena mendaki pebukitan Menoreh, terdengar kabar bahwa Panembahan Cahaya Warastra telah terbunuh dalam peperangan di Menoreh.
“Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Begawan itu, namun Panembahan telah memberiku petunjuk ciri-ciri orang yang bernama Begawan Cipta Hening itu” berkata Raden Wirasesa dalam hati, “Panembahan Cahaya Warastra juga telah mengajari aku bagaimana cara menghubungi Begawan itu dengan sebuah isyarat khusus,”
Raden Wirasena berhenti berangan-angan sejenak. Lanjutnya, “Mungkin sebelum pecah perang di Menoreh, Panembahan itu masih sempat menghadap Begawan dan menyampaikan keinginanku untuk memohon bantuannya.”
Ketika suara siulan itu tiba-tiba terdengar melengking tinggi, Raden Wirasena pun sudah tidak dapat menahan diri lagi. Maka katanya kemudian, “Marilah Kiai, kita lihat siapakah sebenarnya yang telah datang mengunjungi padepokan Sapta Dhahana ini.”
“Baik Raden,” sahut Kiai Damar Sasangka sambil bangkit dari duduknya mengikuti Raden Wirasena yang telah terlebih dahulu bangkit berdiri.
Sejenak kemudian, kedua orang itu pun dengan berjalan beriringan segera menuju ke pringgitan untuk kemudian keluar ke pendapa.
Begitu keduanya membuka pintu pringgitan, dari jauh mereka telah melihat orang-orang yang berkerumun di depan regol. Tampak Putut Sambernyawa sedang membentak-bentak seorang kakek-kakek yang hanya mengenakan kain panjang yang dibebatkan pada bagian tubuhnya dari pinggang sampai ke lutut.
“Begawan Cipta Hening,” tanpa sadar bibir Raden Wirasena berdesis perlahan.
“Benarkah Raden?” sela Kiai Damar Sasangka. Hatinya sedikit ragu akan keberadaan Begawan itu yang hidup ratusan tahun yang lalu.
“Marilah Kiai,” jawab Raden Wirasena kemudian, “Semua itu memang perlu dibuktikan.”
Dengan langkah yang sedikit bergegas, keduanya segera menyeberangi pendapa yang cukup luas itu untuk kemudian turun ke halaman.
Namun ternyata ada salah satu cantrik yang melihat kedatangan kedua orang itu. Maka katanya kemudian setengah berteriak, “Kiai Damar Sasangka pemimpin padepokan Sapta Dhahana bersama Raden Wirasena Trah Sekar Seda Lepen telah berkenan hadir!”
Tiba-tiba saja suara siulan itu berhenti dan kakek yang aneh itu pun segera membuka kedua matanya. Sementara kerumunan para cantrik di depan regol itu segera menyibak memberi jalan kepada kedua orang yang sangat disegani itu.
Raden Wirasena segera saja mengenali kakek tua itu sebagai Begawan Cipta Hening, sesuai ciri-ciri yang diberitahukan oleh Panembahan Cahya Wirastra.
“Selamat datang Begawan,” sapa Raden Wirasena ramah, “Mohon dimaafkan sambutan para Cantrik yang kurang menyenangkan. Sesungguhnyalah mereka hanya menjalankan tugas.”
Begawan Cipta Hening mengerutkan keningnya yang sudah keriput itu. Dipandanginya kedua orang yang datang kemudian itu ganti berganti. Tanyanya kemudian dengan sorot mata yang menyala, “Siapakah di antara kalian yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen?”
Berdesir dada Raden Wirasena mendapat pertanyaan itu. Namun dengan cepat Raden Wirasena segera maju selangkah. Jawabnya kemudian, “Begawan, akulah Trah Sekar Seda Lepen yang seharusnya berhak atas tahta di negeri ini.”
“Omong kosong!” sergah Begawan Cipta Hening, “Setiap orang dapat saja mengaku berhak atas tahta negeri ini. Aku pun juga berhak,” Begawan berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian sambil membusungkan dadanya yang kurus, “Aku adalah keturunan Jaka Umbaran yang kemudian bergelar Menak Jingga di Blambangan. Bukankah seharusnya yang menjadi Raja Majapahit adalah Jaka Umbaran? Mengapa dia justru telah difitnah dan disingkirkan?”
Orang-orang yang hadir di tempat itu telah membeku. Kebanyakan dari mereka memang tidak begitu mengetahui sejarah, atau bahkan oleh orang-orang tertentu sejarah itu dengan sengaja telah dikaburkan.
“Maaf Begawan,” berkata Raden Wirasena kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Sejarah memang harus diluruskan, dan sudah menjadi kewajiban kita bersama. Aku selaku Trah dari Pangeran Sekar tidak akan menutup mata terhadap para pendahulu yang juga mempunyai trah dari Majapahit atau lainnya. Kita akan bersama-sama bahu membahu mengusir orang-orang dari trah pidak pedarakan yang sekarang ini justru sedang berkuasa di Mataram.”
Begawan menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Katanya kemudian, “Memang seharusnya negeri ini tetap dipimpin dari trah Kusuma Rembesing Madu, bukan para petani dari Sela yang hanya karena minum air kelapa muda kemudian keturunannya bisa menjadi Raja.”
“Begawan benar,” jawab Raden Wirasena, “Sekarang marilah kita bicarakan segala sesuatunya di dalam agar lebih tenang dan nyaman.”
Begawan Cipta Hening tertawa pendek mendengar ajakan Raden Wirasena. Jawabnya kemudian, “Apakah aku sudah disiapkan makanan yang enak-enak? Tuak yang terbaik dan terkeras? Gadis-gadis cantik yang akan melayani aku sepanjang malam?”
Berdesir dada Raden Wirasena mendengar permintaan Begawan aneh itu. Tanpa sadar dia telah berpaling ke arah Kiai Damar Sasangka.
Kiai Damar Sasangka tersenyum sekilas. Setelah maju selangkah, barulah Kiai Damar Sasangka itu berkata, “Kami atas nama seluruh penghuni padepokan Sapta Dhahana mengucapkan selamat datang kepada Begawan Cipta Hening. Marilah Begawan, kami persilahkan untuk beristirahat sejenak di tempat yang telah kami sediakan. Urusan selanjutnya akan kita bicarakan kemudian.”
Begawan Cipta Hening untuk sejenak kembali mengerutkan keningnya yang sudah keriput itu. Dipandanginya wajah pemimpin perguruan Sapta Dhahana itu dalam-dalam. Katanya kemudian, “Sapta Dhahana yang berarti api yang panasnya tujuh kali lipat dengan panasnya api biasa,” Begawan itu berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian setengah berteriak, “He! Aku sepertinya pernah mengenal orang sakti dari Sapta Dhahana, Kiai Guntur Geni. Dimana dia sekarang? Panggil dia untuk menyambut aku.”
Kiai Sapta Dhahana tertegun, orang yang disebutkan oleh Begawan Cipta Hening itu adalah Kakek Gurunya yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Maka katanya kemudian, “Begawan memang benar, Kiai Guntur Geni itu adalah Kakek guru kami. Beliau telah meninggal dunia berpuluh tahun yang lalu. Dan sekarang aku, Kiai Damar Sasangka adalah cucu beliau yang memimpin perguruan Sapta Dhahana ini.”
Begawan Cipta Hening menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya kemudian, “Semua sahabatku telah mati, tinggal aku sendiri. Rasanya dunia ini menjadi sepi.”
Mendengar ucapan begawan yang bernada keluh kesah itu, Raden Wirasena pun segera berkata, “Marilah Begawan. Kita dapat membicarakan segala sesuatunya di dalam agar lebih nyaman.”
Selesai berkata demikian Raden Wirasena segera mempersilahkan Begawan Cipta Hening untuk berjalan di depan.
Demikianlah kedatangan Begawan Itu telah menambah kekuatan dari orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen. Kekuatan yang belum disadari dan diperhitungkan dengan cermat oleh Ki Rangga dan kawan-kawannya.
Dalam pada itu ketika Matahari sudah bersinar dengan cerahnya, di rumah ki Gede Matesih, Ki Gede sedang mengumpulkan para bebahu tanah Perdikan yang masih setia mendukung setiap kebijakkan Ki Gede dan dapat dipercaya.
“Keadaan telah berkembang semakin tidak menentu,” berkata Ki Gede memulai pembicaraan, “Kita harus semakin waspada justru di antara kawan sendiri. Aku berharap kelima tamu yang akan datang ke rumah ini akan menambah kekuatan kita untuk melawan pengaruh Raden Surengpati.”
Orang-orang yang hadir di ruang dalam itu pun tampak mengangguk-angguk. Berkata seorang yang berkumis tipis kemudian, “Ma’af Ki Gede. Apakah Ki Gede sudah yakin dengan kemampuan mereka? Maksudku dalam hal ilmu olah kanuragan. Kita semua menyadari bahwa Raden Surengpati dan para pengikutnya tidak dapat dipandang dengan sebelah mata.”
“Engkau benar Ki Jagatirta,” jawab Ki Gede, “Aku memang belum mempunyai gambaran yang jelas tentang kemampuan kelima orang tersebut. Namun aku percaya menilik sorot mata mereka yang tajam dan tenang serta ketegasan mereka dalam berbicara terutama orang yang bernama Ki Sedayu itu. Aku telah menaruh harapan yang besar kepada mereka untuk membebaskan tanah perdikan ini dari pengaruh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen.”
Bagian 3
Ki Jagatirta mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara orang di sebelahnya yang sudah cukup berumur telah beringsut dari duduknya sejengkal sambil bertanya, “Maaf Ki Gede, apakah telah ditunjuk seseorang untuk menjemput para tamu itu?”“Sudah Ki Kamitua,” sahut ki Gede cepat, “Aku telah memerintahkan kepada Ki Wiyaga pagi tadi sebelum Matahari terbit untuk pergi ke dukuh Klangon menjemput para tamu kita.”
Ki Kamitua mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, “Ki Gede, para pengawal di Perdikan Matesih ini telah terpecah menjadi dua golongan. Sebagian tetap bersetia kepada Perdikan Matesih di bawah panji-panji kebesaran Mataram, sedangkan yang lainnya, terutama yang muda-muda, mereka lebih senang berangan-angan bersama para pengikut Trah Sekar Seda Lepen. Aku khawatir jika Ki Wiyaga sebagai pemimpin pengawal Perdikan Matesih lebih condong untuk mengikuti golongan yang terakhir.”
Terdengar orang-orang yang hadir di ruang dalam itu bergeremang satu dengan lainnya. Agaknya masing-masing mempunyai tanggapan yang berbeda.
“Ki Kamitua,” berkata Ki Gede kemudian sambil mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam sejenak, “Aku percaya dengan Ki Wiyaga. Dia telah menjadi pengawal perdikan Matesih sejak masih muda. Kedudukan pemimpin pengawal itu pun aku percayakan kepadanya setelah ayahnya mengundurkan diri karena usia tua. Jadi aku percaya kepada Ki Wiyaga sebagaimana dulu aku juga percaya kepada ayahnya.”
Sejenak mereka yang hadir di tempat itu terdiam. Masing-masing telah tenggelam dalam kenangan masa lalu yang tenang dan tentram.
“Perdikan Matesih adalah perdikan yang tenang dan damai,” berkata seorang yang rambutnya sudah putih semua dalam hati, “Hampir tidak ada gejolak sama sekali di tanah perdikan ini. Semua penghuninya hidup rukun, guyup dan saling membantu. Namun dengan kedatangan orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen dan para pengikutnya itu, penghuni tanah Perdikan ini telah terpecah belah dan jauh dari yang disebut rukun dan damai.”
Pembicaraan itu terhenti sejenak ketika tiba-tiba saja terdengar pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan dapur berderit. Sejenak kemudian dari pintu yang terbuka muncullah seorang gadis yang sedang beranjak dewasa sambil membawa nampan berisi minuman dan makanan.
Semua orang segera menundukkan wajahnya kecuali Ki Gede Matesih. Dipandanginya wajah anak perempuan satu-satunya itu dengan kening yang berkerut merut. Seraut wajah yang menginjak dewasa dengan segala kelebihannya dibanding dengan gadis-gadis sebayanya.
Ratri, nama gadis semata wayang Ki Gede itu segera berjongkok dan meletakkan minuman dan makanan di depan para tamu. Setelah semuanya selesai, Ratri pun kemudian segera mundur setapak untuk kemudian berdiri dan membalikkan badan. Sejenak kemudian gadis cantik dengan keindahan bentuk tubuh yang mulai beranjak dewasa itu pun telah hilang di balik pintu yang tertutup rapat.
Sepeninggal putrinya, tampak wajah Ki Gede menjadi muram, semuram langit yang sedang turun hujan.
Sambil menarik nafas dalam-dalam dan menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali, Ki Gede pun kemudian berdesis perlahan seolah-olah hanya ditujukan kepada dirinya sendiri, “Aku mungkin salah satu dari sekian banyak orang tua yang tidak mampu memberikan tuntunan yang baik kepada anaknya.”
Suara itu terdengar seperti sebuah keluh kesah atau penyesalan yang tiada taranya.
Orang-orang yang mendengar keluh kesah Ki Gede itu tidak ada yang berani mengangkat kepalanya atau pun membuka suara. Mereka tetap menundukkan kepala dalam-dalam menunggu apa yang akan disampaikan oleh Ki Gede.
“Ah, sudahlah,” berkata Ki Gede kemudian mencoba mencairkan suasana, “Semoga sebelum wayah tengange, para tamu kita telah hadir di rumah ini.”
Orang-orang itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Nah,” berkata Ki Gede selanjutnya, “Apakah masih ada yang ingin disampaikan?”
Namun sebelum salah satu dari orang-orang yang hadir itu membuka suara, tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu, pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan pringgitan.
“Masuklah!” terdengar suara Ki Gede cukup lantang.
Sejenak kemudian terdengar pintu berderit dan seseorang telah muncul dari balik pintu.
“Ki Wiyaga?” hampir serentak mereka yang berada di ruang dalam itu telah berdesis.
Orang yang memasuki ruang dalam itu memang Ki Wiyaga. Namun tidak tampak luka di pundaknya. Bahkan bajunya tampak bersih serta memakai kain panjang yang bersih pula. Agaknya Ki Wiyaga sempat mampir ke rumah terlebih dahulu untuk berganti baju sebelum menghadap Ki Gede.
Setelah mengangguk terlebih dahulu kepada orang-orang yang hadir, terutama Ki Gede, Ki Wiyaga pun segera mengambil duduk di sebelah Ki Jagatirta.
Setelah menanyakan keselamatan Ki Wiyaga terlebih dahulu, barulah Ki Gede bertanya, “Ki Wiyaga, mengapa sepagi ini engkau sudah kembali?”
Sejenak Ki Wiyaga menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan getaran di dalam dadanya. Jawabnya kemudian, “Maaf Ki Gede, aku belum sempat menjemput tamu-tamu kita di banjar Padukuhan Klangon.”
“Mengapa?” tiba-tiba dengan serta-merta Ki Jagatirta telah menyela. Namun begitu disadarinya Ki Gede telah berpaling ke arahnya, dengan cepat segera ditundukkan wajahnya.
“Ya, Ki Wiyaga,” sahut Ki Gede kemudian, “Apa sebenarnya yang telah terjadi?”
“Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga kemudian, “Telah terjadi suatu peristiwa diluar rencana kita.”
Ki Gede mengerutkan keningnya dalam-dalam. Katanya kemudian, “Jangan berputar-putar Ki Wiyaga. Ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi.”
Ki Wiyaga sejenak ragu-ragu. Tanpa sadar, diedarkan pandangan matanya ke arah orang-orang yang hadir di ruangan itu.
Agaknya Ki Gede tanggap akan keragu-raguan kepala pengawal Perdikan Matesih itu. Maka katanya kemudian, “Ki Wiyaga, engkau berada di antara para bebahu perdikan Matesih yang dapat dipercaya.”
“Terima kasih ki Gede,” berkata Ki Wiyaga kemudian, “Kelima tamu kita itu ternyata dengan sengaja telah meloloskan diri dari banjar Padukuhan Klangon.”
“He?!” serentak mereka yang ada di ruangan itu terlonjak kaget, terutama Ki Gede. Sejenak wajahnya menjadi merah padam.
“Siapakah sebenarnya mereka itu?” geram Ki Gede, “Apakah mereka mencoba mempermainkan Ki Gede Matesih?”
“O, tidak, tidak Ki Gede,” sahut Ki Wiyaga cepat, “Sungguh mereka berlima itu orang-orang yang dapat dipercaya.”
“Dari mana Ki Wiyaga tahu?” sela Ki Kamitua.
Ki Wiyaga tersenyum. Sambil menyingkapkan baju di bagian pundak kirinya, Ki Wiyaga pun memperlihatkan bekas lukanya yang telah dibebat dengan secarik kain. Katanya kemudian, “Inilah buktinya. Salah satu dari mereka telah menolongku dari luka yang akan dapat membunuhku. Luka akibat goresan pisau belati yang sangat beracun.”
 Dalam
pada itu, di ruang dalam padepokan, Raden Wirasena yang sedang
duduk-duduk ditemani Kiai Damar Sasangka telah dikejutkan oleh suara
siulan aneh yang terdengar sangat jelas dari ruang dalam itu.
Dalam
pada itu, di ruang dalam padepokan, Raden Wirasena yang sedang
duduk-duduk ditemani Kiai Damar Sasangka telah dikejutkan oleh suara
siulan aneh yang terdengar sangat jelas dari ruang dalam itu.
“Begawan Cipta Hening?” desis Raden Wirasena. Namun terdengar nada suaranya sedikit ragu-ragu.
“He?!” kembali orang-orang itu terkejut. Bertanya Ki Gede kemudian, “Bagaimana itu bisa terjadi?”
Ki Wiyaga menarik nafas panjang sambil membetulkan bajunya kembali.
Jawabnya kemudian, “Ceritanya panjang Ki Gede. Cerita itu dimulai ketika
aku tanpa sengaja telah menemukan salah seorang pengawal perdikan
Matesih, Lajuwit, sedang berusaha mengirim isyarat ke Perguruan Sapta
Dhahana di lereng Gunung Tidar.”Kemudian secara singkat Ki Wiyaga segera menceritakan kejadian di dekat gardu perondan itu serta pertemuannya dengan kelima orang yang mengaku dari Prambanan itu.
“Jadi engkau telah ditolong oleh mereka?” bertanya Ki Gede kemudian.
“Ya Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga, “Jika saja lukaku itu tidak segera diobati oleh orang yang bernama Ki Sedayu itu, mungkin aku sudah tidak dapat lagi berkumpul di tempat ini.”
“Ah!” beberapa orang justru telah berdesah. Sedangkan Ki Gede segera berkata, “Syukurlah agaknya Yang Maha Agung masih melindungi kita untuk menyelamatkan tanah perdikan ini dari segolongan orang yang tidak bertanggung jawab.”
Setiap orang yang ada di ruangan itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Bagaimana dengan Lajuwit?” tiba-tiba Ki Gede bertanya sambil memandang kearah Ki Wiyaga.
Sejenak Ki Wiyaga ragu-ragu. Bagaimanapun juga secara tidak sengaja dia telah ikut berperan dalam terjadinya rajapati, walaupun kejadian yang sebenarnya dia tidak begitu jelas.
“Mengapa engkau terlihat ragu-ragu Ki Wiyaga?” desak Ki Gede, “Katakanlah sejujurnya apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Lajuwit.”
“Maaf Ki Gede, jawab Ki Wiyaga kemudian setelah Menimbang-nimbang beberapa saat, “Lajuwit telah terbunuh oleh pisau beracunnya sendiri.”
“He?!” orang-orang yang berada di ruang itu pun kembali tersentak.
“Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?” hampir setiap mulut telah mengajukan pertanyaan yang serupa.
Namun Ki Wiyaga justru telah menggelengkan kepalanya. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu, karena pengaruh racun itu begitu kuat sehingga aku telah jatuh pingsan. Namun sebelum aku benar-benar kehilangan kesadaranku, aku masih sempat mendengar suara benturan yang keras.”
“Mungkin Lajuwit telah menyerangmu sekali lagi dengan pisau belatinya di saat engkau lengah karena pengaruh racun itu,” berkata Ki Kamitua memberikan pendapatnya.
“Mungkin saja,” sahut Ki Gede, “Dan suara benturan keras yang engkau dengar itu adalah lontaran belati berikutnya yang mungkin telah dipatahkan oleh salah satu dari kelima orang itu.”
“Mungkin Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga sambil mengangguk-angguk, “Kemungkinan itulah yang sebenarnya telah terjadi.”
“Berarti engkau telah berhutang nyawa dua kali kepada mereka, Ki Wiyaga,” kali ini Ki Jagatirta yang menyahut.
Ki Wiyaga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
Untuk beberapa saat ruangan itu pun justru telah menjadi hening.
Namun Ki Gede segera berusaha untuk menguasai keadaan. Maka katanya kemudian, “Semua itu mungkin sudah takdir dari Yang Maha Agung. Menurut pendapatku, Lajuwit telah memetik buah dari apa yang telah ditanamnya selama ini.”
Tampak semua orang mengangguk-anggukkan kepala mereka sambil menarik nafas dalam-dalam.
“Di manakah mayatnya sekarang?” bertanya Ki Gede kemudian.
“Mayat itu kami sembunyikan di bawah gardu,” jawab Ki Wiyaga, “Salah satu dari kelima orang itu telah menimbuninya dengan rumput-rumput kering agar tidak begitu tampak jika ada orang yang melewati gardu itu.”
“Baiklah,” berkata Ki Gede sambil memandang ke arah Ki Jagatirta, “Ki Jagatirta, bawalah beberapa orang yang dapat dipercaya bersama Ki Wiyaga nanti menjelang sirep uwong. Usahakan untuk tidak begitu menarik perhatian dan hanya kalangan kita saja yang mengetahui peristiwa ini.”
“Baik Ki Gede,” jawab Ki Jagatirta sambil menarik nafas panjang. Mengubur mayat di malam hari memang tidak menyenangkan, namun apa boleh buat. Perintah Ki Gede harus dilaksanakan.
“Nah, Ki Wiyaga,” berkata Ki Gede kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Mengapa engkau tadi mengatakan bahwa kelima orang itu dengan sengaja telah lolos dari banjar Padukuhan Klangon?”
Serentak semua mata segera tertuju ke arah Ki Wiyaga.
Menyadari semua orang sedang menunggu jawabannya, Ki Wiyaga pun segera beringsut setapak ke depan. Sambil membetulkan letak kain panjangnya terlebih dahulu, Ki Wiyaga pun kemudian bercerita tentang pengepungan para murid Padepokan Sapta Dhahana di banjar Padukuhan Klangon menjelang dini hari tadi. Sebagaimana seperti yang telah disampaikan oleh Ki Sedayu.
“Gila!’ geram Ki Gede begitu Ki Wiyaga selesai bercerita, “Ternyata kita kalah cepat dengan mereka,” Ki Gede berhenti sejenak. Kemudian sambil berpaling ke arah Ki Jagatirta, Ki Gede bertanya, “Ki Jagatirta, apakah engkau tahu di mana Ki Jagabaya sekarang ini?”
Untuk sejenak Ki Jagatirta memandang para bebahu lainnya untuk meminta pertimbangan. Namun semua bebahu yang hadir disitu telah menggelengkan kepala mereka. Maka jawab Ki Jagatirta kemudian, “Maaf Ki Gede, kami tidak tahu keberadaan Ki Jagabaya beberapa hari ini. Menurut keterangan yang aku peroleh, Ki Jagabaya sering terlihat berkunjung ke rumah yang ditempati Raden Surengpati dan pengikutnya.”
Kembali terdengar Ki Gede menggeram. Wajahnya terlihat sangat keruh. Berkata Ki Gede kemudian, “Kalian semua berhati-hatilah jika berbicara dengan Ki Jagabaya Perdikan Matesih. Aku melihat gelagat yang mencurigakan dari Ki Jagabaya,” Ki Gede berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian, “Lain halnya dengan Padukuhan Klangon, kalian dapat mempercayai Ki Jagabaya dukuh Klangon, namun jangan sekali-kali berbicara dengan Ki Dukuh Klangon. Dia telah terpengaruh dengan Raden Surengpati, sehingga Ki Dukuh Klangon sore tadi telah mengerahkan para pengawalnya untuk berjaga-jaga di banjar.”
“Untunglah kelima orang dari Prambanan itu mampu lolos dari pengamatan mereka,” sahut Ki Kamitua.
“Benar Ki Kamitua,” berkata Ki Wiyaga menanggapi kata-kata Ki Kamitua, “Dan yang lebih untung lagi, mereka berlima ternyata juga terhindar dari kepungan para murid gunung Tidar.”
“Itu menunjukkan bahwa mereka bukan segolongan orang-orang kebanyakan,” sahut Ki Gede dengan nada suara yang yakin dan mantap.
Para bebahu yang hadir di dalam ruangan itu pun tampak mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Nah, sekarang,” berkata Ki Gede selanjutnya, “Bagaimana cara kita untuk menghubungi mereka?”
Kembali semua mata tertuju ke arah Ki Wiyaga. Mereka berharap kepala pengawal perdikan Matesih itu dapat memberikan jawabannya.
Namun alangkah kecewanya para bebahu perdikan Matesih itu, terutama Ki Gede. Mereka melihat Ki Wiyaga justru telah menggelengkan kepalanya.
“Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ki Gede?” bertanya seorang yang rambutnya sudah putih semua.
Sejenak Ki Gede menarik nafas panjang. Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Ki Wiyaga, Ki Wiyaga pun segera tanggap. Maka katanya kemudian, “Ki Jagawana, kelima orang itu sudah berjanji akan menghadap Ki Gede, hanya waktunya saja yang belum pasti, sebab mereka masih mempunyai sebuah urusan untuk segera diselesaikan.”
“Urusan apa itu?” hampir bersamaan pertanyaan itu terdengar di ruangan itu.
Ki Wiyaga menggeleng. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu dan aku tidak berani menanyakannya.”
Untuk beberapa saat suasana menjadi sunyi kembali. Masing-masing sedang tenggelam dalam angan-angan tentang permasalahan yang sedang dihadapi Perdikan Matesih.
“Nah, aku kira sudah cukup pembicaraan kita kali ini,” berkata Ki Gede kemudian memecah kesunyian, “Kalian dapat kembali ke tempat kerja masing-masing. Aku akan nganglang bersama Ki Wiyaga.”
Kemudian sambil berpaling ke arah kepala pengawal itu, Ki Gede pun telah menjatuhkan perintah, “Siagakan beberapa pengawal yang dapat dipercaya. Kita akan mengelilingi Tanah Perdikan Matesih ini untuk memberi kesan kepada para pengikut Trah Sekar Seda Lepen bahwa Perdikan Matesih masih ada dan akan tetap ada selama pemerintahan Mataram masih berdiri tegak.”
Demikianlah, perintah Ki Gede itu merupakan suatu perintah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sejenak kemudian pertemuan para bebahu itu pun telah selesai dan mereka segera kembali ke tempat tugas masing-masing.
Dalam pada itu, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan serta Glagah Putih yang mendapat tugas menyelidiki keberadaan Perguruan Sapta Dhahana dari lereng sebelah barat telah mendapat pesan dari Ki Rangga untuk mengamat-amati kediaman Ki Gede Matesih. Tanpa menarik perhatian mereka berjalan di antara ramainya lalu-lalang para pejalan kaki serta pedati-pedati yang sarat mengangkut hasil bumi. Sesekali mereka juga berpapasan dengan orang-orang yang berkuda.
“Guru, mengapa sejauh ini kita tidak melihat para pengawal Perdikan Matesih sedang meronda?” bertanya Glagah Putih yang berjalan di samping gurunya. Sementara beberapa langkah di belakang mereka, tampak Ki Bango Lamatan berjalan sambil menundukkan kepalanya.
“Entahlah Glagah Putih,” jawab gurunya, “Mungkin mereka merasa Perdikan ini sudah begitu aman, terutama di siang hari.”
“Kejahatan tidak mengenal waktu,” tanpa sadar Glagah Putih berdesis perlahan seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri.
“Engkau benar Glagah Putih,” sahut Gurunya, “Memang kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat, akan tetapi lebih tepatnya, kejahatan pun memperhitungkan tempat dan waktu, karena seseorang yang akan melakukan sebuah tindak kejahatan juga mempunyai perhitungan-perhitungan.”
Glagah Putih mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan gurunya itu. Tanpa sadar dia kemudian berpaling ke belakang. Tampak Ki Bango Lamatan sedang berjalan sambil menundukkan kepalanya.
“Orang itu telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam dirinya,” berkata Glagah Putih dalam hati sambil kembali memandang ke depan, “Aku masih ingat peristiwa di tepian kali Opak. Ki Bango Lamatan saat itu berada di pihak Panembahan Cahya Warastra dan sekarang tiba-tiba telah menjadi orang kepercayaan Pangeran Pati,” angan-angan Glagah Putih berhenti sejenak. Kemudian sambil tersenyum sekilas dia melanjutkan angan-angannya, “Semua itu berkat jasa Kanjeng Sunan.”
Tanpa terasa langkah mereka telah mendekati regol halaman rumah Ki Gede Matesih.
Ketiga orang itu pun kemudian berjalan sebagaimana orang-orang yang lain. Namun ketika mereka lewat tepat di depan regol, Glagah Putih telah menyempatkan diri untuk berpaling sekilas.
Tampak kening Glagah Putih berkerut. Apa yang dilihatnya hanya sekilas itu ternyata sangat berkesan. Diujung tangga pendapa dia sempat melihat seorang gadis cantik yang sedang beranjak dewasa tampak sedang bercakap-cakap dengan seseorang.
“Ratri,” tanpa sadar bibir Glagah Putih menyebut sebuah nama.
Ki Jayaraga yang berjalan di sampingnya terkejut. Sambil berpaling dia bertanya, “Siapa Glagah Putih?”
“O,” Glagah Putih tergagap. Setelah menarik nafas panjang barulah Glagah Putih menjawab, “Guru, aku tadi melihat seorang gadis yang sedang beranjak dewasa di tangga pendapa kediaman Ki Gede. Mungkin itu Ratri, putri satu-satunya Ki Gede Matesih.”
Ki Jayaraga mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, “Mungkin Glagah Putih. Gadis yang telah terpikat oleh seorang pria dewasa, yang mengaku sebagai Trah Sekar Seda Lepen.”
“Tentu Ratri telah terbuai oleh angan-angan dan janji-janji dari Raden Surengpati,” sahut Glagah Putih, “Jika perjuangan Trah Sekar Seda Lepen itu berhasil, dia akan ikut menikmati hasilnya. Hidup di kalangan istana, berlimpah ruah dengan harta benda, serta disuyuti dan dihormati oleh kawula seluruh negeri.”
“Ah,” Ki Jayaraga tertawa pendek mendengar ucapan Glagah Putih. Bahkan Ki Bango Lamatan yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka pun ikut tersenyum.
Tanpa terasa langkah mereka telah semakin jauh dari regol halaman Ki Gede. Ketika mereka kemudian menjumpai sebuah jalan simpang, tiba-tiba Glagah Putih telah menghentikan langkahnya.
“Ada apa Glagah Putih?” bertanya Ki Jayaraga yang juga ikut berhenti. Sementara Ki Bango Lamatan yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka telah memperlambat langkahnya.
“Guru, kita mengambil jalan ke kanan,” jawab Glagah Putih kemudian.
“Glagah Putih, jalan menuju ke Gunung Tidar adalah lurus ke depan,” tiba-tiba Ki Bango Lamatan yang telah ikut berhenti menyahut.
“Ki Bango Lamatan benar,” berkata Ki Jayaraga ikut menimpali, “Sebaiknya kita mengambil jalan lurus.”
Sejenak Glagah Putih ragu-ragu. Namun entah mengapa, seraut wajah cantik gadis putri ki Gede Matesih itu tidak mau hilang dari benaknya, walaupun beberapa saat tadi dia hanya melihatnya sekilas.
Setelah menarik nafas dalam-dalam, barulah Glagah Putih mengutarakan kegelisahannya.
“Guru,” berkata Glagah Putih kemudian, “Entah mengapa begitu melihat putri ki Gede tadi, rasa-rasanya aku telah mengkhawatirkan keselamatannya.”
Kedua orang tua itu sejenak saling pandang. Mereka segera menyadari, Glagah Putih agaknya telah tertarik dengan putri Matesih itu, apapun alasannya.
“Glagah Putih,” berkata Ki Jayaraga kemudian setelah melihat Ki Bango Lamatan yang tersenyum dan mengangguk-angguk, “Engkau tertarik pada putri Ki Gede itu memang sudah sewajarnya. Engkau masih muda dan putri Matesih itu pun seorang gadis yang sedang mekar-mekarnya. Namun sejauh manakah ketertarikanmu itu yang harus dipertanyakan.”
“Ah,” Glagah Putih berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rona merah segera saja menghiasi wajahnya, namun dengan cepat segera saja Glagah Putih berusaha menghilangkan kesan itu dari wajahnya. Katanya kemudian, “Guru, aku menyadari bahwa aku adalah laki-laki yang sudah beristri. Aku hanya memikirkan bagaimana nasib putri Matesih itu jika dia benar-benar terjebak dalam jeratan orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu.”
Untuk beberapa saat kedua orang tua itu justru telah terdiam. Memang akan saat mengenaskan nasib putri Matesih yang masih hijau itu jika dia sampai terperangkap jebakan Raden Mas Harya Surengpati.
“Ah, sudahlah,” akhirnya Ki Jayaraga berkata memecah kesunyian setelah sejenak mereka terdiam, “Kita hanya bisa mendoakan masa depan yang baik bagi putri Ki Gede itu.”
Ki Bango Lamatan mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar ucapan Ki Jayaraga, namun Glagah Putih justru mengerutkan keningnya dalam-dalam.
Ki Jayaraga yang melihat muridnya termenung telah menarik nafas panjang. Tanyanya kemudian, “Ada apa lagi Glagah Putih?”
“Maafkan aku Guru dan juga Ki Bango Lamatan,” jawab Glagah Putih kemudian, “Marilah kita bicarakan dengan sungguh-sungguh permasalahan ini”
Selesai berkata demikian Glagah Putih segera mempersilahkan kedua orang tua itu untuk berjalan menepi dan duduk di bawah sebatang pohon peneduh yang tumbuh di kanan jalan.
Setelah ketiganya menempatkan diri duduk di bawah bayangan pohon yang teduh itu, barulah Glagah Putih meneruskan kata-katanya, “Guru, aku mempunyai perhitungan bahwa saat ini Ki Wiyaga tentu telah melaporkan kejadian pagi tadi kepada Ki Gede Matesih.”
Serentak bagaikan telah berjanji, kedua orang tua itu mendongakkan wajahnya ke langit.
“Sudah hampir wayah tengange,” desis Ki Jayaraga
“Ya Ki Jayaraga,” sahut Ki Bango Lamatan, “Tentu Ki Gede sudah mendapat laporan dari Ki Wiyaga.’
“Nah Glagah Putih,” berkata Ki Jayaraga selanjutnya, “Apa hubungannya dengan Ratri, putri Ki Gede?”
“Guru,” jawab Glagah Putih kemudian. Tampak wajahnya bersungguh-sungguh sehingga kedua orang itu pun telah menaruh perhatian sepenuhnya, “Aku mempunyai dugaan bahwa apa yang telah dilaporkan oleh Ki Wiyaga kepada Ki Gede sedikit banyak akan diketahui oleh Raden Surengpati.”
Kedua orang tua itu saling pandang sejenak. Ki Jayaraga lah yang menanggapi, “Bagaimana mungkin, Glagah Putih? Ki Wiyaga tentu tidak gegabah dalam memberikan laporannya.”
“Benar, guru,” sahut Glagah Putih cepat, “Akan tetapi bagaimana dengan keluarga Ki Gede sendiri? Apakah tidak menutup kemungkinan Ratri mendengar walaupun hanya sekilas-sekilas dan kemudian menyampaikannya kepada Raden Surengpati.”
Kini kedua orang tua itu termenung. Memang hal itu sangat mungkin terjadi.
“Jadi apa rencanamu sekarang Glagah Putih?’ bertanya Ki Bango Lamatan kemudian.
Sejenak Glagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun baru saja Glagah Putih akan menjawab pertanyaan Ki Bango Lamatan, tiba-tiba dari kejauhan Glagah Putih melihat seseorang mendatangi tempat itu.
“Penjual dawet serabi,” desis Glagah Putih kemudian. Serentak kedua orang tua itu pun mengikuti arah pandang Glagah Putih.
“Apakah engkau haus Glagah Putih?” bertanya Ki Jayaraga kemudian sambil tersenyum.
Glagah Putih tidak segera menjawab. Pandangan matanya justru mengarah kepada Ki Bango Lamatan.
Ki Bango Lamatan pun lantas tertawa pendek. Katanya kemudian, “Alangkah segarnya minum dawet serabi di siang hari yang terik seperti ini.”
Ki Jayaraga dan Glagah Putih pun akhirnya ikut tertawa.
Demikianlah sejenak kemudian mereka bertiga telah memanggil penjual dawet serabi yang lewat di depan mereka.
Penjual dawet serabi itu pun segera berhenti dan menurunkan dagangannya. Dengan cekatan dilayaninya para pembelinya itu satu persatu.
“Ki Sanak,” berkata Glagah Putih kemudian setelah dia menyelesaikan minumnya lebih cepat dari kedua orang tua itu, “Kelihatannya mangkukku ini lebih kecil dibanding dengan mangkuk yang lainnya.”
“Ah,” penjual dawet itu tertawa, “Apakah engkau bermaksud menambah lagi, anak muda?”
Glagah Putih pun mengangguk sambil tertawa. Sementara Ki Jayaraga sambil menyenduk minumannya telah berkata kepada Glagah Putih, “Lain kali engkau membawa wadah sendiri saja, tempayan atau genthong barangkali.”
Yang mendengar kelakar Ki Jayaraga itu pun telah tertawa.
“Ki Sanak,” tiba-tiba penjual dawet itu berkata sambil memandang satu-persatu pembelinya, “Rasa-rasanya aku belum pernah melihat kalian. Dari manakah Ki Sanak semua ini?”
Sejenak mereka bertiga saling berpandangan. Ki Jayaraga lah yang akhirnya menjawab sambil mengembalikan mangkuknya yang telah kosong.
“Kami berasal dari Sangkal Putung,” jawab Ki Jayaraga sekenanya, “Dan kami sedang menuju ke Padukuhan Paran-paran.”
Penjual dawet ini mengerutkan keningnya. Tanyanya kemudian, “Di manakah letak Padukuhan Paran-paran itu Ki Sanak?”
Ki Jayaraga tersenyum. Jawabnya kemudian, “Padukuhan Paran-paran terletak di antara lembah Gunung Sindara dan Sumbing.”
“O,” penjual dawet itu tampak mengangguk-anggukkan kepalanya walaupun sebenarnya dia tidak mengetahui dengan pasti letak padukuhan itu.
“Terima Kasih Ki Sanak,” berkata penjual dawet itu kemudian ketika Ki Jayaraga membayar harga empat mangkuk dawet serabi, “Semoga perjalanan kalian menyenangkan.”
“Terima kasih,” jawab mereka bertiga hampir bersamaan.
“Semoga sekembalinya kami dari Paran-paran, kita dapat berjumpa kembali,” tambah Glagah Putih.
“O, tentu, tentu ki Sanak,” jawab penjual dawet itu sambil mengangkat pikulannya dan kemudian menaruh di pundaknya, “Hampir setiap hari aku melewati jalan ini.”
“Tapi engkau jangan lupa membawa tempayan,” sahut Ki Jayaraga sambil menggamit Glagah Putih yang segera saja disambut dengan gelak tawa.
Demikianlah setelah penjual dawet serabi itu pergi, Glagah Putih pun segera menyampaikan rencananya.
“Guru,” berkata Glagah kemudian, “Sebaiknya perjalanan kita ke Gunung Tidar kita tunda sebentar. Siang ini sampai nanti menjelang sore kita coba untuk mengamati kediaman Ki Gede. Barangkali putri Ki Gede akan keluar menemui Raden Surengpati untuk menyampaikan berita yang telah dibawa oleh Ki Wiyaga.”
Ki Jayaraga mengerutkan keningnya sambil memandang Ki Bango Lamatan. Agaknya guru Glagah Putih itu meminta pertimbangan untuk menyetujui rencana Glagah Putih.
Untuk sejenak Ki Bango Lamatan termenung. Namun tiba-tiba saja Ki Bango Lamatan berdesis perlahan, “Bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Raden Surengpati itu yang menemui Ratri di kediaman Ki Gede?”
Sekarang giliran Glagah Putih yang tertegun. Kemungkinan itu memang ada, namun menilik tanggapan Ki Gede yang tidak menginginkan putri satu-satunya itu menjalin hubungan dengan orang yang mengaku sebagai Trah Sekar Seda Lepen itu, kemungkinannya sangat kecil jika Ki Gede mengijinkan Raden Surengpati menemui putrinya.
Maka jawab Glagah Putih kemudian, “Kemungkinan itu sangat kecil, Ki Bango Lamatan. Aku justru cenderung hubungan mereka berdua itu masih sebatas sembunyi-sembunyi. Aku yakin mereka berdua belum berani berterus terang justru karena Ki Gede telah memperlihatkan sambutan yang kurang ramah atas kehadiran para pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu di perdikan Matesih.”
“Engkau benar Glagah Putih,” berkata ki Jayaraga kemudian setelah sejenak berpikir, “Memang sebaiknya kita mengamati kediaman Ki Gede siang ini sampai sore nanti. Semoga apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi.”
Demikianlah sejenak kemudian ketiga orang itu segera meneruskan perjalanan. Mereka mengambil jalan yang berbelok ke kanan, jalan yang terlihat lebih kecil dari jalan sebelumnya.
“Agaknya jalan ini sangat jarang dilewati orang,” berkata Ki Jayaraga sambil mengayunkan langkahnya.
“Kelihatannya memang demikian, Ki,” sahut Ki Bango Lamatan sambil mengamat-amati pohon-pohon perdu liar yang tumbuh di sepanjang jalan, “Jalan ini sepertinya sebuah jalan pintas.”
“Aku juga mengira demikian,” kembali Ki Jayaraga berkata sambil ikut mengamati tanah pategalan yang kelihatannya sudah tidak terurus.
Sejenak kemudian jalan yang mereka lewati itu semakin lama menjadi semakin menyempit dan hanya tinggal jalan setapak saja yang terlihat menjelujur di antara rumput-rumput dan ilalang yang tumbuh liar di sana sini.
Selagi mereka berjalan sambil merenungi semak belukar yang semakin lebat, tiba-tiba saja pendengaran mereka yang tajam lamat-lamat telah mendengar langkah seseorang yang terdengar sangat tergesa-gesa dari arah kanan jalan. Memang masih cukup jauh, namun suara langkah itu begitu jelas terdengar di antara suara daun-daun yang tersibak dan ranting-ranting kecil yang berpatahan.
Untuk beberapa saat ketiga orang itu tidak tahu harus berbuat apa untuk menyikapi suara langkah yang terdengar semakin dekat itu. Namun ketika Ki Jayaraga kemudian menganggukkan kepalanya, serentak mereka bertiga pun segera bersembunyi di balik perdu-perdu yang banyak berserakan di tempat itu.
Sambil menahan nafas, mereka bertiga mencoba mengintip dari sela-sela dedaunan untuk melihat siapakah yang akan muncul dari pategalan di kanan jalan yang sudah tak terurus lagi itu.
Semakin lama suara langkah itu terdengar semakin keras. Sejenak kemudian dari balik sebatang pohon sawo kecik, muncul seraut wajah yang sangat dikenal oleh Glagah Putih.
“Ratri?” desis Glagah Putih dengan suara yang bergetar.
Kedua orang tua itu terkejut mendengar desis Glagah Putih sehingga telah berpaling ke arahnya.
“O, jadi itukah Ratri? Pantas!” bisik Ki Bango Lamatan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.
“Maksud Ki Bango Lamatan?” tanya Glagah Putih sambil berpaling.
Ki Bango Lamatan berpaling sekilas sambil tersenyum. Jawabnya kemudian, “Gadis yang bernama Ratri itu sangat cantik. Tentu banyak laki-laki yang ingin menyuntingnya.”
“Termasuk Ki Bango Lamatan barangkali,” sahut Ki Jayaraga
“Ah,” Ki Bango Lamatan hampir saja tidak dapat menahan tawanya, namun yang menjadi merah mukanya justru Glagah Putih.
“Lihatlah,” berkata Ki Jayaraga kemudian mengalihkan pembicaraan, “Putri Ki Gede itu memotong jalan dan memasuki pategalan di sebelah kiri jalan.”
“Kita ikuti,” sahut Glagah Putih cepat sambil berdiri dan kemudian melangkah menuju ke tempat putri Matesih itu menghilang.
Kedua orang tua itu sejenak saling berpandangan. Sambil menahan senyum akhirnya kedua orang tua itu pun berdiri dan melangkah mengikuti Glagah Putih.
Bukanlah sebuah pekerjaan yang sulit bagi ketiga orang itu untuk mengikuti jejak Ratri. Putri Ki Gede Matesih itu hanyalah seorang gadis kebanyakan yang tidak pernah diperkenalkan pada olah kanuragan sejak kecil.
Semakin lama ketiga orang itu semakin jauh memasuki pategalan yang sudah berubah menjadi seperti hutan kecil itu. Setelah melalui jalan setapak yang nyaris tak terlihat dan kemudian menurun, terlihat sebuah parit yang airnya mengalir bening.
“Parit ini mungkin digunakan sebagai pengairan ketika pategalan-pategalan ini masih digarap,” berkata Ki Jayaraga dalam hati sambil meloncati batang pohon yang tumbang karena lapuk dimakan usia.
Beberapa saat kemudian ketiga orang itu melihat Ratri telah berhenti di sepetak tanah yang ditumbuhi rumput. Di tanah sepetak itu kelihatannya dulu pernah didirikan sebuah gubuk untuk tempat beristirahat.
Sejenak Ratri terlihat masih berdiri termangu-mangu. Tampaknya dia sedang menunggu seseorang. Dengan raut wajah yang terlihat gelisah dia kemudian duduk di atas batu yang menjorok di sebelah parit yang airnya mengalir dengan bening.
Dalam pada itu di salah satu jalan di sebelah barat perdikan Matesih, tampak dua orang penunggang kuda, Eyang guru dan Raden Surengpati sedang memacu kudanya dengan sedikit kencang.
“Eyang guru,” berkata Raden Surengpati, “Di depan ada simpang tiga. Sebelum kita meneruskan perjalanan melalui jalan yang membelok ke kiri, ijinkan aku untuk menemui Ratri terlebih dahulu.”
“Raden,” jawab Eyang guru, “Apakah pertemuan itu dapat ditunda? Kita sebaiknya sampai di Tidar sebelum Matahari tergelincir jauh ke barat. Banyak hal yang harus kita bicarakan sehubungan dengan kedatangan Ki Rangga Agung Sedayu.”
“Aku paham Eyang guru,” jawab Raden Surengpati kemudian, “Namun sekarang ini adalah waktunya aku bertemu Ratri di tempat yang sudah kita sepakati. Mungkin Ratri membawa berita yang penting.”
Eyang guru menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, “Baiklah Raden. Kalau begitu aku menunggu saja di persimpangan. Aku tidak ingin mengganggu keasyikan kalian berdua.”
“Ah,” desah Raden Surengpati, “Ratri adalah gadis yang masih lugu. Dia selalu membawa kawan jika bertemu denganku.”
“He?!” terkejut Eyang guru mendengar keterangan Raden Surengpati.
Sambil berpaling sekilas, Eyang guru pun kemudian bertanya, “Apakah teman Ratri itu dapat dipercaya?”
“Ya, Eyang guru,” jawab Raden Surengpati mantap, “Kawannya itu adalah pemomongnya sejak kecil, jadi sudah dianggap seperti biyungnya sendiri. Apalagi sejak Nyi Gede meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, pemomongnya itu seolah-olah telah dianggap sebagai pengganti biyungnya.”
Eyang guru menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Tak terasa derap langkah kaki-kaki kuda mereka telah mendekati simpang tiga.
“Aku akan menunggu di sini,” berkata Eyang guru kemudian sambil meloncat turun dan kemudian menambatkan kudanya pada sebatang pohon di pinggir jalan. Sementara Raden Surengpati masih belum turun dari kudanya.
“Apakah Raden akan berkuda?” bertanya Eyang guru sambil mengambil duduk di bawah sebatang pohon besar yang akar-akarnya tampak menonjol keluar.
Sejenak Raden Surengpati termenung. Namun akhirnya dia pun menjawab, “Aku akan berkuda saja Eyang guru. Tempatnya memang agak jauh dari sini.”
“Pergilah!” berkata Eyang guru sambil merebahkan dirinya bersandaran pada batang pohon itu.
“Terima kasih Eyang guru,” jawab Raden Surengpati kemudian, “Aku pergi dulu.”
Tanpa menunggu lagi, Raden Surengpati pun kemudian segera menghentak perut kudanya agar berlari maju.
Jarak antara simpang tiga dengan tempat yang biasa dijadikan pertemuan Raden Surengpati dengan Ratri memang cukup jauh. Setelah melalui jalan yang menurun, barulah Raden Surengpati membelokkan kudanya menyusuri jalan setapak memasuki sebuah pategalan.
Ketika jalan setapak itu telah menghilang tertutup rumput-rumput liar dan ilalang yang tumbuh rapat berjajar-jajar, Raden Surengpati pun segera menghentikan kudanya dan meloncat turun.
Sejenak Raden Surengpati menarik nafas panjang untuk memenuhi rongga dadanya dengan udara segar siang hari itu. Entah mengapa setiap akan berjumpa dengan Ratri, jantungnya selalu berdebar. Sebenarnyalah bagi Raden Surengpati bukan sekali ini saja dia berhubungan dengan perempuan, namun terhadap Ratri, dia mempunyai tujuan tersendiri.
“Ratri harus bisa membujuk dan meyakinkan ayahnya bahwa perjuangan Trah Sekar Seda Lepen ini memerlukan dukungan penuh dari perdikan Matesih,” berkata Raden Surengpati dalam hati sambil menambatkan tali kekang kudanya pada sebuah batang pohon, “Dengan direstuinya hubungan kami berdua, aku berharap Ki Gede akan legawa untuk melintirkan Perdikan Matesih ini kepadaku sehingga perdikan Matesih akan menjadi tumpuan utama dalam berjuang melawan Mataram.”
Sekali lagi Raden Surengpati menarik nafas panjang. Kemudian dengan langkah yang mantap dia mulai menuruni tanah yang agak miring menuju ke sebuah parit yang sudah tampak dari tempatnya berdiri.
Setelah sampai di tepi parit yang airnya mengalir bening, Raden Surengpati pun menyusuri parit itu mendekati tempat Ratri menunggu dari arah barat. Sementara Ki Jayaraga dan kawan-kawannya telah menempatkan diri di tempat yang agak jauh di sebelah timur dari tempat Ratri menunggu.
Dalam pada itu, Ratri yang sedang menunggu kedatangan Raden Surengpati itu menjadi semakin gelisah. Sesekali dia berdiri dari duduknya dan berjalan mondar-mandir. Namun ketika dirasakan kakinya menjadi penat, dia pun duduk kembali.
“Mengapa aku tadi tidak menunggu mbok Pariyem saja,” berkata Ratri dalam hati sambil sesekali mendongakkan kepalanya ke arah barat, “Tapi mbok Pariyem pergi dari pagi dan belum kembali, sedangkan berita ini sangat penting bagi Raden Mas Harya Surengpati.”
Teringat akan Raden Surengpati, tiba-tiba saja wajah Ratri menjadi cerah. Sebuah senyum manis tersungging di bibirnya yang merah menawan. Gadis putri satu-satunya Ki Gede itu sedang beranjak dewasa bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Mengalami masa-masa remaja yang ingin selalu dipuja dan dimanja, dan agaknya Raden Surengpati telah paham akan hal itu. Pengalaman panjangnya bergaul dengan perempuan telah membuat Ratri menjadi mabuk kepayang.
Tiba-tiba Ratri yang sedang termenung itu mendengar langkah-langkah mendekat dari arah barat. Dengan segera dia berpaling sambil bangkit dari duduknya.
“Raden…” desis Ratri dengan suara yang riang penuh kegembiraan begitu mengetahui siapa yang datang.
Yang datang itu memang Raden Surengpati. Sejenak langkahnya tertegun. Dia tidak melihat kawan Ratri yang biasanya selalu setia menemani.
“Engkau sendiri, Ratri?” bertanya Raden Surengpati kemudian dengan pandangan nanar merayapi sekujur tubuh Ratri.
“Ya, Raden,” jawab Ratri sambil menundukkan wajahnya. Jauh di lubuk hatinya dia telah menyesali ketergesa-gesaannya untuk datang ke tempat itu tanpa mbok Pariyem.
“Nah, berita apakah yang engkau bawa kali ini, Ratri?” bertanya Raden Surengpati kemudian sambil berjalan mendekat.
Sejenak Ratri mengangkat wajahnya. Ketika sepasang matanya memandang ke wajah Raden Surengpati, tiba-tiba saja dadanya berdesir tajam. Wajah itu tidak menampakkan sebagaimana biasanya yang ramah dan lembut. Wajah itu tampak mengerikan, merah membara dengan sepasang mata yang liar menelusuri lekuk-lekuk sekujur tubuhnya.
Dengan segera Ratri menundukkan wajahnya kembali. Sambil berusaha menguasai degup jantungnya yang melonjak-lonjak, dia menjawab pertanyaan Raden Surengpati dengan suara bergetar, “Raden, tadi pagi ayah telah mengadakan pertemuan dengan para bebahu perdikan Matesih.”
“O,” desis Raden Surengpati sambil menarik nafas panjang. Darah di sekujur tubuhnya telah mendidih. Dengan langkah satu-satu, orang yang mengaku trah Sekar Seda Lepen itu berjalan semakin dekat.
“Apa yang mereka bicarakan, Ratri?” terdengar suara Raden Surengpati berbisik di dekat telinganya. Begitu dekatnya sehingga Ratri dengan jelas dapat mendengar desah nafasnya yang memburu.
Seketika gemetar sekujur tubuh putri Matesih itu. Berbagai dugaan muncul dalam benaknya. Ada perasaan takut yang menyergap hatinya begitu menyadari apapun bisa terjadi selagi mereka hanya berdua saja di tempat yang sepi itu.
Menyadari bahaya yang setiap saat dapat saja menerkamnya, Ratri segera berusaha menghindar dari tempat itu. Katanya kemudian sambil melangkah surut, “Maaf Raden, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Setiap saat ayah akan memerlukan aku. Aku harus segera kembali ke bilikku.”
“Tidak Ratri,” tiba-tiba terdengar suara Raden Surengpati itu mirip lolong seekor serigala lapar di telinga Ratri, “Akulah yang sekarang memerlukanmu disini. Tidak ada seorang pun yang akan menggangu. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu, justru aku akan membahagiakanmu dan sekaligus memberikan sebuah pengalaman yang belum pernah engkau rasakan seumur hidup,” Raden Surengpati berhenti sebentar untuk sedikit meredakan dadanya yang seakan-akan mau meledak. Lanjutnya kemudian, “Inilah kesempatan bagiku untuk membuat Ki Gede menyerah dan menuruti segala kemauanku.”
STSD Jilid 4
Bagian 1
Ada sebersit penyesalan yang menyelinap di dalam hati anak perempuan satu-satunya Ki Gede Matesih itu. Jika dia sedikit bersabar menunggu kedatangan mbok Pariyem, mungkin Raden Surengpati akan bersikap lain.
“Raden,” berkata Ratri kemudian mencoba untuk mengalihkan perhatian Raden Surengpati, “Menurut berita yang aku dengar, kelima orang yang bermalam di banjar padukuhan Klangon itu telah lolos.”
“Persetan dengan segala macam tetek bengek itu!” geram Raden Surengpati, “Aku sudah tidak peduli lagi kepada mereka. Yang ada sekarang ini adalah antara engkau dan aku!”
Selesai berkata demikian, Raden Surengpati maju selangkah lebih dekat. Penalarannya benar-benar telah gelap. Di dalam benaknya hanya ada satu keinginan, menguasai Ratri dengan sepenuhnya kalau perlu dengan paksaan.
Namun putri Matesih itu belum menyerah. Dengan menguatkan hatinya, Ratri pun akhirnya berkata dengan nada sedikit memelas, “Raden, kasihanilah aku. Aku harus cepat kembali, dan Raden pun tentu mempunyai kepentingan lain yang tidak dapat ditunda -tunda. Ijinkanlah aku pergi, Raden.”
Suara Ratri yang terdengar memelas itu di telinga Raden Surengpati bagaikan sebuah rengekan manja dari seorang gadis yang haus akan cinta. Darah di sekujur tubuhnya pun bagaikan mendidih dan kemudian menggelegak menelusuri segenap urat-urat nadinya.
“Ratri,” terdengar suara Raden Surengpati yang bergetar hebat menahan gejolak yang sudah menghanguskan jantungnya, “Engkau begitu cantik dan menawan. Aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk menikmati tubuhmu sejengkal demi sejengkal. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu walau hanya seujung rambutmu. Engkau akan kubawa ke alam keindahan dan kenikmatan yang belum pernah terbayangkan dalam seumur hidupmu.”
Mulut Ratri benar-benar sudah terkunci, tidak mampu lagi untuk berkata-kata maupun berteriak. Kengerian yang sangat telah menjalar ke sekujur tubuhnya sehingga tubuhnya telah kaku seperti sebuah tonggak kayu. Bahkan hanya untuk menggerakkan ujung ibu jari kakinya pun dia sudah tidak mampu lagi.
Ketika salah satu tangan Raden Surengpati yang kekar itu kemudian merengkuh pundaknya, hanya terdengar sebuah jeritan kecil dari mulutnya yang mungil. Sejenak kemudian segalanya terlihat gelap dalam rongga matanya dan Ratri pun jatuh pingsan dalam pelukan Raden Surengpati.
Melihat mangsanya ternyata telah jatuh pingsan, Raden Surengpati pun bagaikan menjadi kalap. Dengan kedua tangan yang gemetar menahan nafsu yang bergejolak, dicobanya untuk membuka pakaian bagian atas putri Matesih itu.
Namun belum sempat dia melakukannya, tiba-tiba telinganya mendengar suara seseorang bergumam tidak seberapa jauh di depannya.
Ketika Raden Surengpati kemudian mengangkat wajahnya, tampak seorang anak muda dengan wajah yang merah padam berdiri beberapa langkah saja di hadapannya dengan kaki renggang dan kedua tangan bersilang di depan dada.
“Iblis!” geram Raden Surengpati kemudian sambil menurunkan tubuh Ratri perlahan-lahan dan kemudian membaringkannya di atas t anah. Sambil maju dua langkah, Raden Surengpati pun kemudian membentak keras, “Siapa yang berani mengganggu kesenangan Raden Surengpati, he?!”
Namun Raden Surengpati menjadi heran sendiri. Pemuda yang berdiri di hadapannya itu tidak menampakkan rasa gentar sedikit pun mendengar dia menyebut nama serta gelar kebangsawanannya. Bahkan sambil mengurai kedua tangannya yang bersilang di depan dada, tangan kanan Pemuda itu justru telah menunjuk ke arah wajahnya sambil membentak tak kalah kerasnya, “Surengpati, namamu yang selama ini menghantui Perdikan Matesih akan berakhir hari ini. Sebelum Matahari terbenam di langit sebelah barat, aku jamin mayatmu akan terbujur di pategalan ini sebagai tumbal tanah Perdikan Matesih untuk menemukan masa depannya kembali.”
“Tutup mulutmu! ” bentak Raden Surengpati kemudian dengan wajah membara, “Sebut namamu sebelum aku membunuhmu! ”
Pemuda itu melangkah setapak ke depan. Sambil membusungkan dada, dia pun kemudian berteriak lantang, “Dengarkan baik-baik. Aku Glagah Putih dari Prambanan yang akan mengakhiri petualanganmu hari ini.”
Belum sempat Glagah Putih menutup mulutnya dengan sempurna, terpaan angin yang keras terasa mendahului serangan Raden Surengpati yang telah meluncur dengan deras menyambar dagunya.
Namun Glagah Putih bukanlah anak kemarin sore yang baru saja berlatih loncat-loncatan dalam olah kanuragan. Dengan tangkasnya dia bergeser selangkah ke samping kiri. Kemudian dengan bertumpu pada tumit salah satu kakinya, kaki yang lainnya berputar menyambar lambung lawannya yang terbuka.
Raden Surengpati yang menyadari sambaran kaki lawannya mengarah ke lambung segera menggeliat. Tumit Glagah Putih pun lewat hanya sejengkal dari lambungnya.
Demikian lah sejenak kemudian kedua orang itu segera bertempur dengan sengitnya. Kedua-duanya masih muda dan berdarah panas, sehingga keduanya segera saja telah merambah pada tingkat ilmu mereka yang semakin tinggi.
Dalam pada itu, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan diam-diam menjadi semakin berdebar-debar melihat tandang Glagah Putih. Dari tempat persembunyian mereka, terlihat Glagah Putih bertempur dengan segenap tenaga dan terlihat sedikit menuruti gejolak dalam dadanya.
“Ki Jayaraga, mengapa Glagah Putih terlihat begitu bernafsu untuk segera menjatuhkan lawannya?” bisik Ki Bango Lamatan kepada Ki Jayaraga yang berada di sampingnya.
Ki Jayaraga tersenyum sambil menggeleng. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu. Mungkin terdorong kemarahan yang membakar jantungnya melihat putri satu-satu Ki Gede Matesih itu dalam bahaya.”
Ki Bango Lamatan mengerutkan keningnya mendengar jawaban Ki Jayaraga. Katanya kemudian, “Seharusnya Glagah Putih mengekang diri. Jika terjadi kesalahan tangan sehingga Raden Surengpati terbunuh, apakah tidak akan membahayakan para kawula tanah Perdikan Matesih ini?”
“Maksud Ki Bango Lamatan, Raden Wirasena sebagai saudara kandung Raden Surengpati pasti akan membalas dendam?”
“Benar, Ki,” jawab Ki Bango Lamatan, “Dan tidak menutup kemungkinan Raden Wirasena akan meminta bantuan perguruan Sapta Dhahana untuk membuat Perdikan Matesih menjadi karang abang.”
Sekarang giliran Ki Jayaraga yang mengerutkan keningnya. Namun sambil tertawa lirih Ki Jayaraga pun kemudian berkata, “Jika memang itu yang kemudian terjadi, sekali lagi kita harus menyembunyikan mayatnya agar untuk sementara orang-orang pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu tidak mengetahuinya.”
Ki Bango Lamatan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam mendengar jawaban Ki Jayaraga. Pandangan matanya kembali melihat ke arah medan pertempuran kedua anak muda itu yang semakin lama semakin sengit.
No comments:
Post a Comment